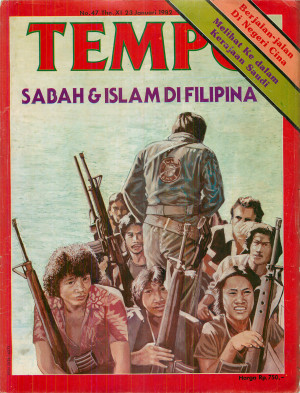ABUL Khayr Alonto, nampak gemuk dan muda--tak seperti fotonya
semasih bergerilya di gunung yang menghias kulit majalah Tirne,
9 Februari 1976. Ayahnya, Abdul Gafur Madki Alonto adalah bekas
Gubernur Lanao dan Sulu di Mindanao, anggota parlemen Filipina
yang beragama Islam. Sang anak yang belajar ilmu hukum di
University of Philippine dan kemudian studi di Al Azhar, Kairo,
sempat lima tahun di hutan sebagai orang kedua MNLF sampai ia
menyerahkan diri, Juni 1978.
Sekarang Abul Khayr Alonto, 37 tahun, jadi Ketua Sanggunang
Pampook (lembaga legislatif daerah otonomi) wilayah (region
XII, Mindanao Tengah. Dengan suara lembut simpatik tapi tanpa
senyum selama hampir tiga jam, Alonto menjawab pertanyaan
wartawan TEMPO Amran Nasution, suatu malam Desember. Nurhayat,
istrinya yang cantik, pengajar di Univer sitas Mindanao, dan
lima anaknya sesekali mendampingi. Sementara Mayor Muhamad,
pengawalnya, terus berdiri di samping. Gagang pistol membayang
dari balik baju barong sang mayor yang tipis. Kejadian ini di
suatu ruangan di Philippine Plaza, hotel terkemuka di Manila,
dan Alonto berbicara terus terang seperti berikut:
Banyak alasan mengapa saya dulu melawan Marcos. Kami muslim yang
berjumlah 4 juta dari 46 juta penduduk Filipina sejak lama jadi
warganegara kelas dua: tak sampai 2% yang jadi pegawai
pemerintah. Kami punya banyak sarjana tamatan luar negeri tapi
tak dapat kesempatan. Kami hanya punya seorang senator. Tak ada
orang kami di lembaga keuangan.
Daerah kami diabaikan. Jalan dibiarkan rusak. Hanya sedikit
sekolah dan rumah sakit di daerah kami.
Saya belajar di Kairo sampai 1965 Ketika itu Presiden Nasser
banyak mengajarkan kebebasan dan revolusi. Setibanya kembali di
Filipina, saya tak mendengar suara seperti itu. Orang tua
bungkam. Padahal penderitaan di sini sarna seperti yang
dirasakan pemuda Palestina. Tapi mereka punya El Fatah. Kenapa
kami harus bungkem seperti orang tua? Padahal kami menyaksikan
orang Luzon dan Vesayas menyerobot tanah kami di Mindanao, dan
mereka dibantu tentara.
Ketika itu saya berkenalan dengan Nur Misuari. Kami tidak
berasal dari satu daerah. Dia dari Jolo (pulau kecil di selatan
Mindanao) dan saya dari Lanao. Misuari mengajar di University of
Philippine. Saya dengar dia dekat dengan kaum komunis Filipina.
Tapi dialah ketika itu yang berani bersuara. Saya lupakan semua
cerita tentang dirinya.
Kami terpaksa memilih jalan kekerasan. Kami bukan saja
berhadapan dengan orang sipil yang merampas tanah kami, tapi
juga dengan tentara. Situasi memuncak ketika (tahun 1970)
terjadi Corregidor Massacre. Anda tahu artinya? Sekitar 300
pemuda muslim dari Sulu dapat latihan militer di Corregidor
untuk dikirim merebut Sabah. Ketika menolak, mereka semua
dibunuh, kecuali dua orang selamat karena berpura-pura mati.
No . . . no . . . saya bukan menyerah. Saya memilih berjuang
dengan cara lain, berbeda dengan sikap Misuari, bekas guru saya
itu. Saya melihat komunis menang di Vietnam. Saya melihat di
Filipina sendiri komunis tambah kuat. Kalau kami terus
berperang, saya khawatir Marcos akan kalah dan komunis berkuasa.
Ketika masih di Malaysia (Sabah), kami berjanji sama berjuang.
Tapi nyatanya kemudian Misuari meninggalkan saya begitu lama di
gunung, kedinginan tanpa selimut, sementara dia tinggal di kamar
hotel yang hangat di Tripoli. Dan sesekali ia mengirim salam
kepada kami.
Sementara itu saya lihat Marcos mulai mengubah sikap. Dia
memberikan kelonggaran kepada Islam dan membangun daerah
Selatan. Dia juga membangun masjid. Tahun 1977, Marcos
mengadakan plebisit menuju hak otonomi untuk daerah Selatan
sesuai dengan Tripoli Agreement. Ketika setahun kemudian Marcos
memberikan otonomi itu, saya dan 3000 teman turun gunung.
Tapi pemerintah masih lamban dan hak otonomi itu belum tegas.
Pembangunan harus benar-benar mencapai daerah muslim yang
terkebelakang di Selatan.Cagayan de Oro Highway (jalan raya)
memang suatu hadiah besar bagi Mindanao. Tapi anda lihat
sendiri, jalan itu hanya melintasi daerah yang berpenduduk
mayoritas Katolik.
Saya pun belum puas. Saya mengirim petisi pada pemerintah
tentang keadaan sekarang. Banyak teman tak sabar. Mereka memilih
kembali ke gunung. Saya memaklumi itu. Tapi saya juga tak hanya
pandai mengirim petisi. Sekedar ilustrasi, dengarlah cerita ini:
Tahun 1972, saya tertangkap oleh tentara dan dipenjarakan di
Camp Crame (Manila). Setahun kemudian atas permohonan ulama
Islam Filipina, Marcos melepaskan saya. Bahkan Marcos mengangkat
saya jadi Wakil Walikota Marawy City . Celakanya, sebagai
pejabat saya melihat lebih jelas perlakuan kejam pihak militer
terhadap orang Islam. Jip dinas saya selalu mengangkut mayat
penduduk Islam yang tak bersalah, korban pembantaian militer.
Setahun kemudian saya lari lagi ke gunung .
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini