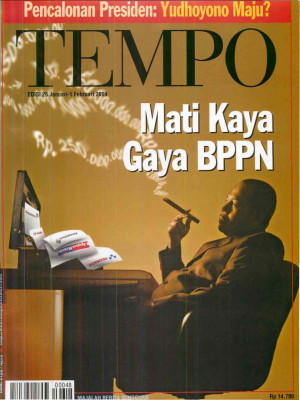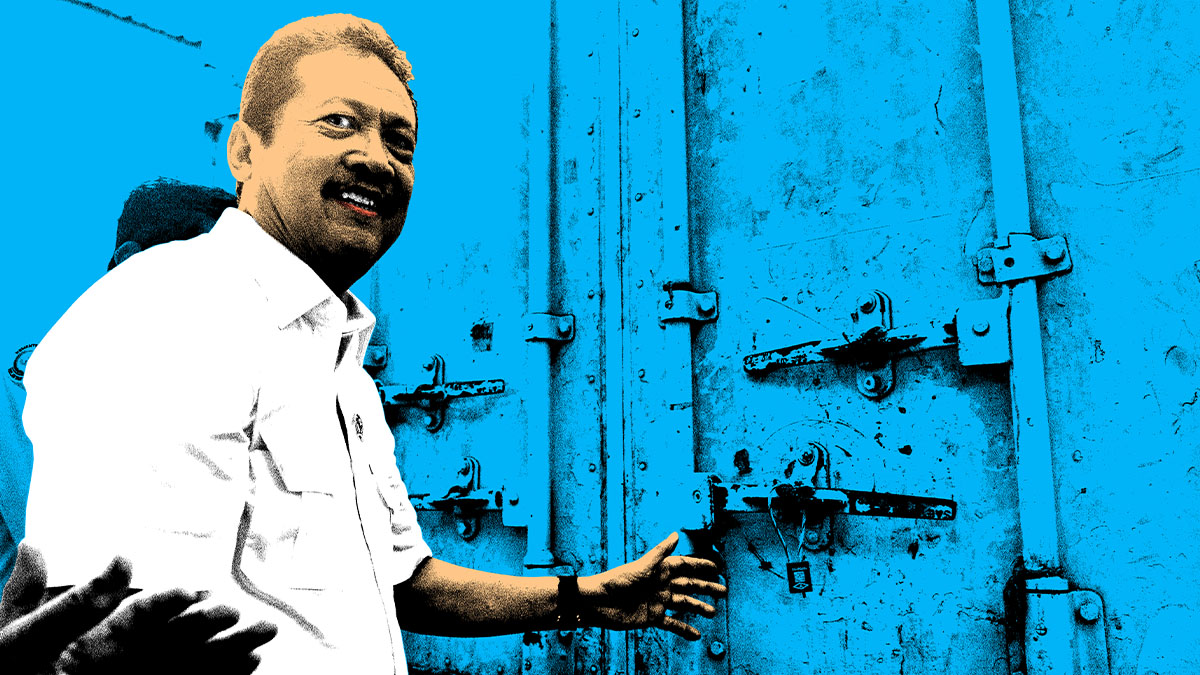Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hawa panas yang menyaput Gunung Kidul, Yogyakarta, tak membuat Presiden Megawati Soekarnoputri kegerahan. Dalam balutan baju batik cokelat bertangan panjang, Presiden duduk tenang di depan para menteri dan ratusan undangan yang sibuk mengipas-ngipas mengusir panas. Hari itu, Rabu pekan lalu, Megawati hadir di Gunung Kidul yang tandus itu untuk satu acara mulia: pencanangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Pemerintah bercita-cita menghutankan kembali 500 ribu hektare lahan kritis tahun ini, dan 3 juta hektare tahun depan. Anggarannya tak tanggung-tanggung, Rp 2 triliun—diambil dari dana reboisasi. Program ini—setidaknya begitulah niatnya—akan meliputi 21 daerah aliran sungai. Hutan Indonesia akan bersemi kembali. Tak ada lagi cerita banjir dan kekeringan. Semua tanah gundul kelak akan menjadi ijo royo-royo.
Satu hal, dalam acara itu tampaknya tak seorang pun mempertanyakan nasib lahan kritis terbesar di jagat ini, yakni kawasan gambut bekas megaproyek sawah sejuta hektare. Membentang antara Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan proyek lahan gambut (PLG) itu telah dinyatakan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) sebagai simbol kehancuran hutan tropis terbesar tahun 1995. Pasalnya, 1 juta hektare hutan habis dalam enam bulan.
Entah kenapa Menteri Kehutanan hari itu tak melaporkan perihal proyek tersebut, yang dahulu disokong penuh oleh, antara lain, Departemen Kehutanan. Seorang staf Direktorat Rehabilitasi Lahan di departemen tersebut mengatakan, lahan bekas proyek lahan gambut tidak masuk skema rehabilitasi itu hingga tahun depan. "Hutan rawa belum masuk prioritas," bisiknya kepada TEMPO. Padahal sebentar lagi presiden akan menerima rancangan baru yang disusun tim pemerintah—yang melibatkan pejabat dari tujuh departemen dan pakar dari beberapa universitas—untuk memulihkan kawasan tersebut, yang telah gagal disulap menjadi lumbung beras nasional.
Beginilah intisari rancangan baru itu. Tim Ad Hoc Pengembangan Eks Proyek Lahan Gambut akan menjadikan kawasan tersebut lahan terpadu. Di situ konservasi hutan, lahan perikanan, dan perkebunan akan menjadi satu. Cuma setengah dari sejuta hektare lahan yang dijadikan sawah. Sisanya? Dihutankan kembali. Ini baru teori di atas kertas. Bayangkan, untuk membuka lahan dan membuat saluran irigasi saja, anggaran negara bisa tandas hampir Rp 2 triliun.
Kendati angka-angkanya belum berwujud, ancar-ancar bujet rencana baru itu bisa empat kali proyek yang lama. Ketua Tim Ad Hoc Pengembangan, Ikhwanuddin Mawardi, dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga belum menyebut besaran nominal. Tapi ia membandingkan, proyek konservasi Departemen Kehutanan saja butuh Rp 100 juta-Rp 500 juta per hektare (lihat Mengayak Beras dengan Jala). Mari kita berhitung secara kasar: kalikan 500 ribu hektare dengan angka di atas. Jadinya, Rp 50 triliun-250 triliun. Bila itu terjadi, rekor anggaran terbesar untuk satu proyek di negeri ini akan pecah di lahan gambut.
Dalam hal perduitan, kali ini Bappenas menempuh prosedur pengajuan anggaran agak berbeda, yakni isian anggaran diserahkan langsung oleh departemen-departemen pelaksana proyek ke panitia anggaran di Departemen Keuangan—untuk seterusnya dimasukkan ke APBN. Tim Bappenas hanya memutuskan sampai tingkat volume pekerjaan. "Kita mulai dari minus, bukan nol," kata Menteri Permukiman, Soenarno (lihat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Soenarno: "Bukan Pemerintah yang Bilang Gagal").
Proyek gambut memang cerita agak lawas. Hikayat ini dimulai pada 1995, ketika Presiden Soeharto datang ke perkebunan milik PT Pulau Sambu di Riau. Dia terkesan melihat padi ternyata bisa tumbuh di tanah rawa. Padahal Soeharto tahu bahwa tanah di rawa tak cocok untuk padi karena terlalu asam. Puncak cerita, mantan Ketua Umum PSSI, Kardono, kemudian membawa bos Sambu, Tay Juhana, kepada Soeharto. Kelak, pertemuan itu membuat Soeharto mengambil keputusan ceroboh: mengubah 1 juta hektare hutan rawa bergambut menjadi sawah, tanpa memperhitungkan dampaknya.
Kepada TEMPO, mantan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan, Siswono Yudohusodo, menceritakan undangan Soeharto saat itu. "Kami langsung disodori peta lahan, lengkap dengan saluran irigasi yang ditarik lurus-lurus," kata Siswono. Teknik irigasi dalam peta itu, menurut alumni Institut Teknologi Bandung ini, tidak masuk akal. "Tak mungkin sungai itu kedalamannya sama sejauh ratusan kilometer," kata Siswono.
Apa daya, perintah tetaplah perintah.
Mantan Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, Suparmono, yang juga hadir saat itu, juga pernah berceritera kepada TEMPO begini. Soeharto, katanya, telah memutuskan proyek itu sebelum para menteri angkat bicara. Padahal sudah ada Keppres No. 24 Tahun 1992 yang ditetapkan sendiri oleh Soeharto, yang menyatakan ekosistem gambut sebagai kawasan lindung (lihat rubrik Investigasi Majalah TEMPO, 12 April 1999). Peta Kalimantan Tengah yang dibentangkan Soeharto menunjukkan, sebelum tujuh menteri itu menghadap, seseorang telah membantunya melukis khayalannya di atas kertas.
Kata Siswono, orang itu Tay Juhana. Dalam investigasi mingguan ini, pada April 1999, pihak Tay membantah menjadi biang keladi. Apa pun, khayalan itu lantas diwujudkan Soeharto dalam bentuk perintah mencetak sawah baru seluas sejuta hektare.
Dengan sejuta hektare sawah, tiap tahun Indonesia akan dilimpahi 1,5 juta ton beras. Lagi-lagi, itu teorinya. Menurut Siswono, para menteri mendukung gagasan pencetakan sawah baru karena dapat meniadakan impor beras dan menyelesaikan masalah petani tanpa lahan di Pulau Jawa dan petani berlahan sempit di Kalimantan. "Kami semua khawatir dengan impor beras yang tinggi," tuturnya.
Sejatinya, mimpi Soeharto tak sepenuhnya khayalan. Menurut catatan Siswono, sejak tahun 1960-an Indonesia sudah berhasil membuka sawah di lahan gambut seluas 1,1 juta hektare. Lokasinya tersebar di delapan provinsi. Tetapi tak ada yang lebih luas dari 40 ribu hektare. Dalam beberapa rapat koordinasi proyek lahan gambut di Bappenas, banyak menteri mempertanyakan kelayakan proyek itu, terutama dari segi pelaksanaan teknik konstruksinya. Namun, "Suasana politis waktu itu tak mungkin menentang Pak Harto," Siswono melanjutkan.
Yang terjadi kemudian adalah tragedy of common. Investigasi TEMPO pada 1999-2001 mencatat kerusakan spektakuler di bidang ekosistem, pemiskinan penduduk secara finansial dan sosial. Orang Dayak berhenti menyokong tradisi perladangan berpindah karena hutannya telah dibabat. Mereka tak bisa bertanam dengan metode yang dibawa petani dari Jawa, karena perubahan musim tak lagi mereka akrabi. "Kami tak bisa lagi membaca musim saat bertanam," kata Yolanda Kenan, orang Dayak dari Dadahup.
Rupanya, kerusakan hutan telah mengacaukan pengetahuan mereka tentang regenerasi ladang di dalam hutan. Belasan ribu transmigran terlunta-lunta (lihat Berkaca pada Air Bah). Sumber daya alam hancur. Hutan tropis basah yang bergambut tebal itu telah dibuka paksa tanpa penelitian terlebih dahulu. Bahkan pekerjaan konstruksi kanal sudah dimulai enam bulan sebelum dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek itu dikerjakan. Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993, dilarang mengerjakan proyek tanpa menyelesaikan dokumen amdal lebih dulu.
Soal lain, untuk mengolah lahan seluas 10 ribu km persegi atau hampir seperempat kali luas Jawa Barat, perlu puluhan ribu manusia. Maka, pontang-pantinglah Siswono—saat itu menjabat Menteri Transmigrasi—mencari transmigran. Siswono mengkalkulasi, areal itu bisa menampung sekitar satu juta orang.
Dalam hitungan bulan, ribuan orang telah menempati satu petak rumah sederhana berdinding kayu, mendapat lahan dua hektare. Untuk penghidupan sehari-hari, mereka disuplai beras, garam, dan kacang-kacangan. Juga kapur untuk menetralkan keasaman tanahnya. Lalu, tibalah hari besar itu: kunjungan Soeharto ke Desa Dadahup dan Lamunti di tepi Sungai Kapuas Hilir.
Di situ, Soeharto melihat dengan mata kepala sendiri padi impiannya sudah tumbuh subur di proyek lahan gambut. Juga tanaman budidaya lain macam pepaya dan ketela pohon. Tentu saja tak ada yang berani berceritera kepada Soeharto bahwa malam sebelumnya orang-orang dari pemda setempat sibuk menanami sawah itu dengan padi yang sudah siap diketam.
Bak menggantang asap, mimpi itu berakhir ketika musim hujan yang pertama tiba. Padi hanya bisa tumbuh pada beberapa hektare saja, tapi itu pun habis ditelan banjir. Usai air bah, giliran tikus dan ular menyerang sisa-sisa beras impian penguasa Orde Baru itu. Musim tanam kedua lebih parah, karena hasil panen padi makin sedikit. Rumah-rumah pun terendam saat banjir karena luapan Sungai Kapuas yang masuk lewat kanal. Tragedi itu berlanjut sampai hari ini—TEMPO menyaksikannya pada Desember silam hingga pekan lalu.
Memang ada klaim bahwa di desa tertentu macam Dadahup padi bisa tumbuh subur. Tapi penduduk setempat tidak heran, karena daerah itu memang penghasil padi jauh sebelum lahirnya proyek tersebut. Lahan yang ditanami padi di dalam proyek lahan gambut akhirnya cuma kurang dari 50 ribu hektare. Sisanya ditanami buah-buahan atau ditinggalkan penduduk yang menebang kayu sebagai nafkah.
Ketika tiba-tiba kekuasaan Soeharto diakhiri secara paksa pada Mei 1998, proyek lahan gambut ikut menjadi obyek penderita. Setahun berikutnya, Habibie naik takhta sebagai presiden. Lewat Keppres No. 80 Tahun 1999, ia meminta proyek itu dievaluasi dan sisa dananya dikembalikan ke APBN. Keputusan ini membuka pintu kiamat kecil berikutnya di lahan gambut. Tak satu pun departemen atau para menterinya merasa bertanggung jawab lagi di proyek gambut. Proyek itu ditinggalkan, bersama para transmigran yang masih terlunta-lunta sampai sekarang.
Megaproyek sawah sejuta hektare itu menjadi tragedi lingkungan terbesar sejagat karena menghancurkan sejuta hektare kawasan hutan di satu lokasi hanya dalam waktu enam bulan. Lembaga konservasi internasional, IUCN, menetapkan belum pernah ada di atas jagat ini kerusakan yang sedemikian luas di dalam satu lokasi yang unik seperti lahan gambut. "Proyek ini seharusnya memakai pendekatan ilmiah, tapi dimulai dengan pendekatan politis," kata mantan Kepala Pusat Riset Gambut Tropika BPPT, Bambang Setiadi, kepada TEMPO ketika itu.
Toh, proyek lahan gambut ternyata belum tamat. Setidaknya, menurut tim dari Institut Pertanian Bogor yang menyusun dokumen amdal proyek itu pada tahun 1997, lahan gambut tetap bisa dijadikan sawah. Cuma, luasnya tak lebih dari 300 ribu hektare atau sekitar 30 persen. Tahun 2002 lalu, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo, membentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek Lahan Gambut. Menurut Ketua Tim, Ikhwanuddin Mawardi, mereka mulai bekerja pada Agustus 2003 dengan anggaran dari Departemen Kehutanan.
Mereka mengaku sudah melakukan studi terhadap semua dokumen proyek lahan gambut, mencari kesalahan proyek itu, dan memberikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Megawati beberapa minggu mendatang.
Direktur Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial pada Departemen Kehutanan, I Nyoman Yuliarsana, menjelaskan rekomendasi departemennya. Mereka meminta seluruh kawasan gambut di hulu Sungai Mengkatip dan Mentangai dijadikan kawasan konservasi. Semua saluran irigasi yang berdampak negatif bagi proyek lahan gambut harus ditutup.
Nyoman juga meminta agar dana untuk semua program di eks PLG itu tidak terlambat datangnya. Mereka telah merancang proyek percontohan berupa demonstrasi plot untuk penanaman spesies seluas 500 hektare, dari sekitar 60 ribu hektare rencana untuk merehabilitasi lahan kritis di situ. Sampai tahun 2002, departemen ini sudah menanam hampir 2 juta batang bibit rotan, purun, gelam, jelutung, mahoni, tumeh, dan aneka buah-buahan.
Lain lagi rencana Departemen Permukiman. Mereka akan membangun sekolah tambahan dan transportasi lewat air (lihat infografik, Petualangan dari Masa ke Masa). Dan Departemen Transmigrasi akan memindahkan transmigran dari lahan yang terkena banjir serta membujuk calon transmigran baru dengan insentif tertentu. Sayangnya, tak ada detail bagaimana rencana itu akan dijalankan—termasuk detail soal anggaran.
Di sebelah utara, persis berbatasan dengan megaproyek itu, masyarakat setempat tengah mati-matian mempertahankan ekosistem Air Hitam yang unik dan dilindungi di seluruh dunia. Ini barangkali sejumput hiburan di tengah kisah-kisah yang memilukan dari Kalimantan (lihat Belajar dari Air Hitam). Kisah Air Hitam adalah pesan gamblang tentang penyelamatan lingkungan yang mampu dikerjakan oleh penduduk lokal; pelajaran yang telak bagi siapa pun yang membedah lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di masa yang sudah dan di masa yang nanti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo