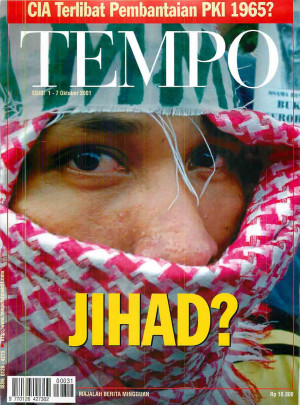SENJA mulai turun ketika perairan di sekitar Pulau Moro, yang tak lagi biru, beriak kemerahan diterpa sinar matahari yang siap menyelam. Tidak ada gelombang besar memecah bibir pantai, tiupan angin pun sepoi-sepoi. Inilah saatnya, Agustus-November, nelayan memanen ikan. Tapi itu dulu. Dua tahun lalu, ahoi, nelayan benar-benar dimanjakan oleh laut: ikan dan udang mudah dijaring.
"Dulu, pada musim panen, kami bisa mendapatkan Rp 2 juta semalaman melaut," kata Misnan, 36 tahun, nelayan asli Moro. Ikan tangkapan biasanya dijual tengkulak ke Singapura. Sekarang, penghasilan Rp 100 ribu saja mustahil.
Kini tiada lagi dorongan bagi nelayan Kabupaten Karimun, Riau Kepulauan, memacu perahu pompongnya ke laut untuk menebar jala atau melempar mata pancing. Serombongan nelayan hanya terlihat duduk-duduk santai di kedai kopi milik seorang "toke Cina".
"Laut kami sudah habis," kata M. Ali dengan geram. Nelayan tradisional ini kini menganggur, sedangkan Misnan menjadi tukang becak. Memang, nasib nelayan Moro sama ironisnya dengan warga Riau lainnya: "mati" di tengah kekayaan alam yang melimpah.
Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun berada di tenggara Kota Tanjung Balai Karimun. Dengan feri antarpulau, Moro hanya sekitar satu jam pelayaran dari Tanjung Balai Karimun, atau dua setengah jam berlayar dari Batam. Berjumlah sekitar 3.000 jiwa, penduduknya mendiami belasan pulau, dengan jumlah terbesar di Pulau Moro.
"Moro merupakan daerah yang pasirnya paling banyak ditambang, baik pasir laut maupun pasir darat," kata Rina Dwi Lestari, anggota Komisi IV DPRD II Karimun. Ketika memasuki kawasan Pulau Moro dengan feri Marina, TEMPO menyaksikan dataran rendah dan perbukitan Pulau Moro yang terkelupas atau terpapas. Di tepi pantai, pasir berwarna putih kemerahan ditumpuk dalam puluhan gundukan, yang menunggu diangkut dengan tug boat ke Singapura. "Di laut dan di darat kami habis," desah Miswandi, anggota DPRD Karimun asal Moro, lirih.
Keadaan serupa juga terlihat di tempat-tempat penambangan pasir lainnya di seluruh Kepulauan Riau. "Di Kabupaten Karimun, khususnya di Pulau Moro, Parit adalah yang paling rusak lingkungan lautnya," kata Rully Sumanda, Direktur LSM Kalitra Sumatra, yang giat meneliti dampak buruk penambangan pasir laut.
Bencana itu bermula ketika PT Equator Reka Citra mulai menambang pasir di daerah itu. Saham perusahaan dimiliki pengusaha asal Bandung, Jhony Rosadi. Kapal-kapal penyedot pasir perusahaan ini mulai menjelajahi perairan Moro sekitar tahun 1990. Di pulau-pulau dengan selat-selat yang sempit, sedikitnya beroperasi tujuh perusahaan: Equator, Nalendra Bakti Persada, Sangkala, Sindika, Anak Watan Karimun, dan Mantap Tatalaksana.
Saking rakusnya, kapal-kapal keruk bahkan seperti sengaja mengeduk pasir malam hari di kawasan bibir pantai. Padahal, peraturan daerah pertambangan Kabupaten Karimun jelas-jelas mengatur batas pengerukan pasir maksimal dua mil laut dari garis pantai. Akibatnya, air laut di sekitar Moro menjadi cokelat karena bercampur lumpur. Baunya pun menyengat.
Bayangkan, pipa penyedot berdiameter sekitar satu meter mengisap apa saja dari dasar laut. Akibatnya, jaring gombang dan jaring tenggiri, yang dipasang nelayan di pinggir pantai, juga ikut terisap ke perut kapal. Lebih celaka, akibat terus-menerus dikeruk, beberapa pulau kecil di antara Pulau Moro dan Pulau Kundur lenyap dari permukaan. Padahal, pulau-pulau itu tempat bernaung para nelayan dari serangan badai.
Lumpur-lumpur itu juga menutupi terumbu karang dan membinasakan plankton yang menjadi pakan ikan. "Bagaimana ikan mau hidup di laut yang sudah tercemar dan miskin makanan," ujar Prof. Dr. Adnan Kasry, pakar kelautan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Pekanbaru.
Lenyapnya sejumlah pulau memang nyata. Ada tempat-tempat yang menandakan "sisa-sisa" pulau yang mencuat ke permukaan. Di satu lokasi, terlihat sebatang pohon mencuat dari bawah laut—yang tumbuh di Pulau Karang yang hampir tenggelam. Padahal, di pulau yang cukup luas itu ada banyak tumbuhan dan pohon.
Keresahan nelayan diabaikan pejabat setempat. Untuk dimintai konfirmasi saja, Bupati Karimun Muhammad Sani selalu berusaha menghindari TEMPO. Padahal, setiap hari ada saja pengaduan nelayan ke DPRD Karimun di Tanjung Balai. Gubernur Riau Saleh Djasit pun setali tiga uang. "Berapa, sih, yang protes dari 400 ribu nelayan Riau?" ucapnya dengan nada menyepelekan.
Meski belum ada protes langsung ke Gubernur, hampir setiap hari tiga DPRD di Kepulauan Riau dibanjiri pengaduan. "Kebanyakan tuntutannya soal dana community development (CD)," kata Rina. Dana CD adalah uang dari pengusaha penambang yang diberikan kepada warga sebagai ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan.
LSM Kalitra sempat mengendus adanya konflik antara warga dan perangkat desa di beberapa kecamatan di Karimun. Di Desa Pauh di Pulau Moro, warga desa terbelah dua, antara pendukung kepala desa dan penyokong sekretaris desa. Juga di Pulau Parit. Masalahnya, ada kecurigaan terjadinya penggelapan dana CD oleh kepala desa.
Ada juga perusahaan yang memberikan dana CD langsung ke warga. Pada 1999 PT Equator menyerahkan bantuan Rp 1 miliar kepada warga Moro. "Itulah pertama kali saya melihat uang sebanyak satu becak," kata Misnan. Pada saat penyerahan dana tersebut, seluruh aparat pemerintahan hadir. Ada camat, Kapolsek, dan wakil dari TNI AL.
Dari jumlah tersebut, setiap kepala keluarga kebagian Rp 4 juta. Itulah yang digunakan Misnan, misalnya, untuk beralih profesi menjadi tukang becak. Merasa sudah patah arang dengan laut, katanya, "Saya membeli 12 becak dengan uang CD." Yang lainnya membeli mesin tempel berkekuatan 2 PK untuk perahu pompongnya. "Lumayan, kami bisa melaut agak ke tengah," ujar nelayan Sholeh.
Inilah awal tragedi. Warga mulai bergantung pada CD, padahal tidak setiap bulan perusahaan bersangkutan mencairkannya—bahkan ada yang ingkar janji. Warga pun gusar. Puncak kemarahan warga terlampiaskan dengan menyandera kapal KM Nile River milik PT Nalendra, yang sedang beroperasi di Selat Durian.
Saat kejadian, Oktober tahun lalu, Nalendra sudah beroperasi setahun lebih di perairan Moro. Warga pun memaksa awak kapal, yang semuanya "bule", agar merapatkan kapal di depan Kantor Kecamatan. Pagi hari, 26 Oktober 2000, warga Moro tua dan muda berbondong-bondong menyaksikan kapal sangat besar itu—yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Anak-anak dan pemuda bahkan menaiki kapal setinggi lebih dari 15 meter itu.
Tetapi, menjelang siang, giliran penguasa dan pemilik kapal menjadi geram menyaksikan puluhan warga berkeliaran di kapal. Awak kapal pun menembakkan pistol isyarat ke arah warga yang berada di geladak. Alasannya, seperti tersebut dalam laporan polisi, warga telah merusak peralatan organik kapal. Timbullah kepanikan. Puluhan warga lari tunggang-langgang, bahkan ada yang mencebur ke laut. Mengantisipasi keadaan yang lebih buruk, Nalendra kabur dalam kecepatan penuh. Dalam catatan Polsek Moro, ada 12 warga luka-luka. Seorang lainnya, Bakar bin Ali, 36 tahun, tewas di tempat kejadian.
Kegusaran warga pun memuncak. Mereka kemudian melampiaskan emosinya dengan merusak Kantor Kecamatan, Polsek, Pos TNI AL, Kantor Syahbandar, dan Kantor Pembantu Bea & Cukai. Kekacauan itu sebenarnya bisa cepat ditanggulangi jika camat dan kepala desa segera datang begitu peristiwa muncul. "Mereka hanya datang jika ada uang. Tetapi, ketika ada masalah, tak seorang pun muncul," ujar Misnan.
Kedamaian Moro lalu beralih rusuh. Sekitar 100 anggota satuan polisi perairan, Marinir, dan Pasukan Khas Angkatan Udara diterjunkan ke Moro. "Itu untuk berjaga-jaga dari emosi warga," kata Inspektur Polisi Satu Kudri, Kapolsek Moro. Untung, dapat segara tercapai kesepakatan antara warga dan aparat: penduduk setempat menolak penambangan pasir di wilayahnya.
Namun, dendam tak mudah redam, walaupun kabarnya PT Nalendra telah menyantuni Ny. Mar, janda almarhum Bakar, yang tewas. Pihak Nalendra tidak ada yang bisa dikonfirmasi. "Bos tidak ada di tempat," kata Purba, seorang stafnya.
Santunan tak selalu membantu. "Bagaimanapun, nyawa tidak bisa diganti dengan uang, berapa pun," kata Rahman, kakak ipar almarhum. Yang penting, kejadian serupa tidak terulang—dan dapat menjadi ranjau di perairan Riau.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini