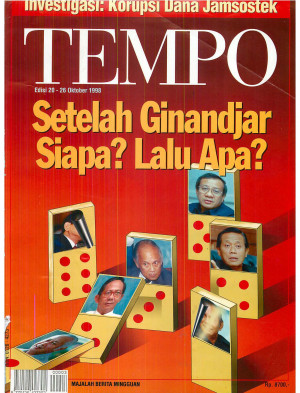Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tempat tinggal mereka rata-rata terbuat dari kardus dan tripleks, menempel di pagar rel maupun di tanah kosong di antara rel. Dari segi ukuran, kediaman itu lebih tepat disebut rumah-rumahan: lebar sekitar 2 x 2 meter, tinggi 1,5 meter. Mirip kandang ayam di kampung. Orang praktis harus menunduk saat masuk maupun saat berada di dalam rumah. Salah satu "kotak kardus" itu berisi ranjang reot dari besi. Di atasnya, penuh tumpukan baju kotor dan piring bekas makan. Sebuah kompor minyak tanah dipepetkan ke ranjang, berdesakan dengan ember, panci, dan tetek-bengek lain.
Di rumah yang lain, suasana tak jauh berbeda. Hanya, lebih ramai. Beberapa pria bertampang sangar sedang sibuk main gaple. Sedangkan ibu-ibu mengobrol sembari memasak bubur merah putih. "Untuk syukuran tujuh hari orok salah satu warga di sini," ujar salah seorang ibu sembari mengaduk bubur. Orok yang dimaksud sedang terlelap dalam kurung bayi, di samping bubur yang sedang mendidih. Hawa panas dan pengap. Namun, bayi merah yang dibedong dengan kain-kain tua itu terlihat begitu nyenyak dan damai dalam tidur.
Hari beranjak lohor. Ruang tempat sang orok tidur kian ramai. Kamar seluas 1,5 x 4 meter itu dipenuhi 10 ibu yang sedang meriung, ditambah sekitar 10 balita yang berseliweran di ruang itu. Percakapan berlangsung dalam suara riuh. Topiknya khas ibu-ibu: soal anak. "Anak ini saya bawa dari kampung. Terpaksa berhenti sekolah karena mau masuk sekolah di sini, tahun ajarannya masih lama," ujar Yeti, ibu setengah umur sambil mengelus sayang kepala putrinya.
Di luar perkara kumuh dan bau, suasana keakraban keluarga sangat kental terasa di tempat itu. Jauh dari kesan para ibu yang siap menjual anak, begitulah selentingan yang sampai ke telinga TEMPO. Tak heran, tatkala Atikah, 40 tahun, mampir ke gubuk itu, ibu-ibu di ruangan itu langsung menyindir beramai-ramai, "Anak kok dijual-jual," ujar mereka. Tuduhan itu bukannya tak bersumber. Sekitar tujuh bulan lalu, perempuan itu menyerahkan anaknya ke orang lain.
Atikah kontan menangkis tuduhan itu. "Saya tidak sekali-kali menjual anak. Saya serahkan anak itu kepada orang yang lebih mampu merawatnya. Kalau saya jual anak, saya sudah tanda tangan surat bersegel," teriaknya mengatasi hingar-bingar percapakan.
Atikah hanya salah satu prototipe keluarga pemulung yang bisa ditemukan dalam kehidupan di sepanjang rel itu: sekali waktu menetap di bantaran, lain waktu pindah ke areal "alam terbuka" lainnya. Dari Kabelan misalnya, Atikah pindah bersama Pendi, 50 tahun, suaminya, ke sebuah taman mungil di pojok Jalan Gunung Sahari dan Budi Utomo, Jakarta Pusat. "Hujan maupun panas, kami tetap di sini," ujar Pendi kepada TEMPO. Sesekali, mereka tidur di emperan Apotik Vetry, Jakarta Pusat.
Dalam usianya yang ke-40, Atikah telah mencatat prestasi luar biasa sebagai seorang wanita: melahirkan 12 anak. Dari suami pertama, Slamet, wanita bertubuh kecil dan kurus ini melahirkan sembilan anak. Dua meninggal, tinggal tujuh. Dari Pendi, suami kedua, wanita ini memperoleh tiga anak. Dua anak sudah meninggal. Dari sepuluh yang tersisa, tak satu pun hidup bersama Atikah dan Pendi.
Lantas, ke mana saja mereka? Lima anak dirawat di Yayasan Aulia,Yogyakarta. Satu anak diurus oleh Yayasan Aulia Jakarta. Eddy Hidayat dari Yayasan Aulia membenarkan hal itu. "Ibu Atikah menghubungi kami, meminta bantuan untuk merawat bayinya," ujarnya per telepon. Satu lagi diberikan ke "orang Kebayoran." Satu anak tinggal bersama ibu tiri Atikah. Sedangkan tiga anaknya saat bersuami Pendi juga sudah "dipergikan". Dua anak diasuhYayasan Aulia, Yogyakarta. Satu lagi diberikan ke "orang Kebayoran."
Malah, yang terakhir "diijon" tatkala kandungannya berusia delapan bulan. Kendati begitu, ibu selusin anak ini bersikeras tak mendapat uang dari mereka. "Saya hanya dikasih uang jamu cepek (Rp 100.000)," tuturnya. Wanita berkulit gelap ini menambahkan, di luar uang jamu, orang Kebayoran itu membayar biaya persalinan Rp 450.000. Bayinya pun diambil langsung dari rumah sakit.
Karena itu, Atikah keberatan disebut menjual bayinya. "Kan saya udah bilang. Saya tidak tanda tangan surat bersegel. Jadi, saya tidak jual anak," sahutnya sambil bertopang dagu. Jika begitu, untuk apa ia melahirkan begitu banyak anak? "Saya sudah ikut KB (Keluarga Berencana), tapi kebobolan terus. Jadi, waktu anak itu lahir, dan saya serahkan sama orang mampu, itu demi masa depan anak-anak itu. Saya sudah siap untuk tidak ketemu mereka lagi. Biar hidup mereka lebih enak," ujarnya. Lalu ia menyambung, "Sekarang, saya sudah ditekuk (tubektomi)," ujarnya malu-malu.
Kisah dari bantaran rel tidak hanya memperlihatkan kemudahan seorang ibu "mentransfer" anaknya ke pihak lain. Pernikahan muda usia dan tingkat kematian anak yang tinggi juga mewarnai kehidupan sehari-hari.
Adalah Wati, 49 tahun, pemukim di kawasan Gaplok, Jakarta Pusat, melahirkan anaknya yang ke-13 pada 11 Oktober lalu. Dari belasan anak itu, cuma enam yang bertahan hidup. Ia menikah pada umur 12 tahun, lalu melahirkan anak pertama pada umur 13 tahun. Suaminya pergi dari rumah menjelang kelahiran bayinya. "Saya tidak peduli lagi sama dia," ujarnya tenang-tenang. Lalu, "Terserah kalau dia mau punya istri lagi."
Dalam hal anak, prinsip Wati jelas: pantang menjual. Ia juga tak mau menyerahkan anaknya kepada orang lain, kecuali saudara. "Tapi kalau ada yang melakukannya untuk dirawat, saya tidak anti," ujar Wati pelan. Ia lalu mencontohkan seorang wanita di Sunter, sebut saja namanya Butet, yang hendak pulang kampung ke Sumatra. Ia meminta bantuan Wati agar dicarikan "orang baik-baik dan mampu diserahi bayinya". "Masa, bayi itu mau diserahkan kepada orang macam kita. Jangan-jangan nanti malah buat kerja," komentar Wati.
Ada lagi teman Wati lainnya, Aminah (bukan nama sebenarnya) melepas anaknya dengan harga tunai Rp 300.000. Transaksi itu berlangsung resmi, di atas kertas bersegel. "Aminah menyesal dan stres sampai sekarang karena kehilangan anak," Wati menjelaskan.
Agak jauh dari Senen, masih di kawasan rel, di daerah Pramuka, Jakarta Timur, hiduplah Sri Amti, 37 tahun. Seperti rekan-rekannya di bantaran Senen, Sri juga merupakan potret suram seorang ibu. Pekerjaan sehari-harinya mengelap kaca mobil yang lewat di Pramuka. "Kalau mujur, sehari bisa dapat Rp 7.000 - Rp 8.000," ujarnya kepada TEMPO. Suaminya seorang penganggur yang benar-benar tak punya penghasilan. Karena itu, Sri tak punya pilihan lain kecuali "turun gelanggang" ditemani Puji Prihatin, bayinya yang berusia empat bulan.
Ketika ditemui TEMPO di Pramuka, kondisi bayi itu memprihatinkan. Badannya panas dan rewel terus-menerus. Bibir atas Puji sumbing cukup besar. Saat menyusu, tetesan ASI (air susu ibu) berceceran ke mukanya, mengalir dari bibirnya yang sumbing. Sri bukan tidak tahu penderitaan Puji. Namun, "Lebih baik ia sakit karena lebih mudah merebut belas kasihan orang," ujar ibu delapan anak ini. Sri mengaku, pernah menerima obat dari sebuah yayasan sosial. Namun, ia enggan memberikannya kepada Puji. "Karena itu tadi, bila bayi saya sehat, penghasilan akan lebih kecil," papar wanita asal Boyolali yang mengaku sangat lelah dengan cara hidup begini.
Kisah-kisah singkat dari bantaran rel ini ibarat potret hitam putih kaum tak berpunya yang bisa kita temukan di mana pun: gelap, muram, keras. Mereka bahkan tak berani bermimpi tentang masa depan. "Saya enggak pernah mikir cita-cita. Yang penting ada makan hari ini, buat anak saya," ujar Sri.
Toh kepahitan hidup tak selalu memupuskan kegembiraan. Itu bisa dilihat, setidaknya, tatkala mereka asyik mengaduk bubur merah putih untuk "menujuh hari" seorang bayi. Di sana, seolah ada rasa syukur kepada kehidupan. Yang paling getir sekalipun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo