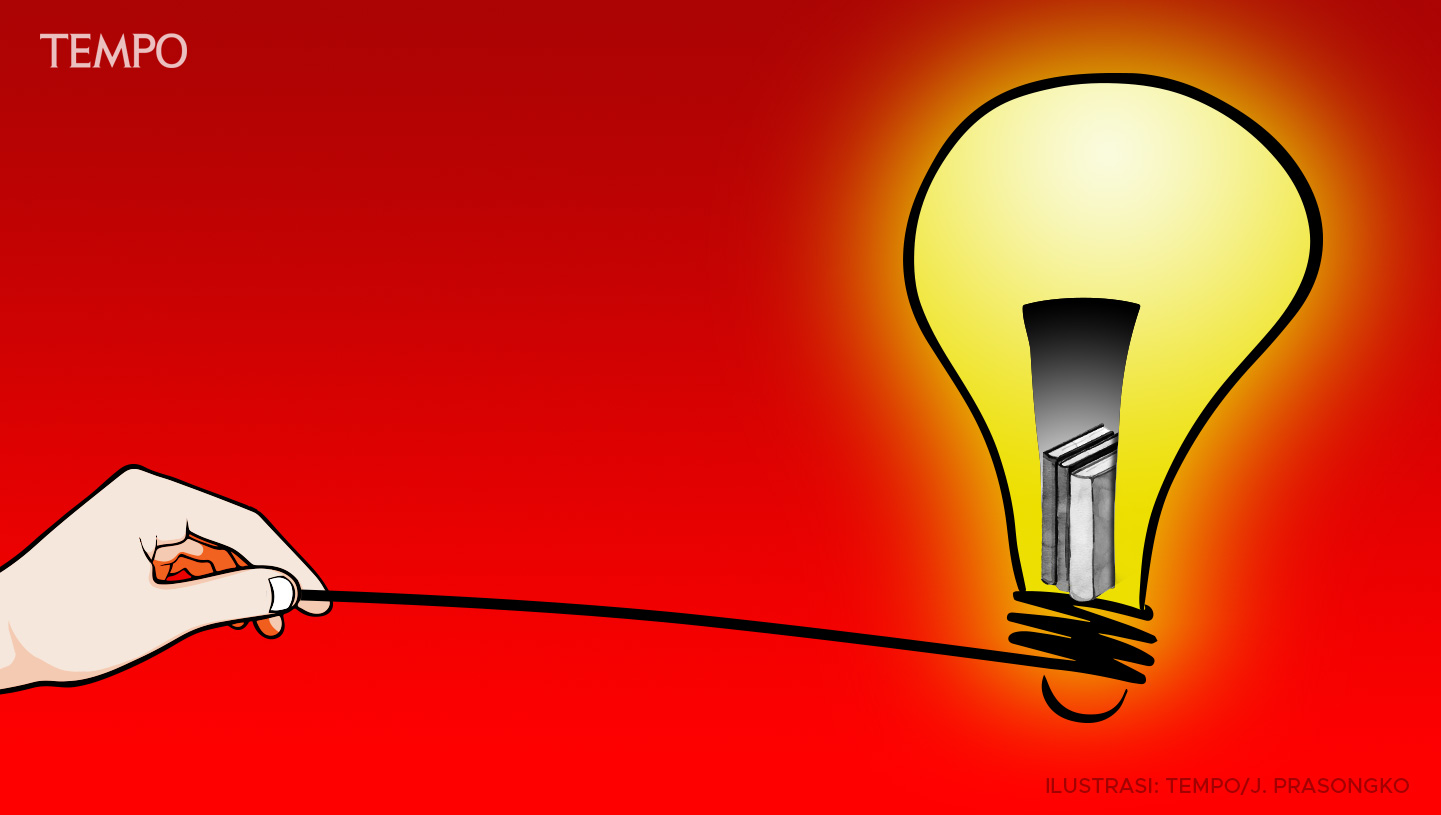Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DALAM gelar wicara literasi di stasiun radio K-Lite, Bandung, jurnalis senior Adi Raksanegara menyebutkan bahwa majalah lawas Aktuil pernah mempopulerkan kata “blantika”. Saya tidak tahu dari bahasa apa kata tersebut dipungut. Setahu saya, kata “blantika” bermakna dunia atau jagat dan biasanya digunakan di kalangan musik, misalnya pada frasa blantika musik Indonesia. Sayang, Kang Adi pun tidak tahu asal kata tersebut. Yang jelas, pada gelar wicara Komunitas Bilik Literasi (Bee-Lit) itu, dua narasumber—Adi Raksanegara dan Kin Sanubary—menceritakan kreativitas pers baheula.
Seusai gelar wicara itu, masih ada yang mengganjal dalam pikiran saya. Dari manakah kata “blantika” berasal? Apakah dari bahasa asing? Belanda? Inggris? Italia? Rasa penasaran itu saya sampaikan kepada Kin Sanubary, sang kolektor media lawas dan pemerhati media. Di media sosial Facebook, Kin punya banyak teman artis ataupun jurnalis senior, termasuk di antaranya Kang Odang Danaatmadja, salah seorang penggawa Aktuil.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo