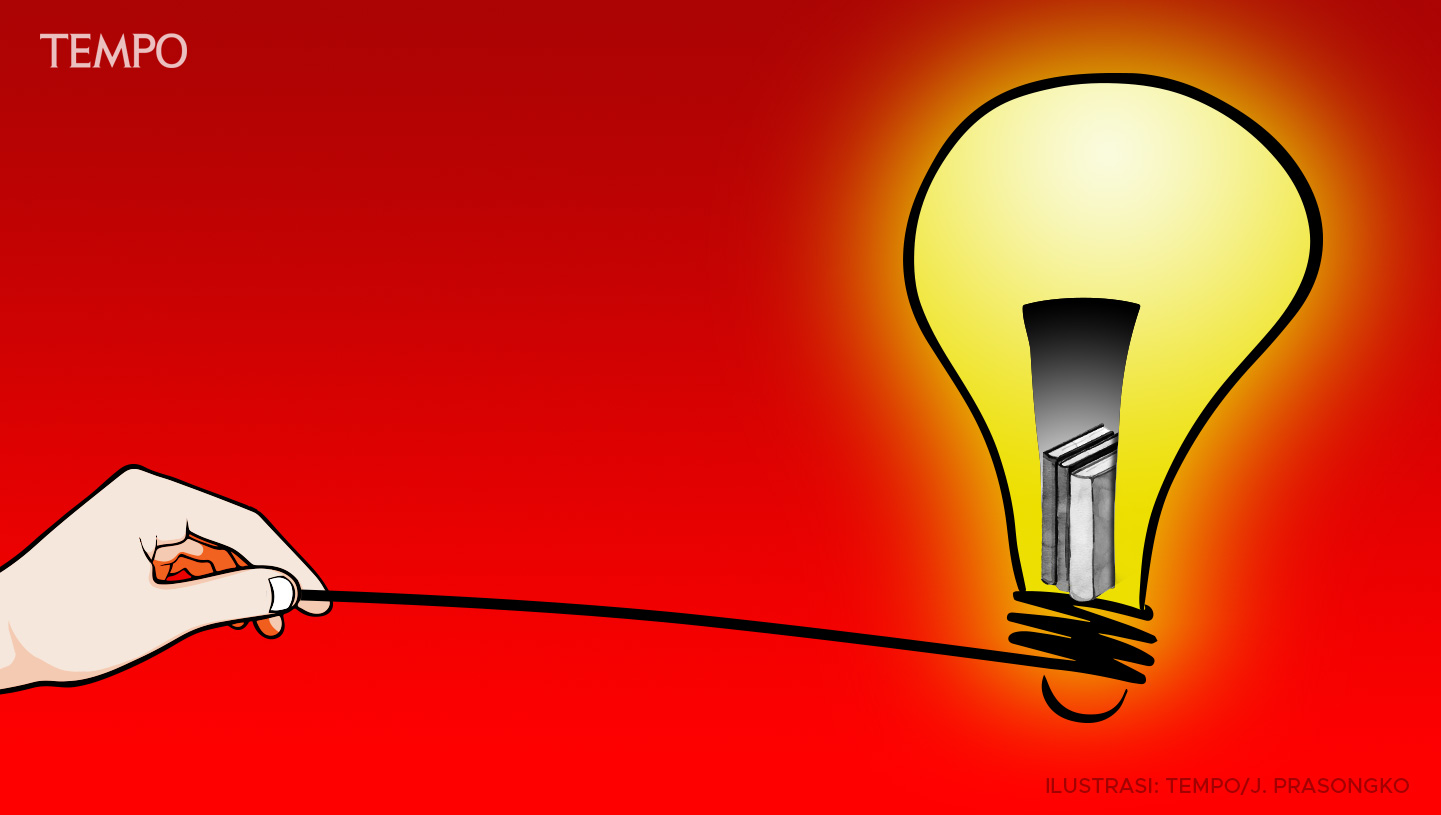Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

ALIH-alih mengedepankan dialog untuk menciptakan perdamaian di Papua, pemerintah malah memberangus kebebasan bersuara. Awal Juni lalu, tujuh orang Papua dituntut 5-17 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Mereka terlibat unjuk rasa yang berakhir rusuh pada Agustus 2019. Protes itu merupakan reaksi atas tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya menjelang peringatan hari kemerdekaan. Jaksa menuding mereka melakukan makar—tuduhan salah kaprah yang menempatkan mereka sebagai musuh negara.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo