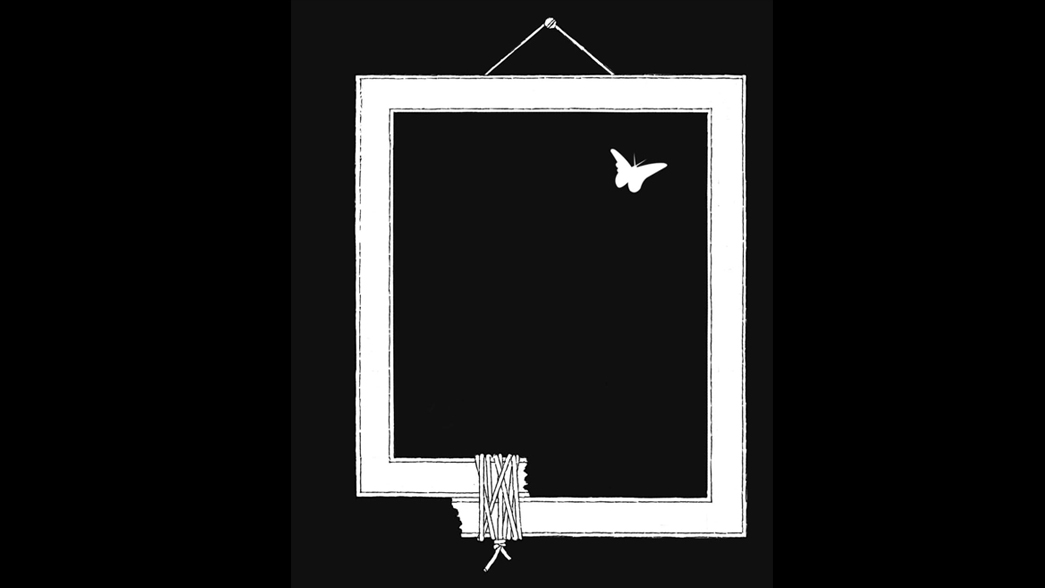Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen still
So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans
Holding me closer 'til our eyes meet
You won't ever be alone, wait for me to come home
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Fotografi"