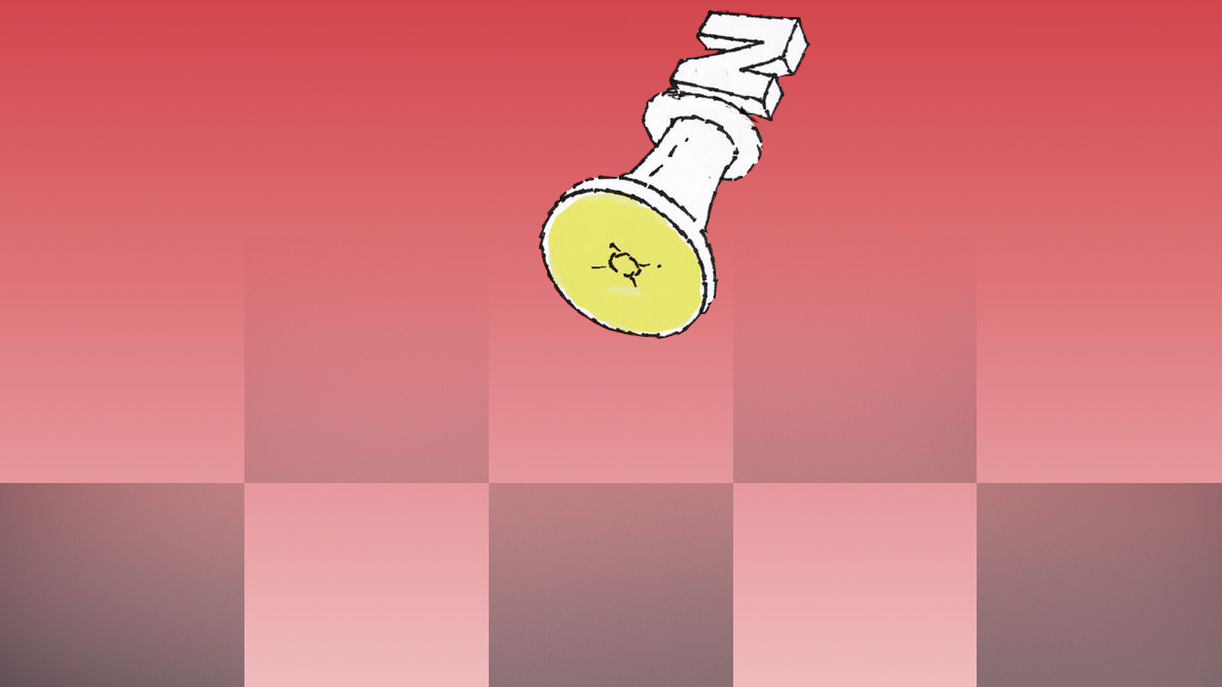Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

MAJALAH Tempo dan beberapa koran berulang kali mengulas laporan Badan Pusat Statistik yang menyebut 9,89 juta penduduk berusia 15-24 tahun, yang dikenal sebagai Gen Z, hidup tanpa kegiatan produktif alias menganggur. Presiden Joko Widodo pernah mengangkat tujuh orang staf khusus milenial dengan alasan agar program khas pemerintah untuk generasi muda bisa muncul. Perusahaan unicorn, yang sempat jadi isu penting di tahun 2019, jadi tagline kala itu. Untuk itu dirintislah begitu banyak bisnis rintisan. Startup.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo