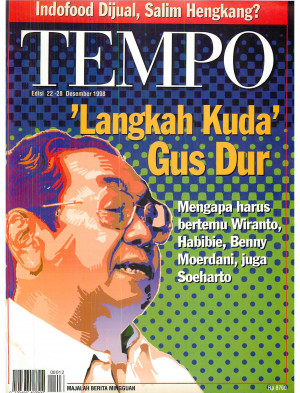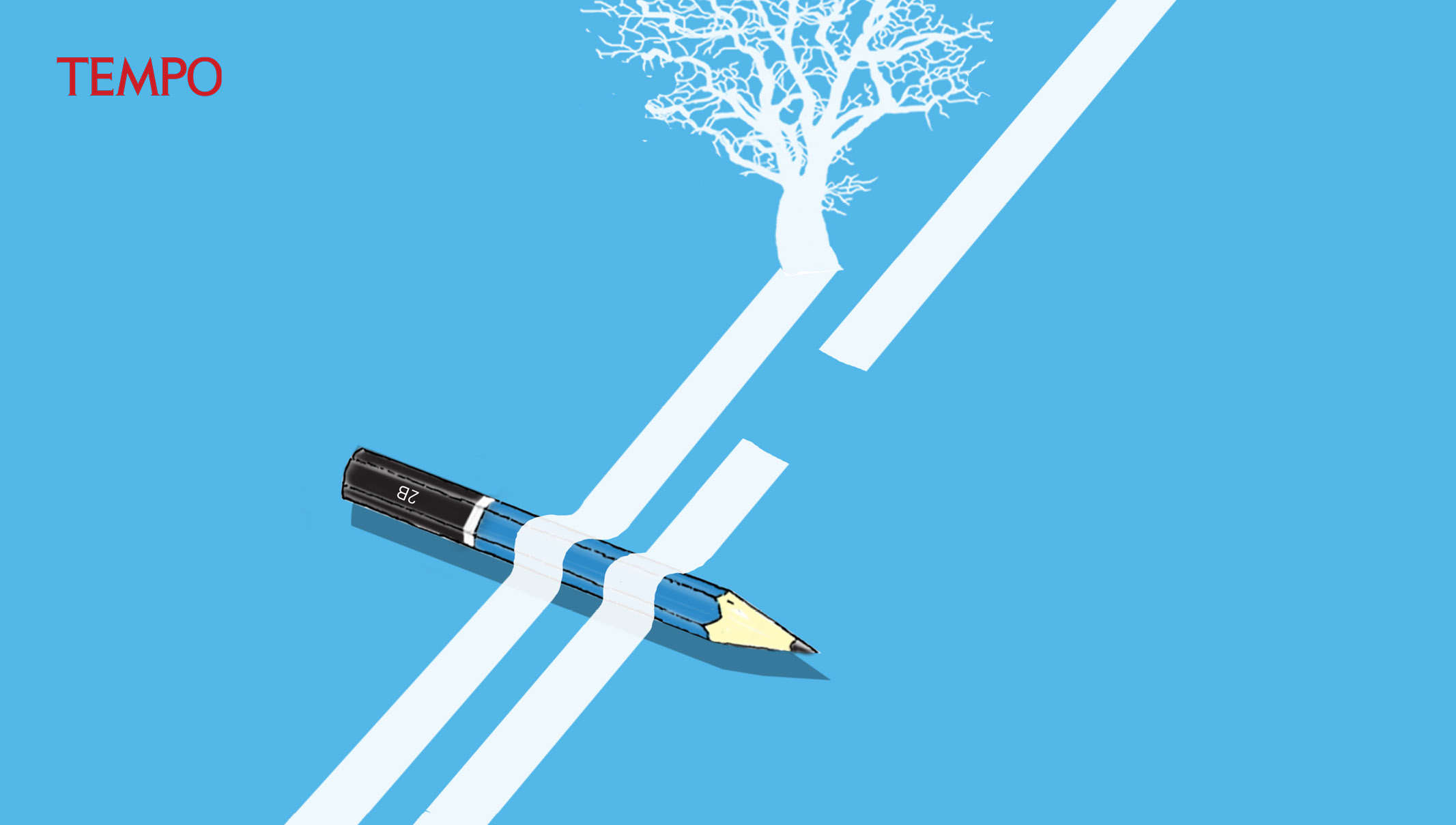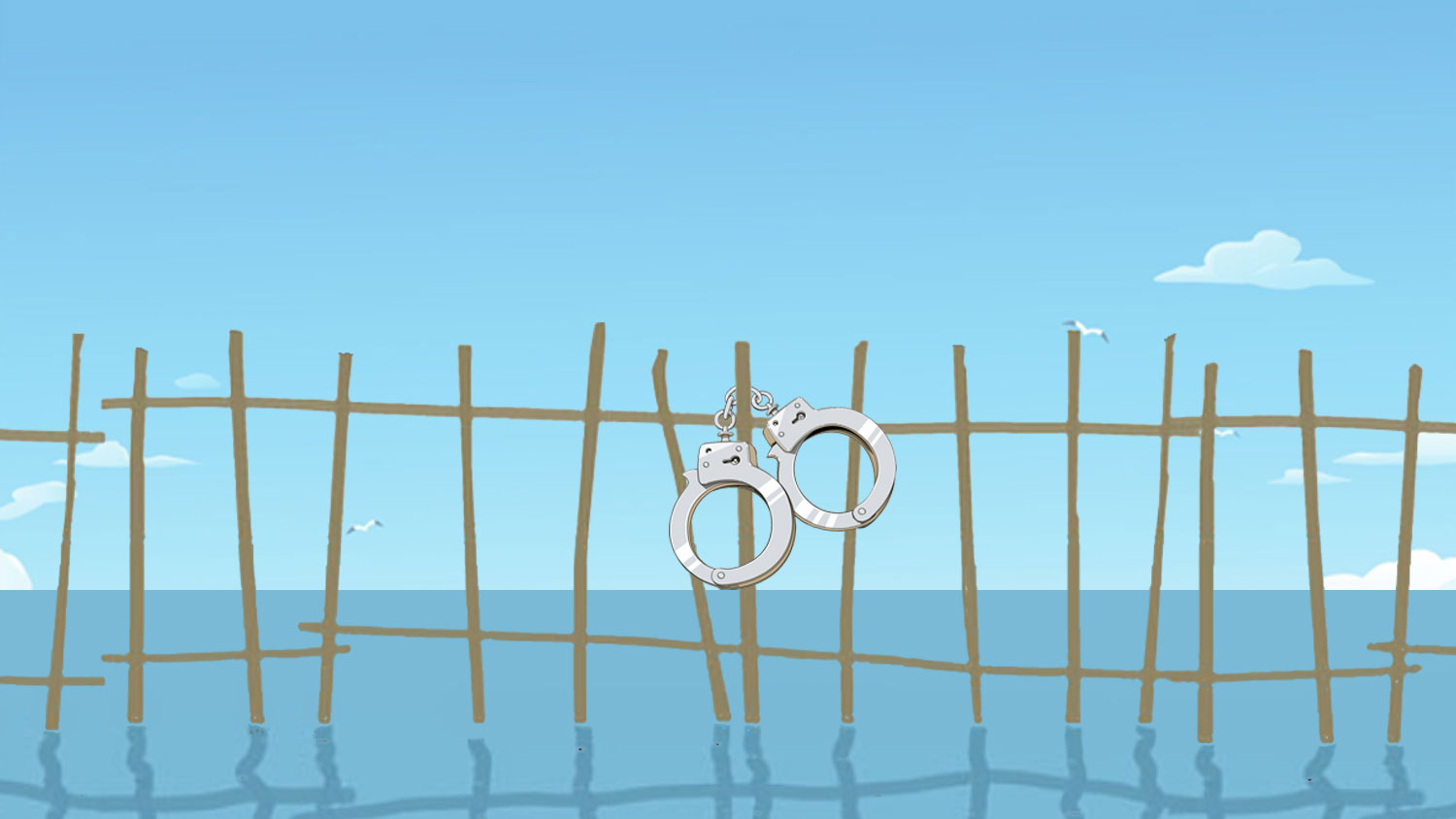Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Kalau mau diibaratkan rapor, rapor politik Orde Baru paling banyak angka merahnya. Represi politik serta KKN-nya merupakan noda terbesar rezim Orde Baru, yang menjadi identik dengan rezim Soeharto. Apakah Orde Baru identik dengan Orde Soeharto? Secara nominal tidak, tapi secara politik bisa dilihat begitu. Kalau Soeharto berhenti, misalnya, di tahun 1985, apakah rapornya akan sama jeleknya? Pasti tidak, karena proses "suksesi" bisa dikelola lebih rapi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo