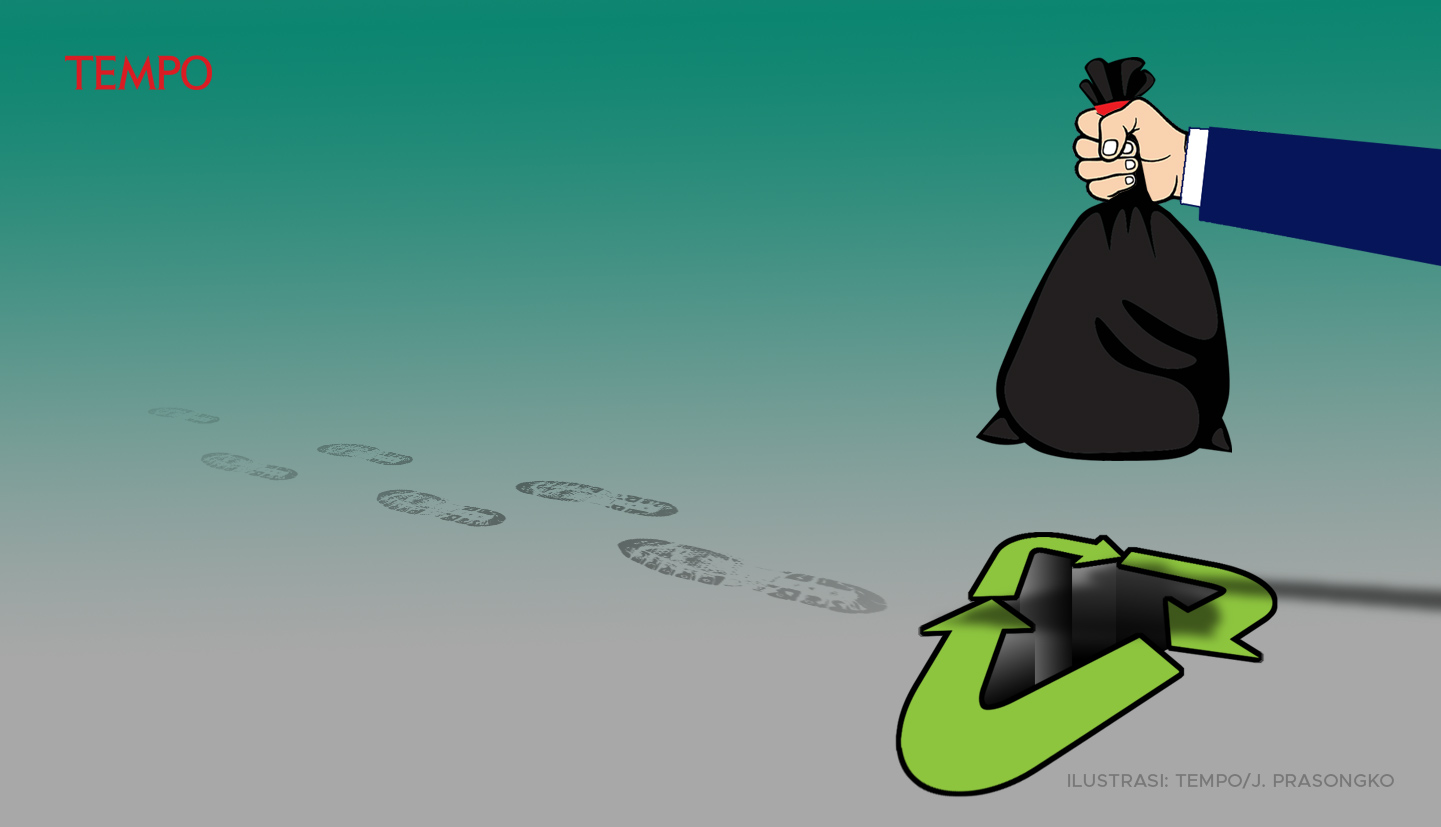Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PIALA Dunia terasa berbeda kali ini. Fokus masyarakat dunia tidak hanya pada tim dan megabintang sepak bola seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar, tapi juga pada demokrasi dan hak asasi manusia. Semua itu terjadi karena event akbar ini berlangsung di Qatar, negara yang memperlakukan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sebagai kriminal. Di sana juga hak perempuan dibatasi dan HAM tak sepenuhnya dihargai.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo