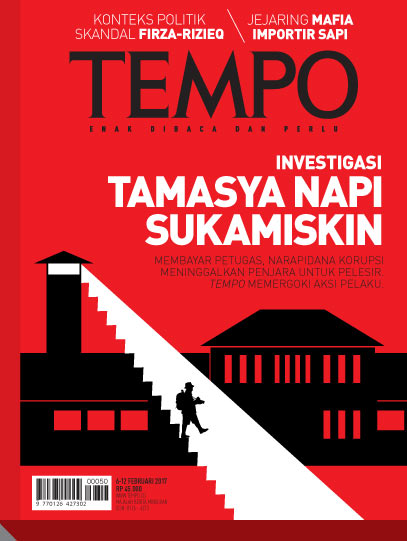Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEMUA pemangku adat Kajang sudah berkumpul di rumah Ammatoa, Rabu pagi dua pekan lalu. Ammatoa, pemimpin tertinggi adat, duduk di salah satu sudut dekat jendela terbuka. Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, juga hadir dalam pertemuan itu. Semua bertelanjang kaki dan berpakaian serba hitam, mengikuti aturan setempat.
Dalam pertemuan yang dihadiri 25 pemangku adat Kajang tersebut, Ammatoa meminta pemerintah menghormati dan turut menjaga hutan adat Kajang. Hutan seluas 313,99 hektare itu meliputi empat desa, yakni Tana Toa, Pattiroang, Bonto Baji, dan Malleleng. Semua berada di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. "Hutan paru-paru kita, tanah leluhur yang tak boleh dirusak," ucap Ammatoa dalam bahasa Makassar dialek Konjo. Kepala Pemerintahan Adat Ammatoa Kajang, Andi Buyung Labbiriya, menerjemahkannya ke bahasa Indonesia kepada tamu yang hadir, termasuk Tempo.
Bagi masyarakat Kajang, hutan punya arti penting. Dalam pasang ri kajang-ajaran hidup yang berisi amanat para leluhur-borong alias hutan adalah bagian dari manusia. Ibu pertiwi yang wajib dijaga. Kalau manusia merusaknya, sama saja menyakiti ibu yang telah melahirkan. Hutan juga dianggap sebagai sumber air. Bila hutan rusak, berarti tak ada kehidupan.
Ammatoa meminta hal itu lantaran pada akhir tahun lalu negara menetapkan wilayah adat Kajang dan tujuh kawasan adat lain sebagai hutan adat. Lima di antaranya ada di Jambi, yakni Margo Serampas, Bukit Sembahyang, Bukit Tinggai, Tigo Luhah Permenti, dan Tigo Luhah Kemantan. Lalu ada Kasepuhan Karang di Lebak, Banten, dan Wana Posangke di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Total seluas 13.122,3 hektare.
Inilah untuk pertama kalinya pemerintah mengakui keberadaan wilayah masyarakat adat. Penetapan ini merupakan klimaks dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 atau dikenal dengan MK35. Putusan tersebut menghapus "negara" di dalam hutan adat. Bisa dibilang putusan ini mengembalikan hak hutan adat kepada masyarakat adat.
Hanya, menurut Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, total luasan tersebut masih jauh dari jumlah yang ada. Dalam catatan Abdon, setidaknya ada sekitar 3,6 juta hektare hutan adat di Indonesia. "Menganggap semuanya milik negara sama saja melanggar hak asasi manusia dan melawan putusan MK," ujar Abdon. AMAN dan Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) kerap mendampingi komunitas adat memperjuangkan hutan adat mereka.
Agar diakui negara, kelompok masyarakat adat harus mendapat pengakuan lebih dulu dari pemerintah daerah setempat melalui peraturan daerah. Di Kajang, proses pembuatan peraturan daerah ini membuat AMAN dan pemerintah Bulukumba berselisih pendapat. AMAN menilai rancangan peraturan tersebut mesti membuka ruang menemukan masyarakat adat lain di Bulukumba. Sedangkan pemerintah berkukuh tidak ada lagi komunitas adat yang masih eksis di luar Kajang.
"Ya, tidak bisa begitu. Harus dicek dulu satu per satu. Kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 41, ada empat kriteria yang wajib dipenuhi," tutur Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba, Misbawati Andi Wawo. Antara lain, harus ada struktur adat, wilayah, hukum atau pranata adat, dan masyarakatnya. Setelah dilakukan survei, kata dia, memang terungkap hanya Kajang yang memenuhi keempat syarat tersebut.
Keberadaan kelompok adat Kajang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan, dan Perlindungan Hak Masyarakat Ammatoa Kajang pada 20 November 2015. Sebulan kemudian, mereka menyerahkan usul pengakuan hutan adat Kajang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Masyarakat Kajang memilih fungsi lindung dan konservasi dalam pengelolaan hutan adat mereka. Sebelum ditetapkan, fungsinya adalah hutan produksi terbatas. "Kami tidak ingin membuat apa-apa di sini. Kami hanya ingin menjaga," ujar Ammatoa. Menurut dia, keputusan tersebut sesuai dengan pasang ri kajang. Dengan cara inilah segala bentuk kegiatan yang bisa merusak sistem ekologi hutan, seperti perambahan dan perburuan satwa, bisa dicegah.
Melanggar adat tentu ada hukumannya. Merusak hutan atau ammanraki borong bisa dikenai hukuman berat (poko' habbala). Siapa saja yang melanggar harus keluar dari Kajang dan tidak boleh kembali. Tak hanya bagi pelaku, tapi juga seluruh keluarganya. "Pelanggaran adat akan diselesaikan secara adat. Pemerintah tidak ikut campur," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Daryanto.
lll
DI Banten, Kasepuhan Karang juga mengantongi surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang hutan adat. Komunitas adat yang bermukim di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, itu melihat hutan sebagai penyokong kehidupan. Sistem pengelolaannya berdasarkan tatali paranti karuhun-aturan adat Kasepuhan. Begitupun pembagian ruang hutan dan ladang.
Tak hanya hidup dari hutan, masyarakat Karang juga hidup dari sumber daya air yang berasal dari tujuh sungai yang mengaliri permukiman mereka, antara lain Sungai Cikamarung, Cimapag, Cipondok Aki, Cibedug, Cilunglum, Cikadu, dan Cibaro. "Kami hidup dari mereka," ujar Jaro Wahid, Kepala Desa Jagaraksa yang juga perwakilan masyarakat Kasepuhan. Jaro adalah sebutan untuk kepala desa atau lurah.
Konon, wargaKarang berasal dari KampungKosala-sekarang Lebak Sangka. Komunitas ini memiliki tugas turun-temurun menjaga situs tersebut. Dari Kosala, mereka sudah beberapa kali bermigrasi. Namun mereka baru pindah setelah kokolot alias kepala pemangku adat menerima wangsit dari leluhur untuk mencari tempat baru.
Meski sering berpindah tempat, sejak 1920-an hingga awal 2000, warga Kasepuhan Karang selalu terlibat konflik dengan perusahaan bidang kehutanan lantaran masalah batas kawasan hutan, khususnya saat mengambil hasil hutan. Barulah pada 2003, ketika hutan produksi diubah fungsinya menjadi konservasi, warga sedikit bisa hidup lebih tenang saat memanfaatkan hutan.
Kasepuhan Karang sempat menemui kendala saat memproses permohonan penetapan hutan adat. Padahal mereka sudah memiliki Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. "Bahkan sempat diminta memenuhi kembali dokumen persyaratan karena dokumen di Kementerian hilang," ucap Jaro Wahid. Perjuangan panjang tersebut berbuah hasil pada akhir tahun lalu.
Presiden Joko Widodo berjanji proses pengakuan tak hanya berhenti di delapan hutan adat. "Di kantong saya masih ada 12,7 juta hektare lahan untuk perhutanan sosial, termasuk hutan adat. Pekerjaan masih panjang," kata Presiden Jokowi di Istana Presiden pada akhir tahun lalu. Dia mengatakan telah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terus mendata hutan adat yang sudah siap.
Adapun Siti Nurbaya mengatakan tahun ini ada beberapa hutan adat lagi yang akan ditetapkan. "Kami ingin luasannya mencapai ratusan ribu hektare. Tapi semua tergantung verifikasi di lapangan," ucapnya.
Direktur Epistema Institute Luluk Uliyah mengatakan pengakuan hutan adat ini harus diikuti dengan pemberdayaan dari pemerintah. Salah satunya memfasilitasi ekonomi berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang bisa diambil dari sekitar hutan. "Masyarakat juga harus diberi akses agar bisa menjangkau dan memasarkan komoditas," katanya.
AMRI MAHBUB
Delapan Hutan Adat
1. Margo Serampas, Merangin, Jambi: 130 hektare
2. Bukit Sembahyang dan Padung Gelanggang, Kerinci, Jambi: 39,04 hektare
3. Bukit Tinggai, Kerinci, Jambi: 41,27 hektare
4. Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Kerinci, Jambi: 276 hektare
5. Tigo Luhah Kemantan, Kerinci, Jambi: 452 hektare
6. Kasepuhan Karang, Lebak, Banten: 486 hektare
7. Ammatoa Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan: 313,99 hektare
8. Wana Posangke, Morowali Utara, Sulawesi Tengah: 6.212 hektare
71 Tahun Menuju Pengakuan
1945: Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kesatuan masyarakat hukum adat, tapi tidak dijelaskan definisinya.
1960: Presiden Sukarno membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menyebutkan hak ulayat atas tanah. Namun tidak disebutkan secara teknis bagaimana cara mendapatkan hak tersebut.
1967: Presiden Soeharto membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Disebutkan seluruh kawasan hutan merupakan hutan negara, termasuk hutan adat.
1999: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Dalam aturan ini, pemerintah menyebutkan dengan gamblang hutan adat dikelola negara.
2012: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 membatalkan kata "negara" dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
2016: Delapan hutan adat diakui pemerintah dan dimasukkan ke peta indikatif hutan Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo