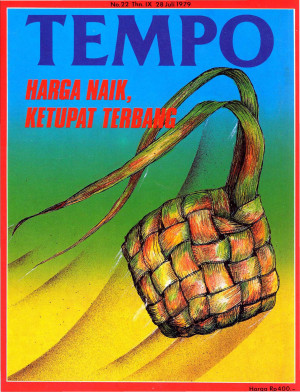IAN Imang, seperti diakuinya, hanya bisa tidur 4 jam sebelum
turun ke perlombaan 45 km. Diduga 204 peserta yang lain juga
tegang memikirkan jarak yang kalaupun ditempuh dengan mobil akan
memakan waktu 1 jam.
Ketika para pelari dilepas pagi itu, 22 Juli, dari garis start
di Silang Monas, cuaca Jakarta menyenangkan. Dari barisan
belakang Ian Imang mengejar saingan kuatnya, Yacob Atarury,
juara ke-2 lomba maraton nasional. Ia "menarik" beberapa
lawannya yang lain ketika mendaki di km 3 Dukuh tas, dan di
tanjakan Slipi. "Ini taktik saya untuk melemahkan lawan,"
katanya.
Menyelesaikan jarak sejauh ini, siapa yang tak mendoakan
turunnya hujan. Tapi begitu matahari naik, langit menjadi cerah.
Beberapa pelari, yang semula meniru gaya Bill Rodgers dengan
sarung tangannya, mulai melepaskan benda yang tak bakal berguna
lagi itu. Bersama mereka turut pula Martin Aleida, wartawan
TEMPO. Kisahnya:
Pada km 7, seorang atlit puteri dan seorang wanita berusia
lebih dari 40 menyusul dari belakang. Ia diikuti suaminya (?)
. . . dengan VW merah.
Melambaikan Tangan
Pos pertama di Km 107 tersedia minuman teh pahit atau manis dan
segentong besar air pengguyur. Saya mengambil segelas air putih.
Untuk pelari yang lambat seperti saya, maraton ini memang bukan
tempatnya. Sejak mendekati bundaran Grogol atau pada Km 17,
saya dan beberapa pelari lain sudah disia-siakan. Kendaraan umum
tak lagi minggir memberikan jalan. Bus dan truk mulai menjepit
kami ke sisi kanan jalan. Hidung mulai disumbat kotoran knalpot.
Melewati Pasar Jembatan Jeling, seorang penjual sayur
melambaikan seikat bayam. "Udah, pinggir dulu Pak!" katanya.
Ketika memasuki daerah Pluit, dari arah yang berlawanan muncul
Ian Imang. Dengan perkasa dia berlari sendirian dengan kawalan
motor. Ia melambaikan tangan kepada saya. Di belakangnya sekitar
seratus meter, menyusul Tjia Tjeng San dari Tegal dengan kaki
telanjang.
Kemudian seorang pemuda yang iseng mengikuti perlombaan ini
menyampaikan info "Kak, di depan ada yang pingsan." Sementara
itu dari kali di kanan jalan mulai mengambang rupa-rupa bau,
bercampur dengan aroma dari sebuah pabrik minyak kelapa.
Melintasi daerah Pluit, pelari yang tercecer ini menekan
perasaan. Hansip yang berjaga di tiap tikungan sudah ogahan
menunjukkan jalan. Jarak 25 Km sudah terlewati. Waktu tempuh
saya 2 jam 23 menit. Beberapa puluh pelari menyerah di sini.
Keluar dari Pluit, saya berlari dalam jarak sekitar satu jam
lebih di belakang Ian Imang. Saya seperti anak ayam yang
ditinggalkan induknya. Sepeda motor memotong jalan seenaknya.
Mendekati bundaran Grogol, saya terhalang oleh barisan
anak-anak. Kendaraan di bundaran Grogol makin menghambat.
Lepas dari situ saya teringat Ian Imang ketika mengikuti seleksi
28 Km. Karena makan rujak kemarinnya, di Grogol ini ia melompat
ke dalam got dan sempat nongkrong 3 menit di situ. Sekarang tak
mungkin nongkrong lagi, karena sepanjang got penuh barisan
pelajar.
Menjelang Km 35, kaki terasa perih Ian mendenyut. Air yang
direguk pada pos berikutnya tak menolong. "Ya Allah," seorang
pelari berbaju hijau mengucap sambil melewati saya. Di depan,
seorang jongkok dan melepaskan sepatu. Ia tinggalkan sepatu
tersebut di pinggir jalan.
Di Km 40? "Pokoknya jarak maraton hanya tinggal 2 km," saya
menghibur diri, padahal sudah lesu sekali.
Dan di gedung Arthaloka, 3 km menjelang finish, di luar sadar
mengucur air hangat di pisak celana. Sudah 30 tahun saya tak
ngompol.
Saya sampai di finish 4 jam 40 menit, beberapa puluh meter saja
di depan Mia Ismangun nyonya yang berumur lebih dari 35 tahun.
Saya kagum pada wanita setua dan sehebat itu.
Ketika itu Ian Imang (waktu 2 jam 9 menit 53 detik) sudah
menerima hadiah untuk kepahlawanannya. Ia unggul 3 menit dari
Yacob. Di antara sekian banyak hadiah, tiket pp Jakarta-Honolulu
masih jadi tandatanya buat anak Larantuka ini. "Kalau dijual
'kan lumayan untuk anak isteri saya," katanya. Sehari-hari ia
menggantungkan hidupnya pada sebuah motor ojek.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini