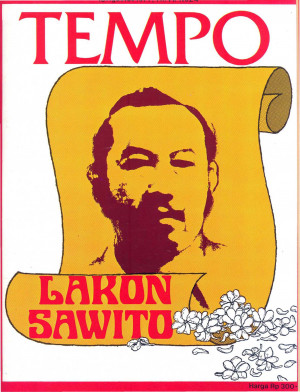JIKA final sepakbola ukuran kesuksesan Pekan Olahraga Nasional
maka PON IX dipersilakan tertawa lebar.
Kesebelasan DKI Jaya dan Irian Jaya yang memperebutkan emas,
kesebelasan Aceh dan Sulawesi Selatan yang memperebut perunggu,
telah mempesonakan 70 ribu penonton Stadion Utama pada acara
terakhir pertandingan sepakbola tanggal 2 Agustus malam.
Selama 4 jam, ke4 kesebelasan itu bergumul dalam pertandingan
yang diperpanjang. Dan dalam perpanjangan waktu itu DKI Jaya
mengalahkan Irian Jaya 4-2 (2-2), Aceh mengalahkan Sulawesi
Selatan 1-0 (0-0).
Penonton stadion utama, Senayan yang pada turnamen "Piala Bang
Ali," Juni yang lalu berubah ganas, kini seolah menjadi jinak
oleh permainan yang bersemangat oleh 4 besar itu. Dan publik
Senayan seolah telah menemukan kembali sifat-sifat sepakbola di
lapangan hijau: toleransi pemain terhadap kesalahan wasit,
permainan keras tanpa ekor baku-hantam.
Dan yang lebih penting lagi, kedua pertandingan yang dipimpin
oleh wasit R. Hatta (final) dan R. Hamlet (juara ketiga), seolah
memberi kesempatan kepada setiap pemain yang galak untuk
menghantam lawannya sejauh ada bola. Seni "makan orang" pada
zaman Tanoto dan Ramang dipersilakan hadir di depan mata kedua
wasit yang nyaris tersingkir karena berani melawan "instruksi
atasan" itu.
Sepakbola kini bukan lagi "biang kerok." Sumber kegaduhan telah
beralih ke gelanggang tinju.
Membutuhkan Disiplin
Tapi apa komentar orang tentang mutu ke4 kesebelasan itu? Irian
Jaya nampaknya masih diguyur harapan. Tanpa Johannes Auri dan
Robby Binur yang pindah ke Jakarta, Irian Jaya toh masih sebuah
kesebelasan yang kompak. Benny Yensenem di kanan luar dan Saul
Sibi di kiri luar merupakan dua pemain yang berkepribadian kuat.
Tapi agak dalam menilai Irian Jaya tak patut orang mempretelinya
dari satu kesatuan. Mereka secara teknis matang. Yang kurang
hanya segi taktis dan pola-pola permainan yang membutuhkan
disiplin.
Misalnya, andaikata imo Kapisa lebih berani meninggalkan daerah
tengah untuk ikut menerjang ke depan, Oyong dkk niscaya akan
mengalami kesulitan. Pemain-pemain Irian Jaya pada umumnya
secara alamiah sudah tertanam ketrampilan bersepakbola.
Lihatlahmereka mendorong, mendribel, menyetop (dengan kaki,
badan dan kepala) bola, semuanya berlangsung dengan wajar. Gerak
tubuh terkordinir dengan indah. Entah siapa pula yang mengajar
mereka menendang bola dengan bagian dalam atau bagian luar kaki
untuk memberi akibat efek.
Faktor-faktor teknis dan alamiah ini sayangnya kurang didukung
oleh faktor taktis. Mereka enggan merubah pola permainan yang
mengasyikkan diri mereka. Bola sering dikuasai berlama-lama.
Kalau sudah kepergok dan hampir mati langkah, baru disodorkan
kepada kawannya. Tapi situasi semacam ini memang yang
menggiurkan penonton. Persis seperti gaya pemain Amerika Latin
atau Brasil. Itulah sebabnya ketika Irian Jaya berhasil
menceploskan bola ke gawang Sudarno, mereka mulai lengah. Sebab
ketika masih asyik menikmati kerjasama Yensenem dan Saul Sibi
yang membuahkan gol pertama Irja itu, mereka kecolongan Iswadi
yang membuat gol balasan.
Seandainya mereka pandai membuat pertahanan yang sistimatis,
misalnya dengan menarik mundur barisan tengahnya ke dalam
pertahanan, selagi Junaedi, Ronny Patti dan Sofyan melakukan
kegiatan di medan tengah, rasanya Persija sulit menemukan
peluang melancarkan tembakan. Mallum, dalam body charge atau
benturan badan, pemain Persija mana yang berani berduel dengan
pemain Irja?
Irian Jaya memang memerlukan permainan terbuka sebagai ekspresi
kepribadian yang khas. Tapi mereka membutuhkan juga sistim
pertahanan yang kuat. Apalagi kiper Jimrny Pieter terbilang yang
paling lemah. Seyogyanya Bas Youwe, tim manajer Irja, menyadari
hal ini. "Andaikata mereka memiliki Ronny Pasla, tidak mustahil
Irja merupakan tim yang bertaraf internasional," begitu komentar
seorang penonton VIP.
Kekalahan Irja dari DKI Jaya tidak mengurangi kedudukan
putera-putera Irian Jaya itu di mata publik. Mereka tetap
dinantikan di lapangan hijau. Lebih-lebih dengan mutu pemunculan
mereka di final, harapan penonton supaya mereka diberi peluang
untuk berhadapan dengan tim luar negeri makin menjadi satu
kebutuhan, bahkan tuntutan. Mereka perlu diberi kesempatan
seperti tim-tim daerah lainnya dalam pertandingan internasional.
Segi komersiilnya akan menjamin ongkos pembiayaannya.
Kemelut Organisasi
Sementara itu Kesebelasan Ibukota di bawah sorotan Pak Tjokro
dan Bang Ali (plus kedua nyonya mereka) di final itu bermain
dengan gaya rutin saja. Jebakan taktik off-side harus dibayar
mahal: gol. Itu terjadi karena Simson Rumahpasal ragu ikut naik.
Keseragaman langkah dalam satu komando perlu latihan juga.
Kelemahan yang masih tampak di tubuh Persija, terletak pada
kombinasi Ronny dan Junaedi. Mereka bergerak terlalu melebar.
Banyak menyulitkan Iswadi dan Suhanta. Sedang kelemahan yang
belum terobati masih saja di sisi kiri: Andilala. Kedudukan Lala
menjadi goyah setelah orang menyaksikan kiri-luar Sulsel, Dullah
Rahim. Yang terakhir ini lebih punya otak. Ini terlihat dari
pertandingan Aceh-Sulsel.
Munculnya DKI Jaya, Irian Jaya, Aceh dan Sulawesi Selatan dalam
4 besar PON IX 1977, memang belum sepenuhnya menggambarkan
kekuatan persepakbolaan di Indonesia. Aceh, misalnya, masih
gemar bermain-main dengan bola di udara. Bola rendah nampaknya
menyulitkan mereka. Tapi semangat dan tekadnya (Aceh menundukkan
Sumatera Utara 2-1) tak pernah kendor. Dengan modal itu tak
boleh diramal Aceh tidak akan dapat mengalahkan kesebelasan
Sulsel yang sama seandainya terjadi pertandingan revans. Aceh
masih polos. Ia perlu diperkenalkan dengan praktek-praktek
sepakbola mutakhir: makin mudah bola dimainkan makin tinggi
teknik sepakbola itu.
Hari terakhir pertandingan sepakbola PON IX membesarkan hati
pencinta sepakbola. Permainan ini telah menemukan daya tariknya
kembali. Harap saja suasana di lapangan ini tidak tercemarkan
oleh kemelut di pucuk pimpinan PSSI. Di dunia ini nampaknya
hanya di Indonesia, bahwa kemelut organisasi lebih ramai
diperbincangkan orang daripada permainan sepakbola itu sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini