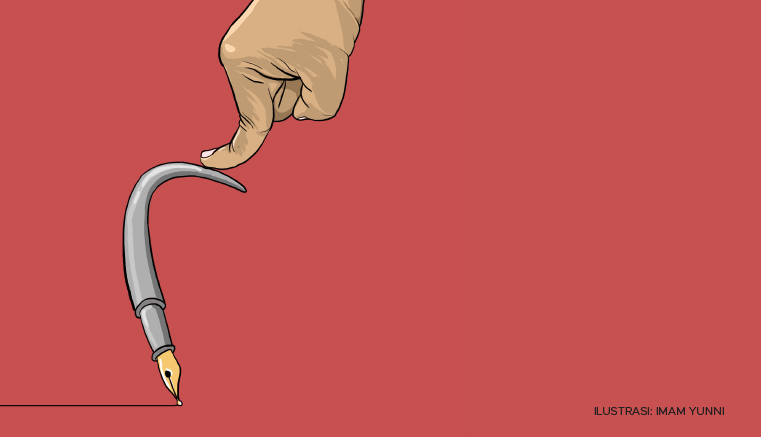Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

JAKARTA – Kalangan pegiat hukum menilai pendekatan restorative justice, yaitu penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada mediasi hingga perdamaian, tidak tepat digunakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Apalagi jika caranya dijadikan alasan untuk menghentikan proses penyidikan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo