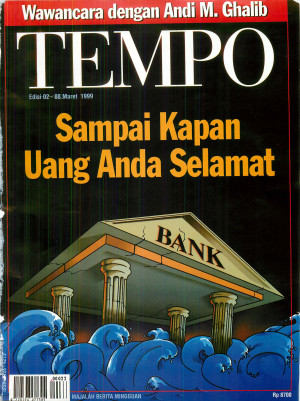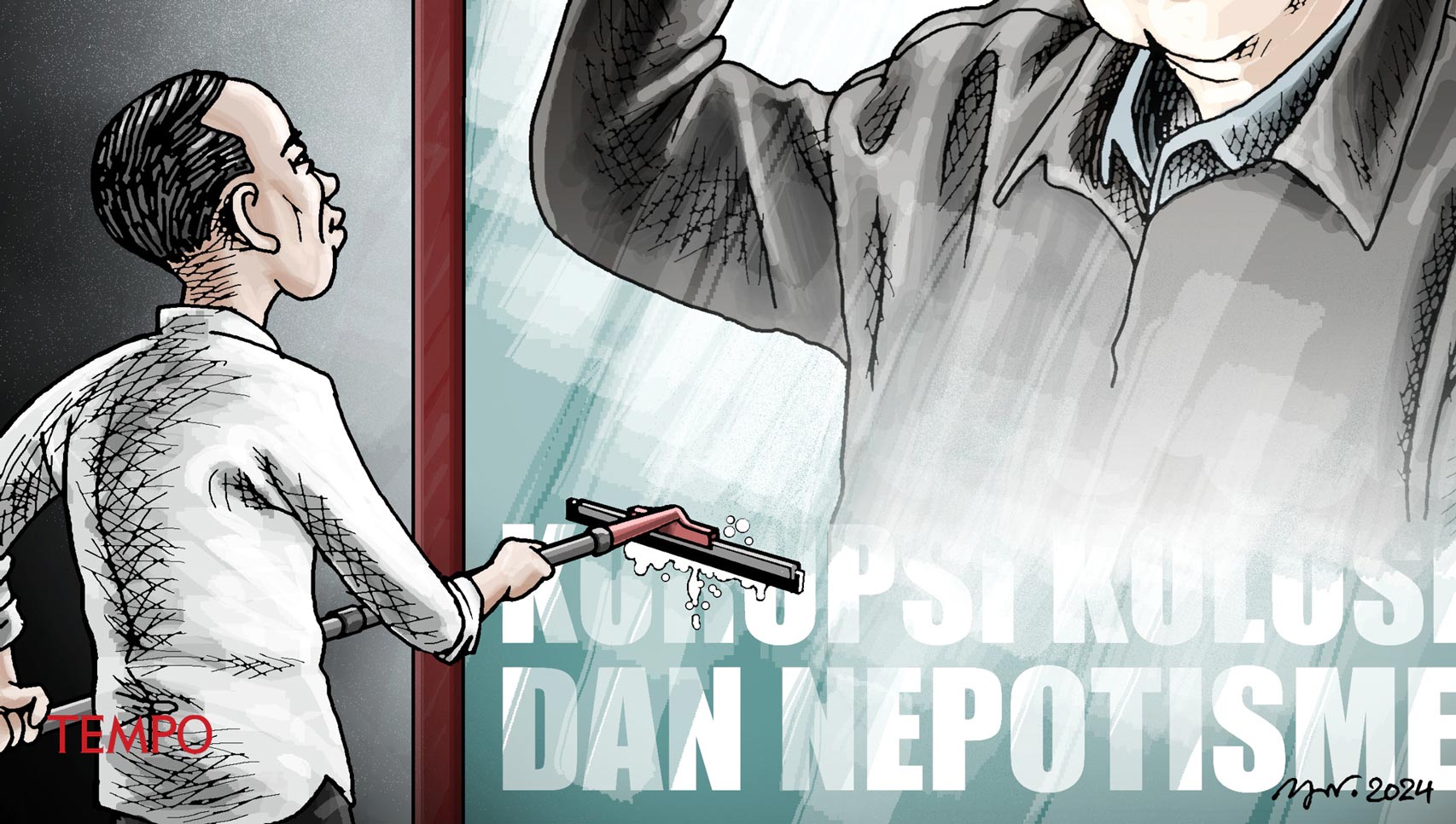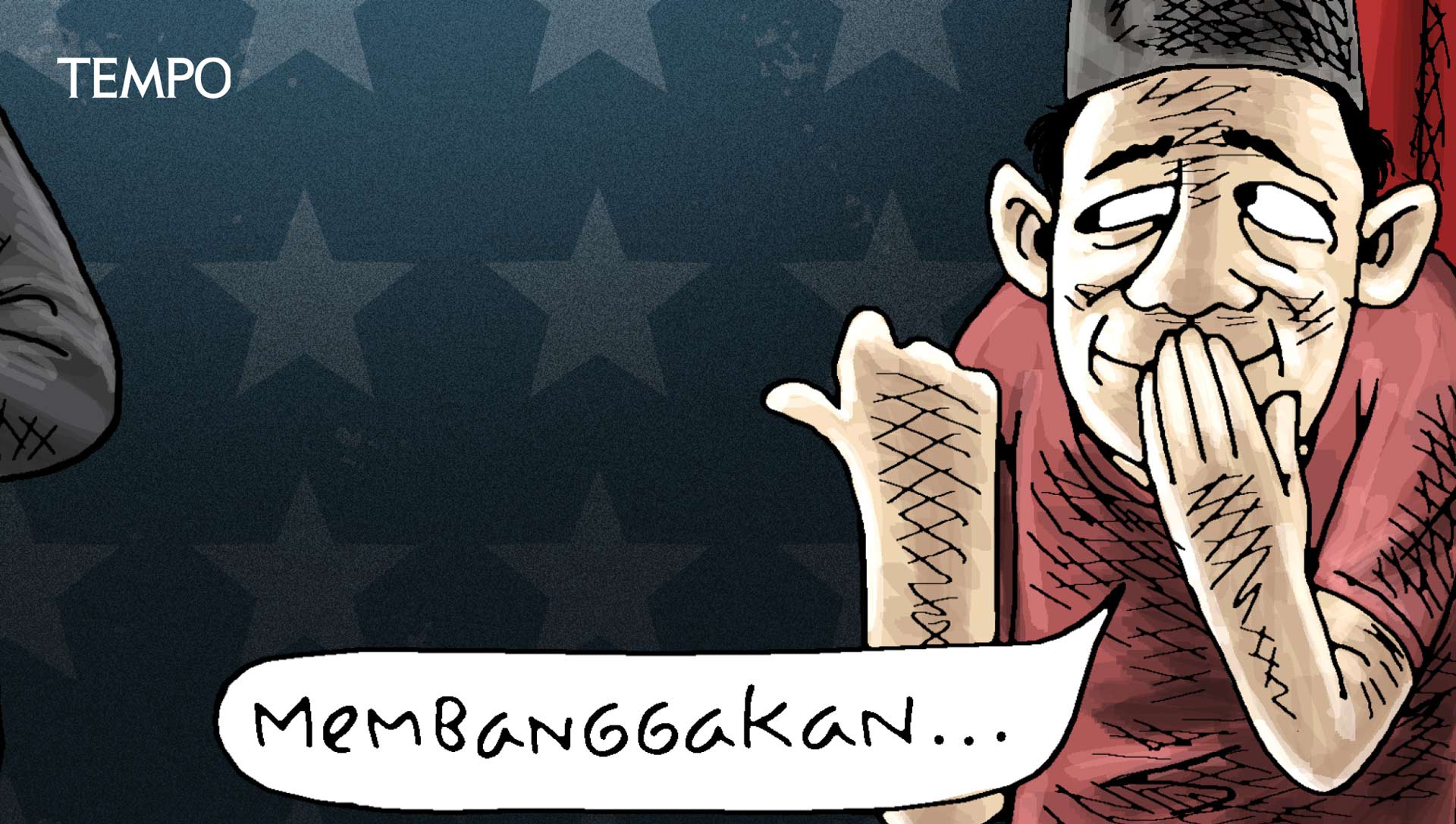Sangat rancu reaksi yang diperlihatkan para pejabat tinggi dan beberapa pakar terhadap skandal penyadapan telepon Habibie-Ghalib, tak terkecuali Habibie sendiri. Yang dipermasalahkan bukannya substansi materi pembicaraannya, melainkan siapa, di mana, dan bagaimana penyadapan dilakukan. Materi pembicaraannya sendiri tak mau disentuh. Padahal seharusnya inilah yang paling utama karena menyangkut kepentingan rakyat, sekaligus memperlihatkan bagaimana karakter pemimpin seperti Habibie dan Ghalib.
Intisarinya adalah pemeriksaan atas Soeharto selama ini—seperti diduga sebelumnya—hanya sebuah sandiwara untuk menghindari pengadilan rakyat. Demikian juga adanya unsur politik yang sangat kuat dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap pengusaha Arifin Panigoro, dan juga incaran terhadap Sofjan Wanandi. Mereka itu sebenarnya dijadikan target karena beroposisi terhadap pemerintahan Habibie, sedangkan alasan pemeriksaan yang secara formal diutarakan oleh Kejaksaan Agung hanya merupakan kamuflase.
Semula Andi Ghalib tegas menolak bahwa dia telah berbicara seperti itu, dengan menuduh isi pembicaraan itu palsu. Tetapi belakangan, lewat Baramuli, dia akhirnya mengaku bahwa pembicaraan itu memang pernah dilakukan. Ini saja sudah memperlihatkan karakter Ghalib yang tidak pantas lagi tetap duduk sebagai Jaksa Agung. Bagaimana atau apa yang bisa kita harapkan dari seorang Jaksa Agung yang ternyata seorang pembohong?
Tak kalah memprihatinkan adalah pembelaan yang dilakukan Baramuli terhadap Ghalib. Sudah berbohong, bukannya meminta maaf, malah membela diri. Itu pun dengan cara yang konyol. Baramuli mengatakan bahwa Ghalib tidak pernah menyangkal (padahal melalui media cetak dan elektronik kita saksikan jelas-jelas Ghalib memang membantah), tapi tidak persis seperti itu isi pembicaraannya, dan Ghalib lupa pembicaraan yang mana karena sudah banyak kali berbicara dengan Habibie. Bagaimana bisa Ghalib sudah mau mengakui keaslian pembicaraan telepon itu tapi membantah bahwa isi pembicaraan tidak persis seperti itu? Rekaman pembicaraan itu sangat jelas berbicara tentang materi seperti di atas. Kalau Ghalib menyangkal materinya berarti seharusnya rekaman pembicaraan itu bukan suara aslinya. Tidak mungkin mengaku suara itu asli, bersamaan dengan itu menyangkal materi pembicaraannya.
Perdebatan soal pelanggaran privasi dan rahasia negara sebaiknya diabaikan saja. Kita semua tahu bahwa materi pembicaraan itu sama sekali bukan soal privasi, dan juga bukan tergolong rahasia negara. Lebih tepat kalau disebut rahasia pribadi antara kedua pejabat tinggi itu, yang bersekongkol menipu rakyat.
Bilamana perlu, jika penyadapnya nanti ketahuan, kita memberinya penghargaan karena sudah berhasil membongkar konspirasi Habibie-Ghalib itu.
Wimar Witoelar dalam Asal-Usul di Kompas, Minggu, 21 Februari, menunjukkan contoh kasus Nixon, yang segera mengundurkan diri karena ketahuan terlibat langsung dalam skandal penyadapan telepon lawan politiknya. Wimar antara lain menulis: "... keberhasilan Bob Woodward dan Carl Bernstein, dua wartawan muda The Washington Post, dalam membentuk opini masyarakat, membangunkan mereka pada kenyataan bahwa sistem politik Amerika Serikat tidak perlu melindungi seorang presiden yang menggunakan jabatan kepresidenan sebagai alat politik. Walaupun legalitas rekaman itu dipersoalkan, yang penting bagi publik adalah gambaran mengenai karakter seorang presiden. Jabatan presiden adalah jabatan kepercayaan, dan tidak bisa dipertahankan oleh legalitas semata-mata. Melihat kebangkitan publik, jauh sebelum Kongres sampai pada proses impeachment, Nixon sudah mengundurkan diri...."
Pertanyaannya, apakah mental seperti ini ada pada pejabat (tinggi) kita. Biasanya mereka malah berkata: "Mengundurkan diri berarti lepas dari tanggung jawab." Padahal "kerusakan" yang telah mereka lakukan itu tidak akan dapat mereka perbaiki dengan terus menjabat. Atau kalau itu terjadi pada level seperti seorang menteri, dia biasanya menjawab: "Saya siap mengundurkan diri kalau presiden memerintah." Padahal, kalau memang dia merasa tak becus, seharusnya dia yang mengajukan permohonan berhenti. Tidak harus menanti perintah presiden (yang diyakini tak akan ada).
Ada lagi argumen yang sering dilontarkan para pejabat kita ini, dengan mengatakan bahwa budaya seperti itu (mengundurkan diri) bukan atau tak sesuai dengan budaya Indonesia. Sama dengan pada masa pemerintahan Soeharto, yang mengatakan konsep hak asasi manusia di Indonesia lain dengan konsep di negara lain. Padahal apa yang disebut hak asasi sebenarnya sesuatu yang universal. Buktinya tercantum dalam salah satu Piagam PBB. Dengan perkataan lain argumen seperti itu hanya bentuk kamuflase bahwa mereka masih haus kekuasaan. Atau seperti sebuah iklan kursi: "Kalau sudah duduk, lupa berdiri."
Daniel H.T.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini