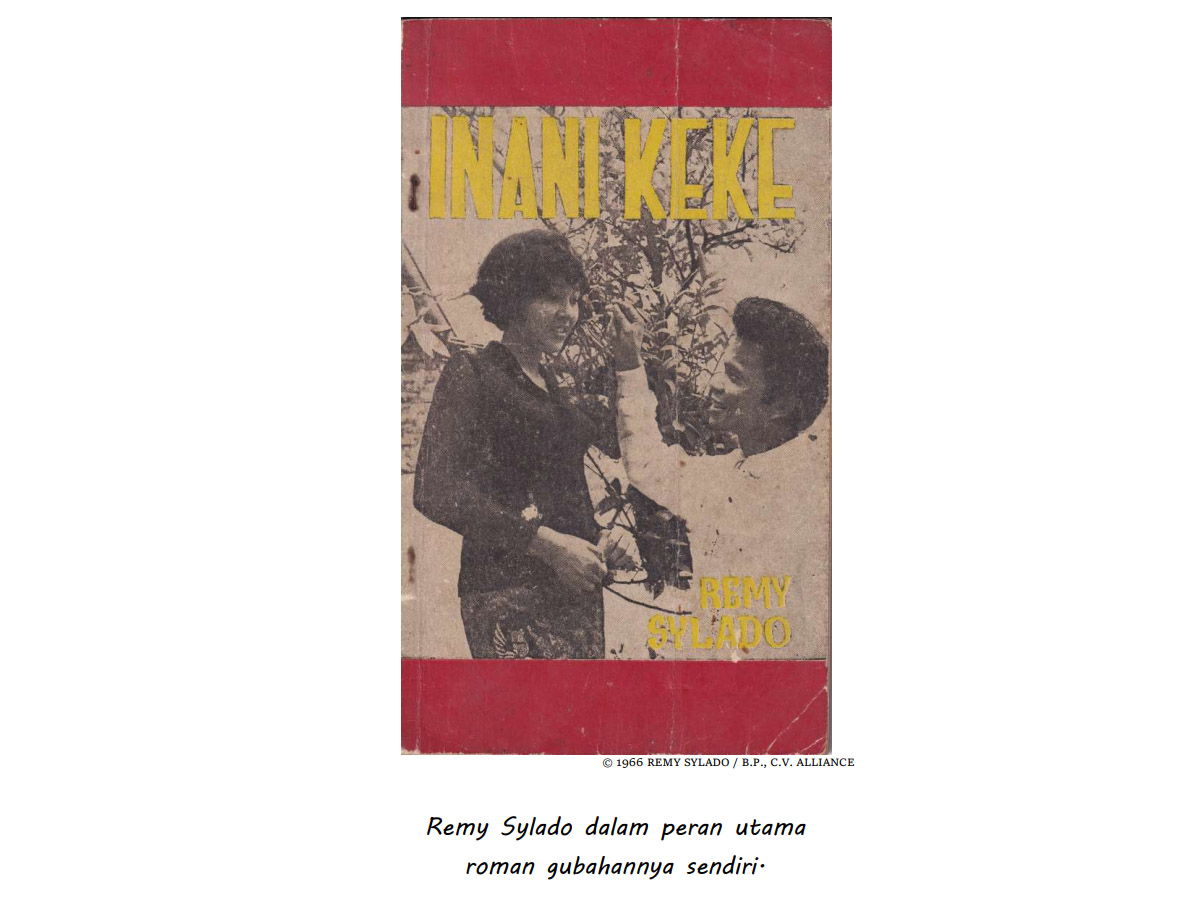Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

JAUH sebelum menjadi mbeling, Remy Sylado (1945-2022) telah membereskan urusannya dengan kemapanan, yang toh ditulisnya dengan kembeling-mbelingan juga. Betapapun kutipan berikut membuktikan penguasaannya atas realisme dalam susastra, sebagai prasyarat bagi pemberontakannya, bahwa ia memberontak bukan karena tak mampu menuliskan yang klasik:
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo