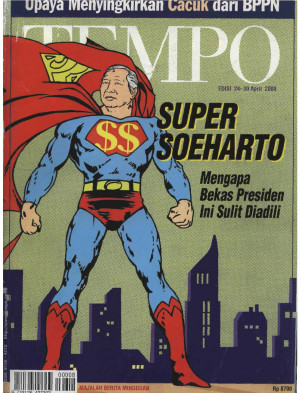Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Setiap kali majalah itu terbit, cerita yang dimuat di halaman depan mendapat sorotan. Artinya, cerita itu dikupas serta dibahas oleh Redaksi. Saya tidak tahu apakah mendapat sorotan juga berarti mendapat nilai tambah. Bagi saya, bila karya tulis saya diterbitkan, sudah sangat menyenangkan. Dan kesenangan itu beralasan dua hal, yaitu karena saya akan menerima honorarium. Ini amat saya butuhkan sebagai anak seorang janda tanpa santunan. Hal yang kedua ialah karena akan banyak orang yang membaca karangan saya. Setidak-tidaknya tulisan itu akan lebih tersebar daripada jika hanya saya bacakan di depan kelompok kami, Kuncup Seri, di Semarang. Karena itu, ketika Pendurhaka disorot oleh H.B. Jassin, saya tidak merasa diri istimewa.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo