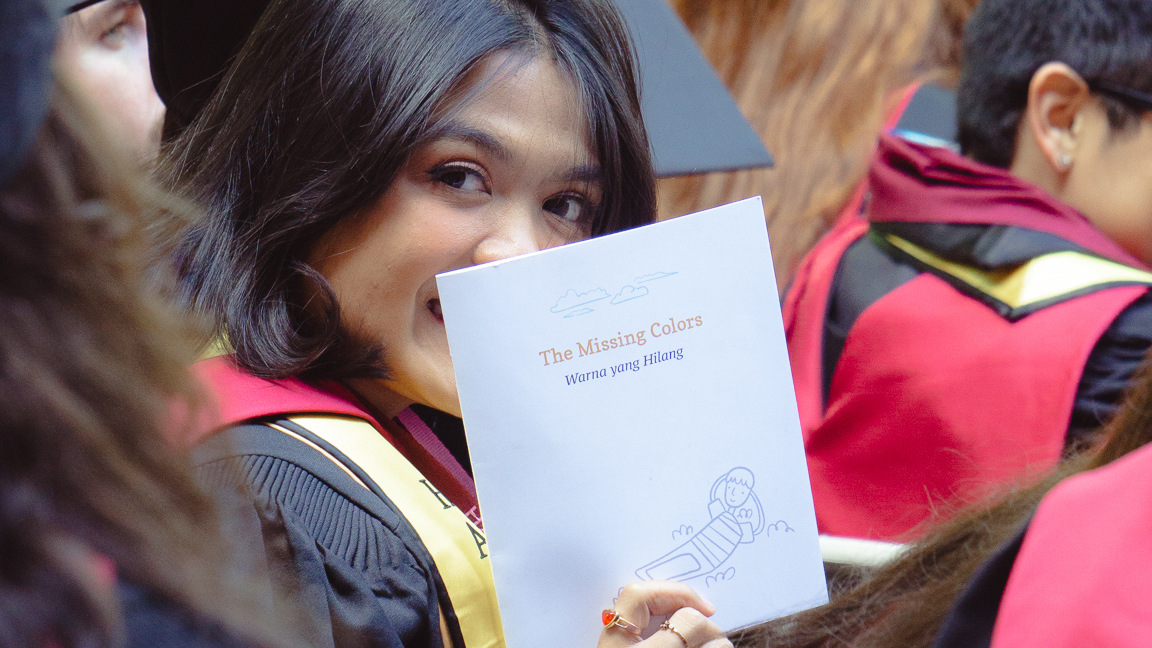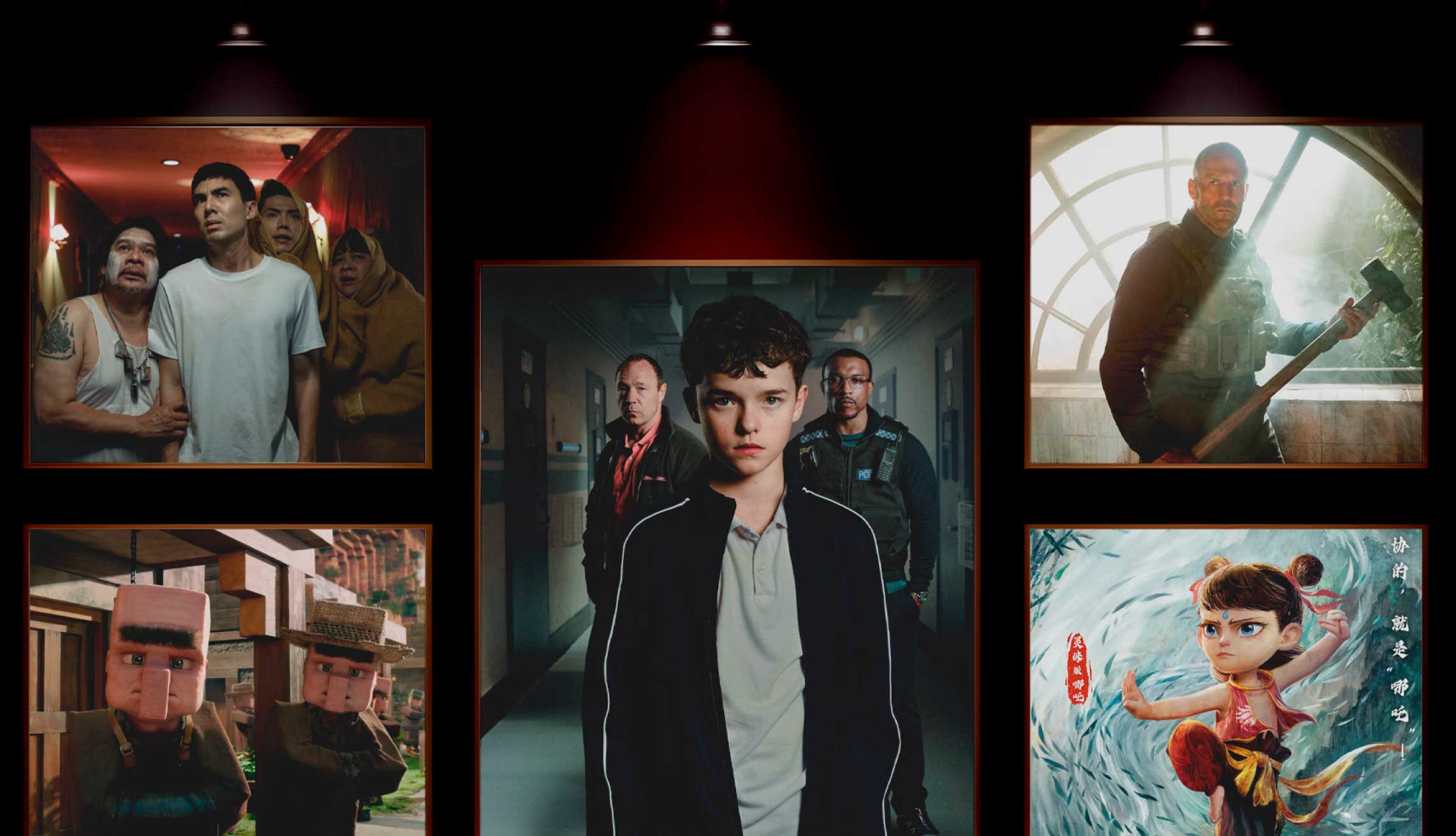Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Gubernur Jakarta Anies Baswedan membangun monumen sepatu lengkap dengan merknya.
Monumen sepatuh umum ada di negara-negara maju.
Pengamat seni rupa Agus Dermawan membandingkan monumen sepatu serupa di negara lain.
PADA Agustus-September lalu, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, menggelar pameran seni rupa publik (public art), terutama patung monumen di seluruh Indonesia. Karena patung monumen itu difungsikan sebagai titik pengingatan akan memori, dan tanda pengingat akan tempat (landmark), pameran tersebut dijuduli “Poros”.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo