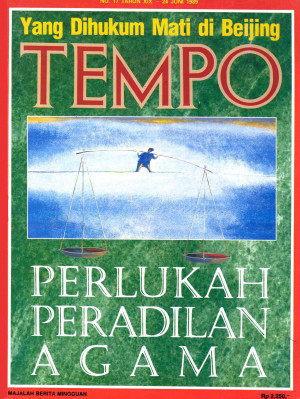Roeslan Abdulgani, lahir di Plapitan, Surabaya, 24 November 1914, pendidikan His, mulo, hBs. Ia menganggap dunia ini tidak hitam putih tapi berwarna, yang penting orang harus bisa menyesuaikan diri dengan warna-warni itu. Di awal kemerdekaan hingga akhir Orde Lama, ia menduduki posisi-posisi penting. Di zaman Orde Baru posisinya tetap kuat sebagai Dubes RI di PBB (1967-1971), ketua tim penasehat presiden mengenai pelaksanaan P4 (1978-sekarang). Belakangan, ia rajin menulis buku, dan artikel-artikel di mass media. Penuturan sebagaian perjalanan hidupnya ini sengaja kami mintakan lewat reporter kami, Priyono B. Soembogo. SAYA dilahirkan di Plampitan, salah satu kampung di Kota Surabaya, di dekat Kali Mas, kelanjutan dari Kali Brantas. Saya punya tiga saudara kandung. Kakak saya laki-laki sudah meninggal. Adik saya perempuan masih ada di Surabaya, sudah kawin. Bapak saya punya istri dua. Ibu saya istri kedua. Dengan istri pertama punya tiga anak juga. Tetapi, tentu saja ibu saya dan ibu tiri saya hidup di rumah terpisah. Kami dididik dengan keras. Bapak mengajarkan kami hidup gemi -- hemat. Meskipun Bapak punya mobil, kalau ke sekolah, kami tidak boleh menggunakannya. Sementara Ibu menyuruh kami selalu eling -- ingat -- pada Tuhan. Bapak meninggal tahun 1929, ketika saya masih di MULO. Sejak itu Ibu yang membiayai sekolah saya. Untung, Bapak mewariskan perusahaan dan sebagainya, sehingga Ibu tetap dapat membiayai saya. Kalau saya ingat kembali, saya ini produk dari pertemuan dua keadaan: keadaan kampung dan keadaan kota. Kampung di Surabaya, bukan berarti 'kampungan' seperti orang 'gedongan' di sini katakan. Kampung itu suatu masyarakat dinamis, masyarakat di mana ada cerminan daripada seluruh kota Surabaya. Nah, Surabaya adalah nomor satu kota pedagang. Kedua, adalah kota di mana agama Islam sangat kuat. Ada Sunan Ngampel, ada Masjid Ngampel, ada pesantren-pesantren yang kuat, dan macam-macam. Ketiga, Kota Surabaya adalah kota kaum buruh. Banyak bengkel-bengkel. Malahan di zaman Belanda "Marine". Di sana ada semangat nasionalisme dan semangat keislaman. Itu semua memberi corak tertentu pada Surabaya. Dan kemudian, Kota Surabaya memiliki banyak kerajinan tangan. Jadi, banyak orang yang hidup bebas, yang tidak hidup dari birokrasi. Birokrasi memang ada, tetapi tidak sebegitu menonjol seperti di Batavia. Tapi jangan dikira Surabaya tidak mempunyai nilai intelektual. Di sana ada sekolah kedokteran yang nomor dua setelah Stovia di Batavia. Di Surabaya ada HBS. Sekolah untuk anak-anak pribumi cuma sedikit. Masa kecil saya tidak bisa saya lepaskan dari kondisi itu. Sebab, itulah yang membentuk pribadi saya. Kebetulan bapak saya, Haji Abdulgani, adalah orang pedagang yang pandangan hidupnya pragmatis, profesional. Dia tergolong pedagang yang cukupan. Sejajar dengan pedagang-pedagang Cina waktu itu. Bapak saya berdagang berbagai macam dagangan: beras, gula, dan lain-lain. Bapak punya telepon, barang yang waktu itu jarang dimiliki orang. Orang yang punya telepon waktu itu tergolong besar. Di samping itu dia punya 10 mobil yang disewakan sebagai taksi. Lalu, punya rumah-rumah yang disewakan. Kalau ndak salah, 20--30 rumah. Zaman sekarang bisa disebut real estate. Namun begitu, Bapak saya ikut Syarekat Dagang Islam. Bapak memang tidak ikut dalam politik, tetapi dia ikut memberikan dana bagi gerakan Pak H.O.S. Tjokroaminoto. Rumah Pak Tjokro di seberang rumah kami. Di rumah Pak Tjokro itu juga ada Bung Karno, yang indekos di sana. Tahun 1926 ada pemogokan-pemogokan. Tahun 1925 Syarekat Islam yang dipimpin Pak Tjokro sudah besar. Ketika Bapak masih hidup, ada pemogokan-pemogokan yang dikerahkan oleh SI pada 1925-1926. Saya masih kecil. Antara SI dan PKI ada kompetisi: Jadi, tidak benar cuma PKI yang melawan kolonialisme. Syarekat Islam juga. Pak Tjokro ditangkap, dimasukkan penjara, dan sebagainya. Bapak juga merasakan hal itu. Beliau memang tidak ikut berpolitik, tapi memberikan dana. Saya sering diajak ikut melihat pemogokan. Misalnya ke Pasar Keling -- rumah Dinas Kereta Api, namanya dulu SS. Mereka ikut mogok malam-malam, hujan-hujan, lantas diusir oleh polisi. Bapak mengantar saya untuk melihat. "Coba lihat itu, mebel-mebel dikeluarkan dari rumah," kata Bapak. Orang-orang Cina, orang-orang Arab, datang untuk membeli mebelnya. Umur saya waktu itu 16 tahun, masih di HIS kelas 6, begitu. "Itulah kejamnya penjajahan Lodo," kata Bapak. Dan saya sudah tertarik pada pergerakan-pergerakan macam itu. Bapak juga bercerita tentang K.H. Achmad Dahlan -- pendiri Muhammadiyah -- yang sering datang ke Plampitan, bertemu dengan Tjokroaminoto. Ada juga Nahdlatul Ulama. Selain itu, Perang Dunia I baru saja selesai. Harga gula naik, dan sebagainya. Kota Surabaya sebagai kota dagang jadi bandar yang ramai. Dengan begitu Surabaya menjadi kancah penggodokan berbagai macam orang. Ada ulama, buruh, Belanda, Cina, Arab, dan sebagainya. Di tengah situasi macam itulah, saya dilahirkan dan hidup. Jadi jangan melihat saya sebagai individu. Tetapi sebagai produk zaman. Ibu saya selalu berkata, "Kita mimpi kapan kita merdeka, kapan Londo itu pergi". Saya punya mbah, namanya Mbah Kasiran. Saya, Ibu, dan Bapak sering pergi ke sana. Kalau Bapak dan Ibu bicara soal orang-orang yang ditangkapi Belanda, Mbah berkata, "Ojo kuatir (jangan khawatir), Joyoboyo sudah mengatakan, nanti akan datang Bangsa Jago Kate (Dai Nippon) kemari. Nanti sesudah itu Bongso Jowo akan merdeka. Tapi wutah getih -- banjir darah." Ibu saya, Sitti Nurat, seorang guru ngaji. Punya murid kira-kira 50-an. Karena dulu rumah kami cukup besar, cukup untuk menampung murid-murid ngaji, perempuan dan laki-laki. Saya kalau sore harus ikut ngaji. Pagi sekolah. Saya hidup di dua dunia. Kalau pagi Sekolah Dasar, sore mengaji. Di SD saya belajar bahasa Belanda, bahasa Jawa juga -- Paromo Sastro Jowo, yang saya harus kenal. Sepulang sekolah, sorenya saya langsung ikut ngaji. Ya, Jus Amma, Yassin. Ibu minta saya harus bisa baca Surah Yassin. Ndak perlu ngerti. Tentu dimulai dengan menghafal surah Albaqaroh. Cara mengajinya bersama-sama, dengan teman-teman lain. Masing-masing memegang Al-qur'an, sementara Ibu menuntun. Itu berlangsung sampai saya masuk HBS. Saya disekolahkan di HIS, sekolah dasar yang terletak di Sulung. Selesai tahun 1928. Lulus dari HIS saya disekolahkan ke MULO di Ketabang sampai tahun 1932. Di Surabaya hanya ada dua MULO. Satu di Ketabang satu di Praban. Lulusan Praban misalnya Widjojo Nitisastro, dan istri saya. Kemudian saya pergi ke HBS Surabaya. HBS ini SMA khusus untuk orang Belanda. Tidak ada SMA untuk pribumi. Semestinya saya harus pergi ke Malang. Tetapi saya mengikuti ujian di HBS Surabaya. Padahal bukan untuk pribumi. Saya masuk, saya ditantang ujian bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, goneometri, aljabar, dan lain-lain. Lulus saya. Masuk! Waktu itu yang berani ujian dari MULO Ketabang hanya empat. Dua orang Cina, satu orang Belanda, satu saya. Belandanya gagal, satu Cina gagal. Swie Ho, yang kemudian jadi pelukis hebat dan sekarang sudah meninggal, tes sama-sama saya. Tujuh ratus murid (700) HBS, 70% di antaranya Belanda totok, 15% orang Indo, 10% Cina. Nah, orang Indonesia cuma 5%. Kira-kira cuma 30 gelintir anak Indonesia. Antara lain Mukarto -- kelak Menteri Luar Negeri -- Sudjatmoko, Murdiyanto. Keduanya adik kelas saya. Di HBS ini saya baru mengenal masyarakat Belanda. Guru-gurunya lain dengan di MULO. Di MULO anggak-anggak -- galak, sombong, keras. Itu karena muridnya banyak inlander. Di HBS, sinyo-sinyo dan noni-noni hidup dengan bebas. Saya lebur dalam dunia Barat. Sekali lagi, saya hidup dalam dua dunia: dunia modern dan dunia Islam. Tetapi sinyo-sinyo dan guru-guru Belanda itu tidak membedakan pergaulan dengan kalangan pribumi. Di sini saya diajarkan berbagai mata pelajaran. Yang paling saya senangi adalah pelajaran sejarah. Tapi yang mengenai Indonesia seperti sejarah Diponegoro hampir tidak ada. Semua sejarah Eropa. Ada Revolusi Prancis, sejarah revolusi Amerika, sejarah pergolakan di Eropa tahun 1948, imperialisme di Eropa, Terusan Suez di bledak tahun 1870 dan sebagainya. Saya sampai hafal. Setelah lulus dari HBS tahun 1935, saya terlempar dalam perjuangan. Tahun 30-an, sebelum 1935, Kota Surabaya masih bergolak. Tahun 1932-1932 ada krisis ekonomi di dunia. Saya masih di HBS. Saya belajar ekonomi juga. Karena ada krisis Belanda mengadakan onslag -- pengurangan tenaga-tenaga pegawai. Bayaran dipotong. Opsir-opsir cuma kena 10%. Kemudian yang rendahan kena 30%. Akibatnya, pergolakan semakin meningkat. Di Marine Surabaya, ada yang namanya Kapal VII. Mereka mengadakan pemogokan dan ditangkapi. Sementara ada kapal yang berlayar ke Aceh. Mendengar adanya penangkapan di Surabaya, mereka berontak. Teman saya, Aleks kebetulan menjadi Marine. Dia yang bercerita pada saya. Marine-marine pribumi yang ada di kapal menuju Aceh menangkap kapten kapal -- orang Belanda. Peristiwa ini mengagetkan dunia. "Bukan main orang-orang Indonesia itu." Pak Sungkono ikut di dalamnya. Mereka berlayar kembali ke Surabaya, menuntut supaya kawan-kawannya dilepaskan. Tetapi kemudian bom oleh kapal udara di Bengkulu. Menyerah. Di HBS Surabaya, ini menjadi pembicaraan. Guru saya, Direktur HBS masuk kelas saya, kira-kira jam 12.00. Saya waktu itu berada di kelas mekanika. "Kamu dengar bahwa pemberontakan sudah dihancurkan. Bom sudah dijatuhkan." Ketika guru itu keluar, salah seorang teman perempuan berteriak sambil tepuk tangan, "Horeee.....!" Lha... guru saya yang lain, yang kebetulan masih di kelas, marah, "Kenapa kamu tepuk tangan. Apa kamu tidak tahu mengapa mereka berontak. Mereka berontak karena melawan ketidakadilan ...." Jadi, di kalangan Belanda sendiri ada perbedaan pendapat, ada yang tidak menyetujui kebijaksanaan Belanda. Nah, itu yang membawa saya ke suatu pemikiran, bahwa perjuangan kemerdekaan tidak harus ditujukan kepada orang-orang Belanda, tetapi kepada sistemnya. Ini pengaruh HBS kepada saya. Ketika tahun 1933 pemimpin surat kabar Suara Umum, Pak Tjindarboemi ditangkap, Bung Karno dibuang ke Digul, saya masih kelas IV HBS. Di tengah situasi macam itulah masa muda saya berlangsung. Sementara Filipina dijanjikan kemerdekaan. Saya belajar jua soal itu. Di HBS pula saya belajar kebudayaan Barat: musik, filsafat, dan sebagainya. Siang saya di lingkungan Belanda, malam di kampung. Pergolakan tahun 1933, 1934, 1935, menempatkan saya dalam satu situasi di mana saya tidak dapat tinggal diam. Apalagi kemudian saya masuk ke sekolah guru Belanda di Surabaya -- namanya OIK. Sebab saya mau jadi guru. Di situ hanya ada 4 (empat) murid pribumi dari sekitar 300 murid. Dua orang Bali, satu anak Ambon, satunya saya sendiri. Tahun 1935 saya dikeluarkan dari sekolah guru. Karena apa, karena saya anggota Indonesia Moeda. Padahal saya, akan menghadapi ujian terakhir. Tetapi maksud Belanda yang sesungguhnya adalah kalau saya lulus sebagai guru Belanda, maka saya berhak mengajar di sekolah Belanda. Saudara tahu, dulu ada sekolah untuk pribumi dan untuk orang Belanda. Itu berarti seorang guru berkulit sawo matang berhadapan dengan murid-murid kulit putih. Dan berarti pula, murid kulit putih harus hormat pada kulit berwarna. Saya memang menjadi anggota Indonesia Moeda sejak tahun 1932. Kemudian tahun 1933-1934 menjadi Ketua Indonesia Moeda Cabang Surabaya. Saya menggerakkan Gerakan Kendi. Yaitu, supaya Indonesia Moeda tidak hanya menjadi wadah para pelajar saja, tetapi juga seluruh rakyat. Mengapa kendi? Rakyat kalau minum 'kan dari kendi, bukan dengan gelas. Kendi kita idealisir sebagai lambang kerakyatan. Ya, itulah, akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah guru. Jadi bagaimana? Saya minta ke sekolah militer di Breeda, Negeri Belanda. Saya boleh, karena saya dari HBS. Tetapi tidak bisa, karena saya bukan dari keraton. Waktu itu ada peraturan, orang pribumi yang boleh ke Breeda hanya mereka yang dari Keraton Solo, Yogya, Paku Alam, Surakarta. Lalu, saya mau jadi pilot. Tapi juga tidak bisa. Karena, menurut mereka, kupingnya orang Indonesia ada yang tidak beres. Kalau saya jadi pilot, nanti akan jatuh. Akhirnya saya terjun ke perguruan partikelir. Saya di Kweek School Islamiyah dan Perguruan Rakyat. Di samping itu, masih ada Taman Siswa, tapi saya tidak di sana. Itulah kurun 1936, 1937, 1938. Pada waktu itu, saya bisa bebas dalam pergerakan Indonesia Moeda. Tahun 1936, awal saya dipilih menjadi Ketua Indonesia Moeda Seluruh Indonesia. Karena pada tahun 1935 itu Sukarni, yang ada di Jakarta, diuber-uber oleh polisi. Dia bisa sembunyi di bawah tanah sampai Jepang masuk. Ya, itulah, akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah guru. Tahun 1937-1938 ada penangkapan-penangkapan anggota Indonesia Moeda. Saya termasuk dalam daftar yang akan dibuang. Ini menurut informasi pihak polisi Belanda yang didengar orang-orang di Surabaya. Dr. Sanusi keluaran Sekolah Tinggi Rotterdam -- dan Ir. Darwamawan Mangoen Kesoemo, adiknya Dr. Tjipto Mangoen Kesoemo. Mereka yang menolong saya. "Kamu berhenti saja dari Indonesia Moeda dan perguruan partikelir, kemudian kerja sama saya." Mereka punya yayasan koperasi untuk memberi penyuluhan pada produksi kerajinan tangan. Namanya Sentral Koperasi Kerajinan Kecil. Sejak tahun ]937 saya berhenti dari aktifitas politik. Ketika kongres Indonesia Moeda berlangsung pada 1937, saya digantikan oleh Soejono Hadinoto, sementara saya kemudian ditarik Ir. Darmawan dan Dr. Sanusi. Itu berarti polisi tidak bisa menangkap saya. Tetapi bukan berarti saya tidak ada kontak dengan anggota-anggota Indonesia Moeda lainnya. Saya terjun ke aktivitas ekonomi, bekerja di koperasi untuk memajukan kerajinan tangan di kalangan rakyat. Selama dua tahun saya keliling desa. Hingga saya mengenal betul keadaan desa. Sebelum itu saya di kota saja. Pergi ke Madura, ke penyamakan kulit, masuk desa, mengorganisir, memberikan penyuluhan tentang teknik-teknik pembuatan secara modern. Saya dibantu oleh guru-guru teknik. Kemudian saya pergi ke Pasuruan, di sana ada kerajinan tangan membuat mebel. Pergi ke Sidoarjo. Di sana ada kerajinan pandai besi. Kami memberikan penyuluhan bagaimana membuat luku -- bajak -- supaya lebih baik. Saya masih ingat, ketika saya pergi juga ke Belimbing -- Malang. Di sini ada kerajinan rotan. Sekarang kerajinan rotan di Belimbing sangat maju. Saya juga memberikan penyuluhan mengenai pembuatan perahu-perahu kecil di pinggir Sungai Brantas, mulai dari Kediri sampai Mojokerto. Ketika Jepang masuk tahun 1942, saya tetap di Surabaya. Pikiran kita, apa betul Jepang akan memerdekakan kita atau tidak. Janjinya 'kan akan memerdekakan. Tapi kita ndak percaya. Dan ibu saya percaya pada Joyoboyo (ramalan Joyoboyo). Begitu Jepang masuk dia menanam jagung. Sebab jika nanti jagung sudah berbuah, Jepang akan mundur. Dan nanti Nusantara akan merdeka, tapi dengan wuah geih (banjir darah). Itulah mistiknya orang tua. Kita anak muda juga yakin bahwa Jepang nanti akan mundur. Ir. Darmawan pandai sekali menganalisa berita-berita yang ada, kekuatan Jepang tentu akan kalah terhadap Amerika. Soal kalahnya kapan, nggak tahu. Zaman Jepang adalah zaman yang penuh dengan kekejaman, zaman yang penuh dengan kesulitan-kesulitan. Tetapi, zaman Jepang yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan. Saya tidak ikut Peta (Pembela Tanah Air). Saya dimasukkan dalam pendidikan semi-militer. Enam bulan lamanya, sejak akhir 1942 sampai permulaan 1943, saya di Jakarta. Jadi, dari Surabaya saya bersama-sama dengan kira-kira 600 pemuda, ditunjuk oleh Jepang untuk mengikuti pendidikan semi-militer di Bruderan, sekarang jadi kantor Pertamina. Pemuda-pemuda dari seluruh Jawa yang ditunjuk Jepang dikumpulkan di sana. Nantinya akan dijadikan tenaga sipil yang memiliki pendidikan militer. Selesai dari latihan militer saya kembali ke Surabaya. Dan saya kembali dipekerjakan di Sentral Koperasi Kerajinan Kecil. Nanti saya akan dijadikan bupati. Rencananya begitu. Tapi saya terus ndekem (meringkuk) di koperasi kerajinan. Tahun 1944, akhir 1945, Jepang menjanjikan Indonesia merdeka. Jenderal Tojo Hideki, Perdana Menteri Jepang datang kemari. Menjanjikan kemerdekaan itu. Bung Karno keliling ke mana-mana. Semula mendirikan Poetera (Poesat Tenaga Rakjat). Saya ikut sebagai pengurus cabang Surabaya. Suatu saat Bung Karno datang ke sana. Itulah pertama kali saya bertemu Bung Karno. Saya lupa tanggal dan harinya. Yang jelas saya masih anak muda, Bung Karno sudah gagah. Kasih tangan. Makan sama-sama. Tetapi dengan yang lain-lain. Ndak saya sendirian. Waktu itu Bung Karno datang dengan Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansyur, mereka 'Empat Serangkai'. Saya nggak sempat mengobrol dengan Bung Karno atau Bung Hatta. Nggak berani. Ha-ha-ha .... Saya kan masih muda. Sebenarnya kita -- pemuda -- nggak setuju main komedi dengan Jepang. Lha . . ., Bung Karno juga ikut main komedi. Nyanyian kita waktu itu, "Amerika kita setrika, Inggris kita linggis." Waktu itu Bung Karno berkata tegas, "Kita harus membantu Jepang. Sebab, nanti kita akan dapat kemerdekaan. Dan kemerdekaan ini musti kita persiapkan sekarang." Itu kan komedi. Pemuda nggak setuju -- tapi cuma dalam hati. Peristiwa 10 November 1945 SURABAYA dinyatakan dalam keadaan perang sejak 1944. Sekutu sering mengebom. Dan di sana diberlakukan jam malam. Lampu harus dibungkus, lampu jalan dimatikan. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Angkatan Muda Surabaya masuk ke sentral listrik, dan memaksa supaya dibuka. terutama lampu-lampu jalan yang dimatikan dari sentral karena tidak bisa dibungkus. Itu yang membawa suatu perubahan psikologis luar biasa. Orang yang hampir setahun hidup dalam gelap, sekonyong-konyong cemerlang. Rakyat mulai keluar. Nah tanggal 28 Oktober adalah pertempuran pertama dengan tentara Inggris. Mereka minta senjata yang kita peroleh dari Jepang. Kita bertempur tiga hari: 28, 29, 30 Oktober. Jakarta bingung. Tentara Sekutu di Wonokromo, Gubeng, Gedung HBS, Gedung Internatio dikepung rakyat. Komandannya resminya Pak Sungkono. Tapi zaman itu rakyat bergerak secara spontan. Bung Tomo memegang radio. Saya lari-lari saja. Saya kan jadi sekretaris KNIP. Pada saat enam ribu tentara Inggris terjepit, Inggris di Jakarta minta bantuan. Mereka menghubungi Bung Karno, Hatta, dan Amir Syarifuddin. Tiga orang inilah yang dibawa ke Surabaya tanggal 29 Oktober untuk mendamaikan. Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir memarahi kita. "Bagaimana ini orang Surabaya? Ini kan Sekutu! Senjata-senjata itu kan hak internasional." kata Bung Karno. Persetan dengan hak internasional. Masa ngerti orang Surabaya. Tanggal 30 Oktober pertempuran dihentikan. Dari Jakarta datang Jenderal D.C. Howthorn -- panglima tentara Inggris untuk seluruh Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Kemudian kita berunding di kamar Gubernur -- Pak Suryo. Saya jadi sekretaris dari pihak Indonesia. Inggris juga menunjuk seorang kapten sebagai sekretaris. Hadir waktu itu Pak Sungkono, Pak Suryo, Bung Karno, Bung Hatta, Amir Syarifuddin, Bung Tomo, dan lain-lain, termasuk saya. Dari pihak Inggris hadir Jenderal Hawthorn, Jenderal Mallaby, Kolonel Pugh, dan sejumlah perwira lainnya. Di sini diputuskan, tentara Inggris akan ditarik mundur dari selatan -- dari Darmo dan sebagainya -- untuk kemudian berada di daerah pelabuhan. Rakyat tidak boleh menghalanginya. Untuk itu perlu dibentuk kontak biro, yang terdiri dari pihak Inggris (Mallaby dan sebagainya) dan pihak Indonesia (Pak Dirman, Pak Dul Hernowo, dan sebagainya). Di pihak Indonesia saya jadi sekretarisnya. Saban kali kita berunding. Hasilnya, rakyat sudah bersedia mundur, terkecuali yang di Gedung Internatio. Dari jam 6 pagi sampai sore gedung itu dikepung rakyat. Rakyat tidak mau mundur. Bung Karno dan Bung Hatta sudah kembali ke Jakarta. Tetapi melihat keadaan itu mereka kembali. Di sekitar gedung itu memang banyak orang Madura. Mereka berani-berani. Nggak mau mundur. Terpaksa sore itu kita datang ke sana. Mallaby, Pak Sungkono, saya, dan lain-lain sama-sama berangkat, bermaksud mendamaikan. Ketika sedang berusaha mendamaikan, dari dalam gedung ada rentetan tembakan ke luar. Akibatnya, bukan malah gencatan senjata, tapi pertempuran lagi. Di tengah-tengah pertempuran tanggal 30 Oktober sore itu Mallaby mati. Jangan tanya siapa yang membunuh. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Saya sendiri nyemplung ke Kali Mas, di dekat Jembatan Merah. Jakarta bingung lagi. Pemerintah Pusat bertanya siapa yang mateni -- membunuh. Kita jawab, "Tidak tahu". Inggris mengeluarkan pengumuman, "Ini adalah pembunuhan yang kejam. Maka, kita akan mengambil tindakan tegas terhadap ekstremis-ekstremis." Kita jawab, "Kita tidak tahu siapa yang membunuh. Dia terbunuh dalam pertempuran, karena Inggris menembak lebih dulu." Pada waktu itu kita pun punya risiko kena tembak juga. Korban banyak sekali waktu itu. Esok harinya tanggal 1 November 1945 tidak ada pertempuran, sebab Pak Mohammad ada di situ. Rakyat mau mundur, tentara Inggris juga mundur ke pelabuhan. Tanggal 1, 2, 3 November Kontak Biro bersidang lagi. Saya ketemu Kapten H. Shaw lagi. Dia ini sekretaris dari pihak Inggris dalam perundingan-perundingan di Surabaya. Saya dari pihak Indonesia. Saban kali setiap bertemu dengan Kapten Shaw, anak-anak tentara pelajar menjadikan saya kapten. Padahal, sebelumnya saya bukan kapten. Tapi menurut mereka karena sekretaris pihak Inggris adalah kapten, maka saya juga harus berpangkat kapten. Anak-anak lapor pada Pak Sungkono supaya saya dijadikan kapten. "Yo, wis, dadekno kono (Ya, sudah jadikan situ)," jawab Pak Sungkono. Maka, saya jadi kapten, dapat pistol, sepatu, pangkat. Makanya, sampai sekarang kalau ketemu teman-teman seperjuangan, mereka memanggil saya "Cap" (Captain). Mallaby diganti oleh Jenderal Manserg. Tanggal 6 November 1945, Manserg ingin bertemu dengan Pak Suryo. Sikapnya angkuh sekali. Waktu itu kita mendapat laporan bahwa Pak Darpo terpegang oleh Inggris di Tanjungperak. Dia berhasil meloloskan diri, dan melaporkan pada saya bahwa banyak sekali tentara Inggris yang mendarat. Kebetulan Amir Syarifuddin, menteri penerangan waktu itu, ada di Surabaya. Dia marah. "Jangan kena provokasi. Inggris tidak akan mendaratkan lagi tentaranya," katanya marah. Padahal, Inggris mendaratkan 24.000 tentara. Itulah sebabnya mengapa sikap Manserg pada Pak Suryo tidak beres. Pak Suryo sendiri sejak tanggal 7-8 November mau lagi bertemu dengan Manserg. Nah, tanggal 9 November kita diundang lagi ke tempat perundingan di Batavia Wecht. Saya, Pak Doel Arnowo, Kundang datang. Pak Suryo ndak mau datang. Saya bawa surat dari Pak Suryo yang isinya, "Saya tidak mau lagi terima Tuan, kalau Tuan tidak bersopan santun." Pulangnya saya bawa juga dari Manserg buat Pak Suryo. Kira-kira sudah jam 11 siang. Ketika dibaca kita kaget. Isinya adalah ultimatum. "Kalau jam enam sore polisi, pemuda, pemimpin pemerintahan, radio, kalau tidak datang di dua tempat, Perak dan Darmo, dengan angkat tangan bawa bendera putih, menyerahkan senjata, kemudian menandatangani penyerahan tanpa syarat, maka akan kita gempur Surabaya. Membersihkan kaum ekstremis, perampok-perampok!" Cak Doel Arnowo marah, "Kurang ajar!" Padahal, dia tidak bisa bahasa Inggris. Saya yang membacakannya. Tanggal 9 November 1945, kapal terbang Sekutu juga menjatuhkan pamflet-pamflet. Bunyinya, "Kalau jam enam sore tidak menyerah, maka Surabaya akan digempur." Sore itu kita rapat lagi. Bung Tomo, BKR, TRIP, Pemuda Republik, kumpul semua. Kita bersepakat untuk mengambil sikap tidak mau menyerah. Tetapi harus menelepon Jakarta dulu. Pak Doel Arnowo menelepon Pak Ahmad Soebardjo, menlu waktu itu. Keduanya kan berkawan sejak dulu. "Bagaimana ini?" kata Pak Doel. "Sabar dulu. Ini baru diadakan perundingan dengan Inggris supaya Inggris mencabut ultimatumnya." Kira-kira jam sembilan malam (21.00), Bung Karno ditelepon Cak Doel. Bung Karno marah. "Wong Suroboyo iku bongo!" (bandel/keras kepala). "Pokoknya, tunggu, masih diadakan perundingan!" Kata Bung Karno. Jam 11 malam (23.00) dapat berita dari Jakarta, Inggris tidak mau menarik ultimatumnya. Besok pagi tetap akan menggempur Surabaya. Kita tanya apa instruksi Jakarta. Dijawab, "Terserah Surabaya!" Woo . . . enaknya 'terserah'. Itu jawaban Pak Bardjo. Kami waktu itu berkumpul di Hotel Maraike. Kita putuskan supaya Pak Suryo, Gubernur Jawa Timur, pidato radio. Rakyat sudah ingin dengar. Jam sebelas malam Pak Suryo pidato. "Segala usaha kita untuk mengusahakan perdamaian tidak berhasil. Apa boleh buat. Sekarang kita siap untuk menghadapi segala-galanya." Malam itu juga rakyat sudah membikin barikade. Tanggal 10 November 1945, jam 06.00 pagi bom pertama Inggris dijatuhkan, mengenai Gedung Kempetai. Terus mereka bergerak ke berbagai penjuru. Pertempuran berlangsung selama tiga hari. Pertempuran berikutnya terjadi di Tunjungan. Semula Inggris mengira Surabaya dapat direbut hanya selama tiga hari. Ternyata, sampai 21 hari. Pada malam sebelum pertempuran, istri dan anak saya ungsikan ke kenalan di luar kota. Begitu juga dengan kawan-kawan. Sementara itu, kita mundur terus, ke Plampitan, Kragan, Ketabang, sampai ke daerah Petemon. Terakhir di Darmo. Belakangan kita ambil keputusan: Surabaya dikosongkan! Juga rumah sakit. Para juru rawat sibuk mengangkat orang-orang sakit. Misalnya dari Rumah Sakit Simpang ke stasiun lalu diturunkan di Malang, Sidoarjo, Mojokerto. Tiga puluh ribu tentara Inggris yang dihadapi rakyat Surabaya. Begitu beratnya perjuangan fisik dan mental yang kita hadapi. Inggris sempat mengatakan "inferno". Dan inilah yang saya sebut urban guerilla warfare ("perjuangan gerilya di kota"), yang berbeda dengan rural guerilla di hutan-hutan. Surabaya menunjukkan hebatnya gerilya kota. Dan enam belas ribu rakyat Surabaya gugur. Menurut catatan pihak Inggris sendiri yang saya temukan ketika di London, korban tewas dan luka sekitar 6.315. Ini menurut catatan Inggris. Saya sendiri tidak tahu persis. Di pihak Inggris sendiri ya ribuan. Itulah peristiwa 10 November 1945. Tahun 1946 pemerintah menjadikannya sebagai Hari Pahlawan, untuk memberikan semangat kepada rakyat, karena kegagalan-kegagalan perundingan dengan pihak Belanda. Peristiwa Madiun Bulan Juli 1947 ada krisis dalam Kabinet Sjahrir. Di tengah-tengah krisis itu saya diangkat menjadi Sekjen Penerangan. Ketika Sjahrir jatuh dan digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin, saya dipanggil dari Malang ke Yogya. Saya diminta menjadi Sekjen Penerangan. Semula saya tidak mau, karena saya lebih senang hidup bergerilya. Sampai dua atau tiga kali, Pak Natsir yang waktu itu duduk juga dalam Kabinet Sjahrir. Pada panggilan ketiga saya diminta Natsir ke Gedung Negara, dihadapkan dengan Bung Karno. Pada waktu itu Bung Karno sedang menyusun kabinet. "Saudara saya perintahkan untuk menjabat Sekjen Penerangan dan pindah ke Yogya," kata Bung Karno. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa background-nya Bung Karno meminta saya? Kabinet Amir ini akan didominasi oleh PKI. Menteri penerangannya adalah Ir. Setiadji. Bung Karno dan Sjahrir menginginkan supaya Penerangan ini tidak kena pengaruh PKI. Jika saya tidak diangkat, Amir akan mengangkat orang lain. Akhir Juni sudah kelihatan PKI mendirikan Marx House di Solo, Madiun, Magelang, Yogya, dan lain-lain. Kerjanya adalah memperkenalkan paham-paham dan teori-teori Marxisme dan Leninisme. Saya baru mengerti mengapa Bung Karno memerintahkan saya jadi Sekjen Penerangan. Begitu saya menjadi Sekjen, dan Mas Harjoto Wakil Sekjen, Mualif Nasution sudah melihat bahwa Marx House-Marx House itu berbahaya. Apalagi akan ada kabinet yang dipimpin Amir Syarifuddin. Untuk menandingi kegiatan Marx House itu, kita merencanakan untuk menerbitkan pidato Bung Karno 1 Juni 1945, yang menandai lahirnya Pancasila. Kita pergi ke Bung Karno mengenai rencana itu. Bung Karno setuju, tapi mesti cari saksi. Mengapa harus ada saksi. Karena pidato itu ditulis dalam bentuk stenografi. Pak Radjimanlah yang disetujui jadi saksi. Pak Radjiman ada di Desa Walikukun -- antara Solo dan Madiun. Kemudian Pak Radjiman tanda tangan pada buku terbitan pidato itu. Jadi, penerbitan pidato itu bukan untuk propaganda Bung Karno, seperti dikatakan banyak orang kemudian hari, melainkan untuk mengimbangi propaganda PKI. PKI waktu itu adalah suatu realita kekuatan. Mereka ada di dalam parlemen, mempunyai laskar. Sjahrir pun terpaksa bekerja sama dengan PKI. Begitu juga Bung Karno. Tetapi Bung Karno tidak menginginkan PKI menguasai. Di situlah saya baru mengerti mengapa saya ditaruh di penerangan. Sebab, begitu Kabinet Amir Syarifuddin terbentuk dan Ir. Setiadji jadi menteri penerangan, saya tidak pernah mendapat pekerjaan. Saya selalu dilangkahi Setiadji -- sebab dia kan dari Pesindo. Kedudukan saya memang sulit. Tapi tidak apa-apa. Pokoknya, saya tidak bisa disingkirkan karena saya langsung diangkat Presiden Soekarno. Untuk melancarkan propaganda mengimbangi PKI, kita membuat pedoman mengenai tugas Departemen Penerangan. Tugasnya antara lain: menerangkan Ideologi Negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar '45. Di samping itu menerangkan politik Pemerintah. Dalam UUD 45 itu ada pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Ribuan kita terbitkan untuk mengimbangi Marx House itu tadi. Selain propaganda dengan penerbitan, kita juga lewat hiburan, seperti wayang suluh. Kita tidak punya televisi, ketoprak, atau dagelan. Tapi yang terpenting. Lakon wayang suluh adalah Bung Karno, Bung Hatta, Van Mook, dan lain-lain. Rakyat senang. Amir Syarifuddin tidak bisa bertahan lama. Amir jatuh, bangkit Kabinet Hatta, tanggal 28 Januari 1948. Bung Karno tetap presiden, sementara Hatta perdana menteri merangkap wakil presiden. Sedang Natsir menjadi menteri penerangan lagi. Kepada Natsir saya bilang, "Natsir . . . bagaimana ini? Selama tujuh bulan saya digebuki!" Natsir menjawab, "Ya, memang. Bung Karno dan saya percaya kalau Saudara tidak akan dapat digulung oleh PKI." Iya, tapi saya mengalami kesulitan luar biasa. Dalam Kabinet Hatta, PKI dalam oposisi. Mereka menggerakkan laskar. Namanya waktu itu TNI Masyarakat. Amir pada waktu menjadi perdana menteri merangkap menteri pertahanan. Dialah yang membentuk TNI Masyarakat. Ketika sudah tidak jadi menteri pertahanan, TNI Masyarakat berubah menjadi laskar. Mereka ikut demonstrasi menuntut bubarnya Kabinet Hatta di Yogya. Mei 1948 Bung Karno memanggil Ki Hajar Dewantara, agar tanggal 20 Mei 1948 diadakan peringatan 40 tahun Kebangkitan Nasional. Inilah untuk pertama kali Hari Kebangkitan Nasional dirayakan di Yogyakarta, di tengah-tengah bentrokan antara PKI dan partai-partai lain. Di situ dicoba untuk dipersatukan antara PKI dan partai-partai lain. PKI juga ikut merayakannya, tetapi untuk taktik saja. Bulan Agustus 1948, Hatta mengadakan perundingan dengan Belanda. Di tengah-tengah perundingan itu, Muso datang dengan Suripno dari Eropa Timur. Muso menyamar jadi sekretaris Suripno. Kira-kira bulan Juli 1948. Mereka datang dari Praha, mendarat di New Delhi, lalu mendarat lagi di Rangoon, Burma, baru kemudian mendarat di Bukittinggi, Padang. Dari Padang mendarat di Campur Darat -- Tulungagung. Terus naik kereta api ke Yogya. Ketika mau lapor, sekretaris Suripno menghilang di Solo. Kemudian si sekretaris itu muncul sebagai Muso. September 1948 Muso mengoper pimpinan di Partai Komunis Indonesia. Dia mengatakan, "Salah taktik kerja sama dengan Sjahrir, dengan Hatta, dengan kaum nasionalis." Memang, di Eropa ada kerja sama antara komunis dan kapitalisme untuk melawan Hitler. Begitu Hitler kalah, Komintern (Komunis Internasional) dibangun lagi. Waktu itulah dicanangkan untuk tidak bekerja sama dengan Barat, juga dengan kaum nasionalis. Jadi, apa yang dijalankan oleh Alimin, oleh Sardjono, semua salah menurut Muso. "Saya, Muso, dapat instruksi baru: tidak boleh kerja sama. Keliru itu Linggarjati, keliru itu Renville. Harus dibatalkan!" Nah, Amir terjepit. Untung, waktu itu Sjahrir sudah memutuskan hubungan dengan sayap kiri, kemudian mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Muso dapat merebut kekuasan. Dan instruksi Moskow, sekarang harus melawan. Hatta yang menjalankan Renville disalahkan. Tanggal 3 September 1948, di parlemen Hatta menjawab. Saya ada di situ sebagai Sekjen Penerangan. Bung Hatta berkata, "Aneh ini. Dulu Renville yang menandatangani Saudara-Saudara. Sekarang Saudara minta membatalkan. Kita yang dulu tidak setuju malah melaksanakan. Ini kan persetujuan internasional," Hatta juga berpidato, "Kita tidak bisa menuruti keinginan PKI." Lha, PKI berkata, "Batalkan. Dan kita mesti bergabung dengan Moskow. Saudara anti kolonialisme, anti imperialis, Moskow juga anti kolonialisme-imperialisme. Kenapa kita tidak bisa bersatu?" Bung Hatta menjawab lagi, "Mengapa kita harus bekerja sama? Di sini perbedaan kaum nasionalis dan komunis. Komunis selalu berkiblat kepada Moskow, kaum nasionalis tidak. Sekalipun kaum nasionalis anti imperialis, anti kolonialis, dalam menentukan strategi mesti didasarkan pada situasi Indonesia sendiri. . . " Cocok dengan Bung Karno. Di samping melakukan gerakan di parlemen, PKI juga mengadakan gcrakan-gerakan di luar parlemen. Yaitu demonstrasi. Beberapa anggota redaksi harian Katholik dan harian Nasionalis diculik. Muso kemudian keluar ke Madiun. Tanggal 1 September ia memproklamasikan "pemerintahan" yang lepas dari pemerintahan Yogya. Karena Yogya dituduh antek Amerika. Namanya Negara Soviet Indonesia. Saat itulah Bung Karno mengucapkan pidato yang terkenal. "Saudara-Saudara, Rakyat Indonesia, kemarin PKI di bawah pimpinan Muso telah merebut kekuasaan di Madiun. Dengan begitu, menentang Republik Indonesia dan akan mendirikan satu Republik Soviet. Sekarang saya serukan kepada rakyat, pilihlah Muso yang akan membawa kebangkrutan atau kamu pilih Soekarno-Hatta yang insyaallah akan mengantarkan kita kepada satu kemerdekaan yang tidak dipengaruhi oleh negara asing mana pun." Kalau saya mengingat kembali Peristiwa Madiun ada yang namanya Badan Kongres Republik Indonesia. Juga banyak pemuda Republik di Surabaya, yang dulu teman saya, dalam peristiwa itu harus berhadapan. Pada waktu kita mengadakan pembersihan terhadap Madiun yang sudah dikepung, saya kebetulan di Jawa Timur, ikut Pak Sungkono. Kita melihat kekejaman PKI di Nganjuk, Ngawi, Ngrambi, dan desa-desa lain. Kita kaget bukan main. Saya melihat anak-anak yang ikut dalam Republik kok begini. Saya kemudian menarik kesimpulan bahwa benar apa yang dikatakan dalam revolusi Prancis, "Revolusi kadang-kadang menelan anak-anaknya sendiri." Bulan September-Oktober, saya datang ke Dungus -- dekat Madiun -- bersama-sama Pak Sungkono, disetop oleh tentara. "Pak, kita menangkap 35 orang-orang PKI. Pegawai Penerangan yang dibunuh PKI ada sekian orang. Sekarang kami sedang membuat Dewan Hakim di Medan Tempur. Ketuanya Kapten Gadyo -- komandan regu. Kemudian seorang dari pamong praja. Sekarang, kami butuh anggota satu lagi," kata tentara itu. "Untuk apa?" tanya saya. "Untuk memeriksa 35 orang ini. Mana yang dihukum mati, mana yang tidak." Sore itu, mulai jam dua siang sampai jam lima sore, saya dan Pak Sutomo Djohar Arifin -- sastrawan penulis buku Andang Taruna -- terpaksa ikut menentukan siapa yang harus dihukum mati. Ukurannya apa? "Ukurannya rasa keadilan Bapak," kata pemeriksa lain. Ya, sudah. Lalu kita tanya segala macam secara cepat. Pemeriksa satu berkata "hukum mati". Saya bilang tidak. Maka, tidak mati. Ada juga yang mati, karena memang terbukti membunuh orang Penerangan. Akhirnya, dari 35 orang 15 dihukum mati. Sore itu harus dilaksanakan, dan saya harus menghadirinya. Masing-masing harus menggali lubangnya sendiri. Sesudah itu dicopoti bajunya, karena bisa kita pakai. Kita memang kekurangan pakaian. Sesudah itu orang yang akan dihukum mati berdiri menghadap liang, lalu ditembak dari belakang. Ia lantas terjungkal ke lubang yang dibuatnya sendiri. Selesai kira-kira jam enam sore. Perasaan apa yang saya alami. Saya tidak bisa bisa berkata apa. Kami segera melanjutkan perjalanan ke Madiun. Tiba di rumah Residen Ardiwinata sekitar setengah tujuh malam. Di situ saya ambruk, nangis. "Nangis kena apa?" tanya Sutomo Djohar Arifin. "Kok revolusi ini begini, menelan anak-anaknya sendiri," kata saya. Bulan Oktober saya kembali ke Yogya. Dari Madiun saya sempat membawa satu peti uang Muso. PKI sudah mencetak uang bergambar Muso. Saya bawa ke Yogya sebagai bukti. Sementara kita masih terus menguber sisa-sisa PKI, tanggal 19 Desember Belanda berkhianat menyerang Yogyakarta. Belanda menjatuhkan tentara payung yang disertai boneka-boneka di Maguwo (lapangan terbang di Yogya). Kita mengira mereka sedang latihan. Baru kemudian dikasih tahu lewat radio bahwa kita diserang. Saya segera naik sepeda ke Rumah Sakit Petronella, di mana Bung Natsir dirawat. Lalu Bung Natsir mengeluarkan instruksi, "Lakukan pembakaran terhadap dokumen-dokumen." Pagi itu, saya segera mengumpulkan pegawai-pegawai Penerangan, untuk menjalankan instruksi A, B, C. Jam 10.00-11.00 saya diminta ke Gedung Negara untuk ikut Sidang Kabinet. Bom Belanda juga dijatuhkan di situ. Kita kirim kawat ke mana-mana, termasuk ke New Delhi. Suasana amat kacau. Ada yang kehilangan pulpen dan macam-macam. Jam 12.00 saya kembali ke Jalan Code kantor Penerangan -- melanjutkan tugas. Saya tidak mengikuti lagi apa yang terjadi di Gedung Negara. Kira-kira jam tiga sore dokumen-dokumen sudah selesai dibakar. Kira-kira jam setengah empat saya naik sepeda dari Jalan Code -- sckarang dekat Hotel Garuda. Lha. . . di situ ada kapal terbang. Ret-tet-tet-tet . . . kena saya. Dan lima orang yang bersama saya, dua mati. Saya dibawa ke rumah sakit oleh mahasiswa. Antara lain oleh Karkono Kamadjaja -- ahli Javanologi sekarang. Saya diantarkan dengan dokar ke Petronella. Badan saya sudah getih (darah) semua. Luka-luka saya di pundak, kaki dapat disembuhkan. Tapi telapak tangan saya, sebagian jari-jarinya harus dipotong, karena terlalu parah. Tanggal 22 Desember 1948 saya ditangkap. Belanda cari rumah saya. Dikira saya sudah mati. Karkono mengantarkan dompet saya ke rumah. Keluarga saya bertanya. Karkono bilang tidak tahu. Setelah tiga hari istri saya tahu bahwa saya di Petronella. Kira-kira empat hari saya sudah bisa jalan. Pada hari keenam, sore-sore, ada tentara Belanda berteriak-teriak, "Mana Roeslan Abdulgani?!" Saya terus ditodong, ditarik, lalu ditandu, dibawa ke suatu ambulans, dibawa lari entah kemana. Empat hari kemudian baru saya tahu saya dibawa ke Rumah Sakit Yap yang diduduki Belanda. Karena dianggap berbahaya, saya ditaruh di kamar belakang, dekat kamar mayat. Setiap malam saya bisa tahu siapa yang meninggal. Nah, istri saya akhirnya tahu bahwa saya di situ. Ia sering datang ke sana. Sampai bulan Maret 1949 saya di situ. Dari situ kemudian saya dipindah ke Panti Rapih. Di sini saya ditahan sampai bulan Mei 1949. Nah, ketika Perjanjian Roem-Royen ditandatangani untuk memperjuangkan Yogya Kembali, Bung Karno akan kembali dari pembuangan. Sri Sultan Hamengku Buwono mengirim orang ke Rumah Sakit Panti Rapih, memanggil saya untuk mengikuti rapat para sekjen. Saya datang dengan tangan dibungkus naik andong. Rapat pertama dipimpin oleh Pak Sri Sultan, tentang bagaimana nanti Belanda mundur dari Yogya. Lha, waktu saya keluar, Belanda marahnya bukan main. Begitu saya kembali lagi ke rumah sakit, saya dimarahi. Setelah Belanda mundur, saya bebas. Saya diajak Sri Sultan untuk mengatur kembalinya Yogya. Tak lama kemudian Bung Karno kembali dari pembuangan. Nah, waktu Bung Karno datang, saya menemui beliau di Gedung Negara. Saya kasih tangan. Tapi saya kasih tangan kiri, bukan tangan kanan. Bung Karno menolak, "Ayo, mana tangan kananmu?" Saya waktu itu malu sebab tangan kanan saya cacat. Bung Karno bilang, "Ayo tunjukkan kebesaran jiwamu!" Ya, saya memberikan tangan kanan. Dari Dulu Dicurigai Konperensi AA di Bandung berjalan April 1955. Di situ dipilih Ketua Konperensi Ali Sastroamidjojo. Sekretaris, saya. Bagian Politik, Ali juga. Bagian Ekonomi, Ir. Roosseno. Bagian Kebudayaan, Mohanmmad Yamin. Jadi, aparat Konperensi Bandung itu di tangan orang Indonesia semua. Sesudah Konperensi AA selesai, disusul adanya Pemilihan Umum 1955 -- PNI dan Masyumi menang, Ali terpilih jadi perdana menteri kedua kali. Lha. . . mungkin karena Bung Karno melihat keberhasilan Konperensi AA, yang saya ikut di dalamnya, saya ditunjuk jadi menteri luar negeri. Tahun 1959-1962 saya menjadi Wakil Ketua DPA. Karena berkali-kali tidak bisa menguasai DPA, saya disingkirkan. Diganti oleh Pak Sartono. Saya tanya kepada Bung Karno, "Mengapa saya tidak didudukkan lagi?" Bung Karno bilang, "Saya akan jadikan kamu lebih tinggi." "Ya, salah saya apa?" "Tidak ada salah." "Lha, kenapa saya dijadikan tinggi?" Kadang-kadang dipromosikan tinggi supaya tidak rewel. Saya kan ndak mau. Satu jam saya bicara dengan Bung Karno di Istana. Bung Karno nggebrak meja. Dan Subandrio juga ada. Saya lihat Bandrio memang maling. Akhirnya saya tidak duduk lagi. Nah, karena Wakil Ketua DPA juga anggota DPA, maka saya anggota saja, sampai Mohammad Yamin meninggal dunia pada akhir 1962. Pak Yamin waktu itu kan menteri penerangan. Setelah Pak Yamin meninggal, Achmad Yani dan Gatot Subroto datang pada saya. Pak Gatot bilang, "Nanti kamu akan diminta Bung Karno menggantikan Yamin. Monyet, jangan sampai nolak, ya. . . !" Saya marah. "Pak, saya bukan monyet." Lha, Pak Yani bilang, "Kamu jangan marah. Kalau Pak Gatot bilang kamu 'monyet', berarti dia senang. Pak Gatot kan orangnya begitu. Kalau dia tidak senang malah bilang sebaliknya: 'Paduka Yang Mulia' begitu. Itu sinis. Sama Subandrio dia selalu berkata, 'Yang Mulia...' Kalau sama saya, 'Monyet'!" Terus saya bilang. "Saya nggak mau...." Pak Gatot bilang, "Kenapa nggak mau? Bandrio sudah punya kandidat buat ganti Yamin. Kamu mesti mau." Akhirnya memang betul. Mayor Jenderal Santoso, Sekmil Bung Karno, datang pada saya. Bilang, "Bung Karno ingin bertemu. Mengapa Saudara tidak mau lagi bersama." Ya, saya jawab terus terang, "Ya, Bung Karno kan tidak mau mendengarkan saya." Dia bilang lagi, "Ya . . . tapi Bung Karno perlu sama Saudara." Akhirnya saya datang ke Bung Karno. Saya bicara terus terang. "Ya, wis, ya, Cak. Kamu saya jadikan menteri penerangan. "Baik. Tapi dengan syarat," kata saya. "Apa syaratnya?" "Saya tidak mau didikte Bung Karno kalau saya menghadapi PKI." "Ya, ya...," jawab Bung Karno. Bung Karno kan orangnya gampangan. Itulah. Jadi, tahun 1963 saya jadi menteri koordinator merangkap menteri penerangan. Lantas bagaimana soal cita-cita kembali ke Undang-Undang Dasar '45 yang dulu dinyatakan lewat Manifesto Politik. Itu sekarang Menteri Penerangan yang menjalankan. Ada panitia Pembina Jiwa Revolusi. Dan karena saya yang sering menerangkan Manifesto Politik, yang sering dikatakan itu adalah USDEK, saya dijadikan Jubirusman. Jubirusman itu bukan pangkat, tapi nama yang diberikan orang, karena saya juru bicara dari USDEK dan Manifesto Politik. Tahun 1963 PKI mengubah strateginya. Kita rebutan lagi dengan PKI dalam berbagai hal. Di dalam pertentangan antara Moskow dan Peking, PKI tidak berpihak. Itu sampai 1963. Tahun 1963 sayap yang keras di dalam PKI menang. Antara lain Lukman dan Dipo. Mereka mengambil keputusan memihak RRC. Tahun itu juga mereka punya rencana Empat Tahun. Artinya, sejak 1963, dalam empat tahun, mereka mesti menang di dalam Pemilu 1967. Rencana itu jatuh ke tangan kita. Dikatakan mereka senang sekali bahwa Roeslan Abdulgani, Muljadi Djojomartono, Nasution, tersingkir. "Tahun 1967 nanti kita akan menang di dalam pemilu, sehingga kita bisa menguasai. Dalam posisi itu, keadaan saya terjepit. Maka itu, kemudian saya menerbitkan buku Kepada Bangsaku. Di situ saya katakan, "Bung Karno pada tahun 1948 mengutuk PKI. Kalau kamu sudah tidak beragama, tidak beriman, kamu jadi manusia yang buas." Bung Karno memang sudah dekat dengan PKI, karena PKI pandai sekali mencari muka. Mereka lapor pada Bung Karno. Jenderal A.N. Nasution juga kaget, "Kok kamu ngomong begitu." Hubungan saya dengan Bung Karno bukan berarti retak. Dia sering menasihati saya, "Kamu itu jangan begitu." Memang sudah tidak terlalu rapatlah. Tapi, tidak mau menyingkirkan saya. Saya juga tahu Bung Karno memerlukan imbangan. Sebab, taktik Bung Karno itu kan mau menasionalisasikan komumis. Saya tanya apa bisa. "Bisa!" jawab Bung Karno. Alasan Bung Karno ada tiga. "Satu, tentang teori Marxisme-Leninisme saya lebih tahu dari Aidit dan itu anak-anak." Mereka kan dianggap anak-anak oleh Bung Karno, karena Alimin, Muso, sudah tidak ada. "Dua, soal menguasai massa. Massa mendengarkan saya. Massa saya masih lebih besar daripada massa PKI. Ketiga, orang luar negeri, komunis luar negeri, kalau mau datang ke sini tidak bisa langsung menemui Aidit, mesti melalui saya." Saya katakan, "Bung, ini agak membanggakan diri sendiri." "Tidak. Pokoknya, saya yakin PKI bisa dinasionalisasikan. Nasakom, apa artinya? Nasionalisme tidak boleh yang nasionalisme yang kemenyan. Agama tidak boleh yang seperti Kartosuwiryo. Komunisme tidak boleh yang seperti Muso. Komunisme mesti menerima agama, komunisme mesti menerima nasionalisme," begitu Bung Karno. Lha... orang PKI manthuk-manthuk -- mengangguk-angguk. Yang geger Peking sama Moskow, marah-marah. Komunisme waktu itu, tahun 1961, 1962, 1963, sedang kuat-kuatnya. Eisenhower sudah agak kalah oleh Khrushchev. Ha . . . Bung Karno menganggap, mengapa komunis Indonesia mesti harus diperintah Peking atau Moskow. Jadi, Bung Karno waktu itu agak pongah. Dia juga memperhitungkan bagaimana kita menghadapi, padahal PKI tidak membuat kesalahan secara formal. Pemilihan Umum 1955 menang enam juta. Bung Karno juga melihat golongan Islam ke DI, sementara ada beberapa orang berkiblat ke Amerika. Inilah permainan taktik antara Bung Karno dan PKI. PKI iya, iya, tapi menikam dari belakang. Saya sering bicara dengan Bung Karno bahwa PKI berbahaya. Bung Karno sadar memang. Tapi kita harus mengetahui bahwa usia Bung Karno sudah 65-66 tahun. Dia punya sejarah enam puluh lima tahun. Apa saja sudah dia alami. Dibuang, dipenjara, membangkitkan semangat nasionalisme, memproklamasikan kemerdekaan, menghadapi DI TII, lemparan granat di Cikini, dan sebagainya. Bung Karno adalah pemain yang besar, musuhnya juga besar. Tetapi Bung Karno adalah orang yang mencintai dan membenci secara dalam. Dia cinta pada negeri, cinta pada keindahan, tapi benci pada kolonialisme. Dia bisa mikir dengan baik, tapi sewaktu-waktu tidak bisa berhitung. Itulah watak orang yang berbintang Gemini. Lha . . . terhadap uang dia tidak bisa ngitung. Orang tidak punya uang, kasih. Kadang-kadang dia minta kita untuk ngasih orang. "Iyo, Cak, ora duwe duit aku (Iya, Cak, tidak punya uang aku). Bung Karno kan juga kenal bapak saya waktu di Plampitan. Dia sering utang rokok, dan nggak bayar. Sering dia cerita sama saya, "Eee . . . aku isih duwe utang bapakmu. Bapakmu iku kapitalis (Ee . . . aku masih punya utang pada bapakmu. Bapakmu itu kapitalis). Jadi, sifat nggak bayar itu diteruskan sampai sekarang (tahun 60-an). Tapi dia nggak malu-malu kalau minta duit. Jadi itulah. Bung Karno sebagai ideolog, wah, hebat. Mengambil pelajaran dari Marxisme, dari agama Islam, kolonialisme, menggali dari bumi Indonesia sendiri. Lalu dia bilang, "Ideologi yang paling hebat Pancasila." Dia kaya di dalam cita-citanya, melarat di dalam uang. Bung Karno terlalu dipengaruhi intelnya PKI, BPI itu, di samping karena tua. Umurnya kan sudah 67. Capek. Bung Karno juga sudah kemasukan Nyono, kemenakan Subandrio. Di dalam dokumen PKI ada dikatakan, yang paling berbahaya itu Roeslan Abdulgani, saya. Dan saya pernah bilang sama Bung Karno, "Bung, awas, hati-hati sama komunis." Bung Karno malah bilang, "Ah, itu terlalu komunistofobi." Dan memang pada waktu saya di Seskoad, menerangkan artinya komunistofobi. Waktu itu ada Pak Harto, Pak Yani, dan lain-lain. Mereka nanya apa itu artinya komunistofobi. Saya katakan, "Sebetulnya arti komunistofobi tidak ada. Yang ada xenophobia. Xeno itu "asing". Phobia itu "takut". Jadi, ada bangsa yang takut sama bangsa asing. Maka itu, bangsa ini jangan takut sama bangsa asing. Berantas xenophobia. Jadi, sebenarnya istilah komunistofobi tidak ada. Bung Karno saja yang membuat. Artinya apa? Artinya, jangan takut pada komunis. Kalau perlu, gasaken -- gasak! kata saya di Seskoad. Eh, Bung Karno dengar. Ndak tahu siapa yang melaporkan. Saya dipanggil. "Cak, kon neng nggon Seskoad cerito opo, Cak? (Cak, kamu di Seskoad cerita apa, cak?)" Saya bilang, "Lho, kan benar, to, komunistofobi kan jangan takut pada komunis." "Jare kok tambahi (Katanya kamu tambahi)" "Ah, enggak....Tambahi opo?" Saya juga bilang, "Bung Karno ngajak kita rangkul-rangkulan sama PKI, Saudara-Saudara. Hati-hati, antara rangkulan dan cekikan tinggal satu jengkal" Haa . . . itu dilaporkan lagi. Tapi, kalau tidak begitu mau apa lagi ? PKI lagi kuat-kuatnya. Jadi, saya lihat, begitulah Bung Karno. Mestinya tahun 1963, setelah Irian Barat, Bung Karno mengundurkan diri. Pernah saya katakan, "Bung, sekarang seluruh Indonesia Kesatuan sudah tercapai." Waktu itu saya dengan Mohamad Said datang kepadanya, mengusulkan supaya Bung Karno mundur. Tapi, banyak vested interests yang tetap menginginkan Bung Karno memimpin. Akibatnya, kasihan Bung Karno. Saya percaya, bangsa ini akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin lain. Ucapan saya kepada Bung Karno soal ini, "Bung Karno may die, but the republic must not die", manusianya boleh meninggal, tetapi Republik yang berdasarkan Pancasila ini tidak boleh mati. Saya juga percaya pada kekuatan rakyat yang beragama dan nasionalistis, maka saya yakin meskipun Bung Karno tidak lagi jadi pemimpin, komunis tidak akan bisa menguasai. Ada yang bilang, "Roeslan itu warnanya bolak-balik." Itu nggak benar. Zaman Belanda saya berani melawan kolonialisme. Zaman Jepang saya ikut gerakan di bawah tanah. Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan saya ikut membela Republik. Zaman PKI saya ikut melawan. Juga pada Islam yang ekstrem. Pada waktu Pak Harto minta saya supaya mewakili Indonesia di PBB (1968-1972), saya tetap mencerminkan jiwa nonblok, jiwa Asia-Afrika, saya kerjakan dengan penuh kejujuran. Tahun 1972 saya kembali ke Indonesia. Saya pensiun. Saya diundang ke Australia, Jepang, dan lain-lain. Orang-orang di luar negeri selalu berkata, Tell me about your theory and your experiences. Saya masuk PNI waktu partai itu dihidupkan kembali tahun 1946 saya masuk. Menjadi anggota terus, sampai jadi Wakil Ketua IV tahun 1964. Bagi saya, partai itu untuk kebaikan, bukan untuk saya. Sebelumnya saya kan ikut Indonesia Moeda. Jadi, di partai, saya lebih banyak jadi anggota. Selama enam tahun, sampai tahun 1978, saya tidak ada pekerjaan di Indonesia. Katakanlah tidak laku di Indonesia. Tapi saya tidak pernah frustrasi. Karena saya bisa mengisi waktu. Akhirnya tahun 1978 bersama-sama dengan tujuh orang, saya diminta Pak Harto untuk menjadi Tim P-7. Sekarang kan sudah 10 tahun. Dan Pak Harto minta terus. Di samping itu saya tetap menulis. Menulis saya anggap untuk dapat memberi pendidikan kepada bangsa melalui tulisan. Sampai kapan saya menulis? Saya ini selalu olah jiwa, olah pikiran, olahraga. Olah pikiran, baca, kemudian menulis. Saya nulis biasanya diminta. Misalnya oleh harian Merdeka. Seminggu sekali mesti ada artikel saya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris melalui The Indonesian Observer. Jadi, saya ini ada semacam kontrak dengan Merdeka. Saya juga menulis di media-media lain. Di TEMPO saya sering menulis Resensi Buku. Dan saya senang menulis resensi, karena saya mesti baca bukunya, dan itu berarti belajar. Surabaya Post dan Amanah juga minta. Dalam menulis saya tidak dibantu orang lain. Saya mengetik sendiri, mengonsep sendiri. Seminggu minimal saya menulis dua artikel. Nah, artinya, manusia tidak boleh berhenti berolah pikiran. Di samping olah pikiran, kita juga harus olah jiwa, mendalami agama. Selain itu olahraga. Karena saya tidak punya uang untuk main golf, saya naik sepeda, jalan kaki bersama istri saya, kadang-kadang sendirian naik sepeda ke Monas. Setengah enam pagi, setelah salat subuh saya naik sepeda. Belakangan saya juga memberikan ceramah-ceramah. Di Lemhanas, perguruan-perguruan tinggi dan lain-lain. Meskipun begitu, saya tidak melupakan keluarga. Hubungan keluarga harus tetap dijaga. Cucu saya sekarang tujuh. Itulah sebabnya, saya tidak mau menghadiri ceramah atau resepsi pada malam hari. Kalau Minggu mereka datang. Di zaman dulu saya dicurigai, zaman sekarang pun ada yang dicurigai. Nah, curiga itu adalah konsekuensi bila kita ikut berpolitik. Di samping curiga ada simpati. Saya tidak melihat dunia itu black and white, tetapi warna-warni. Yang penting, kamu sendiri menempatkan diri dalam warna-warna itu. Saya percaya kepada nasionalisme, agama, keterbukaan, kejujuran. Niat saya adalah untuk berjuang, untuk kebaikan negara. Kalau ada orang yang tidak senang, curiga, biasa. Ada yang simpati, mendukung, juga biasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini