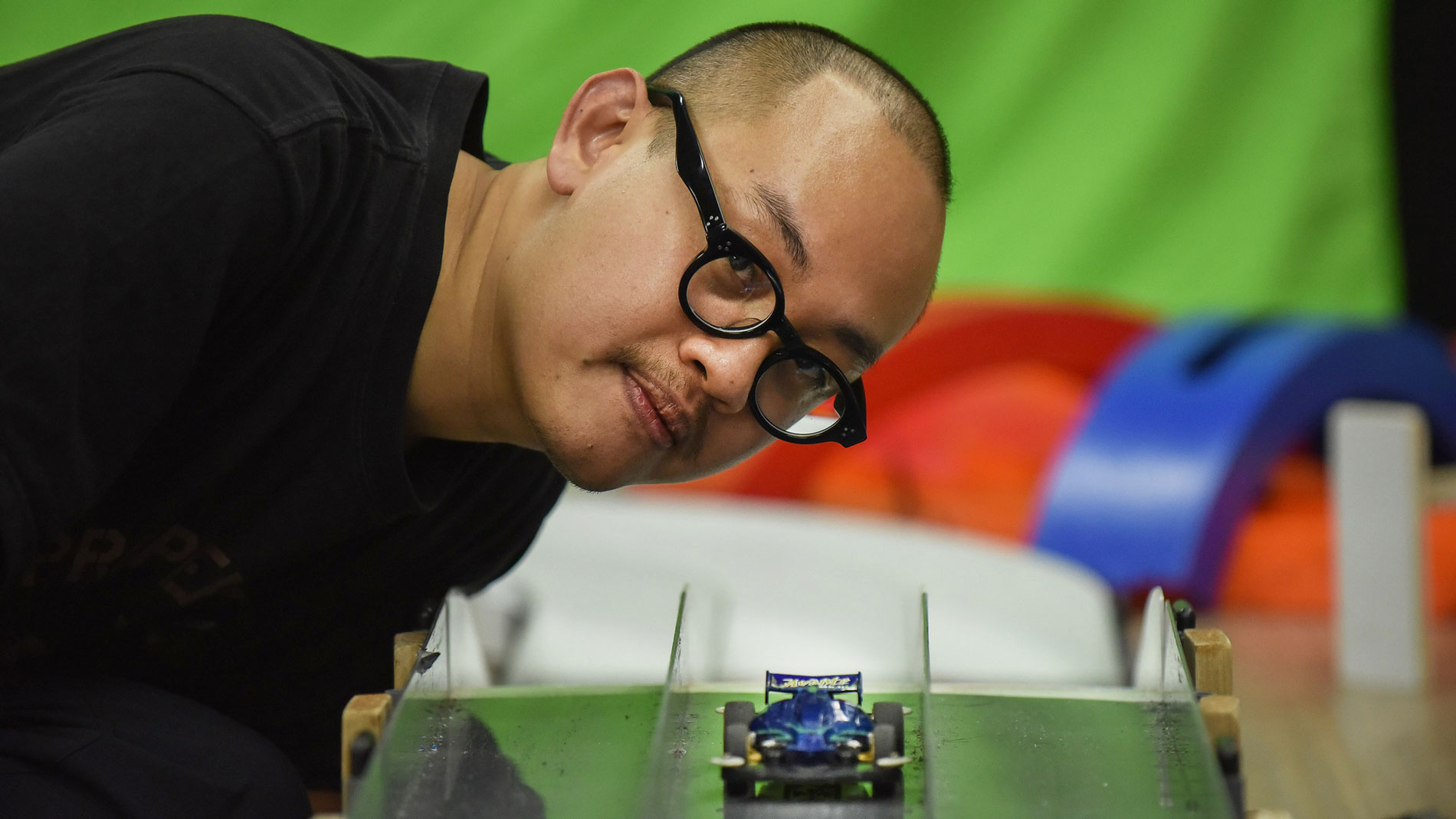Di Perumnas Banyumanik, Semarang Selatan, berdiri Gereja St. Maria Fatima. Di sana, Mgr. Justinus Kardinal Darmojuwono, 75 tahun, tinggal menghabiskan sisa hidupnya. Kardinal pertama, bahkan satu-satunya kardinal bangsa Indonesia itu, kini, memimpin sebuah paroki kecil dengan jemaat empat ribu orang. Setelah melepaskan jabatan sebagai uskup agung, ia memilih menjadi uskup biasa yang langsung melayani umatnya. Dalam menuturkan sebagian kisah hidupnya kepada Wartawan TEMPO Heddy Lugito, ia berbicara dalam bahasa Indonesia, yang sering diselingi bahasa Jawa dan kadang bahasa Belanda. SEBAGAI anak desa, saya senang dan bangga. Keluarga kami tidak kaya, namun cukup, boleh dikatakan harmonis. Hubungan Ayah, Ibu, dan anak-anak sungguh menyenangkan. Disiplin dalam keluarga sangat terjaga, kami semuanya harus kerja keras. Di samping sekolah, saya, kakak, dan adik saya harus kerja di rumah. Setelah pulang sekolah, ada yang kerja di sawah, memelihara tanaman di kebun, atau mencarikan rumput untuk makanan ternak. Karena kami memelihara beberapa ekor kambing, kerbau, dan sapi. Saya sendiri mendapat tugas memelihara tiga ekor kerbau. Di masa anak-anak hingga usia remaja, saya tinggal di Desa Kliwonan, Godean, kira-kira 13 kilometer sebelah barat Kota Yogya. Jadi, tidak jauh dari desa kelahiran Pak Harto. Dan saya pun dilahirkan di desa itu, 2 November 1914. Pada waktu itu sedang berlangsung Perang Dunia I, jadi, zaman rekoso (sulit). Pada saat kelahiran saya, menurut cerita Ayah, makanan susah didapat. Di mana-mana orang kekurangan. Ayah adalah lurah Desa Surodikoro. Ibu bernama Ngatinah. Seperti juga pada umumnya wanita Jawa di masa itu, ibu saya menangani pekerjaan rumah dan ngopeni (mengasuh) putra-putrinya. Selain kerja di rumah, sesekali Ibu juga ke sawah dan kebun. Itu sudah makan banyak waktu. Dari pagi buta hingga mau tidur, Ibu tak pernah berhenti kerja, ada-ada saja yang dilakukannya. Sebenarnya, saudara kandung saya ada delapan orang, tapi dua orang kakak saya meninggal waktu kecil. Saya tidak sempat mengenalnya, juga tak ingat siapa namanya. Dari semua saudara saya yang hidup, saya ini anak nomor dua. Kedua kakak saya laki-laki bernama Djamad dan Djanis. Saya sendiri sebenarnya bernama Djamin, tapi teman-teman sekolah saya memanggil Imin. Adik saya bernama Saminah dan Djamal, yang paling bungsu perempuan bernama Muginah. Kedua orangtua saya bukan Katolik, tapi juga tidak salat, ya, karena dia Kejawen. Dalam keluarga, kami biasa bikin macam-macam slametan (kenduri). Kalau kebetulan ada anggota keluarga yang meninggal, keluarga kami mengadakan slametan, membikin tumpeng, mengundang orang dan santri untuk ndaros (membaca) Quran. Kedua orangtua saya sungguh-sungguh religius. Artinya, setiap malam Jumat, Ayah selalu ngobong menyan, nyebar kembang di tempat yang dianggap keramat. Ketika saya tanya untuk apa Ayah melakukan hal itu, jawabnya: "Ya kanggo nyuwun marang ingkang murbeng jagad, supoyo olehe golek sandang pangan lancar. Supoyo anggonmu podo sekolah ugo lancar." (Ya untuk minta kepada Tuhan, agar mudah mencari sandang pangan. Supaya sekolahmu juga lancar). Mungkin saja orang-orang di desa saya bisa disebut orang abangan atau kejawen. Hanya ada satu masjid kecil di sana, gereja tak ada. Tatkala masih SD, di desa saya hanya ada tiga orang yang masuk sekolah, termasuk saya. Saya sekolah di Sekolah Dasar Desa Gedongan, waktu itu, namanya sekolah Ongko Loro, kira-kira lima kilometer dari desa. Saya selalu berjalan kaki bila pergi ke sekolah. Melompat-lompat di atas balok rel lori tebu. Jika pulang sekolah bersama teman-teman, kami memilih jalan terobosan yang dekat. Melintasi galengan (pematang) sawah dan ladang. Enaknya, kalau tebu sudah mulai tua. Saya dan teman-teman ngrampasi tebu, ha... ha.... Semua anak, waktu itu, sama. Kalau pulang sekolah, pasti nyolong tebu. Kami haus karena jalan kaki jauh. Kalau mau beli minuman, dilarang Ibu. Waktu anak-anak, saya jarang sekali bermain dengan teman-teman sebaya. Karena setelah pulang sekolah, harus kerja. Waktu bermain cuma sebentar, paling-paling ramai-ramai mandi di kali pada sore hari. Setelah itu, ada tugas lain. Sejak kecil, saya sudah terbiasa kerja keras, dari pagi buta hingga menjelang tidur. Meskipun kerja keras, saya senang dalam keluarga. Kami semua rukun, tak pernah cekcok. Di sore hari, kami sekeluarga makan bersama. Setelah makan, kami harus belajar. Sejak masih SD, setiap malam, saya selalu belajar. Di rumah, saya belajar di meja bundar, diterangi lampu teplok. Dua tiga orang teman sekolah SD selalu datang belajar bersama. Seusai belajar, Ibu pasti menyuguhkan makanan kecil dan teh panas. Apa adanya, dari ketela, singkong, kimpul, semuanya hasil kebun sendiri. Setelah lulus sekolah Ongko Loro (SD) pada 1931, kemudian saya diasramakan untuk sekolah guru pada Normall School di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dari sekolah guru, lalu masuk Seminari Menengah, Yogya. Di Seminari, saya harus sungguh-sungguh serius. Karena Normall School dasar bahasanya Jawa, sedangkan di Seminari bahasanya Belanda, semuanya harus mengulang dari kelas satu. Tapi, saya juga banyak dibebaskan dari beberapa mata pelajaran. Dari seluruh keluarga, yang Katolik cuma dua orang. Saya dan kakak saya yang bernama Janis. Dia lebih dulu. Pada mulanya, Ayah dan Ibu juga bukan Katolik, tapi akhirnya beliau berdua mengikuti jejak saya. Ayah dan Ibu meninggal setelah memeluk Katolik. Ayah meninggal pada 1952. Pada saat usia tua dan sudah sakit-sakitan, Beliau minta untuk saya baptis. "Aku ingin mengikuti jejakmu. Aku minta dibaptis. Tapi, aku tidak tahu apa-apa. Yang aku tahu cuma para nabi," ucapnya. Sebuah kitab yang ditulis dengan huruf Arab yang banyak dimiliki keluarga Jawa pada masa itu. Kitab itu berisi semacam riwayat hidup para nabi dan rasul. Setengah tahun kemudian setelah saya baptis, Beliau meninggal dan dimakamkan dengan tata cara agama Katolik. Dimasukkan dalam peti mati, dan diberi pakaian yang bagus. Pada saat upacara pemakaman, saya pun hadir. Waktu itu, Ibu berbisik kepada saya: "Kalau kelak aku meninggal, dandani juga seperti ayahmu. Dimasukkan peti, pakai baju segala." Ibu meninggal tepat di hari Natal 1963. Sesungguhnya, baptis itu tidak dapat menjamin seseorang untuk naik surga. Tatkala saya masih belajar di Seminari Yogya, dilaksanakan Natalan yang bagus sekali. Kalau ibu saya menyaksikan peristiwa itu, tentu saja, tidak akan bisa merasakan dan menghayatinya. Karena, ya, dunianya lain. Tapi, kalau ada surga, tentu, ayah dan ibu saya naik surga. Tidak hanya saya yang mengatakan bahwa Ayah-Ibu itu orang baik. Para tentangga, dulu, menyanjung Ayah-Ibu saya memang orang baik. Hampir semua tetangga saya beranggapan demikian. Kerajaan Allah bukan hanya ikut gereja. Kerajaan Allah adalah untuk siapa saja yang melakukan kehendak Allah. Kalau orang itu baik dan berbudi luhur, tentu, akan masuk kerajaan Allah. Yang dilihat Tuhan itu bukan yang serbanan, bukan pula yang jubahan, tapi hati. Kerajaan Allah lebih luas dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan lainnya. Karena Tuhan tidak bisa diukur dengan semua itu. Apakah semua orang yang ke gereja masuk surga? Koq, enak. Koq koyo ono karcis neng suwargo! (Kok, enak. Kok, seperti ada tiket masuk surga!) Artinya, ya, semua itu, yang penting hati. Maka, Konsili Vatikan juga menghargai semua agama. Kalau memang nggak bisa, kalau memang mau pindah agama, bisa. Tapi jalankan dengan baik, jangan seenaknya saja. Karena agama itu soal hati. Jika orang sungguh berbudi luhur, berbuat baik, sudah melaksanakan kehendak Tuhan, itu berarti sudah 'dipermandikan' secara batin. Ia juga berhak masuk surga. Sebaliknya yang secara formal beragama dibaptis segala macam, pakai atribut ini itu segala macam. Namun, prakteknya sehari-hari menyeleweng dari nilai-nilai susila. Lha, yang demikian, apa ya, berhak masuk surga? Janis, kakak saya, dulu sekolah pada sekolah Misi Katolik. Dari situ, lalu saya ikut membaca buku-bukunya mengenai Yesus, juga Kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, dan sebagainya. Lalu, saya tertarik. Pada 1932, ketika saya sedang sekolah guru di Muntilan, saya dibaptis dengan nama permandian Justinus. Yang membuat saya tertarik untuk menjadi pastor, karena saya terkesan oleh perilaku pastor-pastor Belanda. Tatkala di sekolah guru Muntilan, saya selalu ngluruk dan Cembengan (perayaan menjelang giling) di pabrik-pabrik gula. Kala itu, saya menyaksikan perbedaan tingkah laku Londo Pabrik dengan Londo Pastur (pastur Belanda). Kok, lain sekali. Londo-londo Pabrik itu punya gundik akehe ora karuan (banyak sekali). Selain itu, Londo Pabrik suka muring-muring (marah-marah) kepada orang-orang kita. Tapi, Londo Pastur kok lain, dia arif dan bijaksana, sopan dan tidak pernah marah kepada orang Jawa. Lalu, saya berpikir, daripada jadi guru, ah..., lebih baik jadi pastor sajalah. Setelah lulus sekolah guru, saya mendaftarkan diri di Seminari Menengah St. Petrus Canisius, Yogya. Mendengar bahwa saya ingin menjadi pastor, Ayah keberatan. Beliau menginginkan saya menjadi guru. Ketika saya matur kepada Ibu, Ibu mengizinkan. Tapi, Ayah tetap tidak setuju. Dengan suara lembut dan hati-hati, ia bertanya, "Kalau menjadi pastor itu berapa gajinya?" Saya jawab dengan sedikit ketakutan: "Saya dengar, tak digaji." Lalu, Ayah menasihati. "Pastor itu tidak kawin, tidak punya anak, tidak digaji. Orang hidup tak memiliki keturunan, dan tidak makan jerih payah sendiri, itu tidak lumrah." Saya tak berani membantah langsung. Saya ingat betul, sehari sebelum keberangkatan saya masuk Seminari. Pada waktu itu, 30 Agustus 1935 malam, seluruh sanak famili berkumpul di rumah saya. Simbah-simbah, Bopopaman, Pak De, dan sebagainya, semuanya berada di rumah pendopo. Ternyata, semua orang-orang tua yang hadir pada waktu itu sudah dibujuk Ayah, untuk membatalkan niat saya. Semua yang hadir menasihati agar saya tak menjadi pastor. Saya dengarkan baik-baik, saya tak berani membantah secara langsung. Meskipun waktu itu saya sudah berumur 21 tahun, mereka menganggap anak seusia saya sebagai bocah kemarin sore. Ketika orang-orang itu sudah pulang, saya jelaskan keinginan saya pada Ayah. Menurut agama Katolik, pastor itu panggilan Tuhan. Kalau pastor itu memang panggilan saya, meskipun sudah jadi guru, suatu ketika saya akan menjadi pastor juga. Tapi, kalau pastor memang bukan panggilan saya, meskipun saya sudah memakai jubah, suatu ketika saya akan mundur. "Aku tidak akan menentang panggilan Tuhan. Sebab, menentang Tuhan itu besar dosanya. Sudah, berangkatlah, aku berkati. Hanya, semoga menjadi pastor itu bukan panggilan jiwamu," kurang lebih demikian kata Ayah ketika saya akan berangkat. Setelah lulus dari seminari, saya melanjutkan di Seminari Tinggi St. Paulus, Yogya, pada 1941. Pada waktu saya kuliah Seminari Menengah, guru-gurunya masih lengkap semua. Tahun kedua saya di Seminari Tinggi, ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang, 1942, semua guru Belanda yang mengajar di seminari diinternir. Lalu banyak romo yang di luar ditarik untuk mengajar. Bahkan imam yang masih muda ditarik untuk dijadikan rektor. Habis, mau apa? PERISTIWA G30S-PKI Saya lulus dari seminari tinggi pada 1947, lalu pada 25 Mei 1947 saya ditahbiskan menjadi pastor oleh almarhum Mgr. Soegiyopranoto di gereja St. Antonius, Kotabaru, Yogya, bersama 3 orang imam lainnya, yaitu Romo Pusposoegondo, Romo Pojohardoyo, dan almarhum Romo Hadisudarso. Saat itu negara kita masih dalam suasana prihatin, pertempuran dengan tentara Belanda terjadi di mana-mana. Maka, tidak ada pesta besar-besar dalam tahbisan imam, seperti zaman sekarang. Bahkan juga tidak dibuat foto untuk kenang-kenangan. Sebagai pastor, pertama kali saya ditugaskan di Gereja Kidul Loji, Yogya. Tapi itu cuma berlangsung 35 hari. Kemudian saya ditugaskan di Ganjuran, Bantul, kira-kira 15 kilometer sebelah selatan Yogya. Ketika tentara Sekutu masuk Indonesia, tentara Gurka menguasai Ambarawa, Jawa Tengah. Tentara Gurka mundur, Ambarawa diduduki Belanda. Macam-macam pertempuran itu mengakibatkan Sekolah Seminari Menengah di Ambarawa cerai-berai. Pimpinan Gereja Vikarist Semarang memutuskan untuk mengumpulkan para seminaris di Ganjuran, Bantul. Dan kebetulan saya dipercaya untuk menangani mereka. Selain mengajar di seminari, saya dapat tugas melayani umat Katolik di sekitar itu. Ada juga tugas tambahan, yaitu mengelola rumah sakit di Ganjuran. Pada 1948, tatkala tentara Belanda mulai masuk Yogya, banyak tentara kita terluka karena pertempuran, mereka yang kami rawat di Rumah Sakit Ganjuran. Saya bekerja sama dengan BUDN, sebuah badan milik tentara. Apa artinya BUDN itu saya lupa. Tatkala Bantul mulai diduduki Belanda, banyak tentara yang ngungsi di rumah sakit kami. Kepada tentara yang tinggal di rumah sakit, saya sarankan pakai sarung dan berpura-pura menjadi orang sakit. Maka, ketika Belanda datang, saya katakan pada mereka bahwa yang tinggal semuanya orang sakit, kecuali saya dan suster-suster. Segerombolan tentara Belanda datang, memeriksa semua. Seluruh isi kamar mereka geledahi. Salah seorang bertanya pada saya, apa ada tentara. "Ini rumah sakit, yang ada orang sakit. Semua yang ada menjadi tanggung jawab saya. Kalau kamu akan mengganggu orang-orang di sini, saya akan laporkan pada atasanmu," jawab saya, lalu mereka pergi meninggalkan rumah sakit. Tentara kita yang sakit tetap aman. Pada masa itu bahan makan susah didapat, karena suasana perang. Uang ORI dinyatakan tak berlaku, yang berlaku uang gulden, uang Belanda. Saya keliling dengan sepeda ke berbagai tempat minta sumbangan apa saja, untuk membiayai para korban perang di rumah sakit, juga untuk memberi makan para seminaris, dan pengelola rumah sakit juga gereja. Pada waktu itu rumah sakit tidak punya apa-apa. Saya mencari kayu bakar untuk masak. Kalau tak ada kayu, ya tak bisa masak, kasihan yang sakit. Pertengahan 1950 saya pindah ke Klaten, Jawa Tengah, menjadi pastor paroki pada Gereja Maria Assumpta, Klaten, merangkap sebagai pastor pembantu militer. Pada waktu itu komandan militernya dipegang Pak Harto, yang sekarang menjadi presiden. Menjelang Natal 1950, pabrik gula Klaten dibumihanguskan. Siang-malam orang-orang mengangkuti gula dari pabrik itu. Bahkan ada yang mati tertimbun gula. Siang-malam orang-orang terus menjarah gula sampai habis. Tidak hanya barang-barang yang ada di pabrik gula yang dijarah rakyat, barang-barang yang ada di sekolah pun mereka angkuti. Bangku, kursi, bahkan dinding pun dicopoti. Mereka ketakutan akan bumi-hangus. Daripada diangkut Belanda, lebih baik diangkut sendiri. Kami masih beruntung, karena barang-barang milik pastoran dan gereja tidak diangkuti. Dari Klaten kemudian saya pindah ke Solo, pada 1952. Hanya beberapa bulan saya di Solo. Kemudian saya mendapat tugas belajar misiologi di Universitas Gregoriana, Roma. Saya belajar di sana selama satu tahun. Tapi, sebelum berangkat, saya masih sempat membaptis Ibu. Sekembali dari Roma, saya menjadi pastor pembantu di Purbayan, Solo, merangkap pastor pembantu militer. Selain itu, juga ditugasi merintis berdirinya sebuah gereja di Solo bagian utara. Pertengahan 1961 gereja itu mulai kami tempati, meskipun belum selesai seluruhnya. Kemudian saya diangkat menjadi bouwpastoor, atau pastor kepala, di gereja itu. Gereja itu kelak bernama gereja "Maria Regina Purbawardayan". Pada 1962 saya pindah ke Semarang, menjadi pastor kepala di Paroki Katedral Randusari, Semarang, merangkap Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang. Kemudian, 10 Desember 1963, datang surat dari Sri Paus Paulus VI, isinya mengangkat saya sebagai kardinal. Pengangkatan itu masih dirahasiakan, baru boleh diumumkan 2 Januari 1964. Padahal, ibu saya meninggal 25 Desember 1963. Sayang sekali, Ibu tidak sempat menyaksikan pengangkatan saya itu. Saya ditahbiskan menjadi uskup agung, 6 April 1964, oleh Mgr. Ottavio De Liva, Internunsius (Duta Besar Vatikan) di Indonesia saat itu, menggantikan almarhum Mgr. Soegijapranoto. Beliau meninggal dalam perjalanan ketika menghadiri Sidang Konsili Vatikan II, 1962. Maka, dalam Sidang Konsili Vatikan II tahap berikutnya, Keuskupan Agung Semarang tidak ada yang mewakili. Pada waktu rame-ramenya peristiwa G30S/PKI, saya berada di Vatikan mengikuti Sidang Konsili III. Baru kembali ke tanah air 8 Desember 1965. Saya mendapat perintah untuk selekas mungkin pulang. Saya hanya sempat mengikuti meletusnya peristiwa G30S/PKI dari luar negeri. Dari sana, kabarnya, oh, dahsyat sekali. Banyak orang dibunuh. Bahkan ada pastor dibunuh. Saya tidak sepenuhnya yakin dengan kabar itu. Setiba di tanah air, saya terus berkeliling dan muter-muter mengunjungi pelbagai daerah melihat situasi. Setahu saya, PKI pada waktu itu hanya ingin menguasai secara politis. Sebagai pastor, saya pribadi tidak pernah merasakan adanya tekanan dari PKI. Tatkala ada pawai besar kemenangan PKI, dari Jawa Timur ke Jakarta, entah tahun berapa, saya lupa, dalam hati saya bertanya, "Tahun 1948, PKI memberontak di Madiun. Kok, sekarang pawai lagi. Itu apa maunya?" Kita ini berdasarkan Pancasila, tapi PKI kok juga diizinkan? Padahal, PKI itu ateis, lho! Mereka kan sudah pernah berkhianat, kok sesudah itu masih diizinkan hidup lagi? Saya dapat mengerti, mengapa Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Karena Bung Karno sejak zaman penjajahan berjuang mati-matian untuk mempersatukan bangsanya. Karena keinginan Bung Karno hanya satu, mempersatukan bangsanya. Tidak ingin terjadi perpecahan antarkelompok dan golongan. Jangan sampai nanti malah ada kelompok pemberontakan dari dalam, musuh dalam selimut, yang dapat membahayakan persatuan. Sampai saat terakhir Bung Karno tetap belum membubarkan PKI, itu dapat saya mengerti. Karena, ya memang, dia itu pemersatu, kok. Jasa Bung Karno itu besar. Tanpa Bung Karno apa kamu kira Indonesia bisa jadi satu? Direwangi mau dibuang ke sana, dibuang kemari, oleh penjajah hanya untuk mempersatukan bangsanya. Sementara itu, Gereja Katolik sendiri tidak mendapat tekanan dari PKI. Tapi PKI sudah mendaftar tokoh-tokoh, termasuk tokoh Katolik, yang akan menjadi korbannya. Lalu, siapa yang masuk dalam daftar itu? Saya tidak tahu. Hanya isu yang saya dengar, Kasimo termasuk calon korban. Karena Kasimo itu kan tidak setuju Nasakom? Kom harus hilang, kata Kasimo. Saya sendiri belum ada artinya pada waktu itu. Peristiwa G30S/PKI memang menakutkan. Beberapa bulan, bahkan beberapa tahun sesudah peristiwa itu, rasa takut masyarakat masih begitu kuat. Di mana-mana saya lihat orang ketakutan. KARDINAL PURNAKARYA Saya diangkat menjadi kardinal oleh Paus Paulus VI, 26 Juni 1967, berdasarkan Creassio Dewan Kardinal. Jadi, dibicarakan oleh Sidang Kardinal, dan kemudian diangkat oleh Paus. Dalam upacara Elevasio, pengangkatan, saya menerima baret merah dan jubah merah sebagai tanda pengangkatan kardinal. Pelantikannya dilakukan di Capella Syntina, sebuah kapel di dalam kompleks Basilika di San Pietro, Roma. Kapel itu cukup besar. Penuh sesak dengan orang dari pelbagai bangsa yang menyertai kardinal mereka masing-masing. Pengangkatan saya menjadi kardinal berbarengan dengan pengangkatan beberapa kardinal lainnya, di antaranya Kardinal Karol Wojtyla dari Polandia, yang kelak menjadi Paus Yohanes Paulus II. Pada waktu Paus juga berpidato dalam bahasa Indonesia. Antara lain ia berkata, "Pada hari ini saya sampaikan selamat dan mendoakan bangsa Indonesia, yang putranya diangkat menjadi kardinal." Saya tidak tahu mengapa saya diangkat menjadi kardinal. Yang jelas, sejak saya ditahbiskan menjadi uskup agung, 1963, langsung pada 1964 saya dipercaya menjadi Ketua MAWI (Majelis Agung Wali Gereja Indonesia) -- sekarang istilahnya KAWI (Konperensi Wali Gereja Indonesia). Seumur-umur, saya tidak pernah memimpikan menjadi uskup agung apalagi kardinal. Sejak pertama saya masuk seminari, cita-cita saya hanya pengin menjadi pastor. Sinting apa, berpikir untuk menjadi uskup, uskup agung, atau kardinal. Setelah saya menjadi kardinal, pekerjaan saya lalu banyaknya tidak keruan. Dalam setahun, 180 hari saya tidak di rumah, seratus hari di antaranya berada di luar negeri. Saya keliling dunia untuk urusan gereja. Kadang-kadang di negara Asia, Amerika Latin, Eropa. Bahkan setahun dua kali harus pergi ke Roma. Tatkala kunjungan Paus ke Manila, 1970, saya mengadakan lobi ke mana-mana, bersama Uskup Labayen dari Fipilina, Kardinal Kim dari Korea, merintis terbentuknya FABC (Federation of Asian Bishops Conferences), Konperensi Para Uskup Asia. Di FABC, saya adalah anggota Standing Committee. Untuk itu, saya harus menghadiri pertemuan-pertemuan FABC di luar negeri. Berbicara perihal kardinal, dulu masih ada pastor biasa yang menjadi kardinal. Tapi sekarang kardinal itu harus uskup. Biasanya yang dipilih menjadi kardinal adalah ketua dari Konperensi Gereja di negara bersangkutan. Karena, Ketua Konperensi Gereja di suatu negara itu merupakan primus interparus. Kardinal adalah penasihat paus. Para kardinal itu juga terikat untuk bekerja sama dengan paus. Sebab, setela seseorang diangkat menjadi kardinal, dilakukan semacam upacara atau ikrar, yang menyatakan bahwa kardinal yang bersangkutan selalu setia kepada Sri Paus dan Takhta Suci Vatikan. Seorang kardinal, atau mungkin juga uskup agung, selain masih tetap tinggal di daerahnya, juga punya kewajiban untuk bersedia tinggal di Vatikan memimpin sebuah departemen di sana. Tujuannya supaya pemerintahan Gereja Takhta Suci Vatikan mencerminkan aspirasi berbagai negara. Hanya kardinal yang mempunyai hak dipilih dan memilih menjadi paus sebelum usianya mencapai 80 tahun. Setelah seorang kardinal berusia 80 tahun lebih, secara otomatis kehilangan hak pilih atau dipilih sebagai paus. Pada 25 Agustus 1978, saya hadir dan ikut dalam pemilihan serta penobatan Paus Yohanes Paulus I. Kemudian, 16 Oktober 1978, saya hadir dan ikut dalam pemilihan dan penobatan Paus Yohanes Paulus II. Kardinal itu tidak membawahkan uskup-uskup. Tapi mewakili paus untuk kepentingan gereja nasional di seluruh Indonesia. Seorang kardinal, di antaranya, bertugas menyampaikan aspirasi dari Konperensi Gereja pada paus. Seperti juga pada kardinal, titel uskup atau uskup agung tidak bisa pergi sebelum orangnya mati. Sampai saat ini saya masih tetap uskup agung, masih kardinal, bisa mentahbiskan imam, dan sebagainya. Tapi jabatan uskup yang dinamakan residensial itu bisa berhenti, tidak lagi memerintah wilayah gereja tertentu. Uskup yang masih memerintah daerah atau wilayah gereja tertentu dinamakan uskup yang masih residensial. Kalau seorang uskup sudah mundur, masih tetap uskup. Hanya tidak membawahkan gereja. Saya mengundurkan diri sebagai uskup agung sejak 1981. Meskipun demikian, saya masih bisa membantu sedikit-sedikit, daripada nganggur. Mengapa mengundurkan diri, ya, karena tenaga saya sudah tidak mampu lagi menangani banyak pekerjaan. Daripada pekerjaan itu terbengkalai, lebih baik saya mundur dan digantikan tenaga muda yang masih kuat. Sebagai kardinal, sampai sekarang masih. Tapi sudah tidak menjadi anggota departemen pada pemerintahan Gereja Vatikan. Kardinal, secara otomatis, juga menjadi anggota salah satu departemen di Vatikan. Tapi surat-surat dari Vatikan memang masih berlangsung. Hanya saja, saya sudah mulai tidak diberi pekerjaan. Karena apa? Ya, karena sudah tua itu. Mau apa lagi? Mungkin, saat ini, saya lebih pas disebut Kardinal Purnakarya. Di pemerintahan Gereja Vatikan dulu saya pernah menjadi anggota Departemen Inkulturasi Liturgi, lalu Departemen Non-Kristiani yang membidangi agama-agama non-Kristen. Saya juga pernah menjadi anggota Departemen Sakramen. Setiap lima tahun sekali ada perubahan jabatan kepala maupun anggota departemen di pemerintahan Gereja Vatikan. Kadang-kadang seorang kardinal secara berturut-turut menjadi kepala atau anggota departemen yang sama. Namun, kadang-kadang dipindahkan juga ke departemen lain. Hanya kardinal yang mengepalai departemen yang wajib tinggal di Roma. Tapi kardinal sebagai anggota departemen tidak selalu harus tinggal di Roma. Di Roma ada juga Gereja Titel untuk seorang kardinal. Setiap kardinal, pada saat pengangkatannya, memperoleh sebuah gereja khusus di Roma, yang sering disebut Gereja Titel Kardinal. Dengan demikian, semua kardinal mempunyai ikatan khusus dengan Dioses Roma. Gereja Titel saya terletak di salah satu jalan yang ramai, yakni Jalan Via Del Carso No. 45. Kini para pater Agustin yang mengurus gereja itu. Karena saya banyak melakukan lobbying ke berbagai negara, hampir semua umat Katolik di Asia kenal Kardinal Darmoyuwono. Saya juga sering mendapat undangan dari berbagai negara untuk menghadiri konperensi atau seminar atas nama pribadi, bukan atas nama gereja. Tapi kalau Vatikan tidak mengizinkan, saya ya nggak berangkat. Ketika saya diundang menghadiri Konperensi Kependudukan di Belgrado, dan sudah siap berangkat dengan Menteri Kesehatan, Vatikan tidak mengizinkan. Dan saya pun tidak jadi berangkat. Untuk mengunjungi daerah-daerah tertentu, saya harus selektif dan mempertimbangkan kepentingannya. Kalau ada kepentingan yang sungguh-sungguh, baru saya berangkat. Kalau tidak jelas, saya tidak mau datang. Ke Timor Timur belum pernah saya lakukan. Sebenarnya pemerintah kita sudah mengizinkan, tapi Vatikan melarang. "Jangan dulu, nanti diri kita memihak sana-sini. Sebenarnya kunjungan ke Tim-Tim itu baik dan ada manfaatnya. Karena Vatikan tak mengizinkan, saya tidak ke sana. Saya tidak mau menjadi tontonan anyar sebagai kardinal. Memang, beberapa waktu setelah saya diangkat menjadi kardinal, saya melakukan kunjungan ke berbagai daerah, termasuk Yogya dan Semarang. Kedatangan saya di tanah air, setelah diangkat sebagai kardinal, juga diterima oleh Presiden Soeharto bersama para menteri dan stafnya, 7 Juli 1967. Saya juga pernah diterima Bung Karno di Istana Negara, beberapa waktu setelah saya diangkat menjadi uskup agung, 1964. Saya beberapa kali bertemu Bung Karno, di kediamannya maupun di Jalan Merdeka. Pada suatu pagi, saya mengunjungi beliau di rumahnya. Dia bertanya, "Romo Agung, gimana, apakah orang yang menjadi duta besar di Vatikan itu harus orang yang tidak kawin?" Jawab saya, "Dulu Sukarto Wirjopranoto tidak kawin, dan duta besar di Vatikan itu juga boleh kawin, kok." Dan Bung Karno tertawa lebar. Orang-orang pada waktu itu, termasuk Bung Karno, sering memanggil saya dengan sebutan Romo Agung. Sebenarnya, saya lebih suka dipanggil romo saja, kok. Menjelang pensiun, saya sebenarnya sudah membangun gereja di daerah Srondol, Semarang Selatan. Sebagai tempat peristirahatan di hari sela dan nganggur. Gereja itu sangat sederhana. Terbuat dari gedek, dan sangat kecil. Saya dulu memang sering beristirahat di sana dan melayani umat sekitarnya. Sayang, umur gereja itu tak begitu lama. Karena terkena proyek jalan tol. Tapi kami mendapat ganti rugi yang sangat lumayan. Lalu saya membeli tanah di Banyumanik ini dari umat, bukan dari Perumnas. Harganya Rp 2.750 per meter persegi. Waktu pertama kali dibangun, daerah ini panas sekali. Tak ada pepohonan peneduh. Dan penduduknya pun masih sedikit. Saya dulu memang sering menunggui proses pembangunannya. Sebenarnya saya mengajukan permohonan berhenti menjadi uskup agung sejak 1979. Tapi baru dikabulkan Desember 1981. Saya memang sengaja memilih tempat ini karena masih dekat dengan pusat kota. Meskipun sudah pensiun, saya masih melakukan surat-menyurat ke berbagai gereja, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya berusaha bekerja sedapat mungkin malayani umat menurut kemampuan. Sejak 31 Desember 1982, saya mulai menetap menjadi pastor kepala di paroki ini, dan langsung melayani kepentingan umat. Menjadi pastor biasa lebih menyenangkan. Bisa berhubungan dengan umat secara langsung. Inilah yang mendorong saya menetap di kompleks Perumnas ini. Melayani umat yang hidup di tengah pergolakan hidup. Saya bisa ikut merasakan dan menghayati bagaimana kerasnya kehidupan di zaman ini. Pertama kali tinggal di sini, saya mondok di rumah kecil, yang sekaligus menjadi gereja. Pada waktu itu yang aktif di gereja cuma sekitar 50 (lima puluh) orang. Selang beberapa waktu lalu gereja yang besar ini saya bangun. Saat ini umat di gereja ini mencapai 4 ribu orang. Paling-paling ya cuma itu, tidak akan bertambah lagi. Karena daerahnya cuma kecil, kok. Ketika saya akan pindah ke tempat ini, keuskupan berniat memberi mobil. Saya tidak mau. Untuk apa mobil di sini? Kalau saya mau ke Semarang, bisa jalan kaki lalu naik angkutan umum. Meski saya sudah mulai menetap di sini, ternyata masih banyak juga pekerjaan yang harus saya kerjakan. Sebelum ada uskup agung yang menggantikan saya, saya masih pergi ke sana-kemari mentahbiskan pastor, dan sebagainya. Untuk kepentingan itu, ya, saya memakai mobil keuskupan, karena jauh. Kalau cuma dekat-dekat sini, saya masih kuat jalan kaki. Atau naik angkutan umum. Pertengahan 1983, saya mendapat mobil dari seseorang yang tidak saya kenal. Dia orang Jakarta. "Apakah Romo Kardinal bersedia menerima mobil Jeep Jimny ini?" katanya melalui surat. Semula saya keberatan. Ya, untuk apa mobil bagi saya. Tapi romo-romo lain menyarankan agar saya mau menerima. "Baik, kalau begitu. Kirimkan telegram." Beberapa waktu kemudian mobil itu dibawa ke sini oleh pemiliknya sendiri. Mobil itu masih baru. Belum enrayen. Keuskupan hanya membayar Rp 400 ribu untuk bea balik nama. Eee, oleh keuskupan mobil itu diatasnamakan saya. Karena yang diberi saya, kok. Di sini saya nggak punya sekretaris. Jadi, surat-menyurat, ya, saya lakukan sendiri. Semua surat saya tulis tangan. Sebenarnya, saya bisa juga mengetik. Tapi untuk ndudul mesin ketik saya sudah nggak kuat, tidak punya tenaga. Kalaupun ada sekretaris, ya, surat-menyurat saya lakukan sendiri. Karena surat-surat itu kebanyakan saya tulis dalam bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, kadang bahasa Italia. Saya memang menguasai beberapa bahasa: Inggris, Belanda, dan Italia. Bahasa Pracis dan Jerman sedikit-sedikit, kalau diajak ngomong dan membaca teks, saya tahu. Bahasa Latin, tentu saja, saya kuasai. Tapi itu kan tidak untuk omong-omong. Setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, saya sering minta tenaga tambahan dari keuskupan untuk membantu mengirim ucapan selamat. Untuk itu saja, tahun lalu, saya masih menghabiskan Rp 250 ribu untuk beli prangko. Ya, prangko ke luar negeri itu mahal, kok. Tatkala pindah ke sini, saya tidak bawa apa-apa. Semuanya masih saya tinggal di keuskupan. Bahkan pakaian kardinal juga masih tersimpan di sana. Untuk apa bawa barang-barang ke sini? Selama tinggal di sini saya memang sering menjadi langganan orang-orang yang minta sumbangan dan bantuan. Yang rutin saja, setiap bulannya, ada lima organisasi sosial yang datang. Saya memang tidak bisa memberi sumbangan banyak. Paling-paling cuma Rp 2 ribu sampai Rp 3 ribu per organisasi. Karena memang saya tidak kaya. Selain itu, ada juga orang-orang yang secara pribadi datang kepada saya, meminta bantuan. Ada yang minta bantuan untuk membayar uang sekolah anaknya, ada yang terdampar lalu minta sangu untuk ongkos pulang. Kalau cuma minta sangu atau minta sumbangan, kalau memang itu sungguh-sungguh, ya saya beri. Pernah datang seseorang yang mengaku anggota DPR. Pada saya, ia mengaku mobilnya rusak menabrak pohon, kehilangan barang ini dan itu, dan kehabisan uang. Dia minta uang bensin untuk perjalanan dari sini ke Cirebon. Lalu saya suruh menghitung berapa liter habisnya bensin buat perjalanan dari sini ke Cirebon, dan berapa uang yang dibutuhkan untuk sangu. Waktu itu dia minta duit sekian puluh ribu. Ya, saya kasih saja. Eee, ternyata dia itu penipu. Tapi kan tidak semua orang yang datang kepada saya itu menipu? Andai kata ada yang menipu, toh tidak banyak juga. Kan lebih baik ditipu, daripada menipu? MASALAH KAWIN CAMPUR Akhir-akhir ini saya sudah mulai mengurangi kegiatan. Saya hanya menangani pekerjaan yang ringan-ringan. Setiap Minggu pagi saya masih berkotbah di gereja ini. Tapi, untuk mengelola muda-mudi, saya sudah tidak sanggup. Hanya sesekali saya juga memberi konperensi bagi suster-suster Fransiskanis yang sudah berusia senja, 70-80 tahun. Kalau saya memberi konperensi pada para suster yang sudah pada tua itu, saya lebih banyak cerita tentang surga dan yang lucu-lucu. Kepada mereka saya tidak akan memberikan bahan-bahan tentang teologi Konsili Vatikan II, misalnya. Bangun pagi adalah kebiasaan rutin saya. Karena pukul 5 pagi saya harus mempersiapkan misa untuk umat. Setelah selesai, lalu saya membaca koran dan buku-buku, sampai makan siang. Setelah makan siang, saya beristirahat sebentar. Pukul 14.30 saya sudah siap menerima tamu lagi dan menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung. Pada malam hari, biasanya saya baca-baca buku sampai pukul 21.00. Lalu saya nonton siaran "Dunia dalam Berita" TVRI. Kemudian istirahat. Kebiasaan saya mengunjungi keluarga umat, seperti sering saya lakukan ketika masih kuat, saat ini sudah jarang. Saya tinggal di sini tidak digaji. Tapi nggak perlu takut. Karena para ibu memberi makan dan lauk-pauk setiap hari. Dari kelompok sana, kelompok sini, secara bergiliran. Jadi, tidak usah diberi uang saja saya bisa hidup. Kebiasaan merawat imam-imam di paroki itu sudah dilakukan umat Katolik di Indonesia sejak zaman Jepang. Sandang-pangan para imam mereka cukupi. Zaman Jepang, menurut saya, adalah kesempatan umat Katolik untuk membiayai Gereja dan imamnya. Sering saya katakan, dalam berbagai kesempatan, jangan sampai ada kejadian seperti zaman dulu, sewaktu sebuah gereja dibangun oleh para imam sendiri, bahkan oleh para imam asing. Jangan sampai ada gereja tiban. Tanpa berbuat apa-apa jadi gereja besar. Akibatnya, nanti kalau ada atapnya yang bocor, kalian tidak bisa naik membetulkannya. Buatlah gereja dari usahamu sendiri. Gereja berbentuk rumah biasa, itu juga baik. Supaya, nanti kalau rusak, kalian bisa memperbaiki sendiri. Ini lebih bermanfaat, karena keluar dari keringat sendiri. Saat ini, waktu saya lebih banyak saya pakai untuk membaca buku. Saya membeli buku sendiri dari toko. Setiap ada buku baru, saya beli. Ruang pribadi saya merupakan ruang kerja sekaligus perpustakaan. Saya senang membaca buku-buku masalah sosial, buku tentang pergerakan suatu bangsa, juga tentang pergerakan agama seperti DI/TII. Untuk menulis buku, saya sudah tidak sanggup lagi. Dan saya dulu memang jarang menulis buku. Saya lebih sering menulis naskah pidato atau makalah-makalah untuk seminar. Biasanya mengenai masalah pendidikan, sosial, agama, dan kependudukan. Masalah kawin campur antaragama? Asal dengan cara yang baik. Artinya, kelak bisa menjadi keluarga yang baik. Jangan sampai nanti cerai, dan sebagainya. Toh, dalam kehidupan, masyarakat itu campur. Jadi, kawin campur itu tidak perlu dilarang. Orang Katolik diizinkan kawin dengan orang Islam, tapi hanya satu untuk selamanya. Tidak boleh berpoligami: ada istri dua, ketiga, apalagi cerai. Bagaimanapun, perceraian itu tidak akan membahagiakan. Ini sungguh-sungguh dipertimbangkan dan diteliti dahulu, supaya nantinya tidak terjadi perceraian. Saya bisa memberi dispensasi kawin campur. Kawin campur bisa dilaksanakan di gereja. Dan tidak ada kewajiban membaca "syahadat" Katolik, apalagi masuk agama Katolik, bagi calon istri atau suami yang bukan Katolik itu. Kalau dia mau masuk Katolik, ya harus belajar dulu. Setahun dua tahun, itu baru bisa. Kalau hanya datang, terus masuk, itu tidak ada artinya. Agama harus sungguh-sungguh dihayati. Meskipun tidak punya agama, kalau memang hatinya baik, mati, masuk surga. Karajaan Allah lebih luas daripada agama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini