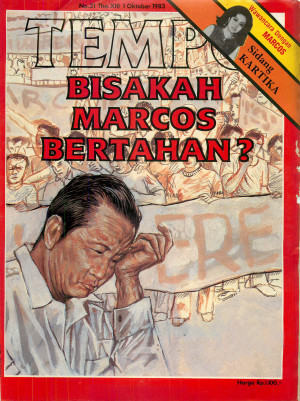DALAM sepucuk surat bertanggal 23 April 1983 ia menulis, ia tak
ragu-ragu untuk "merasa termasuk golongan yang sudah . . .
memfosil".
Nada kalimatnya ikhlas. Mohamad Roem memang selalu demikian.
Itulah sebabnya ketika ia wafat 24 September pekan lalu. dalam
usia 75 tahun, Indonesia bukan saja kehilangan seorang tokoh
sejarah, tapi juga seorang yang berbudi. Yang jelas, bukan
kehilangan sebuah fosil.
Sehari sebelumnya ia baru kembali dari Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo, Jakarta, setelah dua pekan lebih dirawat karena
radang paru-paru. Siang hari itu ia masih sempat makan sop
buntut kambing kegemarannya bersama istrinya, Markisah Dahlia
dan putranya, Roemoso. Sorenya ia terjatuh di kamar mandi. Pukul
18.10 ia tak ada lagi. Mungkin "penyakit jantungnya kambuh,"
kata Roemoso.
Ratusan orang datang melayat, puluhan tokoh, baik dari
generasinya maupun generasi sesudahnya: saksi perjalanan
almarhum yang panjang dan penuh. Buku sejarah hanya mencatatnya
sebagai perunding Indonesia utama menghadapi Belanda, terutama
dalam persetujuan yang terkenal dengan namanya, "Roem-van
Royen", Mei 1949. Tapi mereka yang mengenalnya tahu: Moh. Roem
lebih dari itu.
Diplomat yang berjuang untuk pengakuan kedaulatan Indonesia itu
juga suara damai bagi banyak pihak. Penulis sejarah George Mc
Turner Kahin dari Universitas Cornell menyebut Roem sebagai
orang yang sanggup jadi "jembatan pengertian" antara kalangan
yang berbeda-beda.
Memang tak selamanya ia berhasil. Ia gagal ketika mencoba
mendamaikan: mereka yang bertikai dalam peristiwa pemberontakan
PRRI di Sumatera di tahun 1958. Pemerintah Pusat membom Kota
Padang dan perang pecah. Presiden Soekarno, yang memerintahkan
itu, pada 1960 akhirnya juga membubarkan Partai Masyumi, partai
Islam yang antara lain dipimpin Roem. Lalu Roem, bersama
sejumlah tokoh lain dari Masyumi dan PSI (Partai Sosialis
Indonesia) kemudian ditahan, sampai empat tahun lebih.
Pada 1966, setelah "Orde Lama" dan Bung Karno tergeser, Roem dan
yang lain-lain dibebaskan. Khas bagi Roem, bahwa pengalaman
ditahan tanpa bersalah itu tak menyebabkannya jadi orang yang
pahit.
Seperti ditulis kemudian oleh Mochtar Lubis, rekan setahanannya
semasa itu, Roem memang tak pernah kehilangan proporsi: "Dalam
tahanan Soekarno pun, Mas Roem masih dapat membenarkan Soekarno
di mana Soekarno memang benar." Kepada seorang wartawan Belanda
yang bertanya kepadanya kenapa dalam nada bicaranya ia tak
menunjukkan rasa benci pada Soekarno setelah diperlakukan
demikian tak adil Roem hanya menjawab: "Oh, saya tidak punya
waktu untuk membenci Soekarno." Wartawan itu ketawa.
Dia memang bukan orang yang tegar betapa pun teguhnya ia pada
pendiriannya. Rasa humornya membantunya untuk mengambil jarak
dari pertentangan posisi dan pendapat.
Di tahun 1947, misalnya, beberapa bulan setelah kakinya luka
ditembak pasukan Belanda yang menggerebek rumahnya diJakarta,
Roem dan istrinya ke Yogya. Di Yogya ia ditampung Johan
Syahruzah, seorang tokoh PSI. Waktu itu hubungan antara PSI dan
Partai Masyumi cukup buruk. Melihat Roem di rumah "lawan", tokoh
Masyumi yang lain, Prawoto, bertanya kepadanya: "Bagaimana kau
sampai masuk ke liang singa ini?". Jawab Roem: "Biarlah, tidak
apa. De leeuwin lebih galak." Sang "singa betina", de leeuwin
yang dimaksud Roem, ialah Nyonya Johan Syahruzah.
Kemampuan membuat jarak dari pertentangan posisi dan pendapat
itulah yang menyebabkan ia dihormati siapa saja. Tokoh PNI Ali
Sastroamidjojo menyebutnya "kawan lama saya". Tokoh militer yang
kini jadi tokoh Kristen, T.B. Simatupang, melukiskannya sebagai
pejuang, yang "tidak mudah marah dan benci, sekalipun sering
banyak alasan untuk marah dan benci."
Mungkin itu yang menyebabkan Roem bukan fosil. Ia teladan dari
sejarah Indonesia, yang menunjukkan bahwa berbeda pilihan adalah
sah dalam ikhtiar sebuah bangsa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini