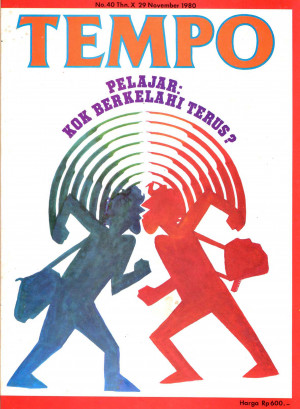MENGAKU tak pernah membaca karya sastra, Mayjen (Purn.) Slamet
Danusudirdjo, Deputy Ketua Bappenas Bidang Pengendalian
Pelaksanaan, toh menulis puisi. Bahkan barusan saja ia, dalam
usia 56, menyelesaikan sebuah novel revolusi, Kereta Api
Terakhir ke Yogyakarta.
Cerita 156 halaman kuarto itu mengisahkan 48 jam yang
menegangkan ketika tahun 1947, para pejuang berusaha
mengungsikan gerbong-gerbong kereta api di Jawa ke Sala. "Supaya
tidak dipakai Belanda," tuturnya. Dan tokoh kisah yang ditulis
selama empat bulan di sela-sela kesibukannya itu, ternyata, dua
orang perempuan kembar.
Barangkali karena "saya sendiri kembar," katanya. "Anak saya
pun kembar, laki-laki," sambungnya, tentang anak yang hanya dua
itu.
Mengapa pejabat tinggi ini menulis novel? "Karena merasa
punya utang pada revolusi," katanya.
Soalnya, dulu, sewaktu bergerilya di kawasan PatiBlora
sebagai Kastaf Pemerintahan Militer di bawah Mayor Munadi (yang
kemudian pernah menjadi gubernur JaTeng), ia kehilangan satu tas
besar catatan hariannya. "Hanyut di sungai Blora."
Sesudah itu, pada suatu malam, ia diganggu oleh kicau burung
kedasih. Dengan kesal burung itu dikejar dan disambitnya dengan
batu. "E, kok berkicau tems," katanya. Puluhan tahun kemudian,
si kedasih mengganggunya lagi.Berkicau di belakang rumahnya, di
Kebayoran Baru - jadi, pasti bukan kedasih yang dulu.
Tapi, "istri saya lantas mengingatkan, mungkin saya masih
punya utang," katanya. Yakni catatan masa revolusi yang hilang
itu. Karena itu, ditulisnyalah novel yang kemudian diserahkannya
pada G. Dwipayana dari PPFN (Pusat Produksi Film Negara) -yang
konon tertarik untuk memfilmkannya--itu.
Tak cuma itu. "Saya masih punya banyak cerita yang bagus,"
ujarnya. Dua judul yang sudah disiapkannya: Rintihan Burung
Kedasih dan Huru-Hara di Kaki Gunung Slamet. Yang terakhir itu,
"ceritanya mengenai apa yang dikenal sebagai 'peristiwa tiga
daerah'," tutur Slamet. Sedang yang pertama, menceritakan seluk
beluk pemerintahan gerilya. "Jadi, revolusi '45 itu bukan hanya
dor-doran tapi juga how to organize warfare."
Di buku itu nanti akan dimasukkan juga sajak-sajaknya.
Orang yang pernah menulis syair tentang operasi anti
penyelundupan "Walisongo " itu, merasa perlu menuliskan semua
cerita itu karena ia menilai generasi muda tak Banyak tahu
tentang itu. Dad katanya, "anak-anak ternyata kepingin
mendengarkan dongeng. Cerita yang lebih hidup mengenai
revolusi." Lalu sambungnya "Untuk mewariskan nilai-nilai '45
tidak mungkin hanya lewat pidato saja ."
Bagi Slamet, apa yang dilakukannya itu adalah "perjuangan."
Sehingga ia terkejut ketika ditanya dibeli berapa novelnya yang
sudah rampung itu oleh PPFN. "Wah, Pak Dwipo tidak bicara
apa-apa tentang itu," katanya. "Tapi PPFN 'kan punya negara.
Jadi biar sajalah."
Slamet Danusudirdjo memang orang yang sederhana. Ia,
misalnya, memakai nama samaran Pandir Kelana. "Pandir itu tolol.
Kelana itu pengembara. Nah, kalau ada pengembara yang tolol,
itulah saya!" katanya bersungguhsungguh -- sambil tertawa.
Dengan jujur -- mungkin Juga bercanda--iapun mengaku,
satu-satunya hobinya adalah: tidur. Dan ia bisa memakan segala
macam makanan. Yang seharusnya tak boleh dimakannya pun
diganyangnya. "Saya ini memang orang yang tidak teratur,"
katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini