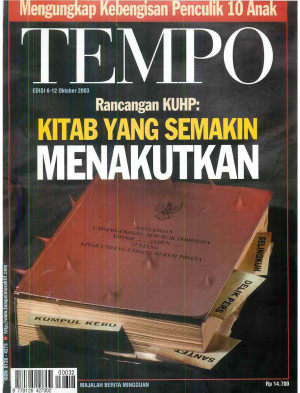SEBUTLAH Bali-dan kita teringat akan ombak, kecak, pura, atau bunga kemboja. Lalu-lalang pelancong ikut menambah gambaran Bali sebagai dunia yang sibuk, terus bergerak, datang dan pergi.
Tapi sebuah rumah? Siapa terpikir akan rumah tinggal pada jagat yang tak pernah ajek seperti itu? Mungkin tak ada, kecuali mereka yang lahir, tumbuh menjadi besar di Bali, atau memiliki ikatan darah dengan Bali.
Namun orang-orang berikut ini, orang-orang yang semula tak punya kaitan apa pun, yang datang dari tempat nun ribuan mil jauhnya, toh memilih meninggalkan tanah leluhur untuk menetap di Bali. Pergaulan, pergulatan, dan pertautan dengan alam, budaya, serta masyarakat rupanya membuat mereka jatuh cinta. Jangankan guncangan bom, bahkan panggilan tanah kelahiran pun tak mampu membuat mereka berpaling. Inilah kisahnya.
Begitu bom Kuta meletup, Leonard A. Lueras sempat bimbang. Korban begitu banyak. Veteran wartawan Perang Vietnam yang sudah 19 tahun menetap di Bali itu mengkhawatirkan aksi balas dendam. Orang-orang Bali yang kehilangan sumber penghasilan dan keluarga kini punya alasan untuk kalap.
Bapak berumur 58 tahun ini tak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika mereka mengamuk, menghakimi kelompok muslim yang dianggap menjadi bagian dari pelaku bom. Kita tahu, balas dendam itu tak pernah terjadi. "Saya jadi tenang," kata Lueras, "dan makin kagum dengan orang Bali."
Ketenangan inilah yang memberinya kekuatan untuk tetap tinggal di Bali, pulau yang membuatnya jatuh cinta sejak pertama kali datang, awal 1970-an. Lueras muda kala itu adalah wartawan lepas The Honolulu Advertiser. Ia datang ke Bali untuk membunuh penat setelah meliput Perang Vietnam.
Pantai-pantai purba, pasir yang seperti tak pernah terinjak, lanskap Bali yang murni, telah menyulap hati Lueras yang gelisah menjadi betah.
Bayangkan, tiga puluh tahun lalu Bali adalah sepotong surga yang belum terjamah. Denyut turisme baru menyentuh kawasan Sanur dan sebagian kecil Kuta. Selebihnya hanya hutan, pantai, dan burung-burung. Bali adalah barisan kampung nelayan dengan gadis-gadis berkain sarung dan kembang sepatu di rambutnya. Bahkan Ubud, wilayah yang kini berkilau sebagai kampung seni, kala itu belum lagi kesetrum aliran listrik.
Namun, di atas semua keindahan itu, yang membuat hati Lueras benar-benar tertambat adalah kedamaian hidup warganya. Waktu itu kriminalitas tak dikenal di Bali. Napas kehidupan seolah-olah berdenyut demi semata-mata kepentingan dewata. Bahkan ngaben, yang tak lain adalah upacara kremasi, dibuat seperti sebuah nyanyian kegembiraan. "Mereka sangat-sangat religius," kata Lueras.
Sejak kunjungan cinta pertama itu, Lueras kerap kembali ke Bali. Setidaknya empat bulan sekali pria Amerika kelahiran New Mexico ini sudah nongol lagi di Sanur. Lama-lama, setelah hampir sepuluh tahun mondar-mandir Amerika-Bali, pada 1984, Lueras memutuskan untuk menetap.
Dengan memboyong kedua anaknya, Lueras, yang baru berpisah dari istrinya, memilih kapling di Jalan Pengembak, Sanur, sebagai tempat bermukim. Kawasan Kuta yang tengah booming kala itu memang sempat mengundang perhatian, tapi Lueras tetap memilih Sanur, yang boleh dibilang sudah lebih tertata.
Di pantai timur bagian "kaki burung" yang tenang itu, telah banyak berdiri hotel mewah. Di kawasan mahal ini, sejumlah resor dirancang agar menjadi semacam tempat pensiun kelas atas. Di sana pulalah tinggal "selebriti" dunia seperti Margaret Mead dan pelukis Jerman, Walter Spies.
Meskipun menempati kawasan yang sudah berkembang, Lueras memilih sebuah pojok yang jauh dari keramaian. "Sewaktu saya datang," katanya mengenang, "cuma ada enam penduduk di sekitar sini. Selebihnya hanya kebun kelapa."
Ia menyewa lahan luas itu, selama 30 tahun. Kini kapling tetangga yang dulu hanya diramaikan oleh gesekan daun nyiur itu telah dipadati pendatang, baik dari dalam maupun luar negeri.
Di rumah itulah Lueras membesarkan anak-anaknya, sambil menulis beberapa buku tentang Bali atau Indonesia. Terakhir, ia menulis Bali Eye, sebuah rekaman setelah tragedi bom. Dalam buku yang penuh foto itu, ia bekerja sama dengan beberapa fotografer lokal seperti Rio Helmi dan Rama Surya.
Selain menulis, sejak tiga tahun lalu, Lueras menggagas sebuah yayasan seni di Ubud bersama penari Restu Imansari. Yayasan yang telah merancang beberapa penyelenggaraan acara seni hingga akhir 2002 itu sempat kalang-kabut begitu bom melumat Bali. "Semua dibatalkan, termasuk Kongres Seni Kontemporer Asia," kata ahli komunikasi dari Western California University ini.
Meskipun sempat bimbang dan kalang-kabut, belakangan Lueras merasa tak bisa dipisahkan dari Bali. Ini mungkin karena ia telah terlalu lama tinggal, mungkin juga lantaran sudah merasa terlalu berumur untuk memilih dan beradaptasi di tempat yang baru. "Bagi saya," katanya yakin, "Bali sudah menjadi rumah pertama saya."
Sementara Lueras sempat bimbang, tidak demikian dengan Jean Couteau, 58 tahun. Budayawan asal Prancis ini menganggap Bali bukan hanya sebagai rumah pertama, tapi juga "tanah air". Karena itu, meskipun Bali diguncang bom, tak sedikit pun ada keinginan untuk pulang ke Prancis. Meskipun ada teror, kata Couteau, "Hidup saya tak terusik. Begitu juga rasa aman saya."
Penulis dan dosen tamu di Institut Seni Indonesia Denpasar ini mengaku mustahil meninggalkan Bali karena persahabatan yang "sangat mengesankan" dengan wartawan, penggiat LSM, penari, pelukis, juga orang-orang biasa, selama 25 tahun terakhir.
Perkenalan Couteau dengan Bali terjadi pada 1970, ketika ia mendapat tugas meneliti budaya masyarakat Bali selama dua tahun. Seusai penelitian, ia terbang kembali ke Prancis. Tak lama berselang, ia harus meluncur ke Amerika, bekerja sebagai staf di Kedutaan Prancis di Washington.
Meskipun telah berkeliling hampir separuh jagat, benak Couteau sering dijejali dengan ingatan tentang Bali, tentang sebuah titik di pojok Samudra Hindia, yang kala itu belum banyak bersentuhan dengan arus komersialisasi. Budaya Bali yang penuh daya magis itu terus menghantui kepalanya, hingga Couteau "menyerah". Pada 1978, ia memutuskan untuk menetap di Pulau Dewata.
Pria kelahiran Paris itu memilih tinggal di rumah sederhana di Desa Peninjoan, Peguyangan Timur, beberapa kilometer di sebelah barat Ubud. Ia melewati hari-harinya dengan menulis dan mengajar. "Saya terpikat dengan warna-warna dan adat istiadat baru yang sungguh mempesona," katanya.
Sementara Lueras dan Couteau menetap di Bali untuk mencari sesuatu yang baru, yang mengusik batin, Muriel Ydo, 45 tahun, mengaku terpaksa meninggalkan tanah leluhur karena tak punya pilihan. "Saya tak punya apa-apa lagi di Belanda," kata perempuan dari Negeri Kincir Angin ini.
Karena itu, ketika 14 tahun silam Ydo terdampar di Bali, yang ada di otaknya hanya ini: mencari kerja atau buka usaha. Dan itulah yang dilakukannya. Bersama seorang teman, ia membuka usaha penyewaan perahu pinisi. Mulanya, usaha ini berjalan lancar. Namun, tak lama kemudian, tahun 1991, Perang Teluk meletup dan usahanya bangkrut.
Sejak saat itu, Ydo bekerja serabutan. Ia sempat memburuh di agen perjalanan, mengajar di Politeknik Pariwisata Denpasar, dan membuat film dokumenter. Pergaulannya dengan banyak kalangan membuat Ydo mulai akrab dengan masyarakat Bali. "Ini yang membuat makin lama saya makin jatuh cinta," kata Ketua Bali International Women Association, sebuah lembaga sosial, ini.
Meskipun belasan tahun tinggal Bali, baik Lueras, Couteau, maupun Ydo merasa tak perlu repot dengan kewarganegaraan. Untuk mempertahankan kecintaan pada Bali, mereka memperbarui visa izin tinggal tiap lima tahun. Tak ingin jadi orang Indonesia? "Prosesnya susah, berbelit-belit."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini