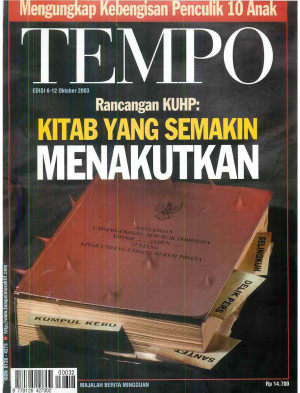Pada suatu hari, ketika Bali mencoba menenteramkan diri, Sabri, 25 tahun, memberanikan diri mengingat sebuah hari yang hitam setahun silam. Di Paddy's CafŽ di kawasan Legian, Bali, tubuhnya bergetar hebat. "Di sini, di sini," katanya dengan kalimat patah-patah dan tak jelas. Di pojok halaman luar bekas kafe yang remuk diguncang bom 12 Oktober tahun lalu itu, ia berdiri. Matanya menerawang. Inilah untuk pertama kalinya, setelah setahun lewat, ia kembali ke tempat itu. Sabri tak menangis, tapi raut wajahnya menunjukkan hatinya sedang teriris.
Pria kurus itu lalu berusaha mengenang. Tapi kerusakan pada saraf di kepalanya membuat ia tak lagi pandai mengingat. Menurut Sabran, kakaknya, pada malam itu Sabri menunggu turis asing keluar dari Paddy's CafŽ. Sebagai pemandu wisata, ia biasa menawarkan kendaraan sewa atau losmen murah kepada para bule.
Tapi nahas. Bom dahsyat itu meledak dan Sabri tak ingat apa-apa lagi.
Keluarganya menemukan dia di rumah sakit lima jam kemudian. Tempurung kepala Sabri pecah dihantam benda tumpul. Beberapa pecahan benda keras menerobos masuk ke otaknya. Dokter berhasil mengangkat sebagian benda asing itu, tapi gagal mengangkat sebagian lainnya. Ajaib, ia tak tewas. "Ia pingsan selama seminggu dan selama satu bulan tak bisa mengenali kami," kata Sabran. Semula Sabri lumpuh dan tuli. Kini ia bisa berjalan dengan diseret serta mampu mendengar. Tapi ia kehilangan sebagian memorinya.
Setahun sudah peristiwa pahit itu berlalu. Sabri malam itu menjadi lelaki asing di kawasan Legian yang gemerlap. Paddy's Cafe telah kembali dibuka dengan nama Paddy's Reload. Dan turis, meski tak ramai, lalu-lalang di kawasan Pantai Kuta tersebut. Kenangan seperti raib ditelan ingar-bingar suara musik di kafe-kafe.
Para tersangka pengebom Bali telah disidangkan. Sebagian dihukum mati, yang lain dihukum penjara 20 tahun, dan sisanya menunggu vonis hakim. "Marah. Dendam," kata Sabri ketika TEMPO menanyakan pendapatnya tentang para pelaku pengebom Kuta.
Ngurah Anom, 32 tahun, korban lain yang kehilangan telinga dan mata kirinya akibat ledakan bom, berujar keras, "Vonis itu memang adil untuk dia." Yang dimaksud Anom adalah Imam Samudra, pentolan pengebom yang diganjar hukuman mati.
Pengadilan memang telah digelar, tapi luka Bali tak mudah disembuhkan. Salah satunya adalah membengkaknya angka putus sekolah akibat banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan setelah Oktober 2002. Laporan Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP), Beyond Tragedy: Bali, menyebutkan mereka yang drop out di Bali melebihi angka 50 persen. Di wilayah Buleleng, mereka yang putus sekolah mencapai 59,7 persen. Di bawahnya ada Karang Asem, dengan tingkat drop out 54 persen. "Siswa yang keluar atau DO di setiap SD berkisar 15-25 orang," kata I Made Ngadeg, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tejakula, Buleleng.
"Saya kelas lima SD. Tapi mereka enggak sekolah lagi," kata Agus Yasa, 11 tahun, penduduk Desa Panji, Buleleng. Mereka yang tidak bersekolah lagi adalah Buda Arta, 15 tahun, dan Kadek Winaya, 13 tahun-keduanya kakak sepupu Agus. Mestinya Buda dan Winaya sudah di SMP. Tapi orang tua mereka, yang menganggur, tak mampu membiayai mereka melanjutkan sekolah.
Kini ketiganya, ditambah adik Agus yang berumur lima tahun, bekerja mencari kaleng bekas untuk dijual kepada seorang lapak penjual rongsokan. Agus telah lebih dulu menekuni usaha ini. Winaya dan Buda menyusul.
"Pak, kami mendapat Rp 9.000," kata Buda Arta. Kadek Adnyana, ayahnya, tersenyum. Ia tahu pekerjaan itu bukan pilihan yang nyaman untuk dia dan kedua anaknya. Tapi hidup mereka tak memberikan banyak alternatif. "Kalian mendapat bagian masing-masing Rp 2.000. Sisanya, Rp 1.000, boleh dibelanjakan es atau apa saja di warung asal kamu bagi bersama," kata Adnyana pelan.
Adnyana, 38 tahun, adalah petani. Tapi ia tak memiliki lahan sendiri. Sebagai buruh penggarap, penghasilannya tak tetap. Dulu pernah ia mencoba bekerja sebagai sopir angkutan di kota. Tapi ia tak punya uang untuk membuat surat izin mengemudi. Sebagai sopir tanpa rebewes, ia tak merasa tenang.
"Bapak sedang di dalam. Silakan tunggu sebentar," perempuan itu berkata tiba-tiba. Yang dimaksud adalah Sabri, yang kini bermukim di kampung istrinya di Mojokerto, Jawa Timur. Melihat TEMPO datang, ia mengunci diri di kamar, tapi sejenak kemudian keluar dengan wajah menyeringai.
Menjelang peringatan setahun bom Bali, Sabri malah menyingkir dari Pulau Dewata. Ini bukan karena ia tak ingin mengingat peristiwa itu lagi, tapi ia takut kehilangan istrinya, Erna Wahyuni, 25 tahun, dan anak laki-lakinya, Zuhri Ahmad Syaifudin, 2 tahun 6 bulan.
Menurut seorang terapis yang mengobati Sabri di Bali, Erna sebenarnya sudah tak sanggup hidup bersama Sabri, yang tak lagi sehat. Dengan ongkos hidup Rp 600 ribu per bulan yang ditanggung oleh sebuah yayasan sosial di Bali, Erna merasa lebih enak tinggal di rumah orang tuanya.
Tapi Sabri menyusul. "Saya kaget suatu hari Sabri datang ke sini sendiri," kata Sumarli, ibu Erna. Tukang ojek yang mengantar hanya bercerita, sejak di terminal Mojokerto hingga ke rumah mertuanya, Sabri hanya memandu dengan bahasa isyarat. Ketika turun dari bus jurusan Surabaya-Mojokerto, Sabri diantar kondekturnya ke pangkalan ojek. "Untunglah di perjalanan banyak yang mau menolong menantu saya," kata Sumarli.
Di kampung, Sabri jadi dianggap seperti benalu. Di rumah mertuanya, yang berlantai tanah, ada enam anak Sumarli-dari tujuh bersaudara. Ditambah Sabri, istri, dan anaknya, kehidupan keluarga itu tambah morat-marit. Terlebih lagi Suwito, ayah Erna, yang sebelumnya bekerja sebagai tukang batu, kini menganggur akibat serangan darah tinggi.
Erna pun semakin enggan mengurus suaminya. "Bahkan ia tega menyebut suaminya wong edan (orang gila)," kata Sumarli, "Saya sering memperingatkan Erna agar jangan kasar. Bagaimanapun, Sabri suaminya." Erna tak membantah. Hidupnya terlalu kusut untuk beradu mulut.
Kini sehari-hari Sumarli menyiapkan mandi, menggantikan pakaian, dan mengambilkan air buat menantunya itu untuk buang air besar dan kecil. "Saya kurang tidur karena merawat Sabri," Sumarli menambahkan.
Tragedi Bali tak cuma menyingkirkan Sabri-yang dalam bahasa Arab berarti sabar. Di Pelataran Hotel Begawan Giri, Payangan, Bali, kemiskinan membuat banyak orang tak sabar. Dua kelompok penari kecak pertengahan Agustus lalu hampir saja beradu bogem karena berebut order menari (lihat Cak, Cak, Cak..., Tunggu 'After' Pemilu).
Kehidupan kesenian di Bali pascabom memang membuat batin teriris. Para penari kecak menurunkan ongkos order hingga angka yang tak masuk akal. Biasanya sekali pentas mereka mematok angka Rp 3 juta, tapi kini, di tengah keringnya permintaan, harga bisa dilorotkan hingga hanya Rp 600 ribu. Dengan anggota kelompok hingga 100 orang, bisa dibayangkan berapa rupiah yang didapat seorang penari sekali pentas.
Galeri lukisan bernasib sama. Museum Neka-museum yang memadukan koleksi lukisan tradisional dan kontemporer-terus kekurangan pengunjung. Sebelum Oktober 2002, museum itu kedatangan 200-300 orang per hari. Pada bulan-bulan pertama setelah tragedi Legian, jumlah itu melorot hanya tinggal seperlimanya. Sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Setidaknya 100 turis datang ke sana tiap hari. "Untung, kami tak sampai mem-PHK-kan karyawan. Bagaimanapun, karyawan adalah aset kami," kata Made Parnatha, Asisten Operasi Museum Neka.
Nasib yang sama dialami Museum Arma, museum yang berada di bawah naungan Yayasan Anak Agung Rai. Menempati lahan seluas 6.500 meter persegi, museum ini memadukan ruang pamer lukisan dengan resor dan restoran. Dulu setidaknya 300 orang datang ke museum ini saban hari. Sekarang? "Pengunjung turun hingga 75 persen. Tingkat hunian resor mencapai nol persen," kata A.A.G. Asrama, pengelola museum Arma, kecut.
Tak semua kisah memang berakhir pilu. Itulah yang dialami I Gusti Agung Ayu Mas Budawati, pengusaha kerajinan di Bali. Tak lama setelah bom meledak, produsen kain Bali ini sempat rugi besar karena konsumen di luar negeri menyetop pesanan. "Saat itu saya benar-benar habis," ujarnya. Utang belum lagi terbayar, pesanan melayang. Untuk mempertahankan usahanya, Budawati terpaksa menjual tiga mobil, termasuk sedan BMW kesayangannya. "Ketika itu, saya bahkan tak mampu beli susu untuk anak saya," kata ibu seorang putra berusia dua setengah tahun itu.
Dua bulan terakhir, Budawati mencoba bangkit. Ia menjemput bola dengan mengadakan pameran di berbagai negara. Karena keuletannya itu, pesanan berdatangan-umumnya dari pengelola toko bebas bea (duty free shop) di bandar udara internasional. Omzetnya, yang sebelumnya Rp 1 miliar dan sempat sampai di titik nol, kini merangkak perlahan menjadi Rp 300 juta. "Tapi itu jauh lebih baik karena saya pernah beromzet minus," ujar Budawati.
Tak semua orang Bali berbisnis ratusan juta rupiah memang. Di Legian, sebelum kembali ke kampung istrinya, Sabri hanya bisa terbengong-bengong ketika ditanya apa yang ingin dia lakukan di kemudian hari. "Kaset..., kaset...," katanya lirih. Maksudnya, ia ingin punya kios untuk berjualan video compact disc (VCD).
Tak tahu dari mana ia bakal mendapat modal untuk mewujudkan mimpinya itu. Di Mojokerto kini dia hanya bisa melamun. Musim hujan sudah datang. Rumah berdinding bata tanpa plester itu lembap diterjang hujan. Dengan mata kosong, Sabri kini hanya bisa memandang ke luar rumah....
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini