Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KETIKA para penyair lain melancong, Kiki Sulistyo bersitahan di Bakarti. Di tempat tinggal kini—sebuah dusun kecil di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat—ia justru melakukan penjelajahan dan penulisan kembali alam dan manusia dusun itu. Sikapnya terhadap Bakarti bukanlah sikap seorang pelancong yang gampang terharu atau pemuja buta kampung halaman, tapi selaku “manusia perbatasan”, dekat tapi juga berjarak, bolak-balik antara sudut pandang “orang luar” dan “orang dalam”.
Dengan posisi seperti ini, Kiki justru bisa menemukan banyak segi menarik Bakarti yang layak dipuisikan. Dengan pendekatan antropologis, ia merawikan sisi magis dusun itu, dominasi haji dan tuan guru, ritual perdukunan, kemiskinan dan godaan buruh migran, mitologi kain tenun, penjelajahan angkasa luar hingga tradisi yang tengah sekarat, serta banalitas dalam kehidupan warga dusun tersebut.
Dengan eksplorasi tematik yang kaya, himpunan puisi Rawi Tanah Bakarti (Diva Press, November 2018) menjadi pencapaian terbaik kerja kepenyairan Kiki Sulistyo, juga buku puisi yang memberi sumbangan berharga bagi perpuisian Indonesia sepanjang tahun ini. Yang tak kalah penting: puisi-puisi dalam kumpulan ini dikerjakan dengan keterampilan bahasa yang terus mencari kemungkinan pengucapan segar dan memberikan kesan kuat-utuh bagi sebuah himpunan puisi.

Rawi Tanah Bakarti
Puisi-puisi Kiki adalah serangkaian upaya pergulatan bentuk yang bergerak antara lirisisme dan narativisme, antara puisi protes dan puisi meditasi, sajak berlagu sekaligus sajak berkisah—antara mematuhi konvensi yang telanjur mapan dan upaya mendobraknya. Puisi-puisi itu adalah pengekstreman dari “puisi suasana”, yang selama ini terlalu asyik dengan lukisan yang membuai dan jukstaposisi citraan yang mengejutkan.
Namun sang penyair tidak berambisi menjajal “puisi ide”, yang di banyak penyair segenerasinya tergelincir menjadi kelewat serebral dan kehilangan daya gugah. Sebaliknya, ia mencoba melampaui lukisan dan jukstaposisi citraan demi menjangkau surealisme yang mencekam dan merongrong akal sehat. Puisi “Pasar Malam Bakarti” adalah contoh terbaik untuk puisi jenis ini. Bagian kedua “#bayi”:
kuda sirkus memasuki mimpi bayi
ruh-ruh berwarna biru menyala di rambutnya
tong terbuka, seorang perempuan keluar dari sana
ia bersenandung seperti biduan yang murung
bayi menunggang kuda sirkus, pusarnya hangus
ular-ular merah merayap dari nganga lubang
seorang kerdil muncul dari balik bulan
menari, menari, bersama perempuan itu dan batu-batu
jatuh ke atas sumur di atas talam....
Dengan kadar surealisme yang pekat, puisi-puisi Kiki masih juga bisa menempuh sikap ilmiah atau kuasi-ilmiah, yakni dengan menyerap fenomena sains yang keras dan mengolahnya menjadi peristiwa puitik yang merangsang imajinasi pembaca. Selanjutnya, ia membenturkan fakta-fakta ilmiah itu dengan mitos yang tumbuh dan terus dirawat oleh warga setempat. Seperti dalam petikan puisi “Binatang Langit” berikut ini.
mereka berpedoman padanya, pada yang berpendar di atas sana
keluar-masuk rongga antariksa, mereka percaya, di situlah awal-mula,
muasal segala, maka sebelum membidik, mereka mesti menampik bisik:
benarkah kijang di balik rindang tanaman, ataukah binatang langit
yang kesiangan dan terlambat pulang
itulah leluhur yang pernah mujur
dilontarkan ke dunia, bersama benda-benda angkasa
benda-benda yang belum diberi nama....
Terhadap fenomena sosial yang dalam banyak kasus telah menjebak penyair sebagai “komentator sosial”, Kiki menempuh siasat yang berbeda. Katakannya, ia melunakkan—atau malah membelokkan—watak puisi protes sosial yang telah lazim dalam puisi Indonesia modern. Ia mengosongkan daya persuasi dari puisi jenis ini dengan memasang “subyek lirik” yang sepenuhnya undur diri dan mempersilakan segala yang ajaib dan penuh daya pukau itu mengambil tempat, berkorespondensi seraya berkontestasi.
Namun, dengan strategi seperti ini, puisi-puisinya tidak kehilangan kekuatan kritik terhadap keadaan. Daya kritik itu hadir dengan cara yang halus atau dengan mendorongnya sampai ke wataknya yang ironis, sesuatu yang seperti menyindir atau menertawai diri sendiri—sebagaimana bait kedua puisi “Batu Kayu”:
Sudah lama aku menyelamatkan diri
dengan berpura-pura mati, menutup mata dan paru-paru
hidupku lebih rendah dari apa-apa yang tidak pernah disebut
bahkan bila api sengaja dipelihara, akulah yang membersihkan
lidahnya, mengisap ludahnya dan menjadikannya cemerlang
seperti intan merah jauh di dasar tanah....
Dalam banyak contoh, puisi-puisi Kiki Sulistyo juga tidak sepenuhnya meninggalkan watak lirik. Ia masih menyisakan permainan bunyi dan rima dalam—itu karena lirisisme adalah watak utama puisi Indonesia sejak semula yang dari haribaannya puisi-puisi Kiki lahir dan berkembang, menemukan pengucapan yang pribadi dan unik. Bagi Kiki, permainan bunyi adalah juga permainan makna. Tidak jarang ia menampilkan sepasang kata yang bunyinya bersisian. Dari penjajaran itu, pembaca mendapatkan bukan hanya makna yang berdekatan, tapi juga berlawanan.
Puisi Kiki Sulistyo serupa kain tenun yang menampilkan warna yang tidak sepenuhnya serasi, tapi membiarkan warna-warna dengan kontras tinggi menjadi anasir pembentuk yang saling memperkuat. Atau, sekali lagi, ia mengosongkan puisi dari pelbagai tuntutan dari luar—sebagai kritik sosial, misalnya—sebagaimana kain tenun yang tidak menampilkan warna apa pun, kecuali kekosongan: “apalah kain ini jika tak mengisahkan apa-apa. serat / setelah serat, serat sebelum serat. pada pudar / bidang datar, cuma kosong / pelataran” (puisi “Tenun Bakarti”).
Dengan begitu, puisi telah kembali menjadi dirinya sendiri, sebagai seni permainan kata dan bunyi—menjelang “puisi murni”; sebagaimana selembar kain adalah tenunan dari berhelai-helai benang—tanpa keharusan memperhitungkan keindahan warna, kesenangan mata si penatap, pembaca yang banyak maunya.

Kiki Sulistyo di Ruang Akar Pohon, Mataram, Lombok Barat, 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Satu tegangan yang juga khas dalam puisi-puisi Kiki Sulistyo adalah tegangan antara kelisanan dan keberaksaraan. Namun kemudian kita tahu bahwa semua itu adalah sepenuhnya permainan sang penyair. Ia mengedepankan aneka citraan dan kosakata dari khazanah setempat dan menyandingkan mereka dengan ragam bahasa Indonesia yang telah lazim. Kedua pihak berdiri sejajar, sama kuat, sama penting. Kelisanan di sini berwatak subversif dan memperkuat bangun puisi.
Dengan kelisanan yang berwatak subversif—ingatlah bagaimana Chairil Anwar dan penyair-penyair tonggak yang lebih kemudian memainkan kelisanan dalam puisi-puisi mereka—puisi-puisi Kiki tampil menyegarkan di tengah puisi yang melulu memamah biak kosakata dan ungkapan yang telanjur digunakan—bersimaharajalelanya klise—dan mengalami pemiskinan bahasa.
Di tangan Kiki Sulistyo, puisi berbahasa Indonesia masih terus menampilkan daya gugah dan kesegarannya. Ia sungguh-sungguh seorang penyair-perawi yang membuktikan bahwa puisi yang berbicara tentang yang daerah akan tetap aktual.
ZEN HAE, KRITIKUS SASTRA
Buku Puisi Rekomendasi Tempo 2018
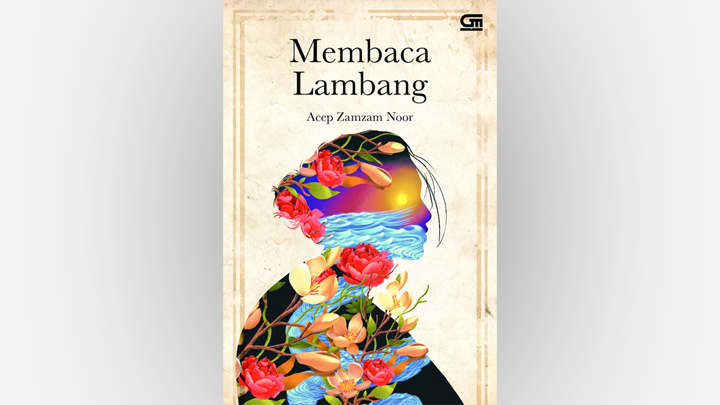
Membaca Lambang
Penulis: Acep Zamzam Noor
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Terbit: 8 Oktober 2018
Tebal: 96 halaman
SESUAI dengan judulnya, buku kumpulan puisi Acep Zamzam Noor yang ketiga belas ini berisi karya-karyanya yang bertolak dari pembacaan atas berbagai lambang yang ia lihat saat melakukan perjalanan ke sejumlah tempat di Nusantara. Dalam 70 puisi yang tersaji dalam buku ini, Acep mencoba mengambil simbol-simbol yang menjadi latar belakang atau ciri khas suatu daerah yang ia singgahi.
Buku Membaca Lambang terbagi atas dua bab, “Mencari Perigi” dan “Membaca Lambang”. Dalam bab “Mencari Perigi”, puisi yang tersaji kebanyakan berupa sajak sederhana yang mengambil pola quatrain atau empat baris di setiap baitnya. Sementara itu, dalam bab “Membaca Lambang”, Acep mencoba menghadirkan warna baru dengan menggunakan bentuk soneta.
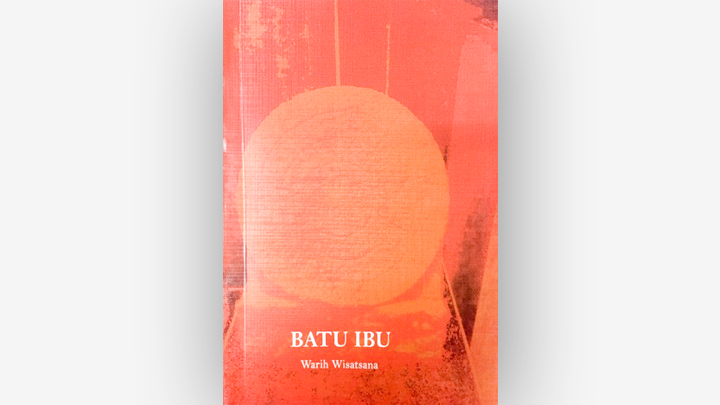
Batu Ibu
Penulis: Warih Wisatsana
Penerbit: Yayasan Sahaja Sehati
Terbit: 1 April 2018
Tebal: 112 halaman
BUKAN tanpa alasan bila Warih Wisatsana memberi judul Batu Ibu pada buku kumpulan puisinya yang kedua ini. Kata “ibu” banyak hadir dalam karyanya pada rentang 1985-2018 yang tersaji dalam buku ini. Ada yang tertulis secara harfiah, berdasarkan pengalamannya sehari-hari bertemu dengan seorang ibu. Ada pula yang berupa metafora, misalnya ibu bangsa dan ibu bahasa.
Kata “batu” pun sering dijumpai dalam puisi Warih dalam buku ini. Suatu ketika ia merasa bahwa disiplin kerja seorang penyair serupa dengan arkeolog. Atas dasar pergumulan itulah Warih mencoba mengangkat hikayat-hikayat tentang sebuah candi, patung, dan artefak lain dalam puisi-puisinya dalam buku Batu Ibu.
Konsep akan waktu juga terasa menonjol dalam buku yang berisi 40 puisi ini. Dalam puisi-puisinya itu, Warih menghadirkan identitas seorang “aku” yang tidak tunggal, melainkan berlapis. Ia berusaha mempertemukan “aku” yang berada di masa lampau dan “aku” yang berada di masa depan dengan “aku” yang hidup di masa kini.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
























