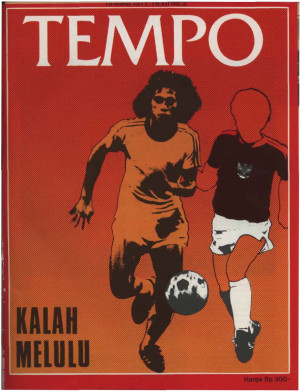YAH, akhirnya toh pindah juga. Setelah agak termangu-mangu untuk
meninggalkan kantor lama, 8 Maret, lepas tengah hari, mendadak
seluruh awak redaksi berkemas-kemas. Sebab kalau toh perasaan
termangu mau diturut-turutkan, kami nanti 'kan bisa dituduh
sentimentil, bukan?
Padahal memang ya, barangkali. Soalnya gedung tua itu memang
"bersejarah". Ibaratnya sejak TEMPO mulai pakai celana pendek,
kami jatuh-bangun dan mati-hidup di situ. Lengkap dengan
perasaan dag-dig-dug menghadapi yang terjadi di sekeliling kami,
atau terhadap kami. Lengkap juga dengan banjir yang masuk
menggenangi bagian tata-usaha di bawah, bila hujan deras
menjotos Jakarta. Juga persahabatan dengan tukang es, tukang
ketoprak, tukang tahu, tukang buah, yang boleh dikatakan satu
lichting dengan kami dalam usaha. (Di sore hari, seseorang
dengan topi hitam dan muka yang blo'on biasanya akan membuka
pintu redaksi di tingkat dua: "Bubur ayam . . . ").
Jangan dilupakan juga, karier satu per satu orang TEMPO, di
dalam mau pun di luar kerja dinas, juga ditentukan di situ. Dan
juga: pacar, untuk sebagian.
Karena itu, begitu Pemimpin Redaksi bilang: "Bagaimana kalau
pindah sekarang?", orang-orang bagai tersedar dan mulai sibuk.
Berbagai dokumen yang sejak beberapa hari sebelumnya sudah mulai
dipilih-pilih, mendapat seleksi terakhir. Dan dengan segera
sampah-sampah bertimbunan di lantai. Di balik map demi map di
dalam laci atau lemari tiba-tiba saja banyak yang menemukan
"barang-barang antik" surat yang tercecer, potret pacar yang
dulu dicari-cari, kartu nama dari seseorang yang jauh di luar
negeri, atau daftar alamat lama. Ada juga yang menemukan Surat
Yasin dan mainan anak-anak. Semuanya berteriak kegirangan dan
menyanyi.
Dan kami pun pindah. Tempat kami sekarang ini memang paling top.
Itulah pucuk Proyek Senen, dari mana kami melayani anda mulai
kini (dan nomor ini adalah nomor pertama yang seluruhnya kami
persiapkan di sini).
Bagaimana bisa sampai di kantor kita?
Mencemplungkan diri begitu saja ke dalam gelora Proyek Senen
yang penuh manusia, lantas naik eskalator dua kali memang bisa.
Hanya saja peribahasa "malu bertanya sesat di Senen" tak usahlah
dipakai, sebab bila anda bertanya, orang malah bingung.
Yang agak menyenangkan, bagi yang bermotor, barangkali memang
melewati jalan mobil yang naik-berputar itu. Ada tiga jalan yang
seperti ini, bisa dipilih yang di Blok 11, yang paling dekat
simpang enam Senen. Dalam istilah seorang dari kami, perjalanan
ini mirip atraksi 'tong setan' atau 'bola maut'.
Hampir "segenap aspek" TEMPO jua dipindahkan lewat jalan putar
itu meskipun sampai berita ini diturunkan ternyata belum
semuanya terangkut. Bagian dokumentasi dan sekretariat belum
bisa bekerja dengan sempurna. Dan lebih penting: telepon belum
dipasang.
Tapi majalah Medika sudah mengungsi pula, lengkap dengan
dokter-dokternya. Mereka mendapat ruang tersendiri di samping
ruang redaksi kita. Ruang itu kini diiuluki: "Puskesmas
TEMPO".
Dan begitu anda turun satu tingkat dari tempat parkir di atas -
di mana terdapat juga Taman Ria sebagai ancer-ancer - anda akan
masuk sebuah kantor yang di hari-hari pertama dingin sekali
karena AC. Begitu dingin sehingga awak TEMPO perlu memakai jas,
jaket, switer, rompi - pokoknya memanfaatkan "simpanan lama",
tak peduli bentuk atau warnanya. Bagai belanda-belanda kecil
mereka mondar-mandir di antara meja-meja pada hari pertama -
masing-masing merasa sedikit asing dan "aneh pada diri
sendiri", belum begitu jelas apa yang mau dibikin.
Gambar-gambar kemudian dipasang. Juga Mushalla Ahmad Wahib,
dihiasi kaligrafi dan juga sajak. Salah satu pigura murah
(harga: 150) bertuliskan Sugeng Rawuh Poro Tamu (Selamat Datang
Para Tamu) - bergambar Petruk Gareng seperti yang biasa dipasang
di warung nasi di Jawa, ada yang tertempel di salah satu sudut
"newsroom". Juga potert-potret besar dari penduduk Jakarta: yang
lagi duduk di kasur di udara terbuka sehabis rumahnya terbakar.
Atau dua orang pekerja DPU yang lagi merogoh pipa dalam kubangan
air got dipinggir jalan raya. Atau seorang gelandangan tua yang
lagi menggundul kepalanya sendiri sambil memegang sepotong kaca.
Tapi yang perlu: Kantor ini sudah didoai. Pada peringatan ulang
tahun ke-6 (kami adakan dua hari setelah 6 Maret, dan beberapa
jam sebelum pindah), kami sudah menggelar tikar dan duduk
bersama-sama. Seluruh karyawan, seluruh direktur dan komisaris
(ir. Ciputra dan drs. Budiman Kusika), juga penjabat Gubernur
Ali Sadikin, berkumpul disitu.
Pertemuan itu sederhana saja. Hanya dan makan siang. Tapi
Pejabat Gubernur juga bicara dan baiklah ini diteriakan sebagai
penutup laporan dapur. Ali Sadikin yang terkejut karena disebut
sebagai pengawas (yang dimaksud sebagai pengawas Jaya Raya,
yayasan yang bersama PT Pikatan mendirikan PT Grafiti, penerbit
TEMPO), berkata : "Jadi saya ini bukan pengawas TEMPO 'kan?
Sebab saudara-saudara ini 'kan banyak menyerang pemerintah DKI.
Kadang-kadang saya baca TEMPO maunya saya sobek ini majalah. Ini
penting, sebab mungkin ada yang mengira TEMPO itu punya Ali
Sadikin atau DKI. Tapi, ya, saya memiliki TEMPO dalam arti TEMPO
tiap minggu menjadi santapan rohaniah untuk saya". Setelah itu
Ali Sadikin bercakap dan bergurau dengan para hadirin.
Bagi karyawan dan wartawan TEMPO, pidato Bang Ali itu merupakan
kado yang menyenangkan: saling kritik ternyata juga bisa
merupakan tanda kepercayaan - dengan cara intim dan diam, tanpa
niat menyakitkan hati, tapi juga tanpa penjilatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini