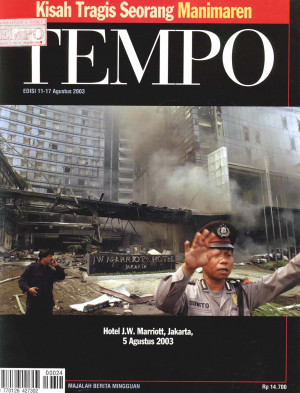Susanna Nur masih menyimpan setiap detail kenangan itu dengan penuh kasih dalam seluruh relung hatinya. Hampir setiap akhir pekan, kakeknya, Teungku M. Daud Beureueh—keluarganya memanggil dia Abu Syi'—mengajak Susanna kecil berjalan menyusuri pantai di Kutaradja (kini Banda Aceh). Berdua mereka menghampiri nelayan, membeli ikan segar, dan langsung membakarnya di dapur rumah si nelayan. Begitu ikan bakar siap terhidang, sang Gubernur Militer Aceh-Langkat-Karo itu menyantapnya bersama-sama dengan para nelayan dan kerabatnya: "Nelayan-nelayan itu amat bangga bisa makan bersama Abu," kata Susanna.
Kenangan masa kecil Susanna, 65 tahun—kini bekerja sebagai pengajar di Pusat Kebudayaan Prancis (CCF), Jakarta—memang tak berlanjut intensif. Tahun 1950, M. Nur El Ibrahimy, ayah Susanna, harus pindah ke Jakarta karena bertugas sebagai anggota MPR dari Partai Masyumi. Ibu Susanna adalah Siti Mariyam (almarhumah), putri pertama Daud Beureueh. Walhasil, interaksi gadis kecil itu dengan sang kakek jauh menurun.
Bertahun kemudian, pada 1978 Daud Beureueh "diculik" pemerintah Orde Baru. Dia ditempatkan di sebuah rumah di kawasan Slipi, Tomang, Jakarta Barat. Tapi, "Tetap saja, kami anak-cucunya tak sempat bergaul rapat dengan Abu Syi'," ujar Nisrina Hanim Nur Ubay, anak ketiga Nur El Ibrahimy. Menurut Nisrina, pengajar bahasa Inggris yang kerap muncul di layar TVRI, ketika itu amat banyak tamu yang mendatangi Daud Beureueh. Kebanyakan warga Aceh yang tinggal di Jakarta yang hendak meminta nasihat keagamaan. "Jadi, keluarga mengalah. Kami hanya sesekali berkunjung dan menyaksikan Abu Syi' melayani tamu," Nisrina melanjutkan.
Ingatan yang lebih kental lahir dari benak Ma'mun Dawud, 65 tahun. Dia anak bungsu dari tujuh bersaudara yang dilahirkan Halimah, istri pertama Daud. Di matanya, sang ayah adalah sosok yang bersahaja. Ma'mun dan saudara-saudaranya tak pernah dibelikan pakaian yang bagus biarpun sang ayah sudah jadi gubernur militer. "Sekolah tetap saja nyeker, telanjang kaki, dan baju seragam dari kain pepe atau belacu kasar, sama seperti anak-anak Aceh yang lain pada saat itu," tuturnya kepada TEMPO. Anak-anak juga tak pernah mencicipi nikmatnya menumpang jip, mobil kuno, kendaraan dinas sang ayah. Namanya juga kendaraan dinas, Daud berkeras tak mau menggunakannya di luar keperluan dinas.
21 September 1953. Daud Beureueh mengangkat senjata memperjuangkan Darul Islam. Karena dikejar-kejar tentara pusat, Daud naik gunung dengan pasukannya dan berpindah-pindah tempat di hutan. Halimah dan anak-anak lelakinya yang masih kecil, yakni Makmun, Saifullah, dan Rusdi (anak dari Aisah, istri ketiga), ikut masuk hutan di kawasan Lueng Putu. Mereka tinggal di gubuk kulit kayu yang dibangun di atas cabang-cabang pohon besar. Di sela-sela kegiatan pergerakan inilah Daud Beureueh mengajarkan ilmu agama, tafsir Al-Quran, kepada Ma'mun dan adik-adiknya.
"Waktu itu ada perasaan sedih juga karena saya tak bisa lagi sekolah," Ma'mun mengenang pengalaman masa-masa di hutan tersebut. Ketika itu dia berumur 13 tahun. Ma'mun baru bisa melanjutkan sekolah SMP delapan tahun kemudian setelah Daud turun gunung. Karena itu, Ma'mun baru masuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada umur 26 tahun. "Telat, ha-ha-ha," kata pria yang kini menjadi pengurus Dewan Dakwah Indonesia (DDI) itu.
Soal kesahajaan Abu Syi' juga amat melekat di hati Ahmad Saifullah Daud, 70 tahun, kakak kandung Makmun. Teungku Daud, katanya, tak pernah memiliki rumah pribadi atau tanah barang sejengkal. Makannya tak pilih-pilih. Meski gemar ileh alias belut goreng, selera Abu tak berkurang bila yang terhidang cuma nasi dan sekadar ikan teri. Presiden Sukarno pernah menawari Daud sebuah rumah pribadi di daerah Lampriet, Banda Aceh. Tapi, Abu menolak.
Kembali ke Aceh setelah masa pengasingan di Jakarta, Abu tetap tak punya rumah. Hingga ajal menjemput, dia menempati sebuah bilik papan di samping Masjid A'la Lil Mujahidin, Beureunen, Aceh, masjid yang dibangunnya pada tahun 1963. Jadi, "Tak ada sepetak tanah pun yang diwariskan Abu kepada anak-cucunya," kata Saifullah. Padahal, Daud Beureueh bisa saja memanfaatkan kedudukannya dan memborong seluruh tanah di Kampung Usie, Kecamatan Mutiara, Pidie, kampung halaman istri Daud.
Saifullah juga terkesan dengan cara Daud Beureueh mendidik anak-anaknya. Sedari kecil mereka dikenalkan dengan prinsip baik-buruk, halal dan haram. Suatu ketika Saifullah kecil membawa pulang buah kelapa muda. Sudah terbayang betapa segar air dan daging buah kelapa yang lunak ini mengaliri kerongkongan. Tapi, ketika tahu bahwa kelapa muda itu diambil dari jalanan dekat rumah tetangga, Daud langsung marah. "Itu bukan milikmu," katanya, "Lekas, kembalikan ke tempat semula."
"Abu juga tak ingin kami berbeda dengan anak-anak orang kebanyakan," Saifullah menambahkan. Semua anak-anaknya dibiasakan bekerja di sawah, bergaul dengan keringat, lumpur, dan cangkul. Mereka juga ikut kalang-kabut di dapur menyiapkan makanan bagi seluruh keluarga ataupun rakyat Aceh yang tiap hari mengalir ke rumah itu.
Sampai kini, Saifullah—dia pernah kuliah di Jakarta tapi putus di tengah jalan—hidup sebagai petani. Abu Syi' memintanya pulang ke Aceh dan hidup di sana. Keluarga Saifullah tinggal di rumah permanen seluas 600 meter persegi, di tengah sawah dan kebun, di Kampung Usie. Rumah itu dibangun di atas reruntuhan rumah panggung khas Aceh untuk pertemuan warga yang pernah didirikan Daud Beureueh. Sebuah meriam tua peninggalan Belanda masih teronggok di halaman.
Nur El Ibrahimy, sang menantu yang kini sudah berusia 93 tahun, juga menuturkan kenangan tentang ayah mertuanya: "Saya meminang Siti Mariyam, putri sulung Abu Daud, dengan bantuan Teungku Abdul Hamid." Sebagai catatan, Teungku Abdul Hamid atau akrab dipanggil Ayah Hamid adalah tokoh cendekia yang disegani dan banyak mempengaruhi pemikiran Daud Beureueh.
Begitu menikahi Siti Mariyam, 1937, Nur dikenai sanksi oleh pemerintah kolonial Belanda. Selama dua tahun, Nur tak boleh mengajar di Madrasah Nahdlatul Islam karena ide-ide nasionalisme yang dia sampaikan kepada para muridnya. Tetapi, hukuman ini justru merupakan berkah, karena Nur jadi punya waktu luang untuk mendampingi kegiatan ayah mertua. Misalnya, Nur menjadi Sekretaris Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) serta ikut memodernisasi pendidikan di Aceh.
"Jarang sekali kita punya pemimpin yang berjiwa seperti dia," kata Nur, yang daya ingatnya masih tajam. Tak hanya pintar menurunkan perintah, Daud Beureueh juga langsung memberi contoh dengan tindakan. Terjun bekerja dengan tangannya sendiri. Ing ngarso sung tulodo, kata orang Jawa.
Pembangunan irigasi di Sigli adalah contoh nyata. Berbilang tahun, hasil panen padi di kawasan ini tak pernah bagus karena sistem pengairan yang buruk. Bupati yang bertugas tak sanggup berbuat banyak lantaran segala proyek pembangunan harus menunggu perencanaan pusat. Akhirnya, rakyat Aceh berpaling kepada Daud Beureueh, meminta sang pemimpin turun tangan. Abu turun sendiri, memimpin seluruh kerja proyek irigasi tersebut, bahu-membahu dengan ribuan warga. Proyek dikerjakan 14 Juli sampai 18 Agustus 1963, melibatkan 300 sampai 2.000 orang yang kerja bakti setiap hari (lihat Batu Cadas dari Beureunen).
Hanya ada satu hari libur, yakni saat Maulud Nabi Muhammad. Aktivitas dimulai pukul 8 pagi sampai 5 sore. Rehat pendek hanya dilakukan siang hari untuk makan dan salat zuhur dan asar. Seluruh peserta kerja bakti membawa sendiri bekal makanan dan peralatan seperti cangkul dan sekop.
Usai bekerja, menjelang magrib Daud berpidato singkat, tentang pentingnya irigasi bagi peningkatan produksi padi, tentang kewajiban ibadah kaum muslim untuk memajukan daerahnya. Suaranya yang berat mampu menggelorakan semangat para relawan. Tidak sedikit orang, termasuk Daud Beureueh, yang berhari-hari tidak pulang dan tidur di gubuk-gubuk di tengah persawahan.
Akhirnya, setelah lebih dari sebulan bekerja keras, irigasi pun jadi. Panjangnya 17 kilometer, lebar 2,5 meter, dengan kedalaman 1,5 meter. Satu sen pun pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk proyek yang diperkirakan senilai Rp 100 juta ini (sekitar US$ 100 ribu dengan kurs zaman tersebut). Tak ada tenaga yang dibayar. Rakyat rela mewakafkan tanahnya untuk keperluan irigasi. Gratis, dengan janji imbalan dari surga. "Harus kita catat, saat itu Abu sudah jadi orang sipil. Tak ada urusan apa pun dengan pemerintahan," kata Nur, "Partisipasi orang sebanyak itu jelas karena mereka tergerak oleh teladan kepemimpinan Abu Daud."