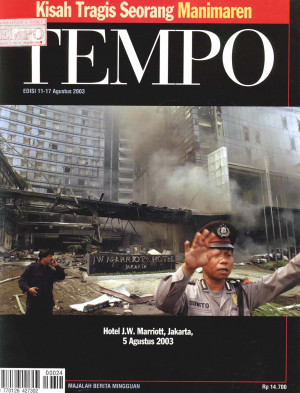Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di kala Aceh berada di dalam status daerah operasi militer (DOM), beredar banyak rumor seputar apa dan siapa Hasan Tiro. Celakanya, hampir tiada bedanya antara rumor, propaganda, dan fitnah politik. Malangnya lagi, kita harus memafhumkan: mustahil menelisik kebenaran isi ataupun kekuatan sanadnya di masa operasi antigerilya serdadu Indonesia mendominasi tanah dan langit Aceh ini. Rumor berikut menggambarkan bagaimana relasi antara Abu Beureueh dan Hasan Tiro.
"Abu! Dahulu Abu meminta kami membuatkan mobil. Dan amanah itu telah kami lakukan. Mobil pun sudah diserahkan kepada Abu. Lalu, Abu meminta agar diperkenankan menjadi sopirnya. Dan kami taat semata. Namun, apa hendak dikata bila takdir mobil itu mengangkut penumpang yang salah, lalu ditabrakkan dan hancur. Nah, sekarang," Hasan Tiro melanjutkan, "saya mau membuat mobil baru, dan saya pula yang akan menyetirnya sendiri. Saya mohon, Abu memberkahinya!"
Rumor ini beredar setelah Abu Beureueh dipaksa meninggalkan Aceh dengan alasan politik bahwa beliau terlibat di dalam gerakan Komando Jihad (Komji) Haji Ismail di Surabaya pada 1 Mei 1978. Dalam versi lain, rumor tersebut diembuskan dengan sebuah pesan kepada publik bahwa Hasan Tiro telah "merampas" tongkat kepemimpinan dari Abu Beureueh. Periwayat rumor ini hendak menyampaikan tak ada kaitannya antara DI/TII dan GAM, dan Abu Beureueh tak mendukung Hasan Tiro.
Sudah barang tentu ada perbedaan antara DI/TII dan GAM, sebagaimana juga antara Abu Beureueh dan Hasan di Tiro. Namun, tidak berarti yang terakhir bukannya buah dari transformasi yang lebih awal. Apalagi, baik DI/TII maupun GAM bukanlah dua entitas politik yang lahir dari tabung yang vakum, melainkan dari kandungan dengan hawa sejarah, politik kekerasan, ekonomi yang eksploitatif, dan penghancuran identitas budaya keacehan, serta merendahkan martabat individu ataupun etnis Aceh.
Abu Beureueh adalah salah seorang ulama modernis yang menginisiasi maklumat ulama Aceh untuk bersetia pada "Indonesia tanah tumpah darah kita" pada 15 Oktober 1945. Bahkan para ulama generasi ini mengobarkan jihad terhadap Belanda. Padahal, andaikan pada saat itu Abu Beureueh dan pemuka ulama tradisional lainnya ingin memerdekakan Aceh, maka jadilah Aceh sebagai sebuah negara. Namun, sebagai gubernur militer, Abu Beureueh justru meneguhkan Indonesia dengan mendeklarasikan terbentuknya Tentara Nasional Indonesia di wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada 1 Juni 1948.
Ketidakpuasan politik Abu Beureueh mulai diungkapkan sejak 1950, yang berkenaan dengan otonomi Aceh. Abu Beureueh membangkang terhadap perintah dari acting gubernur di Medan dengan risiko kevakuman pemerintahan di Aceh. Pemerintah Jakarta pun menempuh kebijakan politik kekerasan (militeristis) sehingga ketidakpuasan Aceh terus memuncak. Akibatnya, sikap orang Aceh, menurut Abu Beureueh, berevolusi sebagaimana pikiran yang telah diwariskan turun-temurun dari tingkatan sabar, tak menghiraukan, hingga ke tingkat melawan. Hal ini tergambarkan pada surat Abu Beureueh kepada Presiden Republik Indonesia pada 8 Oktober 1951.
Dalam realitas sejarahnya, ternyata melawan itu pun bertingkat-tingkat, misalnya Aceh menjadi Negara Bagian dari Negara Republik Islam Indonesia (NBA-NII) sejak 21 September 1953. Lalu, tingkat melawan itu masuk ke pembentukan Republik Persatuan Indonesia (RPI), yang rencananya diproklamasikan pada 17 Agustus 1959. Namun, Aceh menjadi Republik Islam Aceh sejak November 1960. Betapapun, evolusi pikiran politik Abu Beureueh masih dalam bingkai negara federalis.
Hasan di Tiro mulai melawan dengan berpikir kritis terhadap Indonesia yang berjiwa kesatuan pada awal 1950-an. Namun, berbeda dengan gagasan politik Abu Beureueh, ketika Hasan di Tiro memproklamasikan Negara Aceh pada 4 Desember 1976, ia tidaklah memasukkan jiwa Islamisme di gagasan politiknya. Pandangan politik federalis pun sirna dalam atmosfer politik orang Aceh.
Memang ada latar belakang yang sangat berbeda antara Abu Beureueh dan Hasan Tiro. Abu Beureueh sepenuhnya hasil pendidikan Aceh yang tradisional. Namun, ia menjadi seorang ulama yang memulai gerakan modernisasi dalam sistem pendidikan agama. Apalagi, Abu Beureueh didampingi sejumlah kaum muda yang merupakan lulusan dari sekolah agama di Padang, yakni Sumatra Thawalib. Kaum agamawan muda ini menurut sebagian tokoh politik Aceh dianggap berpengetahuan "Islam-merah", yang kemudian menjadikan gerakan Abu Beureueh semakin tertransformasi menjadi gerakan politik keagamaan yang agresif.
Pada saat yang sama, Hasan Tiro baru tumbuh menjadi remaja yang cerdas, di dalam keluarga yang mapan. Ia memiliki kemampuan bermain piano, senang musik klasik dan menulis naskah drama. Suatu hal yang luar biasa bila kita mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik di kota kecil seperti Beureuneun yang dekat dengan desa Beureueh. Lalu, ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta dan mendapat rekomendasi Abu Beureueh untuk menjadi diplomat RI di perwakilan PBB New York.
Latar pengetahuan agama yang kuat menjadikan pola kepemimpinan Abu Beureueh berlandaskan pada karisma. Aura suci melingkari sekujur tubuhnya. Karisma itu terbangun, kalau kita mengacu pada Max Weber, karena kemampuan Abu Beureueh membangun spirit keagamaan baru (modernis) di luar spirit keagamaan lama (tradisionalis) yang telah menjelma menjadi rutinitas. Masalahnya, apakah sebuah gerakan politik untuk membangun sebuah entitas politik modern cukup hanya bertumpu pada pemimpin yang karismatis.
Kepemimpinan karismatis Abu Beureueh mengabaikan sistem pengorganisasian modern yang merekrut anggota secara ketat. Akibatnya, unsur-unsur yang terlibat di dalam gerakan Abu Beureueh menjadi sangat majemuk. Salah satunya adalah kaum desertir dari kaum serdadu Indonesia. Unsur lainnya adalah mereka yang melawan karena kehilangan mode produksinya.
Dalam pola kepemimpinan Abu Beureueh—apalagi keberadaannya di hutan—memungkinkan adanya peluang bagi elite NBA untuk melakukan negosiasi secara individual dengan lawannya. Sejarah mencatat bahwa kedua kaum ini akhirnya berkolaborasi untuk memakzulkan Abu Beureueh pada 15 Maret 1959. Mereka adalah Kol. Hasan Saleh (Menteri Urusan Perang NBA), Ayah Gani (Wakil Perdana Menteri NBA menjadi Ketua Dewan Revolusi), dan Husein al-Mujahid (Ketua Majelis Syura), yang membentuk Dewan Revolusi NBA-NII. Peristiwa ini bisa juga diberi tafsir sebagai perpecahan elite NBA-NII menjadi dua entitas politik.
Pendidikan sekuler dan pengalaman hidup di Amerika merupakan dua hal yang mengkonstruksi pola kepemimpinan Hasan Tiro. Bayangkan saja, pada tahun 1954 ia masih melihat dirinya sebagai bagian dari "putra-putra Indonesia", namun ia telah menggunakan PBB sebagai arena perjuangan politik NBA-NII. Hasan Tiro sudah menilai eksekusi massal yang melibatkan Batalion B pimpinan Simbolon dan Batalion 142 pimpinan Mayor Sjuib di Desa Pulot dan Cot Jeumpa adalah genosida. Bahkan, Hasan Tiro telah mengajukan tuntutan self determination untuk Aceh.
Pola kepemimpinan politik modern Hasan Tiro terlihat dengan upaya pengkaderan kekuatan bersenjata GAM di Libia yang melahirkan generasi Muzakkir Manaf. Mereka yang terlibat dalam gerakan bukanlah kader produk pihak lain. Kedisiplinan organisasi semakin menonjol. Karena itu, faksi kolaborasi antara kaum desertir (Arjuna) dan kaum sipil gagal mengkudeta Hasan Tiro. Peristiwa ini juga menjadi momentum untuk pemurnian dan peningkatan kedisiplinan.
Kedisiplinan organisasi juga terlihat dari kebijakan GAM bahwa hanya ada satu pintu bagi lawan untuk menjalin kontak politik: elite yang berada di Swedia. Panglima yang berada di medan gerilya tidak memiliki wewenang untuk melakukan negosiasi politik. Karena itu, di masa Jeda Kemanusiaan, ketika pihak Indonesia mendesak adanya pertemuan antarkomandan lapangan, pihak GAM "memungut" orang sipil di sebuah kamp pengungsi—lalu diberi baju seragam, pangkat, dan jabatan yang tinggi dan seolah-olah strategis, dan sepucuk pistol—untuk melakukan negosiasi dengan komandan operasi serdadu Indonesia. Kata orang "di warung kopi", inilah tipu Aceh.
Meskipun pola kepemimpinan Hasan Tiro modern, bukan berarti Hasan Tiro sama sekali tak memiliki karisma. Saat pelatihan gerilya di Libia, Hasan Tiro mengkonstruksi kegemilangan Aceh (romantisme sejarah), dan kegetiran hidup orang Aceh hingga saat ini. Ia membangun kembali kesadaran akan identitas keacehan, sekaligus spirit untuk mewujudkannya. Karena itu, bagi mereka, Hasan Tiro adalah sosok yang mengembalikan Aceh yang telah hilang ke dalam jiwa mereka. Dalam kata lain, jika dilihat dari sisi Aceh, Hasan Tiro adalah bapak nasionalisme Aceh. Sekalipun, bila kita melihatnya dari sisi Indonesia, Hasan Tiro adalah bapak separatisme. Apa pun, Tampaknya politik kekerasan negara selalu melahirkan ikon perlawanan orang Aceh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo