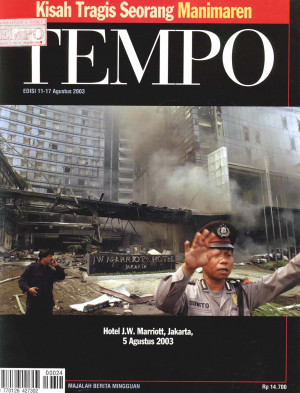Anthony Reid
Asia Research Institute, National University of Singapore
Sekali lagi rakyat Aceh menanggung derita akibat perang, operasi militer, dan hidup di pengungsian. Dan untuk kesekian kali, penduduk di daerah sekitarnya memandang dengan heran, apa yang menyebabkan mereka begitu keras kepala. Mengapa mereka tidak seperti kita, menerima kenyataan adanya penguasa dalam dunia yang tidak sempurna ini dan mengupayakan hidup terbaik dalam batas-batas yang sudah digariskan sejarah? Apakah mereka tidak bisa melihat bahwa perlawanan hanyalah sia-sia dan merusak?
Meskipun berbagai peristiwa, khususnya sejak jatuhnya Soeharto, telah mengubah sikap orang Aceh yang memiliki semangat perlawanan yang sudah dibangun selama 500 tahun. Kerajaan Aceh lahir dalam semangat ini, ketika Sultan Ali Mughayat Shah mengusir Portugis dari pelabuhan Pidie dan Pasai di tahun 1520-an dan untuk pertama kalinya mempersatukan seluruh wilayah pantai utara Sumatera. Abad berikutnya, permusuhan dengan Portugis menjadi tema yang mempersatukan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya saling bertentangan, dan membawa Aceh menjadi sekutu negara Turki. Awal tahun 1600-an, Belanda dan Inggris merangkul Sultan Aceh (Ratu Elizabeth menyebutnya "saudara kami yang terkasih") sebagai sekutu melawan Portugis, tapi tidak diizinkan membuat pangkalan atau benteng di Aceh. Aceh bersaing dengan VOC untuk mengontrol timah dari Malaya dan lada dari Sumatera Barat. Bahkan, setelah kalah dalam peperangan pada tahun 1650-an, Sultan Aceh tidak pernah menyetujui perjanjian tak seimbang yang ditandatangani setiap kerajaan maritim lain di kepulauan ini.
Di dalam periode tahun 1700 sampai 1870-an, Aceh lebih banyak bertransaksi dengan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat dibanding dengan Belanda.
Ketiga negara tersebut memiliki hubungan resmi dengan para sultan, meskipun mereka juga terpaksa menempuh gunboat diplomacy saat pedagang lada mereka diserang. Ketika pada tahun 1871 Belanda mendesak Inggris agar melepaskan komitmen perjanjian atas kemerdekaan Aceh, Belanda tidak memiliki dasar hubungan atau perdagangan di masa sebelumnya untuk membangun pengaruh mereka. Karena itu, mereka melakukan kesalahan besar dalam perang yang paling banyak menimbulkan malapetaka dan pernah mereka lawan di wilayah timur wilayah Belanda di Vietnam dari tahun 1873 sampai sekitar 1913.
Perang perlawanan Aceh terhadap serangan Belanda yang berlangsung lama ini merupakan peristiwa yang menandai transisi menuju modernisasi, dan ini meninggalkan goresan yang sangat berbeda dibanding apa yang terjadi pada sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya. Pada dasarnya sikap hati orang Aceh sudah menunjukkan perlawanan, seperti tergambar dalam sebuah surat yang ditulis tahun 1874: "Kami tidak akan patah semangat bahkan jika ribuan pejuang kami mati, karena tujuan kami ialah mengusir musuh dari negeri ini." Kemudian ketika puluhan ribu orang mati, semangat kesyahidan justru semakin meningkat, dan ulama yang mendukung hal ini menjadi semangat perlawanan. Pada tahun 1885, Teungku Di Tiro menulis surat kepada pengikutnya yang kurang memiliki keberanian: "Jangan biarkan dirimu takut melihat kekuatan orang kafir, barang milik mereka, perlengkapan mereka, dan tentara mereka yang terlatih…, karena tidak ada yang kuat, kaya, dan memiliki tentara yang baik selain Allah taala." Ketika Gubernur Belanda mengajukan negosiasi untuk dicapainya perjanjian, ulama tersebut menjawab tegas bahwa ia harus menganut Islam terlebih dulu, "Kemudian, kita akan dapat menyimpulkan sebuah perjanjian."
Tentu saja Tuhan tidak memberikan kemenangan seperti yang diharapkan Teungku Di Tiro, dan generasi selanjutnya terpaksa menerima kenyataan adanya kekuasaan Belanda. Tapi, bahkan dalam periode yang paling "normal" selama Belanda berkuasa, 1920-an dan 1930-an, terdapat lebih dari 80 kasus pembunuhan (Atjeh-moord) terhadap orang Belanda. Tahun 1938, Gubernur Belanda mengingatkan Batavia bahwa setiap orang Aceh memiliki "rasa cinta akan kemerdekaan yang fanatik, diperkuat oleh rasa kesukuan, dan sebagai akibatnya mereka memandang rendah orang asing."
Sekitar tahun 1920-an, Sarekat Islam menjangkau Aceh dengan membawa pesan bahwa ada harapan baru dalam solidaritas yang lebih luas dengan sesama muslim di wilayah kepulauan Indonesia. Ide ini hanya memperoleh pendukung yang sedikit saat diperkenalkan oleh pergerakan berbasis di Jawa, SI dan PKI (yang pendukungnya membunuh 21 tentara Belanda di Aceh Selatan tahun 1926), tapi kemudian memperoleh lebih banyak pendukung ketika sekolah Islam reformis mempengaruhi gerakan reformasi Minangkabau dengan membawa pesan yang sama.
Gerakan paling populer pada tahun 1930-an sampai 1940-an di Aceh ialah organisasi reformis Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Pendukungnya berhasil mengadakan pemberontakan di seluruh Aceh melawan pendudukan Belanda ketika Jepang datang pada tahun 1942. Aceh menyambut Jepang sebagai negara merdeka. Namun, dengan segera hubungan di antara keduanya memburuk. Ketika perlawanan sekolah agama Tjot Plieng di Bayu berakhir pada November 1942, lebih dari 100 orang Aceh dibantai, delapan orang Jepang meninggal, dan penakluk lain belajar bahwa cara untuk menghadapi Aceh hanyalah melalui kekerasan.
Ide bahwa nasionalisme Indonesia merupakan sarana yang tepat untuk perlawanan bersejarah Aceh mencapai momen besar selama revolusi 1945-1949. Saat itu pemuda Aceh, terutama dari sekolah Islam reformis, mengajak guru-guru muslim agar bersatu mendukung republik baru. Tanggal 15 Oktober 1945, pemimpin PUSA Daud Beureueh dan tiga pemimpin terkemuka lainnya, atas nama ulama seluruh Aceh, menyatakan "bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dulu di Aceh yang dipimpin oleh Alm. Tgk. Cik di Tiro dan pahlawan kebangsaan lainnya".
Sejumlah pemuda Aceh, termasuk Hasan Muhammad Tiro, yang saat itu berusia 17 tahun, dengan bersemangat menceburkan diri dalam perjuangan itu disertai keyakinan bahwa ada kesesuaian antara tujuan historis Aceh dan nasionalisme Indonesia. Tapi kesesuaian ini segera dipertanyakan sesudah Aceh secara efektif bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950, dan justru orang dari daerah lain ditunjuk untuk menduduki kepemimpinan. Daud Beureueh, Gubernur Militer Aceh selama fase perjuangan yang heroik, disisihkan oleh Gubernur Sipil Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1953 ia menyerukan perlawanan dengan nama Negara Islam Indonesia (NII). Tapi pentingnya otonomi Aceh bagi pemberontak ini baru ditetapkan bulan September 1955, ketika mereka mendeklarasikan Aceh sebagai wilayah yang terpisah dari Republik Indonesia dengan nama Negara Bahagian Aceh di bawah NII, dikepalai oleh wali negara (Daud Beureueh), perdana menteri dan kabinet.
Berbeda dengan pendahulunya, para pemimpin perjuangan yang memakai ideologi kesyahidan Islam, Hasan Tiro menekankan nasionalisme klasik, memikirkan kemenangan Aceh yang gilang-gemilang di masa silam dan hak untuk memperoleh kemerdekaan di masa depan. Kebanggaan orang Aceh dalam kesiapan mereka untuk berkorban melawan tekanan dari luar selalu menjadi inti motif perlawanan, bahkan jika hal ini sering diekspresikan dalam istilah kesyahidan Islam. Kebanggaan ini akan tetap menjadi faktor dalam cara pemecahan konflik sekarang ini.