Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEGERA setelah menginjakkan kaki di Sumatera, Hans Tongka, pemuda Jerman berusia 20 tahun dan tokoh utama sebuah novel, dikenalkan kepada dua macam kuli Cina di perkebunan: bad stinker dan good stinker. Menurut pencerita dalam novel itu, stinker adalah sebutan bagi kuli Cina yang fisiknya telah lemah karena penyakit atau candu, tapi tetap dipekerjakan untuk tugas-tugas yang tak begitu berat. Pengisi strata terbawah pekerja perkebunan itu disebut good stinker jika mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan lumayan, tapi akan menjadi bad stinker bila tak berguna sama sekali.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hans, yang baru datang dari Eropa dan sedang dijamu oleh Vonck, seorang pekebun, menyaksikan tatkala tuan rumahnya bersama sejumlah asisten memukuli seorang kuli Cina yang mencoba kabur hingga kulitnya robek dan darahnya mengucur. Perihal penganiayaan itu, seorang asisten berkomentar, “Ah, dia hanya seorang stinker.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

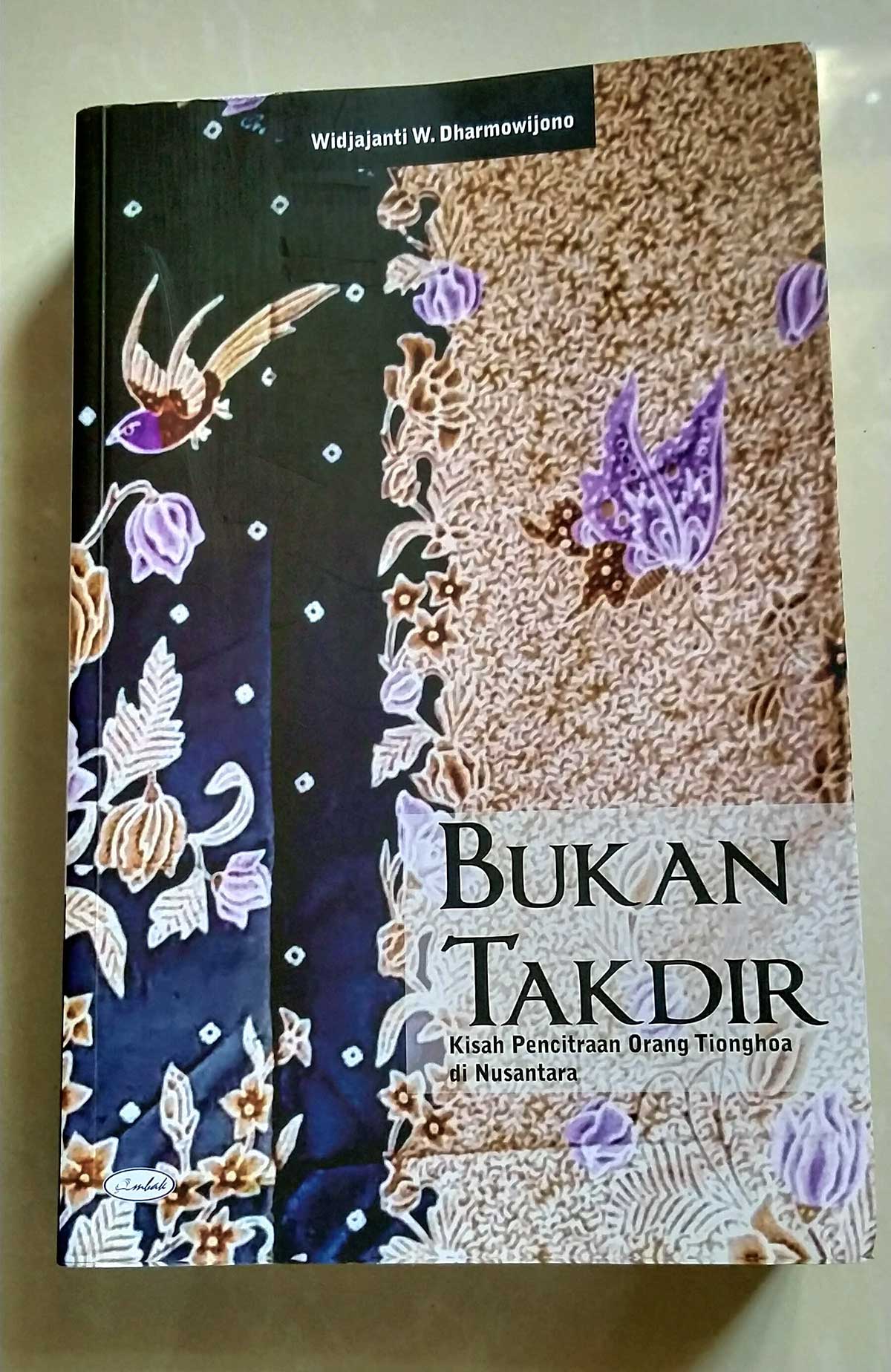
Sampul buku Bukan Takdir, Kisah Pencitraan Orang Tionghoa di Nusantara, karya Widjajanti Dharmowijono.
Novel berjudul Hans Tongka’s Carriére (Karier Hans Tongka) itu ditulis oleh Dé-lilah pada 1898. Fokus utamanya adalah seputar bagaimana Hans yang kurang berpendidikan di negara asalnya membangun impian tentang kesempatan lebih baik di Hindia yang molek dan, pada akhirnya, berhasil memiliki karier moncer di perkebunan Sumatera. Namun, di antara narasi perjalanan Hans, ada informasi tentang bagaimana kuli-kuli Cina yang bekerja di perkebunan itu diperlakukan dan dicitrakan. Hans kelak juga turut menjadi pelaku penyiksaan itu. “Hans tidak ragu-ragu memakai tongkat rotannya yang tebal karena menurut Vonck cara terjitu mengajari orang Cina supaya tidak kurang ajar adalah dengan cara menghajarnya,” begitu tertulis dalam novel.
Pencitraan orang Cina dalam karya sastra ini menjadi fokus penelitian Widjajanti W. Dharmowijono yang dia rangkum dalam buku Bukan Takdir: Kisah Pencitraan Orang Tionghoa di Nusantara. Buku setebal 664 halaman ini diluncurkan pada awal April lalu, 12 tahun setelah Widjajanti menyelesaikan karya itu sebagai disertasi untuk mendapatkan gelar doktor di bidang sastra dan filsafat dari Universiteit van Amsterdam, Belanda. Widjajanti, yang akrab disapa Inge, menelisik lebih dari 200 judul karya sastra kolonial Belanda yang terbit pada 1880-1950 untuk membongkar bagaimana penulis-penulis pada periode itu memposisikan orang Cina dalam cerita mereka. Temuan Inge tak terlalu menggembirakan. “(Karya-karya) ini memperlihatkan sejumlah prasangka atas orang Cina yang sampai sekarang masih terus berkembang,” ujar Inge dalam peluncuran bukunya.
Dalam novel Dé-lilah tersebut, misalnya, Inge menyoroti bagaimana narasi di dalamnya menempatkan kuli Cina bukan sebagai manusia, melainkan menerima perlakuan tak ubahnya seekor hewan. Kadang mereka tak dipanggil dengan nama, hanya angka, misalnya kuli ladang nomor 18. Kuli Cina dicitrakan sebagai kurang ajar, tak dapat diatur, kasar, dan tak apa-apa dibunuh karena “ada cukup banyak orang Cina di dunia ini”. Berbagai penyiksaan yang dilakukan Hans Tongka dikesankan sebagai pekerjaan sehari-hari yang perlu dilakukan ketimbang suatu persoalan yang patut disoroti.

Kedatangan buruh kontrak asal Tionghoa Selatan di pelabuhan Belawan, Medan, pada 1903. KITLV
Dé-lilah adalah nama samaran yang digunakan L. van Renesse, istri seorang pekebun tembakau di Deli. Bukunya tentang Hans Tongka merupakan salah satu judul karya sastra terawal seputar kehidupan di perkebunan Sumatera Timur. Inge menemukan bahwa di antara pelbagai kelompok kuli Cina di Nusantara pada periode kolonial, kuli perkebunan Sumatera yang paling banyak dijadikan cerita.
Beberapa karya yang dianalisis Inge ditulis oleh novelis perempuan, yang umumnya merupakan istri orang Belanda yang menduduki jabatan di perkebunan. Selain Dé-lilah, ada Annie Salomons yang menulis Verhalen uit het verre Oosten (Kisah-kisah dari Timur Jauh, 1930) dan Madelon Székely-Lulofs, mantan istri pegawai perkebunan Belanda, Hendrik Doffegnies, yang menerbitkan seri cerita tentang kehidupan di Deli, antara lain Rubber (1931), Koelie (1932), serta Emigranten en andere verhalen (1933).
Dua buku Székely-Lulofs menimbulkan kehebohan pada masanya dan laris terjual. Salah satu penyebabnya adalah skandal perselingkuhan Székely-Lulofs dengan pekebun asal Hungaria, László Székely. Juga buku ini dianggap memotret pergaulan pekebun dan perlakuan mereka terhadap para kuli. Dalam bukunya, Székely-Lulofs menggambarkan kuli Cina sebagai “tubuh-tubuh kuning seragam” yang bekerja keras. Namun, di sisi lain, orang Cina juga disebut sebagai pria yang merebut wanita dari orang Jawa dengan kekayaannya. Stereotipe orang Cina sebagai orang berpunya diamini sebagai pemicu kebencian dan balas dendam kelompok lain terhadap mereka.
Karya sastra pada periode itu juga ditulis oleh para laki-laki Belanda yang memegang jabatan cukup penting, seperti administrator, bahkan gubernur. Ada juga tulisan dari pengelana atau jurnalis. “Sebagian besar penulis berkisah dari pengalaman mereka sendiri,” tulis Inge dalam bukunya. “Dari posisi itu, sebagai penulis, mereka melihat tokoh Cina.”
Inge menyusun alur bukunya dengan sistematis layaknya sebuah tesis. Di awal dijelaskan bahwa dia mendekati topik ini dengan imagologi, cabang ilmu yang menganalisis secara kritis stereotipe atau pencitraan yang muncul dalam karya sastra ataupun representasi budaya lain. Inge memilih berfokus pada tulisan fiksi naratif ketimbang pada laporan resmi seperti surat kabar atau teks historiografi lain karena meyakini penyebaran stereotipe nasional lebih kuat dipengaruhi genre seperti “roman picisan”.
Bagian paling tebal sekaligus konten utama buku ini ada pada bab keempat yang berjudul “Pencitraan Orang Cina dalam Prosa Naratif India-Belanda”. Buku ini membaginya berdasarkan kelompok pekerjaan rata-rata orang Cina pada masa kolonial, yaitu penambang emas dan timah di Kalimantan Barat, bandar dan opsir Cina, kuli perkebunan, masyarakat Cina sebelum dan saat pembantaian orang Cina di Batavia pada 1740, serta akhirnya perempuan Cina. Tiap subbab dimulai dengan konteks sejarah terkait dengan suatu topik yang dikutip dari sumber resmi, misalnya perkebunan di Sumatera Timur, kongsi di Kalimantan Barat, dan pertambangan di Bangka. Kemudian Inge memaparkan karya sastra apa saja yang dia temukan mengenai kelompok pekerjaan itu beserta ringkasan atau pilihan kutipan paling mencolok dari karya-karya tersebut. Setelah itu, barulah muncul analisis dan kesimpulan bagaimana orang Cina dicitrakan dalam karya-karya yang ditulis dari perspektif kolonial tersebut.

Pekerja Tionghoa di perkebunan tembakau di Deli, Pantai Timur Sumatera pada 1920. KITLV
Tak semua penulis membuat karya yang menyiarkan citra negatif tentang warga Cina di Nusantara. Inge menduga ada perkembangan dari citra negatif ke representasi berwarna positif, tergantung situasi dan fungsi orang Cina di Hindia Belanda. J. J. M. de Groot, misalnya, menulis risalah tentang sistem kongsi di Borneo dan menguraikan sifat perkumpulan politik Cina di tanah jajahan. De Groot (1854-1921) adalah sinologi dan penerjemah bahasa Cina. Dia kelak menjadi guru besar ilmu kemasyarakatan dan etnologi Hindia Belanda di Universiteit Leiden. Dalam catatan kaki pada risalah itu, De Groot mengumumkan dengan terang bahwa dia berharap karyanya dapat mengurangi sinofobia.
Citra orang Cina di Kalimantan Barat yang digambarkan De Groot sangat positif. Orang Cina adalah warga yang paling beradab dan rajin. Koloni Belanda berutang pada kerja keras mereka. Dia menyatakan orang Cina berhak atas penilaian adil yang tidak didasari prasangka. De Groot juga menyebut pandangan buruk terhadap Cina yang muncul dalam karya-karya resmi ibarat parasit bandel yang melekat pada segalanya. Dia menangkis sejumlah deskripsi buruk atas warga etnis Cina seperti yang muncul dalam karya mantan anggota militer, W.A. van Rees, dalam buku Wachia, Taykong dan Amir (1859) yang mengklaim bahwa ciri utama orang Cina adalah “penjilat yang paling pengecut”.
Namun tetap yang lebih kentara adalah prasangka buruk tak berdasar. Dalam bukunya, yang merupakan satu di antara sedikit karya sastra tentang orang Cina kongsi di Kalimantan Barat, W.A. van Rees dengan ekstrem mengabaikan segala jenis prasangka rasial dan sosial dalam masyarakat Eropa karena dia sendiri mengamini segala prasangka itu. Buku Van Rees tergolong sukses dan banyak dibaca, barangkali karena dia berbicara mewakili pandangan mayoritas. Dalam Novellen, levensschetsen en krijgstafereelen, Indische typen en krijgstafereelen (Novela, sketsa kehidupan dan adegan perang, tipe-tipe dan adegan perang Hindia, 1881) Van Rees menulis tentang Kalimantan dan orang Cina yang tinggal di sana. “Tapi saat orang Cina yang kurang ajar tidak puas dengan supremasi atas penduduk asli yang lemah, juga mengangkat tangannya melawan orang Eropa, yang telah mengibarkan benderanya di sana-sini di Pantai Barat tanpa mengganggu politik dalam negeri, ketika itulah tiba saatnya untuk membalas dendam.”
Tokoh utama dalam buku ini bernama Kapten Robert dan dia memuntahkan segala pandangan buruknya saat bertemu dengan orang Cina di Kalimantan. “Jelek”, “serakah”, “pengecut”, “burung pemangsa”, dan “penjarah” adalah beberapa contoh kata yang dia gunakan. Lewat buku ini, Van Rees tak hanya mencitrakan orang Cina sebagai parasit, tapi juga menggambarkan penduduk asli, yaitu masyarakat Dayak, sebagai orang lemah yang tak mau bekerja keras.

Pekerja Tionghoa dan pengawasnya di salah satu perkebunan tembakau di Sumatera, antara 1885-1895. Tropen Museum
Setelah kuli perkebunan, cerita tentang kuli pertambangan cukup banyak ditemukan. Inge menduga jumlah karya yang diterbitkan juga bergantung pada jumlah orang Eropa yang dipekerjakan di bidang tertentu. Ihwal kuli pertambangan timah di Bangka dan di Mendanang, beberapa karya yang utama adalah De berggeest van Mendanang (Hutan Gunung Mendanang, 1925), Van zout en zon (Garam dan matahari, 1934), serta Loten van denzelfden stam (Tunas dari pohon yang sama, 1941). Dalam cerita-cerita ini, tokoh aku atau narator adalah orang Belanda yang punya kedudukan lebih tinggi dibanding karakter Tionghoa. Umumnya, para kuli pertambangan timah Cina digambarkan sebagai kelompok yang mempercayai takhayul.
Pekerjaan orang Cina sebagai saudagar dan pedagang kelontong tentu tak luput pula dari prasangka. Malah periode ini boleh jadi merupakan momen ketika orang Cina paling menarik perhatian. Mereka dikenai pajak yang bahkan lebih tinggi daripada orang Eropa dan harus mematuhi banyak aturan jika menampakkan diri di depan umum, seperti mengenakan pakaian tertentu dan membawa pas jalan. Orang Cina dalam posisi terjepit karena dianggap sebagai rentenir yang mencekik penduduk asli dengan utang riba sekaligus pesaing dagang orang Eropa.
Salah satu stereotipe paling kental muncul dalam karya Robert Nurks den Jongere, yang merupakan nama pena E. van den Gheyn Jr. Dalam buku yang mengisahkan perjalanannya di Jawa dan kunjungan ke Arab dan Cina, dia membandingkan orang Cina dengan orang Arab yang sama-sama lekat dengan stereotipe pekerjaan sebagai saudagar. Sementara orang Arab digambarkan Den Jongere dengan positif (“bangga”, “anggun”, “agung”, “keindahan maskulin”, dan “keberanian”), orang Cina disebut licik, mencurigakan, dan mengisap orang Jawa.

Pekerja Tionghoa di area tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung, 1920. KITLV
Dalam sebagian besar literatur masa kolonial yang membahas orang Cina sebagai pedagang kelontong, Inge menemukan hal paling mencolok adalah para penulis itu banyak menganalogikan orang Cina dengan binatang. Rubah licik, kata Den Jongere. Daum dan Van Oort menyebut orang Cina menyerupai babi. Ada juga yang menyamakan mereka dengan hama, lintah, tikus licik, atau anjing jalanan.
Segala prasangka negatif itu dipupuk, direproduksi terus-menerus dalam karya-karya yang populer dibaca, dan pada gilirannya dapat dengan mudah tersulut menjadi kobaran api yang memusnahkan. Ada subbab khusus dalam buku Bukan Takdir yang mendalami peristiwa pembantaian orang Cina pada 1740. Bagi Inge, mencari tahu akar peristiwa berdarah itu penting karena hal yang sama terbukti terus berulang, seperti dalam kerusuhan 1998. “Saya tidak dapat menghilangkan kecurigaan bahwa peristiwa serupa yang terjadi di tempat yang sama, lebih dari dua setengah abad kemudian, bisa dicegah jika saja kita tahu lebih banyak latar belakang pembunuhan orang Cina di Batavia,” ucap Inge.
Meski menggunakan pendekatan berbeda, temuan yang cukup dapat dibandingkan dengan karya Inge tentang citra orang Cina dalam narasi buatan kolonial adalah hasil penelitian mengenai bagaimana orang Cina sendiri merepresentasikan diri mereka dalam karya sastra. Dalam penelitian berjudul “Masyarakat Peranakan Tionghoa dalam karya sastra peranakan Tionghoa Indonesia pada paruh pertama abad XX”, Dwi Susanto dan Siti Chamamah menelaah karya-karya yang ditulis sastrawan Tionghoa di Indonesia sepanjang 1900-1942. Karya yang dikaji antara lain Nona Tjoe Joe (1922) oleh Tio le Soei, Drama di Boven Digoel (1929-1932) oleh Kwee Tek Hoay, dan Berdjoeang (1932) oleh Liem Khing Hoo. Dalam karya-karya itu, penulis lebih banyak menggali perihal identitas diri sebagai manusia yang berada di antara berbagai oposisi dalam struktur masyarakat kolonial. Sebagian besar karya mengedepankan gagasan agar kelompok Tionghoa mencapai harmoni dengan memadukan instrumen Barat, nilai dan fondasi dunia timur, serta tradisi lokal.

Pekerja tambang Tionghoa di area penambangan timah di Manggar, Belitung, 1903. KITLV
Buku Bukan Takdir juga memiliki semangat menciptakan harmoni baru. Inge memilih judul itu karena ingin menegaskan bahwa diskriminasi yang dirasakan orang Cina di Indonesia bukanlah sebuah nasib yang tak terelakkan, melainkan dibangun dari kisah-kisah pencitraan yang diterima sebagai kebenaran kendati tidak mencerminkan realitas. “Marilah kita membuat pencitraan baru atas dasar kenyataan baru,” kata Inge.
Inge memutuskan menggunakan judul itu setelah membaca catatan sastrawan Goenawan Mohamad atas karyanya ini. Goenawan pertama kali mengetahui penelitian Inge lewat pemaparan di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Dia menyebut buku ini sebagai rekaman yang terdiri atas kesaksian obyektif dan faktual, juga pandangan subyektif dari seseorang yang mengalami langsung situasi menjadi minoritas di Indonesia. Goenawan menulis bahwa buku ini mengandung harapan implisit agar batas-batas identitas yang hanya merupakan bentukan sejarah tak lagi dianggap sebagai takdir. “Salah satu jasa buku Widjajanti adalah mengungkapkan ‘mimpi buruk’ dari generasi yang lampau itu yang memberati generasi yang hidup kini,” tulis Goenawan.
Pembimbing disertasi doktoral Inge, Bert Paasman, juga memuji penelitian ini sebagai pekerjaan perintis karena belum ada peneliti lain yang mempelajari cakupan teks begitu luas untuk topik serupa. Paasman mengaitkan prasangka anti-Tionghoa yang berujung pada pertumpahan darah di Indonesia dengan Kristallnacht atau Malam Kaca Pecah di Jerman pada 1938 yang berakar dari prasangka anti-Yahudi. Penelitian Inge, menurut Paasman, dapat berkontribusi dalam penemuan arah baru sejarah dan budaya Tionghoa di Indonesia. “Akhirnya Widjajanti mencapai pembaca yang dituju: saudara-saudaranya masyarakat Indonesia,” tutur Paasman.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo



























