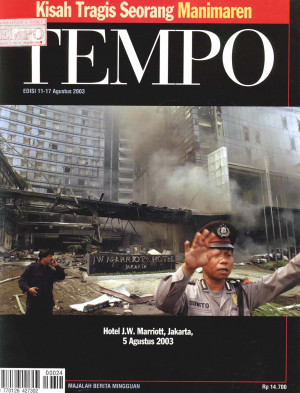RUMAH itu besar, juga megah. Letaknya di sebuah jalan di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Pagarnya putih dengan gerbang besi yang selalu mengatup. Halamannya luas dengan bunga yang bermekar-mekar. Di ruang tengah ada televisi besar, tapi jarang dinyalakan, ditemani sebuah radio transistor. Seperti sebuah kuburan besar, rumah itu senyap siang malam.
Penghuninya adalah seorang pria yang sudah uzur yang kesepian. Dialah Teungku Daud Beureueh, tokoh pergerakan kemerdekaan Aceh yang namanya melegenda itu. Abu Daud, begitu ia biasa disapa, "disimpan" di bangunan itu dari tahun 1978 hingga 1982.
Tadinya Daud adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Pernah pula ia menjadi Gubernur Aceh. Tapi ia lalu merasa disepelekan Jakarta, sewaktu daerah kelahirannya itu dilebur dengan Sumatera Utara pada 1953, dalam periode Perdana Menteri Mohammad Natsir.
Penggabungan itu secara tak sopan memecat sang Teungku dari jabatannya—sesuatu yang bukan saja amat menghina Daud Beureueh, tapi juga melukai hati kebanyakan orang Aceh. Dan luka kian menganga ketika rakyat menganggap para petinggi Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh saat itu berhaluan kekiri-kirian. Republik pun kian terasa jauh dari Serambi Mekah.
Bagi Daud Beureueh, segala kekecewaan itu hanya punya satu jalan keluar: merdeka. Karena itu, setelah tak lagi menjadi gubernur, dari Banda Aceh ia balik ke Kampung Usi, Kecamatan Beureunen, sekitar 15 kilometer dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie. Sebentar saja ia telah menghimpun kekuatan, lalu memimpin perlawanan gerilya melawan serdadu Indonesia.
Sembilan tahun ia berjuang habis-habisan di hutan, tapi "jalan keluar" itu tak kunjung dapat dijejakinya. Lelah berperang, pada 1962 ia lalu menerima tawaran damai pemerintah Indonesia, dan turun gunung pada tahun itu juga. Sebagai imbalan, Jakarta berjanji memberlakukan syariat Islam di Aceh.
Dari gunung ia kembali ke kampung, dan menetap di sebuah bilik di samping masjid di desanya. Menjadi imam di situ, pengaruh Daud Beureueh kian dalam merasuk ke hati rakyat.
Profesor Nazaruddin Sjamsuddin, pakar politik yang pernah menulis buku Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam, punya cerita bagaimana rakyat amat menghormati figur karismatis itu.
Pada 7 Juli 1973, Nazaruddin mewawancarai Daud Beureueh untuk kepentingan studinya. Sedang asyik-asyiknya mereka berbincang, seorang petani lewat naik sepeda. Dia baru pulang dari kebun. Ia mampir sebentar, hanya untuk mencium tangan sang Teungku, lalu memberikan enam biji ketimun yang baru dipetiknya.
Hampir tiap hari Nazaruddin melihat pemandangan itu. Ada saja warga yang datang membawa makanan dan buah-buahan ke rumah itu.
Tapi berbagai pendekatan dan pemberian dari Jakarta selalu ditampiknya. Kesepakatan damai tak kunjung melumerkan kekerasan hatinya terhadap pemerintah pusat.
Abu Daud kecewa. Janji tentang syariat Islam ternyata tak pernah dipenuhi. Iming-iming itu baru terealisasi 43 tahun kemudian, melalui Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang disahkan pada 2002 lalu, 16 tahun setelah Daud Beureueh wafat.
Kekecewaan itulah yang lalu diutarakannya berulang-ulang dalam setiap ceramahnya di masjid-masjid di Aceh maupun Medan. Ahmad Farhan Hamid, putra Abdul Hamid, teman seperjuangan Daud Beureueh, punya kisah menarik soal ini.
Tahun 1976, saat menjadi mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, Farhan pernah mengundang Daud Beureueh berceramah di kampus itu. Semula cuma diminta memberi khotbah agama, eh, Abu Daud malah masuk jauh ke wilayah politik. "Dia juga memaki-maki pemerintah," kata Farhan.
Memang, dalam setiap ceramahnya, Abu Daud tak henti mengkritik kebijakan pemerintah. Ia merasa pembangunan di Aceh tak pernah bisa melayani kebutuhan masyarakat. Ia menjadi saksi betapa di tanah mereka sendiri, orang Aceh cuma jadi penonton ketika Orde Baru membangun berbagai industri besar di sana.
Pada tahun 1970-an, misalnya, di Aceh Utara didirikan pabrik gas Arun. Tapi mesin industri yang menderu cepat itu hanya membuat rakyat Aceh kian tertinggal.
Tak pelak, jurang itu melahirkan kembali perlawanan baru terhadap Jakarta di bawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan Tiro.
Hasan Tiro, yang kini menetap di Swedia, paham betul bahwa restu Daud Beureueh amatlah penting untuk menopang gerakannya. Itu sebabnya, sekembali dari Amerika Serikat, dua kali ia bertamu ke rumah Abu Daud untuk meminta sokongan.
Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, sebagaimana pernah dituturkan langsung Daud Beureueh kepadanya, Hasan Tiro menemui sang Teungku pada akhir 1975, di rumahnya di Beureunen, Aceh.
Dalam pertemuan itu Hasan Tiro penuh semangat menjelaskan isi dan strategi perjuangannya. Tapi Daud tak peduli dengan segala siasat itu. Ia malah bertanya, "Apa dasarmu membentuk Aceh merdeka?"
Hasan tersentak mendengar pertanyaan itu. Belum lagi dijawab, Daud Beureueh sudah menukas sembari menatap tajam, "Kalau dasarnya Islam, silakan. Saya mendukung."
Setelah terdiam sejenak, Hasan Tiro menjawab, "Untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Selama bergabung dengan Republik, Aceh tak mungkin makmur. Jadi, harus berdiri sendiri."
Bukannya memuji, Daud Beureueh malah geleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. "Apa dasarmu sebenarnya?" ia kembali bertanya penuh selidik.
Kembali, Hasan Tiro tercenung.
Aceh, kata Daud, butuh menjadi Islam, bukan merdeka. "Apa nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah kalau dasarnya bukan Islam," kata Nazaruddin mengutip Daud.
Tapi Hasan Tiro tak patah arang. Ia terus meyakinkan Daud Beureueh bahwa orang Aceh memang memerlukan kemerdekaan. Setelah sejam mereka bicara, akhirnya Daud mengangguk memberi restu.
Hasan Tiro langsung bergerak cepat. Kemerdekaan Aceh diproklamasikan pada 4 Desember 1976.
Jakarta berang dan segera mengirim pasukan. Dalam sekejap pasukan Hasan Tiro terdesak, lalu bergerilya di gunung dan hutan.
Namun para petinggi Republik paham betul, roh perlawanan Aceh yang sesungguhnya ada dalam diri Daud Beureueh. Keputusan pun diambil. Legenda hidup itu harus diceraikan dari gemuruh pemberontakan Hasan Tiro.
Sebuah tim khusus lalu dikirim ke Aceh untuk membawa Daud Beureueh ke Jakarta, pada 1 Mei 1978. Dipimpin oleh Sjafrie Sjamsoeddin—kini Kepala Dinas Penerangan TNI—para utusan tiba di kediaman Abu Daud tak lama seusai salat subuh.
Dikisahkan Nur Ibrahimy, menantu Daud Beureueh, tim Sjafrie meminta kesediaan sang Teungku untuk ikut bersama mereka ke Jakarta. "Kami diperintahkan membawa Abu Daud ke Jakarta untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Haji Ismail yang dituding terlibat aksi Komando Jihad," kata salah seorang anggota rombongan itu. Peristiwa ini disaksikan langsung Teungku Nya'Aisah, istri ketiga Daud Beureueh.
Karena sudah tua, sakit-sakitan pula, Daud Beureueh berkeberatan dibawa ke ibu kota Republik. Dengan santun ia menjawab, "Maaf, bukannya tidak bersedia, saya ini sudah uzur. Saya mau bersaksi di sini saja."
Tapi tim Sjafrie berkeras. Masih menurut Nur Ibrahimy, mereka lalu memegangi kaki dan tangan Daud Beureueh. Salah satunya sigap menyuntikkan obat bius. Tapi, karena sang Teungku keras memberontak, jarum suntik pun patah. "Darah berceceran dan membasahi baju Abu Daud," kata Nur.
Daud Beureueh yang sudah terkulai lemas lalu dilarikan dengan jip menuju helikopter yang sudah disiagakan. Ia pun dibawa ke Medan, lalu ke Jakarta. Menurut Nur Ibrahimy, alasan menjadi saksi dalam perkara Komando Jihad itu cuma dalih untuk membawa paksa Abu Daud keluar dari tanah Aceh.
Kepada TEMPO, Sjafrie Sjamsoeddin mengakui memang dialah yang memimpin tim untuk "mengambil" Daud Beureueh. "Ya, kami yang menjemput beliau," ujarnya. Tapi, menurut versi Sjafrie, ketika itu Abu Daud tak sempat melawan, juga tak ada kekerasan berarti, karena obat bius yang disuntikkan cepat bekerja.
Jenderal bekas Panglima Kodam Jaya itu mengungkapkan penjemputan pemimpin karismatik Aceh ini memang dilandasi kekhawatiran bahwa Daud Beureueh akan kembali naik gunung menyokong Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sedang sengit-sengitnya digelorakan Hasan Tiro.
Saat itu perlawanan gerilya Hasan Tiro memang telah merasuki sebagian rakyat Aceh. Dari hutan, mereka gencar menyerang sejumlah fasilitas pemerintah dan perusahaan asing yang beroperasi di Aceh. Pada awal 1978, misalnya, pasukan Tiro bahkan berhasil menerobos masuk ke pabrik LNG Arun di Aceh Utara. Serangan itu menewaskan seorang pekerja warga Amerika.
Namun, di mata Nur Ibrahimy, ketakutan pemerintah pusat itu kelewat berlebihan. Menurut dia, Abu Daud tak pernah sepenuhnya menyetujui gerakan kemerdekaan versi Hasan Tiro itu. Sebabnya, "GAM ini bersifat sekuler dan kurang Islami."
Di Jakarta, mulanya Daud Beureueh tinggal di rumah menantunya, Muhammadiyah Haji, di Jalan Tomang, Jakarta Barat. Tapi tak berapa lama kemudian pemerintah lalu mengontrak sebuah rumah, persis di samping kediaman sang menantu. Bangunannya besar, megah, tapi sepi. Di situlah kemudian Abu Daud harus menetap seorang diri.
Keperluan ia makan diurus anak dan menantunya. "Tiap hari saya dan istri bawa makanan ke rumahnya," kata Nur mengenang. Opor ayam dan ilieh alias belut goreng ala Aceh adalah makanan kesukaan Teungku Daud.
Untunglah, masih ada yang menghibur hatinya. Daud Beureueh selalu berseri-seri saat orang Aceh di Jakarta datang mengunjunginya. Atau juga kala ia berceramah di masjid dan menghadiri acara diskusi, meski dalam lingkup yang sangat terbatas.
Di Jakarta, ruang gerak Daud Beureueh jelas tak lagi leluasa. Aparat keamanan terus mengintainya. Pemerintah cemas, siapa tahu di antara tetamu itu menyusup seorang gerilyawan Aceh. Menurut Nur Ibrahimy, aparat intel, baik dari kepolisian maupun militer, saban hari mengawasi rumah kontrakan di Tomang itu, juga ketat menguntit ke mana pun Daud Beureueh melangkah.
Karena itulah, Abu Daud sendiri menyebut kediaman megahnya di Tomang itu sebagai "sangkar emas pemerintah Indonesia".
Dikungkung begitu, lama-kelamaan tergerogoti juga kesehatan Daud Beureueh. Beberapa kali ia jatuh sakit, dirongrong diabetes dan paru-paru basah.
Berkali-kali ia minta pulang ke Aceh. Tapi baru pada 1982, saat kondisi kesehatannya terus merosot, pemerintah mengabulkannya. Di Aceh, ia kembali menempati bilik di samping masjid di kampung kelahirannya. Tapi sakitnya kian parah. Tahun 1985, ia terjatuh dari ranjang. Engsel pinggulnya cedera berat, dan ia tak sanggup lagi berdiri.
Walau begitu, semangatnya tak pernah pudar. Dalam keadaan selalu terbaring di tempat tidur ia tetap menerima tamu dari berbagai kalangan: pejabat pemerintah, mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, atau petani yang sekadar ingin mencium tangannya.
Sikap kritisnya terhadap pemerintah pusat pun tak lumer. Berkali-kali dia mengirim surat ke Presiden Soeharto, mengingatkan kian merebaknya kemerosotan moral di Serambi Mekah.
Ia baru menyerah ketika ajal datang menjemput. Rabu, 10 Juni 1987, Abu Daud menutup mata, dalam usia 89 tahun. Dari Jakarta, Presiden Soeharto mengirim karangan bunga dan kawat khusus duka cita. Jasad Teungku Daud Beureueh, bersama segenap impiannya tentang masa depan Aceh, dimakamkan di bawah pohon mangga di pekarangan Masjid Baitul A'la lil Mujahidin di Beureunen, sebagaimana yang ia minta.