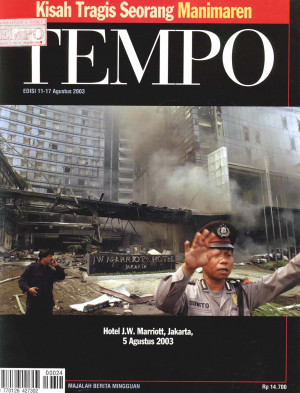SEBUAH pesawat teronggok di sudut luar hanggar skuadron teknik Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Termakan waktu, debu mengerak di sekujur tubuhnya, menutup kemilau perak warna aslinya. Salah satu ban depannya (main wheel) bahkan sobek terantuk batu saat pesawat itu mendarat ketika terbang terakhir kali. Pintu masuknya kelihatan tidak klop lagi dengan "kusen". Tak rapat, tapi bisa dikunci, diamankan gembok hitam dari luar. Ketika TEMPO berusaha masuk ke dalamnya, gembok itu harus dibobok karena kuncinya hilang entah ke mana.
Tak sempurna, tapi kegagahannya tampak masih melekat. Di badan kabinnya yang gemuk, tulisan "Indonesian Airways, RI 001" masih menyala. Bahkan di udara, dengan mesin pistonnya yang terawat baik, dia masih dapat meraung hingga ketinggian 10 ribu kaki dengan kecepatan maksimal 134 knot. Tulisan "Seulawah" di kiri-kanan kokpit pilot bisa berbicara tentang perjalanan-perjalanan heroik yang dilaluinya. Setidaknya begitulah anggapan kebanyakan orang.
Sejumlah penerjun payung yang menggunakannya juga merasa yakin, itulah pesawat yang dibeli dengan dana masyarakat Aceh. Bung Karno menyebutnya Seulawah—gunung emas—sebagai penghargaan. Waktu itu, 16 Juni 1948, Bung Karno berkunjung ke Atjeh Hotel seraya mengutarakan kebutuhan RI akan pesawat buat memperkuat pertahanan udara dan mempererat hubungan antarpulau.
Dalam dua hari, pengusaha Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida) berhasil mengumpulkan 130 ribu straits-dollar, dengan ditambah emas 5 kilogram. Uang itu sejatinya cukup untuk membeli dua pesawat. Pesawat jenis Dakota teregistrasi RI-001 itu diterbangkan ke Tanah Air pertama kali pada Oktober 1948.
Sebagian besar percaya inilah pesawat yang dipakai Bung Hatta mengelilingi Sumatera, Yogyakarta, Payakumbuh, Jambi, dan Banda Aceh. Pesawat itu juga yang menjadi penghubung antara Rangoon (kini Yangoon, Myanmar) dan Kutaraja, di bawah Komodor Udara Wiweko Soepono. Seulawah bahkan mampu menerobos blokade Belanda dengan menyelundupkan senjata dan amunisi dari luar negeri bagi perjuangan melawan agresi Belanda di Tanah Air.
"Seulawah" memang populer, tapi hanya segelintir orang yang tahu bahwa ia cuma replika. Di Indonesia ada dua replika Seulawah lainnya: satu di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, dan satu lagi di Taman Mini Indonesia Indah. Di samping itu, masih ada sebuah replika yang disimpan di museum Rangoon. Myanmar memajang replika tersebut karena merasa berutang budi kepada Seulawah. Saat itu, sekitar tahun 1948, Seulawah sempat dialihtugaskan sebagai pesawat komersial. Saat itu rakyat Myanmar turut menikmati perjalanan udara internasional menggunakan Seulawah.
Menurut Ketua Persatuan Olahraga Dirgantara (Pordiga) Pesawat Bermotor Federasi Aero Sport Indonesia, Frank Reuneker, dia sempat mencari pesawat yang asli. "Tapi rekaman sejarah tentang Seulawah asli yang kami punya sangat sedikit," ujarnya. Untunglah, atas rekomendasi Frank, TEMPO menjumpai satu-satunya saksi hidup. Dialah Sudaryono—adik kandung penerbang Adi Sutjipto—kapten pilot pertama yang menerbangkan pesawat itu.
Dan ceritanya menyedihkan. Pesawat itu milik Amerika Serikat di Filipina kala RI membelinya. Mula-mula ia diterbangkan ke Hong Kong, lalu ke Yogya, dan akhirnya ke Aceh. Selama agresi militer II (awal 1950-an), ia dibawa ke Calcutta untuk overhaul. Saat itu Seulawah tak langsung kembali, tapi membantu penerbangan dalam negeri Myanmar. Baru pada saat penyerahan kedaulatan RI, pesawat ini pulang ke Indonesia.
Di Jakarta, ia sempat muncul dalam pameran di Kemayoran sebagai pesawat RI pertama. Tak lama berselang, pesawat itu dibawa ke depo teknik di Bandung. Rupanya itulah kabar terakhir. Sudaryono masih ingat ketika terakhir kali melihat pesawat ini antre masuk hanggar teknik di Bandung itu. Setelah itu, pesawat ini tidak pernah kelihatan lagi, baik di AURI maupun di Garuda. "Kemungkinan besar Seulawah dikanibal menjadi pesawat lain," ujarnya.
Pesawat asli Seulawah kemudian terlupakan. Sementara itu, replika Seulawah di Bandara Halim (satu-satunya yang masih laik terbang) itu hanya dipakai untuk olahraga dirgantara, termasuk terjun payung, dan terkadang untuk wisata atau joyflight dengan tarif sekitar Rp 6 juta per jam.