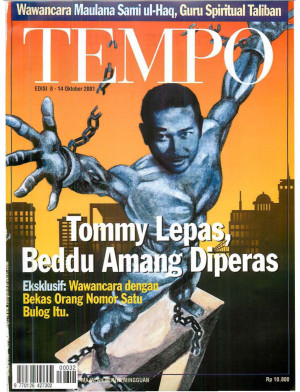Seolah mengalir deras dari kedalaman sebuah sumur, asap berwarna kelabu itu membubung ke udara, lalu—dalam beberapa detik—menghitamkan langit Kabul. Kegelapan membungkus seantero kota, walau sesekali masih muncul kerlip lampu samar-samar di antara lapisan asap tebal. Itulah yang terjadi saat Amerika menghumbalangkan rudal-rudalnya ke ibu kota Afganistan ini pada Minggu malam, 7 Oktober. Peristiwa yang disiarkan Al-Jazeerah—stasiun televisi Qatar—itu tiba-tiba mengembalikan ingatan saya pada sebuah perjalanan panjang ke jantung negeri itu, nun jauh di akhir Mei 1972.
Menyetir mobil Opel setengah tua dari Jerman, saya memasuki Kota Herat di Afganistan Barat. Musim semi baru tiba. Pokok-pokok anggur serta pitzazia menghijau di kota berpenduduk 120 ribu jiwa itu. Masjid-masjid terpelihara dengan baik. Lantai rumah-rumah ibadah itu cemerlang oleh marmer berwarna-warni. Dari Herat, Opel tua itu meluncur ke Kandahar. Di kota asal Mullah Muhammad Umar, pemimpin Taliban itu, saya menemukan banyak gedung tua yang hampir roboh. Tapi Kandahar juga memiliki areal perumahan mentereng milik kaum saudagar kaya.
Daerah ini amat tersohor di Afganistan karena dalam salah satu masjidnya tersimpan sebuah mantol milik Nabi Muhammad saw. Seorang profesor Jerman, Willy Kraus, menuliskan hal ini dalam bukunya, Afghanistan. Penduduk setempat betul-betul ramah. Sembari tersenyum lebar, mereka mudah saja mengajak orang asing mampir untuk sekadar melepaskan dahaga. Melalui jalan tol yang mulus—yang separuh dana pembuatannya disumbang oleh Uni Soviet—mobil-mobil bisa berlari kencang sepanjang 500 km menuju Kabul. Saya memasuki ibu negeri itu pada sebuah senja hari. Terletak di lembah yang subur, kota itu diapit oleh Bukit Asmai dan Sherdarwaza. Dan Sungai Kabul yang jernih mengalir dari belahan kedua bukit tersebut.
Di utara sungai itu, terdapat pusat kota yang terdiri dari banyak bangunan modern. Kota Tua (Old City) terletak di timur laut Sherdarwaza. Keramahan Afganistan ternyata masih kental juga di ibu kota. Tatkala Wali Kota Kabul Abdul Madjid mendengar ada seorang geolog Jerman yang melancong ke kota itu, ia mengutus Karim Madjid, salah seorang putranya, untuk menjemput saya agar menjadi tamu keluarga itu.
Madjid dan keluarganya mendiami kawasan Darulaman. Permukiman modern bergaya Eropa ini terletak sekitar lebih lima mil dari pusat kota, dan dibangun oleh Raja Nadir Shah (1929-1933). Putranya, Mohammad Zahir Shah (1933-1973), kemudian tampil sebagai penguasa terakhir monarki. Ke-kuasaannya tumbang, dan ia kemudian lari ke pengasingan di Roma pada 1973 sampai sekarang. Sejarah monarki Afganistan banyak diwarnai perang dan intrik. Dalam masa pemerintahan Nadir Shah dan Zahir Shah, Kabul boleh dikata mengalami puncak kemakmuran.
Aroma kemakmuran itu terukir di jalanan mulus, gedung-gedung modern, hotel berbintang, dan gedung pertunjukan serta kolam-kolam renang. Beberapa hotel ternama di masa itu adalah Hotel Spinzar, Hotel Kabul, dan Gulshan Park. Restoran-restoran terserak di berbagai sudut kota. Bersama Karim Madjid, saya mampir ke kedai makan paling ternama di Kabul saat itu: Bahg-I-Bala alias Taman di Atas Bukit.
Restoran ini tadinya istana Raja Amir Abdur Rahman (1880-1901), yang arsitekturnya amat dibanggakan Afganistan. Kami memesan pilaus, makanan khas setempat yang terdiri dari nasi dimasak dengan daging dan sayur-sayuran. Sembari menantikan matangnya pesanan, para tamu dipersilakan berjalan-jalan di Taman Zarnegar di seputar restoran. Afganistan adalah negeri yang memiliki banyak sahara sehingga penduduk amat menghargai taman.
Kabul juga populer dengan chai-kana: rumah-rumah minum teh. Dan tentu saja bazar—pusat-pusat perbelanjaan. Bazar yang paling masyhur ialah Char Chatta. Pernah di-bakar Inggris (1838-1842), Char Chatta tetap menjadi pertokoan nomor satu di Kabul pada masa itu. Semua bisa dibeli di bangunan besar ini: perhiasan emas, intan, baju-baju elegan dan dibordir, ribuan permadani, batu permata, rokok Amerika, dan korek api dari Rusia.
Selama berabad-abad, Kabul dan daerah seputarnya menyimpan simbol berbagai peradaban yang pernah singgah di negeri itu. Salah satunya, patung Buddha raksasa—dari abad ke-4 SM—di Guldara, satu jam bermobil dari Kabul. Selamat dari masa monarki dan invasi Soviet, patung ini akhirnya hancur di tangan penguasa Taliban pada Maret silam. Runtuhnya patung-patung Buddha di Guldara dan Baminyan seakan cuma ”kisah pendahuluan” dari kehancuran yang kini kian menggerogoti Afganistan.
Ketika bom-bom Amerika berdebum di negeri sahara itu pada hari-hari ini, Kabul yang cantik dari masa silam tiba-tiba menjadi berharga untuk disimpan dalam kenangan.
Stephie Kleden-Beetz, atas penuturan Werner Beetz
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini