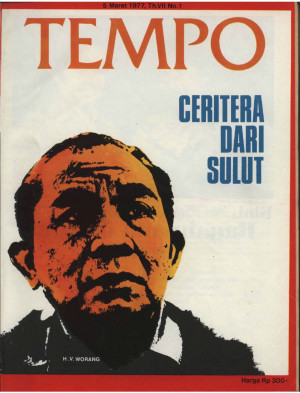MESKI tidak ajeg, Saudara Nurman Sahli (51 tahun) selalu membaca
TEMPO sejak terbitnya. Menjadi wartawan sejak berusia 18 tahun,
kini, untuk menghidupi 6 anak-anaknya, ia bekerja di harian
Suara Merdeka, Semarang. Di Sala, sekitar tahun 50-an, pernah
terbit majalah film yang cukup baik: Star News - yang kemudian
tak terbit lagi tahun 1964. Nurman Sahli adalah pemimpin
redaksinya.
� Majalah Berita seperti TEMPO merupakan kebutuhan bagi orang
yang tidak sempat menelaah isi suratkabar harian. Tapi
ternyata TEMPO justru lebih banyak dibaca oleh khalayak dan
sudah well-informed, yang baca koran-koran dan majala-majalah
yang dengar radio dan nonton TV terutama angkatan mudanya. Ini
merupakan bukti bahwa TEMPO sudah menjadi konsumsi masyarakat
luas sudah berhasil menjadi sumber idiil.
� Setiap TEMPO datang, selalu saya baca lebih dulu Fokus Kita.
Acapkali malah lebih dari satu kali. Padat dan ringkas, tapi
luas dan jero (dalam: Red.) jangkauannya. Saya rasa membuat
Fokus memerlukan kecerdasan dan kejernihan. Suatu kemahiran
menulis yang benar-benar merupakan kurnia. Lepas dari siapa
penulisnya - satu orang atau lebih -- saya usul: kumpulkan Fokus
Kita kelak dibukukan.
� Rubrik Surat-surat ternyata masih tetap belum mantap. Tidak
setiap terbit mesti hadir. Dan isinya masih selalu banyak
koreksi dari pembaca dan rektifikasi dari redaksi. Agaknya TEMPO
belum berhasil mengajak pembaca untuk saling tukar komentar,
tentang --misalnya - laporan utama. Ini merupakan sarana untuk
"senam" pikir dan hati agar demokrasi bisa bergerak.
Kenapa TEMPO sudah latah dengan TTS? Kalau mau "asah otak" saya
pikir lebih tepat diganti dengan semacam "Kuis TEMPO". Muncul
setiap triwulan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan
multiple choice terhadap hal-hal yang pernah dimuat dalam TEMPO
selama tiga bulan. Sekaligus dimuat jawabannya pada halaman lain
untuk pencekan. Tak usah pula dengan hadiah-hadiah penarik minat
segala.
Saudara A. Bambang Pradopo adalah pembaca TEMPO yang paling
banyak menulis, baik untuk rubrik. Surat-surat maupun Sidang
Pendapat. Yang termuat saja ada 22 buah. Berusia 23 tahun dan
belum berkeluarga - mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Trisakti Jakarta ini berlangganan sejak TEMPO terbit.
TEMPO telah membawa tiupan angin segar dalam dunia pers kita.
Betapa tidak. Walaupun membahas masalah-masalah berat tapi TEMPO
mengolahnya dengan gaya bahasa yang indah dan lincah, sehingga
berita-berita yang ditampilkan menjadi ringan dan sedap dibaca.
Tidaklah berlebihan bunyi spanduk di beberapa tempat di Jakarta:
TEMPO, merupakan hasil prestasi sastra dan jurnalistik.
TEMPO juga dapat menghilangkan image bahwa pers kita kalah
dengan pers manca negara. Namun jangan kiranya hal ini
menjadikan TEMPO berpuas diri, sehingga menurunkan kadar
penampilannya dan bahkan membuatnya sekedar menjadi Humas. Dalam
hal ini amat kami sayangkan penghapusan rubrik Esei TEMPO.
Kami sadari pula bahwa masalah dalam masyarakat sekarang ini
lebih sophisticated dan lebih rumit.
Tetapi justru di sinilah terbuka tantangan bagi TEMPO untuk
menjadi besar. Bukankah pahlawan keadilan lebih mungkin lahir
bila terjadi ketidakadilan?
Apakah selama ini TEMPO masih peka terhadap hati-nurani rakyat,
bisa menjembatani pendapat-pendapat, baik dari atas ke bawah
maupun sebaliknya? "Jembatan" seperti itu terasa semakin perlu,
untuk menggalang solidaritas sosial sebagai pangkal-tolak
terwujudnya persatuan nasional serta stabilitas yang dinamis
yang tidak semu.
TEMPO satu-satunya yang berwawancara dengan Ibnu Sutowo
(dikutip AP), dan menyebut hutang Pertamina AS$ 10 milyar lebih
dikutip Reuter), dan dikutip oleh pers asing lainnya (TEMPO,
27 Maret I976) - Red.
S.T. Tjia adalah wartawan kawakan. Untuk memperkenalkannya,
biarlah ia sendiri yang bicara: Saya lahir di Tegal, kota kecil
di pantai utara Jawa Tengah yang terkenal dengan produksi trasi,
ikan asin dan intelektuilnya. Seperti kebanyakan "wong Tegal",
sanak dan keluarga mengembara ke lain kota mencari nafkah.
Umur saya sudah agak lanjut, lebih dari setengah abad. Tapi
semangat masih muda. Setelah tamat SMA di Jakarta, meneruskan
pendidikan di Yenching University (Peking) pada jaman B.C.
(Before the Communists)jurusan bahasa asing dan jurnalistik.
Pengalaman sebagai wartawan antara lain diperoleh di Shanghai,
Chungking, Singapura, Hongkong, Surabaya dan Jakarta. Kini sudah
non-aktip dari dunia pers, walaupun sewaktu-waktu tangan saya
merasa "gatal " ingin menulis lagi.
Sekarang saya menyumbangkan tenaga pada sebuah perusahaan
industri di Jakarta sebagai English secretary. Sudah menikah
(tentu saja), juga dengan "wong Tegal" dan dikaruniai 5 anak
yang sekarang bekerja atau bersekolah terpencar-pencar:
Darmstadt, Houston New York, Atlanta dan Tokyo.
Sebagai ex-wartawan, saya mempunyai hobby membaca banyak koran,
majalah dan buku supaya serba mengetahui (well-informed). Tetapi
lama kelamaan saya merasa terlalu banyak membuang waktu. Maka
saya terpaksa membatasi "kenikmatan hidup" itu dengan mengadakan
seleksi. Antara penerbitan-penerbitan yang saya senang dan
menyegani adalah TEMPO, karena berita-beritanya yang hangat dan
cara menyuguhkannya yang assoooy . . .
Memang saya mempunyai "bias" ( kecenderungan ) terhadap TEMPO,
mengingat bahwa saya pernah menjadi koresponden khusus majalah
Amerika, Time, di Jakarta selama lima tahun. Agak lama juga saya
berkenalan dengan TEMPO melalui pembelian eceran tiap minggu.
Dari majalah TEMPO saya memperoleh gambaran yang cukup jelas
tentang perkembangan-perkembangan berbagai bidang di tanah air
kita. Dari politik ke bisnis, dari hukum sampai olahraga.
Kadang-kadang saya memperoleh beberapa fakta penting yang tidak
dimuat harian-harian.
Menurut pendapat saya, koran-koran kita kurang memuat
berita-berita aktuil (hardfacts) dan penting, melainkan banyak
rencana, anjuran, nasihat dan sebagainya. Kepala-kepala berita
di suratkabar sering mengandung kata-kata seperti "harus",
"akan", "sebaiknya", "tidak dibenarkan", "jangan", "apabila",
dan sebagainya.
Tetapi fakta-fakta saja juga tidak banyak arti atau manfaatnya,
jika tidak dibubuhi penjelasan, tafsiran, latar-belakang dan
sebagainya. Saya suka inter pretatile reporting TEMPO. Selain
fakta-fakta, ia juga memberi interpretasi. Dan latar-belakangnya
cukup pragmatis, walaupun tempo-tempo agak opinionated seperti
majalah Time.
Sudah barang tentu saya tidak selalu sependapat dengan fikiran
redaksi TEMPO, tetapi ini tidak menjadi soal, oleh karena saya
bisa mengambil kesimpulan sendiri. Memang TEMPO adalah majalah
berita mingguan untuk golongan cendedekiawan, politikus dan
mereka yang berpandangan hidup luas, bukan untuk rakyat jelata.
Semoga TEMPO terus bersikap "bebas dan bertanggung jawab".
Bebas mengutarakan fikiran dalam tulisan-tulisannya dan
bertanggung jawab terhadap para pembaca, negara dan bangsa.
Ada 3 koresponden TEMPO yang akan kami perkenalkan. Mereka
adalah Dahlan Iskan (Samarinda), Zakaria M. Passe (Medan) dan
Putu Setia (Denpasar).
Sejak lahir 26 tahun yang lalu, ulang-tahun Dahlan selalu
dirayakan di seluruh pelosok tanah air. Ia lahir tanggal 17
Agustus. Sempat beberapa tahun kuliah di Institut Agama Islam
Negeri Yogyakarta. Di daerahnya sendiri Dahlan sering menulis
untuk beberapa koran lokal.
Awal 1974 ia terpilih menjadi peserta pendidikan pers yang
diselenggarakan LP3ES di Jakarta, selanjutnya mengikuti job
training di TEMPO. Sampai Agustus 1975 ia diangkat sebagai
pembantu tetap TEMPO untuk Kalimantan Timur dan selanjutnya
koresponden hingga sekarang.
"Lima bulan lagi, Insya Allah, akan lahir anak pertama saya,
dari pernikahan 2 tahun lalu dengan 'galuh Banjar' Nafsiah
Sabri", katanya. Ada pengalaman yang tak mudah dilupakannya.
Suatu saat ia membuat laporan mengenai peristiwa yang
dianggapnya penting. Beberapa pejabat ia wawancarai, agar lebih
obyektif. "Tentu saja pendapat mereka tidak sama, bahkan agak
bertentangan", kata Dahlan. Setelah laporan muncul di TEMPO, ada
pejabat yang tidak senang - merasa 'diadu' dengan pejabat lain.
"Ketika kebetulan saya bertemu dengan pejabat tersebut, saya
dituduh 'mengadu-domba'. Saya bermaksud menjelaskannya, tapi
tampaknya pejabat itu sudah apriori. Saya berusaha mengendalikan
emosi, sebab toh tuduhan itu masih mendingan", tutur Dahlan
lagi.
Adapun Zakaria M. Passe, bapal dari 3 orang anak ini, lahir di
Langsa (Aceh Timur) 1 Juni 1942. Marhum ayahnya yang berasal
dari Passe (Aceh Utara) pada zaman Jepan bekerja sebagai pandai
besi pembuat parang dan rencong, kemudian jadi polisi - sampai
pensiun berpangkat peltu. Sementara sang ayah adalah penari
seudati, ibu Zakaria pencinta sastra daerah.
Isteri Zakaria sendiri, Nurhayati Syamsuddin sebelum menikah
suka menyalin hikayat-hikayat berhuruf Jawi (Arab-Melayu) sedang
orangtuanya seorang kolektor hikayat Aceh sampai sekarang.
Itulah sebabnya Zakaria mampu menyusun laporan mengenai kesenian
tradisionil Aceh untuk Panitia Seni Tradisionil Indonesia, 1973,
yang disponsori The Ford Foundation.
Pendidikan terakhir Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara
(tidak selesai). Puisi Zakaria terbit dalam 3 buku antologi
bersama penyair lain: Terminal (1971), Kristal (1974) dan Kuala
(1976). Ia juga menulis naskah sandiwara bahkan main drama
dengan grup Teater Nasional Medan. Menjadi koresponden sejak
TEMPO terbit.
Suka dukanya? "Duka, kalau sumber berita pelit memberi
keterangan atau payah dijumpai. Atau ada larangan menyiarkan
berita". Suka, kalau "tulisan saya mendapat tanggapan positif,
atau honor sudah diterima".
Dan sebagaimana kebanyakan anak Indonesia yang lain, Putu Setia
adalah anak petani. Ia anak petani kopi di Pujungan, kabupaten
Tabanan, Bali - sebuah desa tradisionil yang beradat kuat. Di
bawah ini Putu menulis tentang dirinya sendiri:
Saya hampir saja tidak menikmati bangku sekolah. Untunglah ada
tetangga yang mendesak agar "anak ini disekolahkan". Saya pun
akhirnya menamatkan SMP di sebuah kota kecamatan kecil, 1966.
Agar cepat bekerja, saya lalu memilih sekolah STM di Denpasar.
Saya tinggal di sebuah keluarga yang banyak berlangganan koran
dan majalah. Dan saya tertarik membaca cerita dan sajak-sajak.
Bahkan di ruang praktek sekolah, sementara bergelut dengan besi
dan oli, saya banyak menulis sajak, untuk seorang cewek di
jurusan bangunan. Tak lama, koran daerah pun menampung sajak
saya.
Keluar STM tahun 1969, saya harus pulang kampung. Sebagai lelaki
pertama tanpa ayah, semua persoalan dan beban adat harus saya
pikul. Artinya saya harus berpisah dengan koran. Syukur, saat
itu lagi "wabah" drama gong. Dan saya bisa mengabdi demi adat,
sekaligus larut memimpin drama gong.
Tahun 1972 ada akademi baru: Akademi Jurnalistik Denpasar. Saya
ikut kuliah, terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa, menerbitkan
majalah Suara Jurnalistik lalu mendirikan IPMI Komisariat
Denpasar. Kemudian sayapun merasa bahwa pekerjaan yang paling
cocok untuk saya adalah wartawan.
Koran pertama yang memuat berita saya adalah Berita Yudha
Jakarta, 1972. Dan sejak itu saya berhenti jadi tukang gambar
dan resmi menjadi wartawan harian Angkatan Bersenjata Edisi
Nusatenggara. Saat itu saya sudah berumur 21 tahun (maaf, saya
lahir 4 April 1951).
Setelah konperensi PATA, saya pindah ke Bali Post sampai
akhirnya dikirim ke Jakarta mengikuti pendidikan pers LP3ES.
Saya disuruh praktek di majalah TEMPO -- walaupun sebelumnya
saya protes. Saat itulah, Agustus 1975, untuk pertama kalinya
saya membaca TEMPO, yang bagi saya waktu itu "majalah aneh,
tanpa paha dan pipi di sampul depan". Saya mendapat mesin tik
Royal, hadiah LP3ES sebagai salah satu peserta terbaik.
Karena sekarang musim kampanye, saya kepingin juga
mengkampanyekan diri. Saya pernah dinyatakan sebagai penulis
pariwisata terbaik, menggondol hadiah pertama Lomba Penulisan
Pariwisata Nasional ke-II (1975) dengan hadiah tiket Jakarta-Los
Angeles serta uang Rp 100.000 berikut patung kayu yang disebut
piala.
Kalau anda mau percaya, saya sudah kawin sebelum jadi wartawan.
Tepatnya 19 Desember 1971. Anak tertua lahir 9 Juni 1974,
adiknya menyusul lahir dalam bulan Maret ini juga, barangkali di
saat tulisan ini dimuat TEMPO - menurut ramalan dokter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini