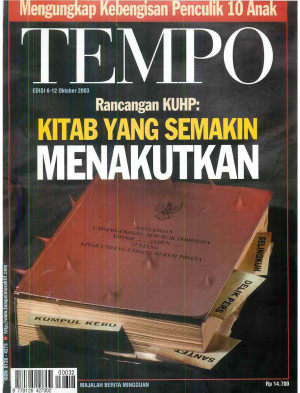Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Hancurkan sebuah jambangan, dan cinta yang menata kembali fragmen-fragmennya lebih kuat dari cinta yang menerima simetrinya sebagaimana adanya ketika ia masih utuh." - Derek Walcott
Ketika itu saya masih amat belia. Pantai Sanur, Bali, seperti rumah kedua. Dua kali setahun kami ke sana, ke sebuah hotel tua di tepi pantai dengan sebuah pasar di sebelahnya. Saya punya teman-teman di sana. Ada yang punya toko kaset, ada yang jual kain dan T-shirt, ada yang kerja di restoran yang sampai tiga bulan lalu menunya masih itu-itu saja.
Seingat saya, yang kami makan di sana juga itu-itu saja—mi goreng yang kami "permak" dengan kecap dan sambal selera (sarapan), "ayam pelecing" yang, lagi-lagi, kami hajar dengan setengah botol sambal selera (makan siang), dan "Shrimp ala Sanur Beach Market", yang asyik disantap malam hari (karena rasa mentega dan bawang putihnya entah kenapa begitu "dewasa", atawa cocok untuk disantap dengan … brem. Maklum, kami masih di bawah umur). Entah berapa ratus kali kami makan terkekeh-kekeh di bawah papan tulis itu, yang bergambar babi guling dengan apel di mulutnya. Kalau bosan, kami jalan kaki seratus meter ke Restoran Lenny dan makan seafood. Di sana, kami merasa tak makan "makanan Bali".
Dua puluh tahun, dan restoran tepi pantai itu masih ada. Pasarnya pun masih ada, begitu pula orang-orangnya. Mereka memang tak lagi ketawa ("Bom Bali telah menghancurkan ekonomi kami"; "Sanur sudah tak lagi dilirik orang"), tapi kami masih saja teringat hal-hal lama. Banyolan, terutama, yang tak selalu lucu, atau berdasarkan fakta lapangan. Salah satunya: "Kenapa orang Bali begitu artistik, begitu nyeni, tapi makanannya enggak enak?"
Bodoh, memang. Waktu itu kami belum kenal be siap atau serombotan. Belum pernah mengalami apa yang diuraikan secara bernas oleh Colin McPhee dan John Coast di dalam buku mereka, A House in Bali dan Dancing in Bali: melihat seorang koki sekaliber I Made Reteg menyiapkan lawar, menyusun betanten, atau menjejalkan bumbu ke dalam bebek betutu. Tak punya duit untuk makan di Tanjung Sari, restoran tradisional Bali milik Wiya Waroruntu. Tak paham yang unik, yang kompleks, tentang bumbu, rasa, dan aroma "Bali".
Dan seperti banyak orang Jakarta sok berbudaya, kami jarang keluar dari Sanur. Bagi kami, Sanur adalah pusat. Kuta? Polusi, "Barat", OKB. Ubud? Ah, tak lebih dari Museum Neka dan penginapan murah di tengah sawah.
Saat itu, beginilah teori kami, kira-kira: makanan Bali sebenarnya biasa-biasa saja, hanya manusianya yang luar biasa—mereka menyerap, bergairah, terbuka terhadap hal-hal baru. Artinya: dengan "pengarahan" yang baik, Pulau Dewata bisa jadi raja dunia. Maka, tak perlu heran bahwa pada awal tahun 80-an restoran makanan asing mutu tinggi mulai bermunculan. Dalam kerangka itulah kami tempatkan Trattoria da Marco dengan spaghetti aglio, olio, dan peperoncino-nya, dan Telaga Naga dengan ayam cabe kering dan remis bumbu tauconya (mungkin restoran Szechuan terbaik di Indonesia). Lalu, datang berita dari Ubud: di Café Wayan, ada carrot cake dan kue death by chocolate yang luar biasa, yang rasanya tak seperti margarin campur krimer; Café Lotus, sebuah kafe dengan kolam yang bestari, menjadi magnet turis mancanegara.... Dari Kuta: anak-anak Jakarta malu kalau ketahuan belum pernah ke Gado-Gado dan La Lucciola....
Teori yang reduktif, memang—seolah-olah ke-"Bali"-an itu ada, atau sesuatu yang tunggal, yang hakiki, yang ditentukan sejak lahir. Tentu ada yang lebih efisien, dan melihat boom restoran sebagai bagian tak terelakkan dari gerak modal dalam "era globalisasi". Uang memang sering lebih tangkas menanggapi gelagat sosial: makanan, bagaimanapun, adalah bagian penting dalam sosiologi sebuah kota. Di Sydney dan Melbourne, di London dan Edinburgh, di KL dan Penang, semesta restoran mengalami revolusi besar-besaran: "rasa" menjadi sesuatu yang asyik—dan demokratis.
Dan Bali bukan Bali jika tak turut bergiat. Dan memang, ia berubah pesat: eksperimen, eklektisme, multietnisitas, semua hadir bersesakan. Makanan Jepang diwakili Kinokawa dan Wasabi; Italia oleh Trattoria Cucina Italiana dan Toscana; India oleh Gateway of India; Yunani oleh Mykonos Taverna dan Panterei. Ku De Ta, Nero, Veranda, Mozaic, semua monumen yang merayakan gaya sekaligus gaya hidup.
Juga, muncul sebuah kelas baru: para pemilik restoran dengan selera tinggi dan kantong tebal, para juru masak impor berkaliber internasional. Lanskap restoran berubah setiap waktu: Said Alem dan Nicholas Tourneville masih menakhodai Café Warisan; Pala Restaurant and Wine Bar merekrut Gees Vermeulen, koki asal Belgia yang sebelumnya memasak di Le Passage di Brussel (kini Gees sedang cuti panjang dan diganti Wayan Sumada) ; Chris Patzold telah meninggalkan Ku De Ta untuk Axiom; Lamak Restaurant & Bar, sebuah restoran papan atas di Ubud, berkibar di tangan koki asal Jerman, Roland Liekert. Di Tanjung Benoa, Heinz von Holzen, penulis The Food of Bali, membuka Bumbu Bali, sebuah restoran dan sekolah gastronomi. Kita boleh yakin bahwa sekarang, di Bali, sebuah generasi muda juru masak telah hadir. Di dunia lain, mereka akan bernasib lain: membuka restoran mereka sendiri, berpose di majalah-majalah kuliner, dan, mungkin, mengendarai mobil mentereng....
Dan keniscayaan itu: yang asing menopang yang asli, dan sebaliknya. Kita ingat Warung Made. Ia bermula pada tahun 1969, sebuah tempat kecil dan sederhana. Saat itu ia adalah satu-satunya warung makan di kawasan Kuta. "Layaknya warteglah, yang pintunya pun hanya dari papan-papan kayu," kata Made Masih, yang mendirikan restoran tersebut bersama ibunya. Saat itu Warung Made hanya menjual nasi campur—yang memang legit menggigit, hidangan kebanggaannya. Tahun 1970-an, restoran ini mulai berkembang. Makanan Eropa—resep-resepnya disumbangkan oleh para tamu bule—mulai menghiasi menu, dari steak sampai pancake. Pada masa yang sama, Warung Made menjadi pembuat es krim pertama di Bali.
Jelas, ada sebuah hubungan timbal balik di sana, yang tak hanya bernilai dalam urusan penyerapan selera "global" dan transfer pengetahuan. Makanan tradisional Bali, yang—seperti kebanyakan makanan daerah—tak pernah jadi bagian dalam tradisi "makan di restoran" (dining out), tiba-tiba ikut "naik pamor". Dan sampai saat ini, apa pun daya tarik Warung Made, nasi campur gado-gadonya masih merupakan hidangan yang paling dicari orang.
Tahun 1983, ketika Ubud mulai merekah, seorang Anak Agung Gede Ariawan (saya mengenalnya sebagai Odeck) mendirikan Ary's Warung. Target awalnya adalah wisatawan kelas back-packer, yang bisa melakukan apa saja yang diinginkan atawa self-service. Sistem pengelolaannya pun sangat sederhana. ''Siapa pun yang mau membantu saat itu bisa jadi kasir," Odeck mengenang.
Masa itu telah lama lewat. Sekarang Ary's Warung sudah menjelma emporium modern bertingkat tiga. Desainnya ajek, ringkas, artistik, sebuah paragon gaya: bar dan lounge di lantai dasar, ruang makan malam di lantai dua, kantor di lantai tiga. Yang ditawarkan: persandingan Interior Asia Baru dan Makanan Asia Baru. Bangunan dan makanan, di sini, adalah konstruksi yang serba ramping dan terukur, antara ruang dan estetika, yang tradisional dan yang kontemporer. Tapi, jangan salah: ini bukan fusion, dalam arti menciptakan makanan baru melalui eksperimen bumbu Timur dan Barat. Tampaknya, distingsi ini penting bagi Odeck: ''Kami memang menggali khazanah budaya, terutama masakan khas Bali atau Indonesia. Lalu kami kemas menjadi modern. Jadi, bukan soal Timur dan Barat."
Kisah Bebek Bengil lain lagi. Di Ubud, di lahan sebesar satu hektare, orang ramai menyantap bebek betutu. Ada juga jukut urap, nasi campur—tanpa embel-embel "Barat". Memang, sejarahnya belum panjang—restoran berbentuk sekepat ini didirikan tahun 1990. Tapi, seperti namanya, ia mengusik: ia percaya diri. Dan ketika restoran ini mulai dikunjungi kalangan "atas"—birokrat, politikus, artis—kaum selebriti internasional ikut-ikutan latah ke sana. Contoh: Mick Jagger, Chow Yun Fat, dan, baru-baru saja, koki kenamaan asal New York, Jean-Georges Vongerichten, beserta para koleganya. Yang terakhir ini begitu terkesima oleh masakan Bebek Bengil, hampir semua yang saya tawarkan di Jakarta setelahnya tak menyisakan kesan (kecuali kepiting lada hitam Pondok Sedap Malam).
Maka, kita prihatin ketika setahun yang lalu bom mengoyak Bali. Menurut data Departemen Pariwisata, imbas dari tragedi World Trade Centre setahun sebelumnya sebenarnya baru mulai sirna bulan Juli 2002. Saat itu memang musim libur panjang, dan wisatawan mancanegara baru saja mulai melirik Bali lagi. Pada 12 Oktober 2002: Bali, jambangan itu, hancur. "Kami sempat tutup dua bulan tanpa pemasukan sama sekali," ujar Made "Kadek" Wiranatha, salah satu pemilik restoran Ku De Ta. "Omzet penjualan pada bulan pertama (setelah tragedi) turun hingga 80 sampai 90 persen," kata Nyoman Sutena, Asisten Manajer Bebek Bengil. Biasanya, dalam musim ramai, restoran tersebut menampung 500 sampai 600 orang sehari. Sekarang, setahun setelah peristiwa jahanam itu, jumlah itu turun setengahnya.
Banting harga, gebyar promosi, semuanya dilakoni, bahkan oleh restoran sepopuler Warung Made sekalipun. Yang paling menyakitkan bagi Made Masih: ketika ia harus memberi komisi kepada sopir taksi dan tukang ojek yang membawa tamu ke "warung"-nya. "Dulu saya suka nolakin tamu, sekarang saya obral habis-habisan," ujarnya pahit.
Di tengah kemuraman ini, ada saja yang tetap optimistis. Santa Fe Bar & Grill di Jalan Dhyana Pura, Seminyak, bahkan berencana menambah kapasitas dari 200 ke 600 orang. "Kami sering menolak tamu karena keterbatasan tempat,'' tutur Eka Mustika Sari, manajer pemasarannya. Dan rasanya bukan sekadar bravado. Di kawasan padat bar ini, paling tidak, bisnis jauh dari mati. Wow Café, Pattaya Café, Oxygen, Nazar, dan Space hanya segelintir contoh restoran dan bar yang baru dibuka. Persaingan, menurut para pelakunya, "semakin tajam".
Pada akhirnya, "Sebuah budaya, kita semua tahu, dibuat oleh kota-kotanya," tulis Derek Walcott dalam esainya yang indah tentang Trinidad. Kalau kita percaya penyair pemenang hadiah Nobel ini, jambangan bernama Bali, yang seakan selalu hidup untuk seribu kota sekaligus, akan terus menata kembali fragmen-fragmennya, untuk tetap hidup dan berbunga. Dan cinta kita bisa jadi semakin kuat.
Laksmi Pamuntjak
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo