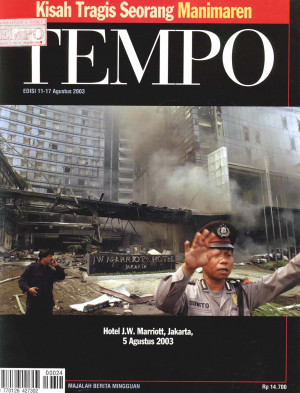HANYA dua bulan sebelum pergolakan—yang kemudian disebut sejarah sebagai Darul Islam—pecah pada 21 September 1953, Boyd R. Compton berkunjung ke rumah Daud Beureueh di Beureuneun, Pidie. Compton, peneliti dari Amerika Serikat itu, bisa menangkap kegundahan hati si empunya rumah. Compton mencatat sebuah isyarat yang dilemparkan Beureueh, bekas Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Isyarat itu: pemberontakan bersenjata segera meletus di Aceh.
"Kami di Aceh ini punya impian," ujar Beureueh seperti dikutip Compton dalam bukunya, Kemelut Demokrasi Liberal. "Kami mendambakan masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda ketika Aceh menjadi Negara Islam," ujar Beureueh.
Beureueh merasa Jakarta menusuknya dari belakang. Pada masa revolusi, dia adalah barisan "kaum republik" yang mengganyang kolonial Belanda dari Aceh. Kini, Jakarta pula yang menyakiti hatinya. Jakarta, misalnya, membubarkan Divisi X TNI di Aceh yang terkenal heroik itu. Lalu, pada 23 Januari 1951, status provinsi bagi Aceh dicabut pula oleh kabinet Natsir. Aceh dipaksa lebur dalam Provinsi Sumatera Utara.
Ketegangan kian memuncak ketika isu "daftar hitam" dikeluarkan oleh kabinet Sukiman. Di Jawa, daftar itu dipakai untuk menjerat anggota PKI. Tapi, di Aceh, sejumlah tokoh mendadak masuk daftar. Mereka ditangkap serta dijebloskan ke bui. Padahal, mereka ulama yang punya jasa mengusir Belanda. "Kita tak bisa lagi bekerja dengan pemerintah tukang tipu," ujar Beureueh.
Kebenciannya kepada Sukarno menyala. Meski begitu, dia tetap menghadap Sukarno di Jakarta. Tujuannya satu: mempertegas nasib Aceh. Dia juga menagih janji Sukarno pada awal kemerdekaan untuk memberikan status otonom bagi Aceh. Jawaban Sukarno membuatnya patah arang: "Apa boleh buat. Negara baru, tentara baru. Apa yang terjadi tak bisa dibantah lagi." Jawaban Sukarno itu dikutip oleh Mansoer Ismail, sekretaris pribadi Beureueh yang masih hidup dan kini berusia 103 tahun.
Menurut Mansoer, Beureueh pun memukul gong pemberontakan itu, 21 September 1953, setelah kongres ulama di Titeue, satu kecamatan di Pidie. Di sana dia menyatakan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia, mengikuti jejak Kartosoewirjo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata dimulai. Bersama Beureueh, sejumlah pasukan TNI pun balik gagang menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai sebagian besar daerah Pidie, dan bertahan di Garot.
Jakarta tak kalah cepat. Dari Sumatera Timur (kini masuk wilayah Sumatera Utara), pasukan pemerintah yang dipimpin Kolonel Simbolon turun ke Garot. Pertempuran pecah. Garot, kota kecil itu, akhirnya jatuh ke tangan TNI. Sejak itu, Beureueh menjalankan taktik gerilya. Posisinya makin kuat karena sejumlah tokoh militer masa revolusi di Aceh, seperti Hasan Ali, Hasan Saleh, Husin al-Mujahid, Ilyas Leube, segera bergabung. Juga sejumlah pejabat sipil setingkat bupati bahkan turut serta dalam kabinet Darul Islam itu.
Dari Pidie, pengaruhnya kian luas hingga meliputi seluruh daerah Aceh. Berkali-kali pula TII menyerang tentara pemerintah. Yang tragis adalah buntut kontak senjata di perbatasan Aceh Barat dan Aceh Besar. Saat itu, satu truk TNI yang membawa drum minyak plus 16 serdadu dihajar peluru pemberontak. Kendaraan berat itu meledak. Semuanya tewas terbakar. Tentu saja aksi itu membuat TNI marah besar.
Hari itu, 26 Februari 1954, pasukan TNI dari Batalion 142 asal Sumatera Barat memburu para pemberontak Darul Islam di kawasan Lhok Nga, Aceh Besar. Mungkin karena sasaran tak ditemukan di Desa Cot Jeumpa, mereka lalu jadi murka. Sekitar 25 petani tak bersalah di kampung itu ditembak mati. Dua hari kemudian, pembantaian berlanjut ke desa tetangga, Pulot. Serdadu TNI rupanya telah gelap mata. Mereka menghajar 64 nelayan di kampung miskin itu sampai tewas. "Termasuk orang tua dan anak-anak," ujar Ahmad Chatib Amarullah, yang akrab dipanggil Acha, wartawan senior Aceh.
Acha, kini berusia 73 tahun, masih ingat betul detail peristiwa itu. Dia mencatat, aksi brutal itu baru disiarkan sepekan kemudian di harian Peristiwa edisi 3 Maret. Di koran lokal miliknya itu, Acha memuat berita tersebut dengan judul Banjir Darah di Tanah Rencong. Berita itu juga sampai dikutip oleh koran nasional dan asing, semisal Indonesia Raya dan New York Times. Gara-gara itu pula parlemen sempat guncang. "Warga Aceh di Jakarta protes keras ke Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo agar mengirim misi ke Aceh untuk kasus itu," ujarnya.
Namun, Ali Sastroamijoyo tetap berkeras bahwa pemberontakan Beureueh memang harus ditumpas. Dia makin yakin setelah Tangse dan Takengon, dua basis pasukan pemberontak, jatuh ke tangan pemerintah. Tapi, sampai kabinet Ali jatuh di tahun 1955, perlawanan di Aceh masih terus berlanjut. Beureueh tak mundur setapak pun.
Gerilya diteruskan, pasukannya itu terus berpindah-pindah tempat. "Tapi paling sering kami bermarkas di hutan Lueng Putu," ujar Mansoer. Di hutan belantara itu, Beureueh hidup di sebuah bilik yang disebutnya "rumah kulit"—karena seluruh dinding dan lantainya terbuat dari kulit pohon. Memang, tak ada lagi pertempuran besar. Meski begitu, Aceh kerap disebut daerah sangat rawan "gangguan keamanan".
Sementara itu, Jakarta dalam percobaan demokrasi liberal. Pertikaian antar-partai politik begitu panas. Kabinet sering kali jatuh dan kekuasaan politik pun bongkar-pasang. Dalam situasi begitu, soal Aceh timbul tenggelam. Akhirnya Sukarno dan Hatta memang mengirim kurir khusus pada Juni 1955 untuk berbicara dengan para pemberontak. Hasilnya nihil. Perubahan terjadi pada 1956, ketika Komandan Daerah Militer Aceh, Kolonel Sjamaun Gaharu, mencetuskan konsepsi Prinsipil Bijaksana. Artinya, selain operasi militer, tetap dijalin kontak dengan pemberontak untuk mencari jalan damai.
Kontak itu tak banyak membuahkan hasil secara politik, kecuali kesepakatan yang disebut Ikrar Lamteh pada 8 April 1957. Isinya, semacam gencatan senjata kedua belah pihak. Selain itu, ada kesepakatan antara pemerintah lokal dan pemberontak untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan daerah Aceh di atas kepentingan kelompok. Gencatan senjata ini sempat berjalan sampai 1959. Dan momentum itu pun menjadi titik balik pemberontakan.
Di masa itulah Perdana Menteri Djuanda mengunjungi Aceh. Dia sempat bertemu dengan Hasan Saleh, Panglima DI/TII. Bersama Hasan Saleh, hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri Negara Bagian Aceh Negara Islam Indonesia.
Dalam buku Mengapa Aceh Bergolak, Hasan Saleh mengisahkan saat dia bertemu Djuanda. Dia tetap menuntut kepada Djuanda agar Negara Bagian Aceh dijadikan saja bagian dari Republik Indonesia. Tuntutan berbau federalisme itu ditolak oleh Djuanda. Alasannya, Indonesia telah berbentuk kesatuan. Tak ada tempat buat negara bagian. Meski begitu, Hasan Saleh setuju mencari jalan keluar secara damai.
Rupanya, pandangan damai itu tak sejalan dengan Beureueh, sang Wali Negara Bagian Aceh. Dia meminta Hasan Ali membatalkan gencatan senjata dan mulai lagi serangan gerilya besar-besaran. Saat itu, seperti diakui Hasan Saleh, pengaruh Beureueh masih cukup kuat. Dia juga dibantu oleh Angkatan Kepolisian Aceh yang membelot ke DI/TII dengan 300 pucuk senjata. Itu belum terhitung bantuan dari Kompi Sidikalang pimpinan Ibrahim Saleh.
Didera perang selama dua dasawarsa, sebagian tokoh pemberontak itu tampaknya telah letih. Hasan Saleh malah setuju agar pemberontakan Aceh diakhiri saja. Baginya, sebagian tuntutan DI/TII Aceh toh bisa dipenuhi Pusat. Diam-diam, dia bersepakat dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI, Jenderal A.H. Nasution, bahwa tak ada lagi pemberontakan di Aceh. Karena tahu Beureueh pasti tak setuju dengan jalan damai itu, Nasution berpesan kepada Hasan Saleh. "Kekanglah Daud Beureueh agar dia tak bergerak lagi," ucap Nasution seperti dikutip Hasan Saleh.
Dari situ, Hasan Saleh melakukan manuver yang kelak dikutuk habis oleh sang Wali. Dia dipecat sebagai panglima. Sebagai "pengkhianat", darahnya dinyatakan halal. Dosanya tergolong gawat: dia membentuk Dewan Revolusi Negara Bagian Aceh-Negara Islam Indonesia pada 26 Mei 1959. Saat itu, Dewan Revolusi menabalkan Teungku Husin al-Mujahid jadi wali negara. Sementara itu, Hasan Saleh duduk sebagai panglima perang. Sebagian besar tokoh penting Darul Islam Aceh ternyata berpihak ke dewan ini.
Yang menyakitkan Beureueh, para pelaku adalah kawan-kawannya sendiri. Kelompok Dewan Revolusi inilah yang berunding dengan Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi, yang lantas memutuskan Aceh sebagai daerah istimewa. Sebagian tentara pemberontak, seperti yang disepakati dalam perjanjian, bergabung dalam divisi khusus yang menjadi bagian dari Komando Daerah Militer Aceh.
Surutkah Beureueh? M. Nur El Ibrahimy, menantu Beureueh, mengatakan apa yang terjadi dengan Dewan Revolusi bukanlah sebuah kudeta, melainkan sebentuk "split". Artinya, kelompok DI/TII terbelah dua: faksi Hasan Saleh dan Daud Beureueh. Buktinya, di Aceh tetap saja ada pergolakan setelah tahun 1959 itu. Terutama di sejumlah daerah yang masih setia pada Beureueh, umpamanya Aceh Timur, Aceh Tengah, Tanah Alas, Aceh Utara, dan Aceh Barat.
Sementara itu, di tengah perseteruan politik, sebagian orang terus mengupayakan damai. Lagu-lagu damai diciptakan. Isinya mengajak perang berhenti. Yang sangat kondang dan banyak dinyanyikan rakyat adalah lagu Aman, ciptaan Ceh Daman Dewantara, seniman tradisional asal Gayo. Dia dikenal cukup dekat dengan Teungku Ilyas Leube, tangan kanan Beureueh yang sangat setia.
Lagu itu mungkin juga pucuk dari gunung harapan. Seperti pesan kuat pada liriknya itu: "Dengan jari sepuluh, saya sampaikan permintaan rakyat/ Kepada Tuan yang sedang bertikai/ Sirih dan tikar telah kami gelar/ Agar Tuan berdua duduk bersama". Begitu arti lirik yang aslinya dalam bahasa Gayo itu. Rupanya, lagu itu sangat mengena di hati sebagian besar rakyat di pedesaan. "Air mata sampai tumpah menyanyikan lagu itu," ujar Daman, yang sekarang telah berusia 75 tahun.
Gencatan senjata memang berakhir pada 1959, dengan diterimanya proposal daerah istimewa bagi Aceh. Tapi Beureueh masih tetap berkelana di hutan. Di ujung masa pemberontakannya, Beureueh bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia, bersama PRRI dan Permesta. Bersama itu pula sejak 1961 nama Negara Bagian Aceh/NII diubah menjadi Republik Islam Aceh (RIA). Hasan Ali menjabat perdana menteri dalam RIA itu. Belakangan, Ali juga turut meninggalkan Beureueh, dan menganjurkan sang Teungku segera turun gunung.
Pemerintahan Aceh memang belum kuat. Saat itu Sjamaun Gaharu digantikan Kolonel Mohammad Jasin menjadi Komandan Daerah Militer Aceh. Jasin pula yang mendekati Daud Beureueh dengan rasa hormat, dan terus-menerus menyerukan agar pemimpin pemberontak itu mau turun gunung. Sejak 1961, surat menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Jasin berani bertemu langsung dengan Beureueh, untuk berdialog empat mata, di sebuah tempat rahasia (lihat Diplomasi tanpa Todongan Bedil).
Pada hari-hari terakhir di hutan, Beureueh praktis hanya ditemani delapan tokoh, semisal Teungku Ilyas Leube, Hasballah, Amin Negara, Amin Basyah, dan Baihaqi. Posisi mereka kian terjepit lantaran semua daerah basis telah diambil alih oleh Hasan Saleh. Menurut Mansoer, "Pengkhianatan membuat kami tak bisa bergerak bebas lagi." Mereka kian sulit melakukan perlawanan. Setahun kemudian, dengan bujukan Jasin, akhirnya Beureueh luluh. Dia bersedia turun gunung, pada 9 Mei 1962, beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Teungku Ilyas Leube.
Tapi, soal turun gunung ini, Mansoer memberi catatan keras. "Abu Beureueh sebenarnya belum puas karena perjuangannya belum membuahkan hasil," ujarnya. Bagi Beureueh, Jakarta tetap dinilainya sebagai penipu. Soalnya, kesejahteraan rakyat Aceh belum terwujud, meski telah ada status daerah istimewa. Ekonomi masih morat-marit, meski banyak sumber daya alam ditemukan pada awal 1970.
Mungkin itu sebabnya Aceh kembali bergolak, empat belas tahun setelah Beureueh turun gunung. Panggung itu lalu diisi oleh tokoh yang pernah menjadi pengikut Beureueh: Hasan Tiro, yang memulai Gerakan Aceh Merdeka pada Desember 1976. Beureueh memang tak terlibat lagi. Tapi sejumlah rekannya, semisal Teungku Ilyas Leube, memilih bergabung dengan kelompok Hasan Tiro, yang ternyata punya fantasi politik sama: "mengembalikan kegemilangan Aceh zaman Iskandar Muda".
Sampai meninggal di tahun 1987, Beureueh tak pernah memberi komentar terbuka bagi gerakan Tiro itu. Mungkin dia setuju, atau kecewa dengan fantasi politik itu. Sebab, seperti kata Mansoer: "Dalam pidatonya, Hasan Tiro tak pernah menyebut akan mendirikan negara Islam."