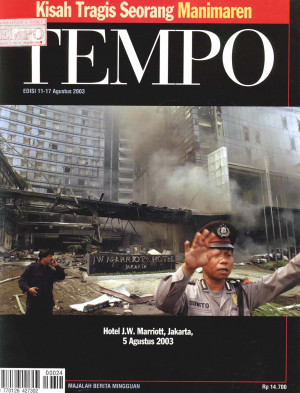Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Suara itu bergetar. "Saya tidak mau membicarakannya," kata Profesor Teuku Ibrahim Alfian, ahli sejarah dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ayah dan ibu Ibrahim memang selamat dari Perang Cumbok, Aceh, 1946. Tapi nenek, kakek, pamaaan, juga banyak sepupunya jadi korban massa yang marah pada keluarga uleebalang, bangsawan. "Saya tak tahu di mana kubur mereka sampai kini," kata Ibrahim.
Dan bukan hanya Ibrahim Alfian yang berduka. "Kita semua menangis mengenang kejadian berdarah itu," kata Farhan Hamid, anggota DPR dari Fraksi Reformasi. Farhan adalah anak ketiga dari Teungku Abdul Hamid—akrab dipanggil Ayah Hamid—ulama, juga sahabat Teungku Daud Beureueh.
Seperti disebut James T. Siegel, antropolog dari University of California, dalam bukunya The Rope of God (1962), Perang Cumbok tak bisa lepas dari konteks tatanan sosial pada saat itu. Tatanan yang sengaja dibangun demi kepentingan Belanda.
Awalnya, 1867, Sultan Aceh diminta tunduk pada kedaulatan Hindia Belanda, yang berpusat di Batavia. Sejak itulah muncul gelombang perang panjang lagi mahal yang melahirkan pahlawan nasional sekelas Cut Nyak Dien, Teuku Umar, dan Teungku Cik Di Tiro (1867-1942).
Demi memenangi perang, Belanda menugasi Snouck Hurgronje, ahli ilmu Islam, guna mempelajari karakter masyarakat Aceh. Dalam The Atjehnese (1906), Snouck menganjurkan Belanda memanfaatkan uleebalang. Setiap uleebalang punya wewenang penuh mengendalikan nanggroe (negeri). Ada 103 nanggroe di Aceh.
Kekuasaan sebesar itu mendorong bangsawan seperti Teuku Haji Cik Mohamad Johan Alam Syah, dari Peusangan, memakmurkan rakyatnya. Ia mengadopsi teknologi irigasi dan pendidikan, dan akomodatif terhadap ulama. Sebaliknya Teuku Keumangan Oemar. Ia jadi gila kuasa: menguasai lebih dari separuh areal persawahan di nanggroe. Kala terbit sengketa di masyarakat, uleebalang seperti Oemar berpihak pada Belanda. "Mereka punya hakim, pengadilan, polisi, juga penjara sendiri," kenang M. Nur El Ibrahimy, menantu Daud Beureueh.
Jepang masuk pada 1942, polarisasi lama mulai menampakkan wujud yang pukul rata: para uleebalang di satu pihak, rakyat bersama ulama di pihak lain. Lalu, 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan menajamkan polarisasi itu. Sang kabar tak cepat sampai, tapi segenap ulama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)—dipimpin Teungku Daud Beureueh—lalu menyambutnya gegap-gempita, langsung menyatakan sumpah setianya.
Namun, kubu uleebalang tak sejelas itu. Ada Teuku Nyak Arief, Teuku Hamid Azwar, dan Teuku Ahmad Jeunib yang mendukung Republik. Tapi ada Teuku Daud Cumbok yang lebih merindukan kembali datangnya Belanda. Wajarkah hal ini? Tak demikian bagi Profesor Anthony Reid, penulis buku The Blood of the People _ Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra.
"Dia sangat berani, kalau tidak boleh dibilang nekat dan sembrono," kata Reid, yang kini Direktur Asia Research Institute (ARI), Singapura. Di tengah-tengah suasana gandrung kemerdekaan, Daud Cumbok malah gembar-gembor Indonesia belum siap merdeka. Ada banyak cerita tentang dia. Pasar malam di Lam Meulo, markas Daud Cumbok, punya judi dan mabuk sebagai menu utama—simbol pelecehan ulama. Ia memerintahkan penurunan bendera Merah-Putih, penggerebekan rumah para pemimpin PUSA. "Daud Beureueh kami ungsikan ke rumah penduduk di Desa Garot, Metareum," kata Nur Ibrahimy.
Akhirnya, Desember 1945, pemerintah pusat memaklumkan Teuku Daud Cumbok pengkhianat Republik dan harus dihukum. Sang uleebalang menampik.
Pada 10 Januari 1946, ribuan rakyat, ulama, dan tentara Angkatan Perang Indonesia (API)—sebagian komandannya kaum ningrat—menyerang markas Cumbok di Lam Meulo. Tiga hari pertempuran sengit berlangsung. Senapan, meriam saling berbalas. Hari ke-empat, mereka kabur ke hutan. Pertempuran resmi berakhir 17 Januari 1946. Nama Lam Meulo diganti menjadi "Kota Bakti" guna menghormati ratusan orang yang gugur di sana.
Tapi, kemarahan massa tak lekas reda, revolusi sosial meletup. Rumah indah milik Teuku Oemar Keumangan beserta seluruh isinya—senilai Rp 12 juta saat itu—dibakar habis. Tapi Teuku Ahmad Jeunib, yang jelas-jelas menyatakan setia pada Republik—tidak luput dari pembantaian. Para korban termasuk orang tua dan anak-anak uleebalang yang tak berdosa.
Farkhan Hamid ingat satu peristiwa yang dituturkan oleh ayahnya. Serombongan orang meminta ayahnya datang ke sebuah lapangan. Di sana, puluhan orang bersiap-siap menghabisi belasan bocah, anak-anak para uleebalang. Ayah Hamid terperanjat, berteriak: "Tunjukkan padaku hukum Allah yang membenarkan tindakan ini." Massa terdiam. Anak-anak itu lantas dilindungi di pesantren milik keluarganya.
Salah satu keturunan uleebalang yang selamat berhasil dihubungi TEMPO, dia tidak mau disebut identitasnya, menolak berkomentar. "Saya ini sudah uzur, lebih baik tak usah ngomongin hal itu," katanya. Terlalu pahit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo