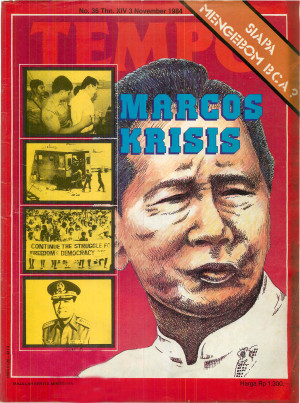Aku tak ingin dirangkai-rangkai menjadi kalung bunga di leher pangeran. Aku tak ingin ditabur di kaki ratu. Aku tak ingin menjadi buah tangan di antara orang yang berkasihan. Aku ingin dibiarkan menyebarkan sari dan wangi sendiri. (Nyanyian orang Desa Chirora, India) COBA, bagaimana?" tanya James Traub kepada Mihil Lal Shukla di suatu pagi yang bening. "Adakah Desa Chirora berubah sejak masa kanak-kanak Anda?" Traub sendiri bilang, sangat sulit mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Tapi yang ditanyainya sekarang, Shukla, seorang pemuka agama Brahma yang dipermuliakan. Kaca mata bulat berbingkai kawat yang dipakainya konon membersitkan uap kecerdasan. Shukla tertegun. Kulit keningnya yang berIipat terangkat, tapi mulutnya terkatup diam. "Bagaimana jalan kotor berdebu yang membawa kita ke sini?" tanya Traub lagi. Benar, jawab Shukla akhirnya, jalan itu baru saja dibangun. Tetapi seorang penduduk desa yang dekil memperkirakan usia jalan tadi 15 atau 16 tahun dan usia itulah yang konon "baru" bagi ukuran Desa Chirora. Apa yang dilakukan orang jika ada yang jatuh sakit? Yah, kata Shukla, orang itu harus digotong dulu ke jalan besar, kemudian diangkut ke dokter yang jauhnya sekitar lima atau enam mil. Sekarang sudah ada kemajuan: tabib modern itu bisa dicapai pada jarak dua atau tiga mil. Traub mendesak terus: Bagaimana jika musim penghujan? "Putus hubungan sama sekali," jawab yang ditanya, seperti sudah maklum. Jika ada yang sakit berat, ada yang selamat, ada yang mati, kata Shukla kalem. James Traub mengangkat kembali tanya jawab ini ke dalam tulisannya berjudul A Village in India: Reluctant Progress, yang muncul dalam The New York Times Magazine. Pengarang buku India: The Challenge of Change itu bercerita dengan enak dalam gaya "aku". Kita biarkan saja ia meneruskan gayanya. * * * Petang itu, ketika matahari condong ke pinggir dataran luas bagian utara India, aku melintasi padang-padangnya yang terbuka bersama Indrapal Singh. Jangkung dan serius, si Singh ini dari "aliran muda" - seorang petani teladan yang memandang jauh ke depan. Indrapal mengharuskan pertaniannya memakai bibit unggul, pupuk, dan herbicide. Di sini, kupikir, orang tidak hanya melihat perubahantetapi juga dengan segera menerimanya. "Mengapa Anda tidak membeli traktor?" tanyaku. Pemerintah India, yang menyadari kesulitan penerapan modernisasi di bidang pertanian, memberikan pinjaman tanpa bunga untuk peralatan pertanian. Indrapal termenung sesaat. "Mengapa saya harus melilit diri dengan utang?" jawabnya. "Saya cukup makan dan pakaian, dan sanggup menghidupi keluarga. Buat apa traktor?" Aku datang ke Chirora, desa berpenduduk 1.500 jiwa di Negara Bagian Uttar Pradesh, untuk mencoba memahami kenyataan dari yang biasa disebut "India yang sesungguhnya". Di daerah bagian utara India ini, setengah milyar manusia hidup di desa-desa. Di dalam dua perlawatanku yang terakhir kemari - yang berjangka waktu setahun - telah kulintasi berbagai desa tanpa mendiaminya. Padahal, hanya dengan menetap di suatu tempat, dan gulang-galing dengan permasalahannya, walaupun untuk waktu singkat - seminggu, katakanlah - kukira baru dapat dipahami ruang lingkup dan laju perubahan ekonomi dan sosial di India. Chirora tampak seperti umumnya desa-desa bagian utara India lain yang pernah kukunjungi. Jalan-jalan sempit, yang melingkar-lingkar di antara rumahrumah lempung, tetap berlapis lumpur lama setelah hujan turun. Sapi dan banteng menggelandang dengan mata berkaca-kaca di halaman yang bergunduk-gunduk candi-candi memperagakan patung-patung tanah dengan mencolok. Toh, desa-desa tidak memperlihatkan sebuah stereotip. Di sini tidak ditemui daerah pedalaman India seperti di dalam khayalan kita, yang terus nyenyak dalam tidurnya yang abadi dan ingkar dari hukum sejarah modern. Tidak. Tidak pula Chirora. Desa ini berjalan seirama dengan era India modern yang meledak dalam pidato-pidato kampanye Perdana Menteri Indira Gandhi dan para anggota Partai Kongres yang sedang berkuasa, yang sedang menyongsong pemilu sebelum Februari. Di dalam pidato-pidato politik mereka, sistem kasta atau kutukan terhadap kaum hina dina konon sedang dibantai. Program-program ekonomi telah dengan mencolok menyentuh kehidupan fakir miskin. Dan, seperti mengutip bahasa poster, mereka bilang, the nation is on the move. Nasion sedang bergerak maju. Itulah retorika di podium. Chirora tidak pernah ada bicara tentang huru-hara berdarah yang menyeret-nyeret kepekaan etnis dan keagamaan, yang membuat Ibu India berurai air mata - di tengah si Sikh dan si Hindu bersibunuh di Punjab, dan orang Islam dan Hindu bertarung. Chirora, seperti umumnya desa-desa India, terdiri dari hampir semuanya orang Hindu. Tema pokok Chirora adalah teka-teki perubahan. Kami menginginkan perubahan, demikian Brahma tua dan petani muda menyanyikan paduan suara. Tentu saja, itu tidak pernah datang - mereka menambahkan - kendati aku dapat melihatnya. Segala prasarana untuk membikin kehidupan lebih baik sudah di tangan - sekolah, bank, pabrik, proyek perluasan pertanian. Tetapi sesuatu terjadi di antara tangan yang ingin meraih perubahan dan prasarana yang hendak digenggam, jatuh terbentang bayangan hitam. Apa? * * * Ketika pertama kali aku tiba di Chirora, sekelompok petani yang bersahabat mengajakku berkeliling ke ladang-ladang. Kami mengitari beberapa bidang tanah sekitar setengah akre luasnya, masing-masing menanam palawija - bawang, kentang, wortel, terung, gandum, dan sejenis padi-padian (millet). Ada juga sejenis pepohonan semak berbulu panjan, disebut arhardal. Mostar (mustard) berbunga putih lembut, dikenal dengan nama shenwa memagari ladang bagai bordiran pada pinggir serbet hijau. Kami bertemu dengan dua lelaki ramping tak berbaju yang sedang menyirami ladang garapan. Mereka secara berirama menimba ember demi ember air dari bak penampungan yang satu ke bak penampungan lain yang terletak 12 inci lebih tinggi. Pada kami diperlihatkan sumur pompa yang digerakkan mesin, yang diharapkan dapat mengairi tanah-tanah pertanian, tapi hanya bisa digerakkan antara pukul 9 pagi dan pukul 4 petang. Pemda setempat, yang terus-menerus kekurangan tenaga listrik, harus bergilir memberi jatah: rumah kediaman, industri, dan pertanian. Pekan ketika kami datang, para petani mengairi sawahnya di bawah sinar bulan purnama. (Pekan berikutnya sejak pukul 5 subuh sampai pukul 11 pagi.) "Jatah listrik," kata seorang petani berpakaian bagus, sambil kami menyaksikan pompa yang menganggur, terasa "omong kosong bilkul" - omong kosong besar. Pembicara bahasa Inggris yang rusak-rusakan itu menoleh ke pemilik mesin pompa yang dicercanya tadi. Orang itu bernama Natwar Singh, sosok yang barangkali tidak mungkin tercapai oleh seorang kelahiran Chirora. Natwar, seperti Indrapal yang tadi, adalah seorang Thakur, kasta tuan tanah utama di Uttar Pradesh bagian tengah. Dia memiliki 35 bikha tanah, sekitar 171/2 akre - pemilikan yang luas menurut ukuran setempat. Rata-rata petani di sana memiliki cuma dua akre tanah. Setelah didesak berkali-kali, Natwar baru mengaku bahwa penghasilan tahunannya mencapai US$ 1.500. Natwar terbilang pedandan paling berselera di Chirora. Sepatunya model kota, jaketnya dari kulit warna hitam, ditambah rompi sweater, dan - melengkapi cita rasanya yang gawat - ada sebatang pena di sakunya. Ia juga pemilik yang bangga ijazah yang paling diidam-idamkan di Chirora: kolese dengan degree ilmu hukum. Kadang-kadang ia berbicara tentang upayanya mencari klien untuk mempraktekkan ilmunya, tetapi terbukti ia tidak terlalu serius dengan profesinya itu. "Ketahuilah," katanya (dalam bahasa Hindi, menyadari bahasa Inggrisnya yang gawat), "Saya putra tunggal ayahku. Saya terpaksa menetap di desa ini apa lagi yang dapat kulakukan?" Natwar adalah pemeluk teguh keyakinan bahwa kerja badan bisa melunturkan martabat seorang Thakur - kepercayaan yang juga merasuki kebanyakan penduduk desa. Sekali aku bertanya kepadanya apa yang menyibukkannya sepanjang hari. Ia tak bisa menjawab. Akhirnya, Tripathy, temannya berleha-leha di desa itu, membantu memberikan jawaban. "Kontrol," katanya. Natwar mengangguk-angguk. Ia dengan datar menolak permintaanku berbicara dengan istrinya: perempuan yang sudah menikah tidak boleh berbicara dengan orang asing. Natwar berusaha menerapkan pengetahuannya agar bisa menjadi petani teladan, tapi tanpa hasil. Beberapa tahun silam, Proyek Percontohan Desa Ramnganga yang bertetangga menyelenggarakan peternakan ayam, dan Natwar membeli sejumlah ayam. Tapi binatang-binatang itu jatuh sakit, dan Proyek Percontohan tidak dapat mengirim dokter hewan. Tak lama kemudian ayamnya mati semua. Penggilingan padi seharga 7.000 rupee (US$ 700) mulai membesi tua di halaman rumahnya, karena ketika Natwar membeli mesin itu di desanya sudah ada tiga penggilingan milik orang lain. Dan yang terakhir mesin pompa itulah, yang airnya - seperti akhirnya diakui Natwar - tidak dimanfaatkan orang. Sawah dan ladang umumnya sudah dicukupi air Sungai Rind yang mengalir di sekitar sana. Sang tokoh sentral Natwar ke mana-mana selalu dibuntuti rombongan pengiring yang riang ria. Di dalamnya tergabung seorang yang berkarakter lain - Guria. Dia ini pendiam dan pemurung, dengan rambut pendek yang asal gunting dan bola mata syahdu kegelap-gelapan. Ia selalu memakai kemeja tanpa potongan berwarna pucat, dan celana piyama putih kedodoran yang menjadi pakaian kebiasaan seluruh India Utara. Guria adalah anggota salah satu kasta"belakang", suatu istilah yang biasa dipakai untuk secara kontras membedakannya dengan kasta "depan": kaum Brahmin dan Thakur. Dia seorang Mallah, berarti nelayan - karena ayah nya seorang nelayan. Padahal, Guria sendiri kini sudah beralih menjadi petani. Guria telah meraih semacam kekuasaan politik formal, dengan terpilih sebagai wakil kepala disebut u-pradhan - organisasi desa yang dikenal sebagai panchayat. Mungkin dengan memanfaatkan kedudukan inilah ia berhasil menyewa empat akre tanah dari gram seva, organisasi desa yang mengawasi tanah umum, di samping setengah akre miliknya sendiri yang tidak memadani. Rumah bata Guria yang kecil memiliki hanya sebuah kamar. Ditengah berkarung-karung padi itulah ia tinggal bersama istri dan dua anaknya yang masih kecil-kecil. Di samping itu, ia juga harus menopang kehidupan orangtuanya. Peralatan rumahnya hanya sejumlah kecil perabotan dapur, selembar poster keluarga berencana - lebih bersifat pajangan ketimbang propaganda pembatasan kelahiran, dan sebuah pecahan cermin sebesar jempol yang hampir terbenam di sela-sela atap jerami rumahnya. Cermin itu dipakainya untuk bercukur. Dalam kunjungan singkat di desa itu, aku kaget melihat hampir separuh rumah di sana dibuat dari bata, bahan bangunan yang di desa-desa bagian terbesar India lainnya hanya dipakai orang-orang kaya. Chirora, dengan sistem pengairannya yang baik memang bisa dianggap lebih makmur ketimban rata-rata desa di sekelilingnya. Sebuah desa tetangga, yang menghadap ke perladangan, merupakan hamparan gubuk-gubuk tanah liat yang diatapi jerami. Kebanyakan penunjuk jalanku berusaha menyingkir ketika kami tiba di permukiman melarat itu, padahal aku ingin tahu siapa yang tinggal di sana. Itulah, demikian dijelaskan, permukiman kasta ketiga dan paling rendah di kawasan itu. Kaum "Tak Tersentuh", yang dikenal di India dengan panggilan Kaum Harijan. Atau disebut pula dengan istilah Kasta Jadwal, karena mereka seperti direncakan untuk diubah nasibnya . . . dalam reinkarnasi. Ketika aku datang beberapa hari kemudian, tidak seorang pun tampak di sana. Tetapi beberapa menit kemudian 40 atau 50 orang berkumpul: wajah-wajah kurus, waswas, dengan pakaian lusuh dan kuno. Dibandingkan dengan penduduk desa lain, mereka kelihatan terlalu cepat tua. Setelah beberapa lama ragu-ragu, mereka memberanikan diri berbicara, dan di dalam percakapan terasa benar bahwa hanya sedikit yang tidak mereka anggap musuh. Di Chirora, seperti di bagian India lainnya, pemerintah daerah setempat memiliki tanah umum untuk dibagikan kepada yang tak bertanah - sebagian terbesarnya dari kasta hina dina ini. Tetapi begitu saat pembagian tiba - sekitar 15 tahun lampau - tekanan jumlah penduduk telah membuat seluruh tanah di Chirora menjadi lahan garapan. Yang tersisa hanya sekitar 10 akre tanah berpasir, di dekat sungai. Sisa itulah, meski tak bermanfaat sebagai lahan pertanian, yang akhirnya dibagikan kepada Kaum Harijan. Tiap kepala keluarga kebagian sepotong kecil - lalu apa yang bisa diperbuat. Hanya sebagian kecil keluarga nemiliki tanah yang memadai untuk menghidupi mereka yang lainnya hidup secara mengais-ngais. Umumnya bekerja sebagai mazdoor, kuli harian, yang berpenghasilan lima sampai delapan rupee (50-80 sen dolar) sehari. Mereka sebenarnya lebih menyenangi bekerja di proyek-proyek pembangunan, tapi pekerjaan yang tersedia di sini langka. Karena itu, beberapa kelompok beralih ke pekerjaan kerajinan tangan, seperti membuat keranjang yang sulit terjual. Toh pekerjaan ini sekadar menunggu datangnya masa panen, saat tenaga kasar mereka kembali dibutuhkan. Merasa terperangkap di dalam kekalahan, Kaum Harijan terpencil atau memencilkan diri dari kehidupan desa. Mereka tidak membuntutiku dari rumah ke rumah seperti yang biasa terjadi di desa-desa. Pada petang hari biasanya anak-anak atau kaum muda bermain bola voli di lapangan pinggir desa, tetapi kasta malang itu tidak ikut. Menonton saja tidak. * * * Praktis kehidupan di desa berputar di sekitar kasta - tetapi tidak dalam cara yang kuperkirakan semula. Aku tadinya menganggap bahwa petani Harijan tidak dibenarkan ikut dalam pekerjaan yang memakai sistem bagi hasil karena prasangka-prasangka masa lalu. Tetapi yang terjadi ternyata jauh lebih maju. Para tuan tanah, menurut Indrapal Singh, "Takut petani penggarap akan mengklaim tanah merekadan karena pemerintah selalu berpihak kepada Kaum Harijan, petani penggarap bisa saja mengambilnya." Tetapi kekhawatiran itu tidak pernah sampai terjadi, Indrapal mengaku - walaupun Anda tidak akan pernah tahu. Aku hampir tidak percaya bahwa kasta atas seperti juga kasta bawah, merasa takut akan "kekuasaan" sebagian besar kelompok tak berkuasa di desa. Di kalangan orang-orang muda kasta atas, atau kasta depan, yang mampir ke tempat tinggalku pada suatu petang (aku tinggal di pinggir desa pada sebuah "bungalo inspeksi" yang dibangun untuk petugas pemerintah yang berkeliling ke daerah) hal itu adalah pokok perbincangan yang tak habis-habisnya. Tak ada yang lebih menggusarkan mereka selain kebijaksanaan "reservasi" pemerintah yang menyisihkan bantuan pembangunan dan mengalihkannya ke beasiswa dan jaringan pelayanan umum bagi Kasta Belakang, suku-suku dari sejumlah kelompok teri lain. Di Uttar Pradesh, seperti telah kusinggung, hampir 45% kegiatan pemerintah diperuntukkan bagi kelompok minoritas ini. Bahkan ada pula pinjaman dan beasiswa khusus untuk mereka. Dalam gelora amarah yang tak terkendali, Natwar Singh dengan susah payah berusaha melontarkan kalimat Inggris kepadaku, "Semua fasilitas diborong Kasta Jadwal, hingga tak lagi bersisa untuk kasta lainnya." "Tapi bagaimana tentang para keluarga Kasta Jadwal di Chirora?" aku mendebat. "Mereka benarbenar papa sengsara." "Anda benar," jawab Tripathy dengan cengir di bibirnya. "Tetapi mereka sudah terbiasa lebih miskin." Aku sempat bercerita kepada sejumlah pekerja Kasta Jadwal tentang status istimewa mereka yang diirikan kasta lainnya. Mereka ribut sesama sendiri. "Ya," jawab salah seorang, "ada tersedia lowongan bagi kami di kantor polisi tapi untuk mendapatkannya kami harus menyogok para sahib polisi." Berapa duit? Beberapa orang menyebut 300 rupee, yang lain berkata 3.000. Kelewat banyak, tentu, bagi si miskin. Bagaimana dengan beasiswa? "Bahkan untuk beasiswa," kata seorang bernama Ran Chander, sambil duduk bersila di tanah di hadapanku. "Kami harus pergi ke sini, harus pergi sana, mengisi kertas ini, mengisi kertas itu. Kertasnya sendiri berharga 50 atau 100 rupee." Kendati demikian, Kasta Jadwal memiliki sebuah kisah sukses. Pralad Kureel, seorang Harijan, berhasil lulus sekolah tinggi dan menjadi orang penting pemerintahan di Lucknow, kota terdekat paling besar setelah Kanpur. Ketika aku mengunjungi Kureel, kulihat ia sudah mendaki jenjang yang tak dapat dipahami orang desa biasa. Sebagai pejabat keuangan sebuah institut riset perkeretaapian, ia menduduki jabatan yang memberinya kekuasaan tertentu. Terlihat para bawahannya keluar masuk terbungkuk-bungkuk dengan berkas di tangan untuk minta tanda tangan. Dan ia memperlakukan anak buahnya dengan sikap keras - perlakuan lumrah di India, dan sering-sering juga di Inggris. Pada usia 47 ia berpenghasilan 2.500 rupee (US$ 250) sebulan, ditambah tunjangan perumahan. Anak laki-lakinya yang tertua kini sedang merampungkan skripsi fisika di Institut Teknologi India ternama di Kanpur. Toh Kuree masih merasa dirinya malang. "Di sini," katanya di belakang tumpukan buku memo dan telepon, "mereka menghargaiku tanpa ada tolok bandingannya. Tapi kalau aku pulang ke desa, orang-orang Thakur itu, mereka seperti menuntut aku mengangkat tabik bila berpapasan." Dan di dalam banjir perasaan yang tiba-tiba meluap, ia mengulang cerita panjang tentang penghinaan dan siksaan yang pernah diterimanya sejak masa remaja hingga sekarang. Dendam pribadinya telah mengental menjadi semacam pandangan hidup. Karena keluarganya relatif sudah berada, ia menganggap contoh dirinya tidak membuktikan apa-apa. Kasta itu-itu juga yang menguasai desa, katanya, dan merekalah pengendali institusi dan administrasi pemerintahan desa. "Sampai dominasi Kaum Thakur berakhir, tidak akan ada satu hal pun yang akan berubah." Padahal, sudah banyak hal mulai berubah dikalangan Kasta Jadwal, walaupun beban pokok yang mendasar tetap menekan kehidupan mereka. Satu generasi silam, Kaum Harijan dilarang keras menggunakan candi dan sumur desa. Larangan-larangan resmi itu kini sudah dianggap tak masuk akal lagi oleh warga masyarakat yang berpikiran waras. Seorang Thakur bernama Bechan Lal dengan bangga berkata kepadaku, "Kami tidak memiliki lagi rasa kekastaan." Tapi, tentu saja, ia tak terniat menerima makanan matang dari rumah Kaum Harijan." Itu 'kan bagian dari kodrat alam," katanya. Masyarakat Harijan telah mendapatkan suatu kejutan di Chirora. Pada 1982, saat berlangsungnya pemilihan panchayat - pemilihan pertama dalam masa 10 tahun - Kasta Jadwal memberikan suara sebagai suatu kubu tersendiri. Mereka memilih pradhan, atau ketua dewan desanya sendiri. Pilihan jatuh pada Jawala Prasad, seorang tuan tanah Harijan yang disegani yang telah mengambil sumpah sannya - miskin suci - setelah istrinya mati 25 tahun lampau. Panchayat hanya bersidang beberapa kali saja dalam setahun dan memiliki kekuasaan yang sangat terbatas. Ini membuat Jawala prihatin. Tetapi pilihan terhadapnya adalah pernyataan lugu tentang kemerdekaan dari golongan tertindas. Tentu saja hal ini memberikan aba-aba peringatan kepada kasta lain. Seperti yang aku simak sendiri, orang-orang Brahmin dan Thakur telah menekan Jawala agar tidak membantu golongannya sendiri. Guria, petugas desa yang mengamat-amati dengan ketat keberadaanku, tiba-tiba jarang terlihat mengunjungi perkampungan Kaum Harijan. "Tak ada perlunya memperbincangkan persoalan ini," desis seorang wanita. Dan tampaknya begitulah. Keharmonisan kasta lama, yang didasarkan pada tirani yang tak tergugat, memberikan jalan ke persaingan yang sedang-sedang saja. Kasta Jadwal telah meraih secuil kekuasaan. Kasta Atas, yang begitu terbiasa dengan kekuasaan mapan, memberikan reaksi di luar batas, malahan dengan sangat bernafsu. Hubungan antarkasta telah menyerupai hubungan antarkelas ketika unsur ritual kasta mulai menyusut. Di tempat-tempat lain di India, terutama di daerah-daerah tempat para tuan tanah berkuasa melakukan kontrol feodalistis ke seluruh segi kehidupan desa, persaingan kaum tak bertanah dengan pemilik tanah menjurus ke huru hara dan kekerasan yang mengerikan. Di Chirora, lebih khas, tidak seorang pun memiliki lebih dari 20 akre tanah. Karena itu, suhu ketegangan jauh lebih adem walaupun dalam masa kunjunganku ke sana ada kericuhan, seorang petani terang-terangan menghajar kemanakannya di depan umum. * * * Kaum tani Chirora sudah melalui masa pahit getir yang panjang sebelum kena embus angin perubahan. Seperti juga seorang Brahmin bernama Mihil Lal Shukla, mereka yang lainnya juga tidak begitu percaya akan janji perubahan. Seperti si "darah muda" Indrapal Singh, mereka yang lain juga tidak yakin seberapa banyak perubahan yang diinginkan. Vinod Kumar Shukla, pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan pedesaan, sudah mencoba meyakinkan sejumlah petani muda agar sudi membeli traktor (dua petani lebih tua sudah membelinya), tapi tanpa hasil. "Mereka terlalu terbiasa dengan lembu janian," katanya, "sehingga merasa sapi jantan mesti lebih baik." Keragu-raguan penduduk desa tentang masa depan membuat ambisi mereka tidak muluk-muluk. Ambisi yang terlalu subyektif dengan cepat menimbulkan tertawaan, sikap acuh tak acuh, dan masa bodo yang mencengangkan. Setiap orang menginginkan hal yang lebih baik bagi anak-anaknya, tapi yang benar-benar baik justru dinilai tak masuk akal. Indrapal Singh bercerita dengan bangga kepadaku bahwa salah seorang anak laki-lakinya bersekolah di SMP, yang lainnya di SMA. Kedua-duanya akan melanjutkan ke sekolah tinggi. Lalu? Indrapal mempunyai seorang saudara laki-laki yang bekerja di kontraktor pembuat jalan di Gwalior, 200 mil jauhnya. Tetapi ia tidak dapat membayangkan anak-anaknya mencari uang di suatu tempat yang jauhnya begitu. Akhirnya, Indrapal berkata, "Polisi." Polisi, hebatnya, memakai seragam gagah, tinggal di kota, dan mendapat penghasilan tetap ditambah sabetan dari hasil suap. Ini memang angan-angan khalayak Chirora, dan itulah batas impian yang bisa dicapainya. Tentu saja tidak semua berangan-angan lugu begitu. Cukup banyak di Chirora yang memiliki cita-cita modern, seperti pendidikan dan pembebasan diri sebagai kelas papa sengsara - sayangnya mereka tidak sanggup membawa dirinya ke sana. Dua puluh pasal program negara bagian Ny. Indira Gandhi, misalnya, menuding mahar sebagai kejahatan sosial, dan orang-orang desa dipermalukan oleh kelanggengan daya tahan emas kawin yang dibayarkan oleh pihak perempuan itu. Mulanya setiap kepala ngotot bahwa mahar tidak dikenal di desa itu. Kemudian Ram Shanker Pathak, seorang Brahmin kaya raya, beringas, dan ugal-ugalan, menceritaiku bahwa 20 tahun lalu ia menerima mahar 10.000 rupee (US$ 1.000), seperangkat sofa, meja kabinet, dan barang pecah belah. Kini, katanya melanjutkan, jumlah emas kawin bisa mencapai 50.000 rupee. Pathak tertawa terkekeh-kekeh ketika kukatakan bahwa semua orang bilang mahar sudah tidak ada. "Tidak ada satu persen keluarga beruang yang tidak ingin meminta mahar," katanya. Barangkali orang dapat mengukur keampuhan gagasan-gagasan baru dari kesan yang didapatnya di Chirora. Tidak seorang pun, misalnya, tidak kaget akan status yang merosot dari istri dan anak-anaknya. Gerakan kaum feminis yang ekstrem hangat-hangat tahi kucing tidak berjalan sama sekali. Kaum wanita, khususnya yang telah menikah, tidak terlihat tampangnya. Mereka tersembunyi di balik dinding-dinding bata di dalam rumah yang jarang tersentuh cahaya, meremas-remas adonan tepung, merajang sayur, menghidupkan kompor, mengasuh bayi. Ketika aku melangkah di lorong berdebu, kulihat sekelompok wanita rumah tangga buru-buru membetulkan letak sari-nya masing-masing di kepala, khawatir si orang asing memandangi wajah atau bahkan menatap langsung ke mata mereka. Aturan memakai purdah, yang didapat Hindu India dari orang-orang Islam yang pernah menaklukkan mereka, dilaksanakan utuh di Chirora. Golongan wanita tertentu tidak menilai mulukkewanitaan yang gemulai. Ini bisa dilihat di luar rumah - gadis-gadis bujangan, para janda, dan wanita Kasta Jadwal, yang bekerja banting tulang bersama kaum pria di ladang-ladang pertanian. Seorang gadis bujangan adalah sosok yang tak dipandang sebelah mata pun, kecuali sepasang tangan dan sebuah mulut, dan juga sebuah cekikikan. Seorang penduduk desa dengan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan akan menjawab "tiga" jika ditanyakan berapa jumlah anaknya. Sekarang ini banyak gadis kecil yang berhasil duduk di delapan sekolah desa, tetapi hanya sedikit yang mampu melanjutkan lebih tinggi. Dan sekali seorang gadis menikah, pada usia 14 atau 15 tahun, lengkaplah sudah perjalanan hidupnya: masa depannya adalah masa lalu ibunya. Ada satu lembaga yang mendobrak lingkaran abadi itu, paling tidak bagi anak laki-laki: sekolah. Tidak ada orang muda yang sudi tinggal di Chirora, walaupun mungkin nasib yang memaksanya tetapi satu-satunya jalan ke kota ialah melalui sekolah. Chirora membangun sekolah lanjutannya sendiri lima tahun silam, dan pada saat itu sekolah telah menjadi penyumbang yang pasif dari mobilitas sosial. Tahun ini ada 146 anak tercatat menduduki kelas tujuh dan delapan dan sebanyak 50 sampai 60 berhasil tamat. Anak kelas tujuh belajar di halaman, di antara tumbuhan marigold dan bunga matahari. Sang guru menulis di salah sebuah tiang sekolah berwarna merah. Anak kelas delapan belajar di ruang kecil, bagaikan para pertapa duduk bersamadi di gua tua. Enam anak laki-laki berjajar di sebelah kiri, enam anak perempuan di sebelah kanan. Ketika aku masuk ke sana, anak-anak sedang diajari bagaimana menghitung luas tanah yang digambar persegi empat atau persegi lima atau jajaran genjang. Guru kelas delapan, Kailash Narayan, yang datang awal tahun ini dari daerah asal bernama Etawah segera menghadapi ruang-ruang kelas yang kosong. "Harap maklum," katanya, "anak-anak disibukkan tugas ke ladang." Suatu hari tidak sampai 20 anak hadir di sekolah. Setengahnya, banyak di antaranya setelah dibisiki Narayan, berkata bahwa mereka bercita-cita ke sekolah tinggi - tapi tak seorang pun tahu mengapa. Satu-satunya hasrat jujur yang dapat kutangkap, ucapan "polisi" yang meluncur begitu saja. Aku memutuskan, tololnya, menjajal murid-murid perempuan. Mereka dikeluarkan dari liang guanya, mengumpul jadi satu, saling sikut dan saling dorong, bagaikan anak kijang bertemu pemburu. Mereka tidak akan masuk sekolah tinggi. Lalu buat apa ke sekolah? Tampaknya mereka tidak punya pendapat. Seorang anak perempuan bersembunyi di balik tiang. Dua lainnya pandang-memandang, bahu mereka membungkuk. Yang keempat menatap pangkal tiang. Aku belum pernah menghadapi percakapan yang begitu beku. * * * Penduduk Desa Chirora tidak menganggap dirinya terbelakang. Para petani dengan ngotot menolak rencana mendesak dari pemerintahnya untuk menghadapi abad ke-20. Terasa ganjil, mereka menganggap itu permasalahan pemerintah, bukan urusan mereka. Di antara mereka ada keyakinan yang mengganjal bahwa pemerintah, ini berarti bahwa kaum politisi, lembaga-lembaga pelayanan umum, dan aparat yang berhubungan langsung dengan mereka sesungguhnya tidak tertarik dengan masalah kesejahteraan hidup masyarakat. Mereka korup tak tanggung-tanggung, dan canggung dengan permasalahan rakyat banyak. Aku menanyai beberapa orang Kasta Jadwal tentang golongan politik yang disukai. "Tapi apa bedanya?" kata Sunderlal, lelaki jangkung yang agak bungkuk. "Setiap pemilu mereka membikin janji sama: Kami akan membagikan tanah kepada kalian akan ada listrik masuk desa akan kami bagi-bagikan batu bata." Adakah janji-janji itu ditepati? Nothing, Sir. Kami tidak akan percaya sedikit pun lagi." Orang-orang desa berkata bahwa para pejabat begitu korupnya sehingga semua rencana pemerintah tentang swausaha perbaikan justru menimbulkan lebih banyak kesukaran. Apalagi makmur sejahtera. Bahkan yang patriotik seperti Vinod Kumar Shukla harus angkat angguk kepada kenyataan pahit itu. "Misalnya ada seorang petani yang ingin mengambil pinjaman pembelian traktor sebesar 50.000 rupee," kata si Kumar. "Pertama-tama, ia harus menyogok pejabat pemerintah yang memutuskan pemberian kredit. Kemudian, ia harus memberi uang semir kepada pegawai bank yang mencairkan uang. Dan setelah itu, ia harus pula menyodorkan uang pelicin kepada agen traktor, agar luku bermesin itu diserahakn kepadanya." Para petani yang merubung mengangguk sengit, dan menambahkan lebih banyak cerita seru seram. Setiap kepala setuju bahwa "penyogokan sudah mencapai puncak yang belum pernah dialami sebelumnya". Barangkali mereka dapat berkata begitu 20 tahun yang lalu tetapi dua dasawarsa silam pemerintah hanya memiliki sedikit dana untuk urusan pembangunan wilayah pedesaan - sehingga sosok korupsi di anak benua itu tampak lain. Dewasa ini, hanya sekelumit negeri sedang berkembang yang mampu menyamai program pemerintah India untuk turun membangun kawasan pedesaan. Toh aparat pemerintah yang bejibun beringsut bagaikan siput ke wilayah desa dan kawulanya seperti juga lamban dan melempemnya kawula desa menyongsong para abdi negara yang datang bersama rencananya. Aku tadinya tidak percaya bahwa tidak seorang pun di Chirora pernah mendengar Proyek Perencanaan Ramnganga, padahal letaknya tiga mil dari sana. Aku baru meyakini setelah mengetahui bahwa orang-orang di Proyek juga belum pernah mendengar nama Desa Chirora. Proyek itu bermaksud mendirikan kelas-kelas peternakan lebah madu pengawetan makanan, hortikultura, dan jahit menjahit - keterampilan yang penting sekali. Tetapi pejabat pemerintah yang menanganinya menganggap tidak ada perlunya promosi dan upaya menarik para peserta. Lalu ada program kesehatan dan keluarga berencana. Secara kebetulan aku mengetahui bahwa di Chirora ada seorang yang disebut penuntun kesehatan masyarakat. Tetapi tampaknya ia tidak dapat memperbarui stok obat-obatan yang ludes saban tiga bulan, seperti yang diharapkannya. Akibatnya, sempat berlangsung setengah tahun tidak ada satu jenis obat pun bisa diberikan kepada pasiennya. Ia juga bercerita bahwa ia sering pergi berkeliling untuk berpropaganda tentang "keluarga besar bencana bagi kalian". Tapi sia-sia. Di seluruh desa, hanya 20 orang sudi dimandulkan - satu-satunya cara pembatasan kelahiran yang bisa jalan di India. Padahal, pemandulan paksa itu yang menjadi salah satu sebab kekalahan Indira Gandhi dalam kampanye Pemilu 1977. Setiap orang sesungguhnya telah menyadari perlunya perencanaan keluarga, toh tidak seorang berniat melakukan persuasi yang bergairah dan bisa masuk ke hati. * * * Sejumlah golongan masyarakat yang berbeda seperti berseteru mencegah penduduk desa mengenali perubahan-perubahan di sekeliling mereka. Padahal, nilai-nilai perubahan itu dapat memberikan kekuatan tambahan kepada orang desa untuk meraih nasib. Rintangan-rintangan keterbelakangan itu ditimbulkan oleh keputusasaan, penyerahan kepada nasib, puas diri, tirani kasta, korupsi, dan penyianyiaan. Dan juga keindahan. Bahwa ada keindahan di dalam kehidupan seperti itu, terasa hampir mengada-ada. Tentu saja ada keindahan pada saat matahari meluncur turun di langit yang jernih benderang. Atau waktu sisa-sisa cahaya matahari bertemperasan di padang-padang diam, dan menyapu mostar kuning dan hamparan ladang-ladang gandum yang menghijau. Tetapi ada jenis keindahan yang menciptakan rasa sakit yang tak tertanggungkan, dan membuat semua ambisi tampil tertolol-tolol. Lalu, adakah sesuatu yang secara mendasar tampak atraktif tentang kehidupan ini? Malam terakhir di Chirora aku diundang makan oleh saudara laki-laki Babu Singh Chauhan, tuan tanah yang ayahnya ternyata menjadi pemilik desa, dan sokogurunya. Kami bersantap di lantai atas yang terbuka. Duduk di belakang meja putar, tuan rumah, penerjemah, dan aku sendiri di antara sekumpulan teman, yang mengaku merasa senang bertindak sebagai pelayan untuk kesempatan yang langka itu. Tuan rumah ternyata telah membeli sebotol wiski - tidak ada yang terlalu baik bagi tamu asing. Karena aku tidak suka minum air yang tidak disaring, dan dia tidak pernah mendengar wiski-soda, aku terpaksa mereguk wiski sepanjang malam itu. Sebagai acara istimewa ia menghidangkan daging, dan kari kambingnya yang terlalu pedas, seperti yang disukai penduduk desa. Aku harus melahapnya, dengan tiap gigitan yang bagaikan melangkah setapak lagi ke pembakaran arang. Aku tidak disediai cuci mulut untuk meredakannya, kecuali wiski. Tuan rumah, yang merasa puas telah menjamuku secara mewah, tidak berusaha menjalin percakapan. Tetapi malam di luar sungguh indah. Beribu bintang, belum pernah aku melihat sebanyak itu, menerangi langit. Di bawah, di beranda, terdengar orang berceloteh dan tertawa lembut, sambil duduk mengitari tabunan. Di seberang sana, desa terhampar diam, walaupun malam belum lagi beranjak pukul delapan. Dan kemudian, seperti masuk dari dunia lain, terdengar tuan rumah berkata. "Maukah Anda menyampaikan sebait puisi?" pintanya. Ini membuatku kaget. Tapi segera aku sadar, di India puisi tergolong hadiah atau bunga tangan. Dan menyampaikan hasrat hati yang mulia dengan puisi dinilai cermin ketulusan pribadi. Kucoba gali dari perbendaharaan kecil puisiku, sebuah bait sajak penuh kenangan dari Emily Dickinson. Diterjemahkan baris demi baris. Tuan rumah dan para pelayan mendengarkan dalam kediaman yang asyik, lalu sorak sorai dan tepukan. Mereka terhanyut. "Sekarang giliran Anda," kataku. Mereka salin tatap sekejap dua kejap saling ajuk. Kemudian, tanpa pendahuluan, datang sebuah suara dari dalam kelompok. Aku tidak tahu siapa yang melagukannya. Hanya beberapa kuplet sajak itu selesai tapi ia mampu mengungkapkan perasaan secara utuh, bahkan berikut nilai filsafatnya secara lengkap. Ambisi, budi daya manusia, keduniawian, begitu ucap sang puisi, untuk pihak lain - yang jauh lebih baik adalah kedamaian dan kesepian. Penyairnya menyalurkan suara sekuntum bunga. Inilah, lebih kurang, apa kata sang bunga: Aku tak ingin dirangkai-rangkai menjadi kalung bunga di leher pangeran. Aku tak ingin ditabur di kaki ratu, Aku tak ingin menjadi buah tangan di antara orang yang berkasihan, Aku ingin dibiarkan menyebarkan sari dan wangi sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini