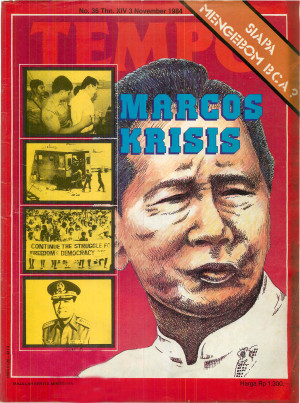JEFFERSON adalah sebuah kota kecil tradisional di New Hampshire, Amerika Serikat. la dikelilingi dinding-dinding. Pegunungan White, dan hampir sepanjang tahun diselimuti salju. Penduduk kota itu menghabiskan waktu mereka untuk bekerja dan kegereja. Di kota itu, wajah-wajah asing yang hitam, yang Spanyol, atau lebih lagi yang Asia - jarang sekali terlihat. Tapi di tempat seperti itulah empat tahun lalu muncul Pendeta Peter L. Pond membawa delapan anak berkulit cokelat. Anak-anak ini bicara "cecowetan" - anak-anak Kamboja. Bapak Pendeta tidak bermaksud aneh-aneh dia bahkan punya tujuan yang mulia: menghidupkan kembali jiwa dan mental anak-anak yang selama bertahun-tahun dihancurkan perang dan teror itu. Jiwa anak-anak itu memang sudah remuk. Sejak sebelum berusia 10 tahun mereka sudah dipaksa merasakan ngerinya kecamuk perang saudara, ledakan bom Amerika, pembantaian oleh teman sebangsa mereka - Khmer Merah - dan penghancur leburkan tatanan masyarakat serta aturan moral. Antara-1970 dan 1975, rezim militer yang berkuasa menyelewengkan nilai-nilai kemasyarakatan. Sebagai anak, waktu itu imajinasi mereka adalah imajinasi yang bersih. Ketika teman-teman sekampung mereka mulai berpaling ke kelompok komunis yang sedang bergerilya, mereka pun dengan penuh minatikut mendengarkan cerita-cerita tentang Khmer Merah. Tentang gadis-gadis dan jejaka-jejaka yang dibawa ke hutan dan dilatih bertempur. Beberapa bahkan berpikir, alangkah enaknya jika Khmer Merah berkuasa - bayangkan, tak akan ada lagi sekolah Lalu Khmer Merah benar-benar datang - menyapu desa-desa, memberangus kota-kota, dan pada tahun 1975 memberlakukan sebuah eksperimen masyarakat baru. Masyarakat Kamboja dibagi dalam dua kelas: "masyarakat inti" - para petani buta huruf yang tak pernah menentang kaum komunis, dan "masyarakat baru" - penduduk Phnom Penh dan para pengungsi yang menyesaki jalanan Ibu Kota tanpa makanan dan sarana kesehatan sedikitpun. Realitas itu membuyarkan segenap angan-angan kekanakan. Dengan segera mereka dipaksa menyaksikan pembantaian sepertiga tetangga mereka yang hidup di kota dan seperenam saudara mereka yang hidup di desa. Yang tertinggal adalah kenangan tentang ayah ibu yang dibawa ke hutan dan tak pernah terdengar lagi beritanya, atau tentang kakak atau adik yang dibunuh di depan mata mereka sendiri. Di Amerika, mereka harus mencoba membuang semua trauma itu. Mereka harus mulai membuka kembali hati yang sudah lama tak mengenal rasa cinta dan percaya kepada orang lain. Itulah tujuan Pendeta Peter Pond membawa mereka ke Jefferson ke lingkungan orang-orang Protestan saleh yang sangat Amerika itu, dan mengangkat mereka menjadi anak. Mereka harus mencari jalan baru dan harapan-harapan baru di tanah air baru. Dan mereka - berarti juga sang pendeta tampaknya akan berhasil. Anak-anak yang mampu selamat di tempat penuh gejolak itu ternyata bisa menyesuaikan diri di tempat yang semula asing. Selama empat tahun mereka telah membuktikannya meski tidak gampang. Dan keberhasilan mereka ini bisa jadi merupakan titik terang bagi 5.600 anak Kamboja lain yang ditolak masuk AS oleh pemerintah setempat, serta 14.500 lagi yang nasibnya masih terkatung-katung di berbagai penampungan sementara. Mereka tertolak oleh peraturan yang melarang pengungsi yang "terlibat" Khmer Merah memasuki AS - peraturan yang tak jelas, karena pemerintah tak memberi definisi pasti untuk "terlibat". Kedelapan anak itu sendiri dalam beberapa hal jelas terlibat. Mereka, paling tidak, pernah menggembalakan ternak atau bekerja di ladang untuk Khmer Merah. Beberapa bahkan pernah dipaksa jadi tentara untuk melawan Vietnam. Yang seperti ini, misalnya, dialami Arn Chorn. * * * Arn Chorn punya mata luar biasa. Penuh cahaya, tetapi juga kesenduan. Biasanya mata seperti itu bebas berbinar-binar, seperti umumnya mata anak kecil. Tetapi mendadak mata itu bisa jadi gelap, tertutup aneka kenangan hitam. Ibunya, pemilik warung sayur di dekat lapangan terbang Kota Battambang di tepi barat Kamboja, hilang begitu saja. Ayah dan kedua belas saudaranya dibunuh - beberapa bahkan di depan matanya sendiri. Dia sendiri lalu diserahkan kepada pamannya, sebelum akhirnya diambil milisi Khmer Merah. Dua tahun pertama pemerintahan komunis itu Arn ditempatkan di Wat Ek, bekas pagoda yang dijadikan penampungan anak yatim. Di dekat tempat itu ada sebuah tempat yang disebut "Arena Pembantaian". Arn ingat betul apa yang terjadi di situ. Ia - juga anak-anak lain - dengan sengaja memang disuruh menonton. "Tiap hari Khmer Merah membawa banyak orang ke situ pada pukul 05.30. Mereka disuruh menggali liang kubur mereka sendiri," tutur Arn - kini 18 kepada Gail. "Pukul enam persis pembantaian dimulai. Kebanyakan pakai kapak yang dipukulkan di tengkuk. Suaranya seperti kelapa digebuk, tapi lebih keras. Kadang-kadang ada yang tak sampai mati. Yang ini juga langsung dikuburkan. Darah di manamana. Mereka bilang, mereka membunuh 15.000 orang di situ. Anak-anak tinggal dalam ketakutan di waktu siang, di waktu malam. Menjerit dalam kegelapan ketika mimpi buruk datang. Tak bisa tidur, meski kerja sangat berat." "Khmer Merah di distrik kami punya sebuah permainan," tutur Arn selanjutnya. "Dua orang saling melempar bayi sampai bayi itu jatuh. Mereka menyuruh anak-anak menyaksikannya. Tak bisa bicara, tak bisa berteriak. Cuma menonton. Pembunuhan seperti itu ada di depanku. Mataku melihat, tetapi pikiranku kosong. Aku tak merasakan apa pun. Yang lain mungkin juga begitu. Aku cuma berpikir, alangkah enaknya jika ada nasi. Kadang-kadang aku berpikir begini: jika kamu beri aku semangkuk besar nasi, kamu boleh bunuh aku." Suatu hari Arn mendapat tugas membantu memasak di sebuah pusat penampungan anak-anak salah satu tempat mempekerjakan dan mengawasi anak-anak di atas delapan tahun. Di situ ia dipaksa menyaksikan kejadian ini: Khmer Merah menyembelih dan membongkar tubuh manusia untuk mengambil ginjalnya. Buat apa? Buat digoreng dan disantap para pemimpin mereka - sebuah tradisi para pahlawan Kamboja untuk memperoleh kekuatan lawan. Tugas Arn yang lain adalah mengawasi anak-anak bekerja di ladang. "Kubayangkan, seandainya aku punya sedikit kekuatan, mungkin bisa kubantu mereka." Ketika anak-anak itu benar-benar datang kepadanya - karena sakit, tak kuat bekerja, mencari akar-akar pohon, tikus, ketam, kecoak, atau apa saja yang bisa dimakan - Arn mengaku merasa wajib melindungi mereka, meski ia tahu bahwa ia sendiri bisa dihukum, bahkan dibunuh, jika diketahui. Kemudian datanglah Vietnam. Arn 12 tahun waktu itu. Semua anak di atas 10 tahun dipersenjatai, tapi tak dilatih atau diberi petunjuk memakai senjata. Khmer Merah cuma bilang begini: "Jangan lari kalau lari, kamu mati." Ancaman orang-orang yang sudah kepepet itu tentu saja tak mempan. Arn lari ketika kesatuannya dipojokkan tentara Vietnam di sebuah hutan. Ia lari terus, sampai akhirnya ia merasa aman di bawah lindungan hutan tropis lebat di dekat perbatasan Muangthai. "Di hutan aku bebas," kata Arn, mengenangkan. "Kita bisa mempercayai binatang mereka tidak seperti manusia. Monyet-monyet mengelilingi aku, pengin bersahabat, membuat mimik-mimik lucu. Mereka selalu berkelompok satu keluarga. "Aku tinggal kulit, menderita sakit kepala dan demam karena malaria. Aku tak bisa memanjat pohon mencari makan. Kucari sekelompok keluarga monyet. Monyet-monyet itu selalu main lempar buah ketika makan. Kuambil yang terjatuh. Tiap kali aku tak punya makanan lain, aku terpaksa membunuh seekor kera. Sedih sekali. Berbulan-bulan ia mengelana dalam hutan seperti itu, sampai akhirnya alam terbuka tiba-tiba terbentang di hadapannya. Ia jadi takut. Ia tak ingin meninggalkan rasa aman dalam hutan. Tetapi rasa ingin berjumpa dengan manusia akhirnya mendorongnya keluar, menyeberangi sungai dan masuk wilayah Muangthai. Dan bertemu dengan Peter Pond. * * * Peter Pond lulusan Yale Divinity School tahun 196., - seorang yang tak pernah mau memimpin jemaah. Dia humanis tulen. Bertahun-tahun ia mengorganisasikan gerakan-gerakan perdamaian di Dunia Ketiga, dan selalu ingin menempatkan diri di tengah krisis. Maka, tak ada yang aneh kalau ia segera lari ke Muangthai ketika negara itu diserbu para pengungsi Kamboja dari Vietnam. Apalagi ia pernah tinggal di Muangthai sebelumnya. Ayah tirinya adalah duta besar Amerika pertama di Muangthai setelah PD II. Tiga puluh lima ribu orang saat itu, yang dijumpai sang pendeta, memenuhi pusat penampungan pengungsi PBB di Sakeo 1, Muangthai. Semuanya dimakan malaria dan kelaparan. Salah satunya adalah Arn Chorn, yang saat itu berupa sekumpulan tulang-tulang hidup berumur 14 tahun. Arn tergolek di tikar rumah sakit dengan malaria dan kaki penuh koreng. Rambutnya kaku bagai lidi. "Anak kecil itu menggapai dan menyentuh aku," kisah Peter mengenang. "Halo, sapaku waktu itu." Peter tinggal berbulan-bulan di tempat itu. Ia ikut membangun sebuah candi Budha, dan ikut menata kembali berbagai tradisi Kamboja buat 35.000 pengungsi yang tanpa jiwa itu. Juni tahun itu, Peter secara naif terlibat dalam rencana pemerintah Thai untuk memulangkan ribuan pengungsi. Pendeta kuil Budha di situ, Maha Ghosanando, marah dan menyatakan kuilnya sebuah tempat suci. Beribu-ribu orang berkumpul didalamnya dan menolak keluar. Tentara Thai jadi marah. Peter ditangkap, diasingkan selama seminggu. Meski begitu, usaha-usahanya cukup berhasil: hanya 7.500 pengungsi - kebanyakan terdiri dari para anggota Khmer Merah - yang dikembalikan ke negara mereka. Setelah dibebaskan, Peter minta izin PBB untuk mengadakan suatu program orangtua asuh di Amerika. PBB menolak: badan itu sedang berusaha mengadakan perjanjian repatriasi dengan Hanoi. Tapi tawaran justru datang dari Ratu Sirikit, yang mengundang Peter ke istananya. Sang ratu memperbolehkan Peter mengambil tiga anak - untuk menghapus kesan buruk penahanan Peter. Peter memilih anak-anak belasan tahun: Soneat, seorang anak nakal yang tak populer di penampungan Lakhana, seorang anak rapuh, berbakat jadi penyair, berwajah orang tua, dan senang menghabiskan waktu menghafalkan kamus bahasa Inggris serta Arn Chorn, anak dengan mata luar biasa. Dibawanya anak-anak itu pulang ke kampung halamannya di Amerika, Jefferson. * * * "Lihat apa yang kubawa untuk kamu!" Begitu Peter berkata setelah memasuki kantor kepala sekolah menengah White Mountains, Patrick W. Kelly. Tiga orang anak yang habis digosok bersih-bersih berdiri di sampingnya. Anak-anak itu tersenyum setengah malu tetapi hasrat mereka tampak meluap-luap. Mereka tahu sedikit sekali bahasa Inggris. Sekolah harus menyediakan pembimbing di dalam dan di luar kelas. "Gairah belajar mereka luar biasa," ujar Patrick tentang tiga anak itu - dan lima lainnya yang datang belakangan. Kenyataannya memang begitu. Anakanak itu umumnya berhasil masuk "Daftar Kehormatan" - Honorary List namanya. Tiga di antaranya bahkan di National Honour Society dan tiga lainnya diberi beasiswa ke New England Preparation School. Mereka juga contoh kelakuan baik. "Remaja Amerika sering melawan dan tak rasional, tetapi anak-anak ini benar-benar membawa masalah moral dalam diskusi-diskusi," kata Lorenzo P. Baker, direktur penerimaan Akademi Gould, Bethel, Maine. Di rumah, anak-anak itu punya pembantu yang setia dan cakap. Shirley Wilson, teman lama Peter dan calon Nyonya Pond yang kedua, tiap hari bangun pukul setengah lima pagi untuk membantu anak-anak ini belajar. Toh anak-anak itu tak selalu bisa menurut. Mereka masih sering tak mampu membedakan kritik dengan usaha merintangi kehendak mereka - sisa-sisa masa lampau. Itu misalnya terjadi pada Arn ketika ia mula-mula tiba. Tiap kali ayah angkatnya menyuruh dia membersihkan tempat tidur, dia akan membisu selama satu minggu. Bagi Arn, yang menghubungkan setiap perintah dengan kekuasaan kasar, bahkan permintaan sederhana bisa berarti "dia benci padaku". Untung, perlahan-lahan Arn mulai bisa mengerti. Kini dia bahkan sudah bisa berkata begini: "Barangkali semua anak Kamboja punya perasaan seperti itu pada awalnya." Lain lagi dengan Soneat. Ia sangat pintar di sekolah, tetapi rasa superioritasnya menyebabkannya kurang disenangi di rumah. Peter, untungnya memberi banyak pengertian - bahkan melihat sebagian dari dirinya di masa muda pada diri Soneat: penentang yang agresif, selalu berkeinginan mengontrol orang lain, untuk menutupi rasa kurang di dalam. Di sekolah semua anak itu istimewa. "Anak-anak Amerika tak melihat pendidikan sebagai semacam tiket," keluh Pak Kelly, kepala sekolah. "Mereka cuma mau menerima apa yang ada. Anak-anak ini lain. Mereka bangun pukul tiga fajar, menyelesaikan PR di bawah lampu tempat tidur." Perbandingan semacam itu sering mengusik perasaan anak-anak setempat. "Susah lho, berada di satu kelas dengan anak yang baru belajar Inggris tetapi nilainya lebih bagus," gerutu Peter Kecil, anak Peter Pond dari perkawinan pertama. Jenny, 12, anak Shirley yang sebenarnya antusias pada proyek orangtuanya, kadang-kadang juga kehabisan kesabaran. "Orang-orang ini sudah keterlaluan!" pekiknya. Shirley tahu, anak-anak ini di negara mereka harus egoistis supaya bisa selamat. Ia juga tahu rasa egoistis ini tak dengan segera bisa disesuaikan dengan lingkungan baru. Tapi baru setelah ia membaca puisi pertama Lakhana yang kuat tetapi gelap, ia tahu rasa kurang anak-anak ini. Dalam Mengapa Begitu Banyak Hal Buruk Terjadi padaku, Lakhana ternyata menumpahkan semua kesalahan dan semua trauma itu pada dirinya sendiri. Aku tahu aku manusia Cuma kadang kurasakan aku mirip binatang Yang membuat aku tak bisa dimengerti Kini semuanya jadi tak tertahankan Kadang kurasakan aku tak pernah belajar, tak pernah berpikir, tak pernah berubah Yang bikin orang lain beranggapan - bahwa aku tenggelam dalam kegelapan yang menyayat Ini melukaiku, melukai sangat dalam. Aku tak bisa katakan Tak bisa tunjukkan, tak bisa bicarakan Burukkah si cacat yang memakai tongkat, dan aku tak punya codet atau tanda yang lain Korbankah aku? Atau nasib? Barangkali cuma sebuah dosa. * * * Peter sendiri adalah anak yang sejak kecil asing dengan ayahnya. Sudah bertahun-tahun pula ia tak pernah melihat orang tua itu. Suatu saat, secara kebetulan, ia lewat di depan rumah sang ayah di Guilford, Connecticut. Ia merasa wajib mampir. Soneat bersama dia. Ia tak yakin bahwa ayahnya mau muncul melihat muka asing kecil ini. Tapi kejadiannya ternyata lain. Begitu melihat orang tua itu, Soneat langsung menyapa, "Halo", dan melingkarkan tangan ke pinggangnya. "Aku tak punya kakek maukah kau jadi kakekku?" Si tua hampir menangis. "Tentu", sahutnya segera. Itu benar-benar saat yang indah bagi Peter Pond. "Anak kecil dari kegelapan ini bisa berkata, 'cintailah aku', dan itu betul-betul terjadi." Namun, ketika segalanya mulai makin baik, Arn justru terlibat perkelahian dengan Soneat. Mula-mula mereka cuma saling ejek. Tetapi ejekan itu makin meningkat, dan tiba-tiba Soneat mengucapkan kata-kata yang langsung menusuk hati Arn: "Aku tahu siapa kamu - Khmer Merah!" Dengan kalap Arn meloncati meja dan memiting Soneat. Terkejut, yang lain berusaha memisahkan. "Kita bukan binatang buas!" pekik Shirley memegangi mereka berdua. Arn bangkit, melihat bajunya yang penuh darah, dan lari ke luar. Lari terus, 14 mil, tanpa sepatu, menuju Lancaster. Dalam benaknya ia kembali berada di hutan. Kata-kata Soneat meletup-letup di kepalanya. "Kamu Khmer Merah! Khmer Merah!" "Tidak! Tidak!" Teriak Arn sepanjang jalan di kegelapan malam New Hampshire. "Khmer Merah membunuh kakakku. Aku juga seperti mereka. Aku juga seperti mereka, aku juga ...." Setelah semalaman berkeliaran, Arn akhirnya tenang kembali dan menyerahkan diri pada mobil polisi yang sedang mencarinya. "Semuanya salahku, salahku," geremengnya sesampai di rumah. Kemudian ia menerangkan sebuah kejadian yang menjadi trauma bagi dia. "Setelah pendudukan Vietnam," katanya, "Khmer Merah memaksa kakak perempuanku memikul satu karung besar beras. Dia sakit keras, sangat lelah. Kami tak boleh bicara. Tapi dia selalu menggumam, 'Tunggulah, akan kita cari Ibu'. Suatu hari kakakku tak pulang. 'Di mana dia?' tanyaku pada seorang penjaga. Dia cuma mengangkat bahu. 'Mengapa kau tak tahu? Kau 'kan bersama dia!' Aku kalap. Hari berikutnya, kakakku yang sekarat dibawa ke luar hutan. "Dia mengenaliku, dia membuka matanya lebarlebar, tetapi tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Muka dan tubuhnya kotor, seperti habis diinjak-injak. Aku berdiri gemetar. Bedil di tanganku. Rasanya, aku pengin menembak siapa saja. Juga kakakku supaya dia tak menderita." Peter lalu menenangkannya. "Semua yang terjadi itu bukan salahmu, Arn," katanya. "Semua orang juga begitu seandainya dihadapkan pada pilihan bekerja atau mati." Pada pertemuan keluarga selanjutnya Peter lalu berpidato. "Kalian anak-anakku. Aku orangtua kedua kalian. Untuk selamanya." Setahun kemudian, seorang gadis Kamboja bergabung lagi dengan mereka. * * * Jintana Lee, gadis itu, punya paras ayu, tapi agak dingin. Barangkali tingkat sosial dan kekerasan hati membikinnya begitu. Ayahnya dulu seorang mayor jenderal yang merelakan tanahnya dijadikan tempat penampungan para petani yang lari dari desa. Kontrol diri Jintana begitu kuat - dia bisa mempertahankan ketenangannya, meski agamanya begitu dihinakan dan menyaksikan begitu banyak kekejaman. Tahun 1979 dia diselundupkan ke Muangthai dan dilindungi oleh bekas duta besar Muangthai untuk Kamboja, Chana Saudjavan. Dari situ nasib membawanya ke rumah keluarga Pond. Di keluarga barunya ini, Jintana, 17, tetap mempertahankan keangkuhan aristokratnya dengan selalu mengambil jarak. Dia sama sekali tak mau membicarakan pengalamannya. Sampai suatu saat, bersama keluarga barunya, ia menyaksikan sebuah demonstrasi antinuklir besar-besaran di New York - Juni 1982. Riuh-rendah suara orang yang berdemonstrasi, kerumunan begitu banyak orang, tiba-tiba membuat semua kejadian di Kamboja muncul kembali. Masa lampau berdengung di kepalanya. Phnom Penh-nya yang tercinta jatuh, dia digelandang dari kemewahan ke dalam kejorokan, hancurnya semua kehormatan yang dia miliki, ejekan-ejekan petani buta huruf yang dulu begitu direndahkannya - "Kamu itu debu! Kami jauh lebih mulia dari kamu!" Teriak mereka. Dia juga teringat ayahnya yang dikhianati Khmer Merah, yang diberi janji amnesti jika menyerah bersama anak buahnya, tetapi akhirnya dibunuh bersama ibunya. Siapa yang bisa dipercaya? Apa alasanku untuk tetap hidup? Sepanjang perjalanan pulang ia meratap dalam hati. Begitu sampai di rumah, pertahanannya jebol. Ditenggaknya sebotol pil tidur. Untunglah, Soneat, Lakhana, dan Arn melihatnya tak sadar di bawah pohon dekat rumah. Mereka segera menolongnya. Setelah kejadian itu, Jintana akhirnya mau menceritakan masa lampaunya. Dia bicara tentang kakaknya. Disuatu saat kakakku lari sambil memekik-mekik, 'Mereka membunuhi saudara-saudara kita! Mereka membunuh Ayah-lbu! Mengapa mereka tak membunuh aku sekalian?' Kusuruh dia diam, tetapi dia terus memekik-mekik, sampai terdengar Khmer Merah. Begitulah, akhirnya dia juga mati." Dia bicara tentang seorang anak 15 tahun yang menjadi penjaga desa dan ingin menunjukkan dirinya prajurit nomor satu. "Suatu hari dilihatnya ayahnya mencuri makanan. Dia segera mendatanginya dan berkata, "Kamu melanggar. Kamu harus mati." Aku saat itu menggembalakan sapi di dekatnya. Kulihat dia mengangkat senapan dan menembak. Malamnya aku tidur di samping sang ibu yang terus-menerus menangis." Di Amerika, suatu hari, Jintana bertemu dengan pembunuh ayahnya secara tak sengaja di jalan. Orang itu menegurnya dan bertanya, "Apa katamu tentang hal itu?" Jintana cuma memandangnya lebar-lebar, lalu pergi. * * * Sudah jelas kini, anak-anak itu memiliki begitu banyak keistimewaan yang tak dimiliki orang lain hal yang memungkinkan mereka tetap selamat sementara teman-teman dan saudara-saudara mereka pada mati. Mereka punya kekuatan menahan diri yang luar biasa. Mereka juga punya naluri survival yang tinggi. Mereka juga cerdas. Jintana kecil begitu tenang mendengar keluarganya dibantai. Arn mampu menonton dengan dingin bayi-bayi dijadikan permainan dan dibantai. Arn bahkan juga punya kelenturan jiwa yang hebat, meski yang lain juga memilikinya. Dengan tenang ia bisa menghadapi Jintana yang sengaja membangun tembok. Di hutan ia bisa menjadi anak monyet. Di Amerika ia mampu membuat dirinya dihargai teman-teman sekolah. Cuma kadang-kadang anak-anak itu memang masih bisa meledak. Natal tahun lalu, misalnya. Ketika suasana sedang meriah-meriahnya, pohon-pohon sudah disulut, hadiah-hadiah dibagikan dan orang-orang bersuka cita, Lakhana tiba-tiba ngambek. Masalahnya sepele: Shirley minta dia membantu mencuci piring di dapur. Lakhana memang lalu ke dapur, tetapi di sana ia bukannya mencuci melainkan membantingi gelas-gelas anggur Shirley. Shirley jadi ikut meledak. "Aku bosan begini terus! Kamu sangat susah disayangi!" Lakhana menjadi liar, menggigit jari Shirley, lalu lari ke atas. Peter segera mendatanginya dan duduk di sebelahnya. Lalu Arn menyusul. Lalu Soneat. Lalu semua anggota keluarga duduk melingkari Lakhana dan mengguncang-guncangkannya - sebuah tradisi Kamboja jika seorang anggota keluarga sedang susah. Lakhana berangsur-angsur tenang kembali. Dia lalu menceritakan pergalamannya seperti Arn dan Jintana, dia juga membiarkan saudaranya mati begitu saja. Setelah kejadian itu semuanya menjadi tenang kembali. Arn sudah lama tak pernah mimpi buruk lagi. Di Akademi Gould ia memang kadang-kadang masih mengalaminya - terkadang sampai terpekik dan jatuh dari tempat tidur. Untung, teman sekamarnya, Camm Groughton, penuh pengertian. Dia biasanya ikut bangun, memeluk, menenangkan, dan membaringkan Arn kembali. Mimpi Arn umumnya seperti ini. Dia sedang di ladang dengan senapannya. Di dekatnya sekelompok pasukan Khmer Merah sedang menyiksa seorang wanita tua. Di sebelah yang lain anak-anak sedang berloncat-loncatan di kubangan. Dia kepingin sekali ikut anak itu main-main, tetapi dia tahu bahwa dia akan ikut disiksa jika ia tak ikut menyiksa wanita tua itu. Dia bingung. Tetapi akhirnya ia membuang senjatanya dan ikut anak-anak bermain. "Saya belum orang baik," katanya. "Sampai saya siap mati untuk menolong wanita itu." * * * Begitu mobil yang membawa Arn pulang berlibur sampai di halaman rumah, Soneat menjerit gembira, lari ke luar dan menari-nari telanjang kaki melintasi salju. Diguncang-guncangkannya Arn. Tak ada lagi perkelahian di antara mereka. Cinta telah menggantikannya. Saat itu anggota keluarga mereka telah bertambah: Thorn, 19, Thy, 17, Rom, 17, dan Dara, 12. Thorn membawakan tas Arn ke dalam. Bau jahe tersebar di mana-mana. Jintana, dibantu Rom, sedang memasak. Tak lama kemudian sang ibu, Shirley, datang dengan segudang belanjaan. Untuk semua itu keluarga Pond menghabiskan lebih dari 100.000 dolar setahun - untuk belanja, uang sekolah, sumbangan-sumbangan. Gaji Peter sebagai konsultan Lutheran Services Association of New England, dan Shirley sebagai pensiunan direktur sebuah yayasan untuk kemelaratan, paling banyak 40.000 dolar. Untung, ada sumbangan dari pemerintah AS bagi yang masih berusia di bawah 18 tahun, dan beberapa mendapat beasiswa. Toh dari minggu ke minggu Shirley tetap harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan. Ketika makan malam tiba, Peter memulainya dengan sebuah doa. "Terima kasih, Tuhan, terima kasih buat istriku inilah saat terindah dalam hidupku. Aku berterima kasih untuk setiap anak yang Engkau berikan. Kami ingin cinta kami jadi nyata, bukan hanya kata-kata. Kekuatan cinta bisa membuat kehidupan baru untuk keluarga kami, untuk negara kami, untuk Kamboja." Suara angin terdengar dari sekeliling meja. Selesai makan, si kecil Dara mendemonstrasikan kepandaiannya bersiul dengan empat jari di mulut suaranya campuran antara suara kudus dan suara jalanan. Dara adalah anggota baru - baru tiga minggu. Datang ke Amerika dengan 12 pengungsi lain, ia ditampung seorang wanita Kamboja tua di Providence Rhode Island. Dara segera jadi anak bandel, dan oleh wanita itu kemudian diserahkan ke sebuah kuil Budha. Perjalanan selanjutnya membawanya ke rumah keluarga Pond. Malam itu pertemuan diisi dengan membahas cara mendidik Dara. Thorn sangat keras dalam hal ini. "Kamu tak boleh terlalu memperhatikannya, Papa. Kau harus membuatnya disiplin," katanya. Yang lain segera mengamini. "Jangan biarkan dia seenaknya duduk di pangkuanmu, dia bisa jadi manja." Peter tersenyum bijaksana. "Pernahkah kau dibelai ayahmu waktu kecil?" Tanyanya kepada Thorn. "Tidak", jawab anak itu. "Demikian juga aku," kata Peter, yang sejak orangtuanya bercerai dibesarkan oleh sederetan perawat. "Karena itu, kenapa kita tidak saling membelai selagi kita bisa?" Lalu mereka bergantian memegangi lengan Dara. Pukul setengah empat pagi hari berikutnya, anak-anak muda itu ke luar rumah. Yang laki-laki memakai baju putih dan dasi, yang gadis memakai sepatu bertumit tinggi. Tak seorang mengeluh, meski hawa sangat dingin. Peter berteriak dari kejauhan: "Oriental Exspress siap berangkat! Ada yang perlu bantuan?" Pemberangkatan sepagi itu tidak luar biasa. Peter biasa membawa mereka malam-malam menghadiri hearing Kongres, upacara-upacara Budha, dan acara-acara kebudayaan yang menarik. Kali ini mereka menuju Providence, menghadiri perayaan yang diadakan Perhimpunan Kerja Sama Bangsa Kamboja cabang Rhode Island. Ketika mereka sampai, gaung mantra-mantra doa, bau kemenyan yang dibakar, dan gambar elektronis Norodom Sihanouk di layar televisi memenuhi ruangan. Anak-anak itu melihat bekas raja mereka turun dari limusin di Daratan Cina. Di belakangnya menyusul bekas perdana menteri Son Sann, dan Khieu Samphan, tangan kanan Pol Pot. Kerajaan dan Khmer Merah telah berjabat tangan. Sihanouk bicara tentang usaha bersama untuk "menendang Vietnam ke luar Kamboja - dengan risiko apa pun." Sebuah usaha yang disokong Amerika dan Cina. Anak-anak itu sedikit bingung. "Sungguh membingungkan," keluh Rom. "Orang Cina membantai. Orang Cina juga mengganggu." Jintana lain lagi. Dia tak setuju dengan pendirian ayah angkatnya. "Dia bilang, tak apa-apa Khmer Merah kembali asal bersama Sihanouk. Omong kosong. Mereka tak pernah berubah. Mereka akan tetap membunuhi kita." Penolakan pengungsi-pengungsi Kamboja yang ingin memasuki AS juga persoalan yang sering mereka bicarakan. Peraturan bilang, orang-orang yang pernah menjadi anggota brigade kerja Khmer Merah dilarang masuk. Padahal, hampir semua orang yang tak menjadi tentara Khmer Merah atau jadi pegawainya pasti menjadi pekerja paksa. Menurut seorang pejabat Joint Voluntary Agency, sebuah kelompok nonpemerintah yang berpangkalan di kedutaan besar AS di Bangkok, "Keadaan benar-benar sudah gawat. Mereka menolak 10.000 pengungsi dan secara tak sadar menerima beberapa orang Khmer Merah sejati." Untung, kini tampaknya perbaikan mulai dipikirkan. State Department dan Kongres sedang berusaha membuat kriteria yang lebih jelas. Senator Mark O. Hatfield, ketua komisi Senat untuk masalah bantuan, juga telah memperkenalkan aturan-aturan pokok dana bantuan tahun fiskal 1985. Peraturan ini bisa digunakan oleh Kantor Imigrasi dan Naturalisasi untuk lebih tegas menentukan tindakan. Menurut peraturan ini, orang-orang Kamboja yang bukan anggota Khmer Merah - tentaranya, birokrasinya, atau politisinya - hanya bisa ditolak jika pernah terlibat perbuatan yang melanggar kemanusiaan. Anak-anak di bawah 18 tahun sewaktu Khmer Merah jatuh juga bebas dari segala peraturan, kecuali terbukti pernah melakukan tindakan yang melanggar kemanusiaan. Pada pesta dansa di perayaan itu, lebih dari 1.000 orang Kamboja dari New England hadir, untuk sesaat melebur isolasi mereka dalam suatu kebersamaan. Tak seorang anak pun memakai pakaian asli negaranya. Gadis-gadis kecil Asia itu berdansa dengan sepatu Nike mereka sambil memperhatikan pemudapemuda Pond. Dengan pakaian resmi mereka, anak-anak Pond itu memang tampak mencolok. Anak-anak lain yang umumnya tinggal di kota sudah melebur dengan gaya masa kini pemuda Amerika yang kumal. Mulut gadis-gadis itu baru ternganga ketika Arn mulai ikut mengayunkan pinggulnya di lantai dansa, mengikuti alunan suara Elvis Presley. Rom - anak ini dulunya calon pendeta - jadi pingin menangis. Keriaan dan kemeriahan semacam itu betul-betul berlebihan dan belum pernah dilihatnya. "Jangan takut," kata Peter menguatkan hatinya. "Sekarang kau bisa sedih karena kau sudah cukup aman untuk bisa dilukai lagi." Tak lama kemudian Rom sudah ikut menari-nari. Ketika semua anaknya sudah tidur, Peter dan Shirley menengok Dara. Diciumnya anak itu. Soneat, di tempat tidur sebelah, menggeliat. "Bagaimana dia?" tanya Peter. "Pasti berhasil," sahut Soneat mengantuk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini