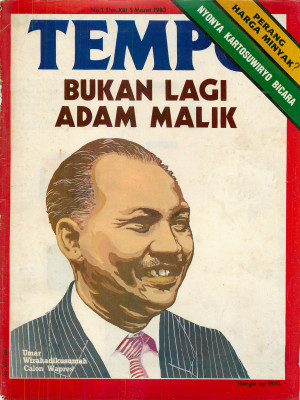KISAHNYA dimulai pada penghujung 1941. Dunia sedang berada
dalam. bayangan masa depan yang tidak pasti. Ancaman perang
Jepang sudah melintasi Indocina, dan menjatuhkan bayangannya
yang panjang ke kawasan Hindia Belanda. Protes Amerika Serikat
terhadap gerak maju itu bagai anjing menggonggongi kafilah.
Dan, seperti tidak habis-habisnya, berbagai kisah anak manusia
lalu muncul ke permukaan--setelah perang usai. Hal Drake,
penulis senior pada Pacific Stars and Stripes, mencoba
mengungkapkan salah satunya: pengalaman dua serdadu yang
sebelumnya telah berperang di pihak yang bermusuhan. "Dari
rangkaian penderitaan, kedua orang itu mendapatkan pelajaran
yang sama," katanya dalam sebuah tulisan di majalah PHP,
Desember kemarin.
Jacob DeShazer berusia 28 tahun pada akhir 1941. Waktu itu ia
baru saja mengalami nasib sial dalam mencoba beternak kalkun.
Tidak kurang dari US$1.000 uangnya terbenam habis dalam bisnis
keparat itu.
Dan Madras, kota kediamannya, bukanlah tempat yang terlalu
menarik. Apalagi untuk orang seusia DeShazer. Ini bukan Madras
di India, Lho. Terletak di Negara Bagian Oregon, kota Amerika
itu kecil saja hanya berpenduduk 300 orang. Jalan raya utamanya
lapang, dan lengang. Sekali-sekali melintas mobil Ford model A,
atau Packard dan Maxwell kuno. Bangunan-bangunannya lugu dan
agak bego, membuat orang teringat pada suasana kota perbatasan
zaman Buffalo Bill. Madras memang tidak banyak berubah sejak
pemukim pertama menginjakkan kakinya di sana.
Namun, kota itu sesungguhnya tidak terlalu jelek. Terselip di
sela gunung-gemunung, udaranya lumayan nyaman. Penduduknya bagai
terpulau, jarang berhubungan dengan orang luar. Dalam keadaan
seperti itu koran menjadi jendela yang amat penting untuk
meninjau dunia lain di seberang sana.
Dan DeShazer, tokoh kita ini termasuk anak muda yang paling
getol mencari bacaan. Kecuali koran lokal, ia juga rajin
berusaha mendapat media informasi dari kota yang agak besar, di
kawasan pegunungan itu juga. Nah, dari bacaan itulah ia suatu
hari mendapat kejutan. Konon, para balatentara dari Nazi Jerman
dan Kerajaan Jepun sedang maju malang melintang di luasan dunia.
Terpanggil untuk mempertahankan nusa dan bangsa, anak muda itu
mendaftarkan dirinya pada Korps Penerbangan Angkatan Darat. Ia
ingin menjadi pilot, dan seseorang yang kurang bertanggung jawab
dengan sembrono mengatakan kepadanya bahwa persyaratan yang
diperlukan sangat ringan adanya.
Belakangan baru ia sadar: usianya sudah melewati ketentuan. Ia
sudah hampir 30 tahun, terlalu tua untuk kadet penerbang.
Tetapi, alhamdulillah, Korps Penerbangan masih bisa memanfaatkan
DeShazer. Ia dimasukkan ke dalam kesatuan bomber.
Segera menerima latihan menembak dengan papan sasaran, tokoh
kita ini girang bukan buatan. "Sama seperti berburu kelinci di
Oregon Tengah," katanya. Ia pun segera memotong pendek
rambutnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.
Dibanding kehidupan Madras yang lengang, suasana barak dan gurau
serdadu tidaklah begitu jelek. DeShazer segera menemukan
temanteman baru.
Sekarang tokoh kita yang kedua: Mitsuo Fuchida. Untuk Fuchida
hidup boleh dikata teramat keras. Tamat dari Akademi Angkatan
Laut Eta Jima, 1924, ia memang mempersiapkan diri untuk suatu
kehidupan yang penuh disiplin. Di akademi tersebut ia sekelas
dengan Minoru Genda yang brilyan--dan kemudian termasyhur.
Mereka bahkan berteman.
Kedua-duanya mengikuti latihan 'Garuda Liar'. Kesatuan ini
memang tidak begitu dihargai para ahli strategi penganut garis
kuno. Sebab kelompok terakhir ini lebih suka mengandalkan kapal
perang, penjelajah, dan pertempuran dari kapal ke kapal.
Di awal 1941, Fuchida berusia 39 tahun. Ia sudah tampil sebagai
komandan yang utuh. Malah ialah opsir muda tempat
bertanya-bahkan bagi sebagian "perwira berjenggot putih". Dan ia
sadar, ia semakin berangkat tua.
Suatu hari, Fuchida diperintahkan berangkat ke lautan pedalaman
lepang. Di sana ia menemukan Genda sedang menunggu
kedatangannya. "Perang mungkin saja pecah setiap saat," kata
yang terakhir itu. "Bila saat itu datang, Anda akan menjadi
komandan sebuah satuan serbu udara."
Fuchida mengeraskan hatinya. Mungkin ini ujian tertinggi. Semua
godaan, kewajiban belajar keras, kehidupan spartan, dan
penyangkalan diri selama ini, akan menemui penggenapannya. Ia
sedang mempersiapkan diri mengangkat senjata melawan musuh-musuh
negerinya.
Dengan penuh kerahasiaan, latihan khusus dimulai.
Pesawat-pesawat terbang Angkatan Laut Jepang yang ringan itu
dipaksa terbang rendah seraya melepaskan torpedo, kadangkadang
hanya sekitar 12 meter di atas permukaan laut. Hanya setan yang
bisa menganggap pekerjaan ini main-main.
Langit putih cerah tatkala Fuchida naik ke pesawatnya, sebuah
bomber. Ia sudah memenuhi kewajibannya terakhir, menulis sepucuk
surat ke kampung halaman. Kepada ayahnya yang uzur ia bertutur:
"Saya yakin saya akan gugur. Tetapi kematian ini agung dan penuh
hati." Ayahnya mengangguk-angguk, tentunya. Maklum Jepang.
Dan pesawat Fuchidalah yang pertama-tama tiba di atas kapal
induk Akagi. Di belakangnya segera menyusul pesawat lain. Dari
sana seluruh informasi bergerak menuju sasaran .
Mereka terbang pada ketinggian 3.000 m, di atas sebaris awan
tipis berarak. Tiba-tiba awan terkuak, dan garis pantai tampak
di bawah sana. Mendadak, dan sangat mengesankan muncullah Pearl
Harbor nun di depan, luas dan lengang. Tidak sebuah isyarat
kehidupan tampak di bawah. Serangan yang bersejarah itu memang
betul-betul kejutan total.
Di tempat duduk pesawatnya, di antara pilot dan navigator,
Fuchida menggapai mikrofon. Ia mulai mendesiskan kata-kata sandi
yang kelak merupakan isyarat bagi sukses impian Genda. Inilah
kata yang kemudian mengangkat nama tokoh tersebut ke latar
sejarah: "Tora, tora, tora."
Dan di geladak Akagi dan kapal perang lainnya, suka cita pecah
tiada terkira. Dalam satuan serbu yang sedang mengamuk di atas
kapal-kapal perang Amerika itu, hanya kegarangan yang mewarnai
angkasa.
Fuchida berputar sejenak bersama satuan pengebomnya, menyaksikan
tiang asap raksasa menyembur dari kapal-kapal perang yang sedang
terbakar jauh di bawah. Ia tampak lesu. Tali temali yang
merangkai sejumlah bom itu sudah bergantungan lepas.
Ia tidak akan melupakan akhir riwayat kapal perang Arizona yang
dibomnya. Kapal itu lenyap dalam sebuah sapuan cahaya, berubah
menjadi gumpalan asap raksasa. Ia memperhatikan dengan seksama
bagaimdna kapal-kapal yang lain berangkat ke dasar laut. Mereka
hanya bisa dikenali dari nyala api dan asap.
Sementara Fuchida menengok ke bawah, pesawatnya
terumbang-ambing, bagai dihantam tinju raksasa. Ia melihat ke
belakang: sebuah pesawat lainnya berpusing dan berubah bentuk
menjadi keping-kepingan.
Pesawat Fuchida sendiri mulai menggeletar. Dan ia dirasuk
kecemasan akan hal yang lebih buruk. Awak yang duduk di
belakangnya meraih sesuatu di bawah kursi Fuchida, ternyata
kawat kemudi yang putus. Awak tersebut berusaha memegangi kawat
yang putus itu. Dan meriam-meriam anti-serangan udara mulai
menggonggong dari Pearl Harbor.
Dengan komando Fuchida, satuan penyerang itu bergerak
meninggalkan pelabuhan yang berantakan itu. Dari 353 pesawat
terbang yang berangkat, 29 tertembak jatuh - harga yang sangat
murah untuk pembinasaan yang demikian dahsyat .
Beberapa minggu sebelum serangan Pearl Harbor tersebut, Jake
DeShazer berangkat ke Columbia, Carolina Selatan, untuk
mengikuti latihan lanjutan. Hari Minggu itu ia berada dalam
posisi tak sedap: dapat hukuman mengupas kentang di dapur.
Dan, ketika sebuah berita singkat terdengar di radio, DeShazer
bagai disengat tawon. Ia membanting sebiji kentang yang belum
selesai dikupas ke dalam periuk. "Hai, Jepang!" katanya
berteriak. "Tunggulah pembalasan kami!" Berita radio itu
menyebutkan penyerbuan Pearl Harbor.
Toh sampai beberapa minggu kemudian tidak ada yang bisa
dilakukan. Paling-paling DeShazer dan rekan-rekannya hanya
menyimak dan menyimak dan menyimak berita perang melalui koran
dan buletin, dengan dahi makin mengerut. Anak muda itu makin
berang dan senewen ketika Wake dan Guam pun ikut jatuh.
Suasana barak yang tidak berubah membuatnya penasaran. Ia ingin
bergerak - ke mana pun jadi. Ia ingin melakukan sesuatu, bukan
sekadar terbengong-bengong. Dan demikianlah pada suatu pagi,
awal Februari 1942, seseorang menyampaikan: "Anda diperintahkan
menghadap Komandan."
"Bah," pikir DeShazer. Palingpaling kebagian omelan, atau
keputusan perpanjangan masa hukuman di dapur. Ia berangkat
ogah-ogahan.
Tapi di kantor yang rapi itu sudah ada sekitar 15 atau 20
rekannya. Kapten hari itu tampaknya agak santai, tidak
kekantor-kantoran. Ia seperti mengajak hadirin mengendurkan
saraf, bermanis-manis, dan - kemudian - secara mendadak
mengatakan: "Saya memerlukan beberapa sukarelawan untuk sebuah
misi yang berbahaya."
Semuanya terdiam. Dan segera waspada. "Well,"seorang prajurit
terdengar menggagap, "misi macam apa itu?" dan sang kapten
ternyata tidak bisa menceritakan apa-apa kepada mereka. Ia hanya
bisa mengulangi: "Tugas itu penuh risiko dan berbahaya. Dan saya
membutuhkan tenaga sukarelawan."
Untuk DeShazer, justru tugas macam begini yang dinanti-nantikan.
la sudah jenuh dengan kegiatan rutin yang sontoloyo. Ia maju ke
depan dan mengacungkan tangan. Dan yang lain segera mengikut.
Mereka kemudian diperintahkan pulang ke tempat masing-masing.
Semuanya merasa barlgga, karena akan mengemban tugas yang sangat
rahasia, meski mereka sendiri belum tahu benar apa.
Tapi dalam beberapa hari mereka sudah berada di Englin Field,
Florida, dan latihan pun dimulai. Di sana ada lapangan terbang
yang tampaknya sama lebar dan sama panjang dengan jalan utama di
kota kecil Madras. Bedanya, di lapangan ini ada sebuah sudut
kecil yang ditandai dengan kapur.
Para penerbang diharuskan melakukan beberapa olah gerak pesawat
di sudut yang kecil ini. Pekejaan yang sungguh berbahaya, dan
penuh tantangan. Namun DeShazer tidak khawatir. Ia dan awaknya
dipersatukan oleh keterampilan dan kepercayaan yang besar.
Teknik lepas landas yang unik itu akhirnya berhasil dikuasai.
Lalu datanglah perintah yang membingungkan. Mereka harus
berangkat ke Pantai Barar--San Francisco.
Pesawat-pesawat bomber dinaikkan ke kapal induk Hornet. Kemudian
mereka semua dikumpulkamn. Lalu, tanpa basa-basi, mereka
diberitahu: "Kita akan mengebom Tokyo, Yokohama, Kobe, Osaka
Nagoya ...."
Sebagai sebuah aksi militer, langkah itu bisa dinilai
'manusiawi'. Enam belas pesawat bomber bermotor dua akan
mengamuk secara 'hati-hati', khusus memilih sasaran militerdan
industri.
Sasaran sesungguhnya adalah moral dan psikologi kedua rakyat:
Amerika dan Jepang. Amerika memerlukan headline yang semarak
tidak sekadar berita kekalahan dari hari ke hari. Dan orang
Jepun itu patut diberi pelajaran. Selama ini mereka yakin garis
pantai mereka tidak bisa ditembus musuh.
Dan ternyata pertempuran kali itu jauh lebih dahsyat dari yang
pernah dibayangkan DeShazer. Ada rasa cemas menyelinap dalam
kalbunya. Entah mengapa, tiba-tiba saja ia teringat pelajaran
agama di sekolah dulu.
"Saya mulai berpikir, hanya berapa hari lagi saya boleh hidup di
dunia ini," katanya dalam sebuah tulisan. "Saya khawatir: ke
mana saya akan pergi setelah mati ?"
Kekhawatiran memang beralasan. Operasi itu direncanakan berjalan
sampai pada menit dan tetes bahan bakar terakhir. Bagaimana
memasuki daerah musuh, menyapu sasaran, kemudian memilih jalan
terpendek ke Laut Jepang, dan kabur ke daerah Cina yang aman
untuk para prajurit Amerika.
Dan di geladak Hornet, kawanan pesawat pengebom itu-tampak bagai
kipas terkembang ketika berpencaran ke pelbagai sasaran. Hanya
DeShazer yang menuju Nagoya, kota pusat industri yang riuh,
dengan penduduk lebih 1,3 juta.
Kesan pertama DeShazer menxenai Jepang dalang dari
lukisan-lukisan kuno negeri itu: gunung-gunung yang hijau,
ditudingi awan dan dicadari kabut tipis. Dan kini ia menyaksikan
tamasya itu dari ketinggian. Di bawah terbentang pemandangan
yang sejuk, halaman dengan pagar tanaman yang tampak, hutan
tipis dan lebat. Tiba-tiba tampak Nagoya.
Kota itu kelihatan cokelat dan kelabu. DeShazer meriksa
sasarannya yang pertama, Perusahaan Gas Toho. Pabrik ini penuh
tangki ang mungkin berisi propane, gas CH8 yang gampang
terbakar.
DeShazer menjatuhkan sebiji bom. Dan itu rasanya lebih dari
cukup. Api marak dan asap mengepul DeShazer membawa pesawatnya
menyingkir dari pemandangan berantakan itu.
Ia bergerak menuju sasaran berikutnya. Kelak ternyata mereka
keliru menyangka sasaran ini kompleks pabrik. DeShazer kembali
menjatuhkan bom. Dan dari bawah terdengar sayup suara rentetan
meriam penangkis udara. Tetapi tidak berbahaya. Dan DeShazer
mulai merasakan semacam kebuasan merasuk dirinya.
Ia mulai menggila. Ia meraih senapan mesin dan menyapu penumpang
sebuah kereta api yang dipergokinya. Ia bahkan menyikat seorang
lelaki yang sedang berperahu .
Mengapa? "Kemarahan saya bangkit ketika mengingat berita yang
pernah saya baca di koran," katanya. "Saya dengar para penerbang
Nazi Jerman menembaki penduduk sipil Prancis."
Tapi jalan menuju daratan Cina ternyata makan waktu berjam-jam.
Sampai merah mata mencari, tidak tampak lapangan terbang
bersahabat yang mungkin mereka darati. Lalu terjadilah apa yang
selama ini sangat dicemaskan: angka penunjuk bahan bakar
mendekati garis nol. Nah.
Dari pesawat interkom terdengar perintah: "Kita harus terjun."
Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka meloncat ke tengah
kegelapan, dan payung mulai terbuka. Dan, mereka ternyata
mendarat di daerah Cina yang dikuasai Jepang.
Untuk waktu yang lama, Fuchida akan senantiasa terkenang
audiensinya dengan Kaisar Hirohito, dan pertemuannya kembali
dengan ayahnya yang gembira bukan kepalang. Ketika satuan tempur
itu bergerak kembali, mereka mencatat sejumlah kemenangan
gemilang. Mereka menenggelamkan kapal pengangkut Inggris Hermes
di sekitar Srilangka. Pekerjaan itu sama mudahnya dengan merebut
Singapura, Hongkong, dan Indonesia.
Kemenangan itu hanya dicacatkan satu hal: serangan udara Amerika
ke daratan Jepang. Presiden Franklin D. Roosevelt mengatakan
ketika itu, para penerbangnya berangkat dari suatu tempat
bernama Shangrila. Keterangan ini sempat membuat Fuchida
membongkar peta setengah mati. Di mana Shangrila? Belakangan ia
tahu, Shangrila hanyalah nama kerajaan mistik dalam novel James
Hilton, LostHorizon.
Di suatu tempat di Negeri Cina, para pemeriksa sia-sia memaksa
DeShazer bicara. Tidak sebutir pengakuan keluar dari mulut
prajurit yang bengal alias tangguh itu. Hakim lalu mengatakan,
besok pagi ia bakal dipancung.
Ia dilemparkan kembali ke dalam selnya yang pengap. Tangan
tergari, mata ditutup. Sepanjang malam ia menggeletuk oleh udara
dingin yang nyaris tidak tertangguhkan.
Ketika secercah kehangatan terasa meraba tubuhnya, tahulah ia
bahwa fajar mulai merekah. Ia merasa tubuhnya dipaksa berdiri,
kemudian disorongkan ke luar sel. Ada terlintas dalam pikirannya
niatan untuk berdoa. Kam penutup matanya tiba-tiba ditanggalkan.
Pemeriksa yang kemarin tidak kelihatan. Tetapi ada beberapa
orang, satu di antaranya menyandang kamera. Semuanya tampak
mengumbar senyum.
Kemudian ia, pilotnya, dan awak lain yang turut tertangkap,
dinaikkan ke pesawat udara dan diterbangkan ke Jepang. Mereka
berpikir, di sana pasti sudah menunggu mahkamah militer
bohong-bohong - sekadar jalan untuk menghukum mati mereka
sebagai penjahat perang.
Untuk Fuchida, serangan udara dari pihaknya itu dinilai lebih
bersifat lihai ketimbang jahat. Ia ingin Fiji dan Samoa direbut,
untuk memutuskan mata rantai yang tipis antara Amerika clan
Australia. Tetapi Laksamana Isoroku Yamamoto, staf Markas Besar
Angkatan Laut Kerajaan Jepun, memilih Midway. Beliau percaya
tindakan ini merupakan tekanan terhadap Hawaii, dan mencegah
Amerika melancarkan serangan udara baru.
Itulah pertempuran Fuchida yang terakhir. Diangkat sebagai
komandan satuan serbu udara yang bertugas menamatkan armada
Amerika Serikat, dan menghancurkan pertahanan Midway, ia dengan
penuh rasa tanggung jawab naik ke kapal Akagi. Tetapi, oh
sayang, enam hari sebelum melancarkan serangan ia ambruk
diserang penyakit usus buntu. Tepat pada saat itu terdengar
teriakan-teriakan panik: "Kyukoka!"Musuh ternyata lebih dulu
mengirimkan pesawat-pesawat mautnya.
Akagi berantakan oleh ledakan yang tidak kepalang tanggung.
Fuchida tercampak ke laut kedua tumitnya remuk. Ia kemudian
dipungut sebuah kapal perusak Jepang.
Banyak penerbangnya yang tertembak jatuh. Ada juga yang pulang
kembali untuk menemukan puing dan asap, yang menandai tempat
Akagi terbakar. Mereka tidak bisa berbuat lain kecuali
menyingkir ke tempat yang agak jauh dari api, kemudian
mencemplungkan pesawat-pesawat yang kehabisan bahan bakar itu ke
laut, lalu menunggu 'jemputan'. Tiga kapal pengangkut lainnya
lenyap menjadi abu. Dalam beberapa menit yang mengerikan,
perimbangan kekuatan Perang Pasifik mengalami perubahan drastis.
Para dokter mengatakan kepada Fuchida: ia tidak boleh terbang
lagi. Tiba-tiba ia merasa tua. Ia mulai menjadi pemarah, muak
akan tugas staf yang kini harus diterimanya. Ia kemudian
dipindahkan ke Tinian di Kepulauan Mariana.
Tetapi tak lama kemudian ia diperintahkan pulang ke Tokyo.
Tempatnya digantikan seorang bekas temannya di Akademi dulu.
Dan peristiwa itu seperti tangan gaib yang sengaja bertindak
untuk menyelamatkan jiwanya: dua minggu lagi Tinian akan menjadi
neraka. Pada saat-saat terakhir, bertahan sampai mati di pulau
tersebut, seluruh prajurit staf, termasuk sahabat Tinian itu,
berkumpul dan berlutut. Mereka membuka jas militer masing-masing
dengan khidmat, kemudian membelah lambung mereka dengan kelewang
masing-masing. Fuchida mulai berpikir: "Apa makna 'penyelamatan'
ini, sebenarnya?"
Dalam pada itu DeShazer sedang terus-menerus menimbun dendam.
Hatinya sangat sakit ketika Jepang-Jepang itu memaksanya
berlutut. Tulang keringnya ditekan dengan papan yang kasar dan
tajam. Setiap ia menggeliat, kepalanya dihajar dengan sebatang
bambu.
Kalau dendam sudah sampai puncaknya, ia mencoba berharap. Tetapi
harapan nyaris mustahil di penjara militer lepang, dengan segala
suasana yang menekan itu. DeShazer mencoba berharap untuk
terakhir kalinya dengan iman yang masih tersisa. Tiba-tiba ia
terpukau: apakah sesungguhnya makna iman, hidup, harapan ?
DeShazer mendengar, pilotnya bersama dua awak lain sudah
dikembalikan ke Cina dan mengalami nasib buruk: ditambatkan pada
sebatang salib, di sebuah pemakaman di Shanghai, kemudian
diberondong habis.
DeShazer sendiri dan sisa pasukannya "hanya"di jatuhi hukuman
seumur hidup. Malah setelah seorang terhukum kedapatan mati
karena kurang makan, sikap para penguasa Jepang berubah lunak.
Suatu hari seorang pengawal datang menawarkan buku ke seantero
sel. Mereka boleh membaca. Buku-buku itu ternyata Bibel dan
beberapa karya teologi--mungkin hasil jarahan di suatu
perpustakaan misi. Jepang-jepang itu sendiri tidak makan Bibel.
Juli 1945 Okinawa jatuh. Dan Fuchida merasa tidak lama lagi
keadaan akan berubah. Jepang tengah bersiap-siap melakukan
pertempuran terakhir. Kali ini di kandang sendiri.
Pada 5 Agustus, setelah sidang yang sangat gencar, Fuchida
ditugasi ke Nara untuk memeriksa pembangunan sebuah markas besar
baru, yang berjalan lamban. Pada suatu sarapan pagi di sana, ia
diberitahu bahwa Hiroshima telah diratakan dengan tanah oleh
"sebuah ledakan yang ajaib dan bertenaga dahsyat."
Laporan pun mulai berdatangan dari kota yang kini sudah berubah
menjadi belantara maut itu. Fuchida mendengar keterangan tentang
GroundZero, pusat ledakan. Balai Promosi Industri yang dibangun
pada 1914, dan berada pada titik itu, lenyap sama sekali,
berubah menjadi hanya segumpal wujud yang membingungkan. Jepang
bertekuk lutut.
Setelah segalanya usai, Fuchida kembali ke kampung halamannya.
Dan mencoba bertani. Ia sering tampak di jalanan: seorang opsir
yang sakit hati, dan kehilangan kepercayaan. Seseorang yang
dipatahkan oleh kekalahan.
"Inilah hari-hari mendung dalam hidup saya," katanya. "Semuanya
kehilangan makna dan warna, kecuali kenyataan bahwa saya tetap
bernapas. Berkali-kali saya selamat dari maut, tetapi untuk
apa?"
Selama beberapa waktu, sebagai bekas opsir Angkatan Laut
Kerajaan yang terlibat dalam Perang Pasifik, Fucnida dituntut
sebagai penjahat perang. Ia memang kemudian berhasil melalui
rangkaian pengusutan dengan selamat, tetapi tetap harus muncul
berkali-kali di pengadilan sebagai saksi.
Dalam suatu kesempatan seperti itulah, ketika Fuchida
diperintahkan menghadap Markas Besar Tentara Pendudukan AS untuk
memberi kesaksian, ia naik kereta api di stasiun Shibuya, Tokyo.
Di depan stasiun itu adaseorangAmerika, I-imothy Pietsch, yang
mengelola Pusat Alkitab Tokyo. Orang ini bukan serdadu, dar
tidak punya sikap pemenang terhadap bangsa yang baru kalah itu.
Ia tersenyum kepada Fuchida, mengangguk ramah, seraya
mengulurkan sesuatu.
Ternyata sebuah risalah keagamaan, dalam bahasa Jepang. Fuchida
melihat potret pengarangnya yang terpampang di kulit depan. Dan
membaca namanya: Jacob DeShazer. Orang inilah yang turut membuat
Fuchida dulu membongkar peta untuk mencari Shangrila!
DeShazer, menurut risalah itu, mengalami siksaan berat, dijatuhi
hukuman mati, dan diterungku dalam kondisi yang sangat buruk.
Terbenam dalam bacaan Bibel di penjara, ia berjanji pada diri
sendiri untuk memaafkan musuh-musuhnya. Dan setelah perang, ia
kembali ke Jepang sebagai misionaris. Misionaris Kristen,
memang.
Fuchida mula-mula hanya sekadar kagum. Kemudian seperti
diingatkan. DeShazer ini telah mengalami peristiwa yang sangat
dahsyat, toh ia berbicara tentang kasih. Fuchida membaca risalah
itu lebih khusuk.
"Maka demikianlah yang terjadi," kata Hal Drake menutup
tulisannya. DeShazer akhirnya menjadi pendeta, di sebuah gereja
sederhana di kota kecil, sekitar 20 mil di barat laut Tokyo.
Tidak kurang dari 26 tahun ia mengabdi di sana. Kemudian pulang
ke kampung halamannya di pedalaman Oregon.
Fuchida sendiri ditahbiskan menjadi pendeta Presbyterian, dan
mengabdikan sisa hidupnya bagi karya penginjilan. Ia meninggal
1976.
Betulkah, kata orang, jalan hidup kita sudah ditetapkan dari
sononya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini