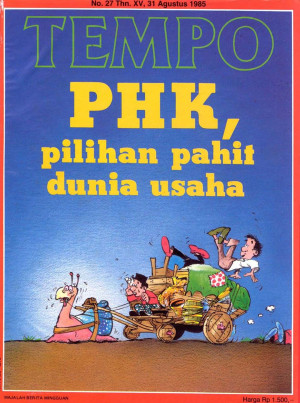SEKITAR 1.000 laki-laki, bertelanjang dada, menghambur dari arah alun-alun, sambil bertempik sorak. Mereka menyibakkan jubelan penonton, menembus lapisan orang yang sudah merubung sejak pagi. Mereka memasuki lapangan di sebelah kanan Puri Agung Gianyar. Mereka begerak seperti sebuah stampede kecil, sebelum berhenti tiba-tiba. Hari terang, terik. Pukul 11 siang lebih. Tapi keseribu laki-laki Bali itu, dengan antusias dan tangkas, mendatangi dua usungan besar yang tersedia di lapangan sehari sebelumnya. Beberapa orang meloncat naik, memberi komando. Dengan ikat kepala putih yang melingkari rambut, dengan kain bercorak papan catur yang disangkutkan seperti cawat yang longgar, mereka mulai bekerja. Meskipun, dalam kenyataannya, usungan belum beranjak dari sana. Beberapa orang hanya tegak di sekitar empat patung kertas warna-warni yang diletakkan di empat pojok usungan besar itu - patung empat kera termasyhur dari kisah Ramayana. Beberapa lagi naik ke bagian lebih tinggi, ke menara usungan. Yang mayoritas mengambil tempat di bawah, di sanan, bagian dasar konstruksi bambu dan kayu itu, di antara sejumlah buluh besar yang disilang-silangkan. Orang-orang itu, bagaikan massa yang bersemangat dalam sebuah pawai raksasa, pada hakikatnya menyatakan bahwa mereka telah siap. Mereka siap mengangkat bade. Orang Bali menyebut bangunan besar yang portabel itu bade, atau, dalam bentuk yang lebih sederhana, wadah. Di situlah terletak, dan menjulang setinggi enam meter, sebuah menara dari kayu ringan, dari bambu, cermin-cermin, dan kertas kuning Cina yang keemasan. Seperti tampak di hari itu, tumpang, pucuk menara itu, bertingkat sembilan. Ujung tertingginya berkilau: di sana terpasang emas tipis berbentuk kembang - atau sejenis lambang. Dan ribuan pasang mata menyaksi kan. Suasana memang riuh, mungkin galau. Bau dupa, kembang, parfum bercampur bau keringat, dan asap rokok. Toh tiap orang tahu apa yang dituju. Sebab, 3 Agustus 1985 itu adalah hari puncak upacara pembakaran jenazah Anak Agung Niang Putu, setelah tiga hari sebelumnya, dari siang sampai malam, pelbagai acara ditempuh. Dan seperti hampir tiap orang dewasa di Gianyar tahu, itulah upacara palebon yang termeriah di Bali yang pernah ada selama 10 tahun terakhir ini. Meskipun tak disiarkan secara luas. Menara dengan tumpang sembilan susun itu memang segera menunjukkan martabat orang yang wafat: itu jenis tumpang kedua tertinggi setelah tumpang yang khusus di buat untuk seorang raja yang pernah berkuasa, yakni 11 tingkat. Dan tak cuma itu. Hari itu tampak pula orang menyiapkan bale Nagabanda, sebuah kendaraan, khusus bagi seekor naga besar. Naga mitologis ini tentu saja hanya patung - adalah sebuah kepala besar yang bermahkota meriah, dengan ekor kira-kira 30 meter. Ekor itu berjela bagaikan tali tambang yang hitam, yang bila diangkat harus dipegang terlipat oleh beberapa belas orang. Konon, itulah pertanda bahwa jenazah, yang dilingkarinya sejak kemarin dulu di ruang persemayaman, adalah jenazah seorang aristokrat, yang akan dibakar dengan upacara lengkap. Yang akan diperabukan memang bukan orang kebanyakan. Semasa hidupnya, jenazah itu adalah salah satu istri Sri Paduka Ide Anak Agung Ngurah Agung, raja yang telah mangkat hampir seperempat abad yang lalu, bekas yang dipertuan dari Puri Gianyar. Dan dalam banyak hal, Puri Gianyar tetap puri yang terpandang di Bali. Di satu bagian, tinggal keluarga Anak Agung Gde Agung, bekas menteri luar negeri dan diplomat terkemuka Indonesia, yang kini sedang berada di Negeri Belanda mempersiapkan sebuah buku. Di bagian lain, tinggal saudaranya seayah, tapi bukan seibu: Anak Agung Gde Oka, pensiunan kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring. Dialah orang yang punya kerja hari itu: yang akan diperabukan adalah jenazah ibundanya - dan Anak Agung Gde Oka adalah anak tunggal. Puri yang terbagi dua itu juga - yang luasnya tak lagi diketahui persis - masih tetap terawat, meskipun umurnya telah lebih dari 100 tahun. Di dalamnya, kehidupan keluarga masih berjalan dan berfungsi. Setidaknya di bagian tempat Anak Agung Gde Oka, yang disebut Puri Anyar. Itu berarti, tidak seperti halnya beberapa puri lain di Bali, Puri Gianyar tak berubah jadi hotel. Atau jadi sekadar tontonan turis. Bahkan di hari itu, selama upacara yang spektakuler itu, para turis tak banyak dapat kesempatan mendekat. Seorang petugas berkain dan berdestar dan berbaju safari beige menyuruh para pelancong dari negeri jauh itu menyingkir dari tempat tertentu suaranya keras tapi kalimatnya sopan, dengan pengeras suara di tangan. Palebon memang suatu kemeriahan, tapi bukan sekadar tontonan. Ini sebuah cara bagi arwah ke surga. Ada saat-saat khidmat di antara suasana pesta yang penuh hidangan dan baju warna-warni. Ada banyak doa dipanjatkan waktu muspa bersama. Lontar-lontar kuno dibaca, dengan suara mengalun di dekat tubuh yang mati, sementara, di sebuah gubuk di sudut, gambang kematian, yang bersahaja dan ditabuh empat orang tua, tak putus-putusnya berbunyi - sayu dan misterius. Anak Agung Niang Putu wafat dalam usia 89. Kematiannya tepat terjadi pada hari Purnama, 3 Juni yang lalu. Hari itu kebetulan pula Waicak, dan bagi orang Bali, keyakinan Budha adalah sebuah versi lain dari Hindu: tak heran bila upacara pelabon-nya berlangsung dalam ukuran besar. Kekhususan lain kali ini ialah bahwa segalanya dilakukan dengan persiapan yang cepat: praktis cuma sebulan. Konon, tak begitu mudah melangsungkan ngaben yang diduga menelan ongkos sekitar Rp 30 juta itu, dengan jarak waktu yang begitu pendek untuk menata. Setidaknya bagi pelbagai keluarga bangsawan Bali di zaman ini - yang tak lagi berkuasa dan tak jarang jatuh miskin. Maka, yang dilakukan Anak Agung Gde Oka, dalam usia 60-an, dan dengan jantung yang tak sehat, boleh dibilang suatu prestasi yang mengesankan. Seorang sopir dari Ubud - yang tak memandang tinggi orang Gianyar - berkata bahwa semua itu bisa terjadi berkat hubungan-hubungan Anak Agung Gde Oka sendiri. "Beliau itu disukai rakyat, tidak sombong dan suka membantu," katanya. Ngaben memang suatu proses bantu-membantu. Bagi sebuah puri di abad ke-20, itu juga bisa mencerminkan sebaik mana kontaknya dengan masyarakat orang kecil di sekitar. Dalam upacara besar kali ini di Gianyar, misalnya, tercatat 13 banjar dari dua desa adat ikut terlibat menyumbangkan kerja, bahkan beras dan kue-kue. Seorang Bali menunjukkan pertanda kerja sama yang baik dalam wujud lain: dalam usungan besar itu, bade. Lihatlah bade itu. Tempat penyunggi menara yang dasarnya dibuat dari bambu panjang yang disilang-silangkan itu - dan disebut sanan - bisa menjadi sebuah cara untuk mencelakakan. Usungan itu harus dipanggul ratusan lelaki. Sebagian berada di tepi-tepi dan sebagian lain terkungkung di tengah. Semuanya harus bergerak serentak. "Kalau tidak kompak, kalau ada yang nakal saja kepada yang lain, pasti orang yang di tengah akan mati terjepit," kata seorang petugas upacara. Dan hari itu, semua orang tampaknya kompak. Keluarga, tamu dan masyarakat ramai, mungkin rakyat dari 13 banjar di dua desa adat yang menyumbangkan tenaga itu, hadir, tertib. Di sudut kanan puri, di sebuah gardu agak di ketinggian, Anak Agung Gde Oka - dengan safari biru gelap dan destar yang dihiasi kembang merah yang baru dipetik - menyaksikan. Ia bersama tamunya, gubernur Bali Prof. Ida Bagus Mantra. Di lapangan di bawah sana, upacara berlangsung persis seperti dalam jadwal. Upacara itu, tak ayal lagi, adalah sebuah festival dengan banyak rol. Turis-turis, kebanyakan orang putih dengan T-shirt dan kulit terbuka, sibuk dan berdesakan. Sehabis jamuan makan siang, tamu-tamu berjalan hilir mudik, mencari tempat terbaik untuk menonton. Gamelan bertalu-talu. Dan pada pukul 12.30, jenazah pun diusung dari ruang persemayaman. Dilindungi sebuah payung, iringannya pelan-pelan menaiki sebuah tangga bambu, yang mendaki tinggi sepanjang 15 meter - mirip tangga pesawat terbang sebelum boarding. Tangga itu memang dibangun khusus beberapa hari sebelumnya, untuk menaikkan jenazah. Kakinya berada di halaman dalam puri. Ujungnya tepat merapat ke menara bade, yang sehari sebelumnya disiapkan di luar puri. Ke dalam salah satu bilik dalam menara itulah jenazah diletakkan. "Kematian, di Bali, adalah sebuah saat yang mengasyikkan," kata seorang ahli, "tak harus lagi bersentuhan dengan bumi, yang sengsara." Dalam bilik di menara itu, sang jenazah mungkin "merasakan", buat pertama kalinya, bagaimana asyiknya berada jauh dari tanah. Apalagi setelah bade dijunjung, bergerak dalam derap ratusan orang, bergoyang-goyang mengitari lapangan seperti candi gemerlap yang kena gempa. Di dekatnya, sebuah usungan lain juga diangkat, sebuah bangunan yang berbentuk miniatur sebuah pendopo. Itulah kendaraan khusus bagi sang Nagabanda. Dan sang Naga harus siap. Ia hari itu harus dipanah. Jenazah yang akan bebas dari bumi yang sengsara juga harus bebas dari dirinya - simbol segala pikiran "rendah", dan "duniawi", yang masih melingkari. Lalu gamelan diam. Teriakan berhenti. Pada pukul 13.00, di bawah matahari Bali yang membakar, busur pun di pasang. Dupa dibakar, semerbak. Seorang pedanda tua, diiringi dua pedanda lain, akan menjalankan tugas. Anda yang mungkin pernah melihat adegan upacara ini dalam sebuah lukisan Bali barangkali akan mengharapkan sebuah adegan yang seru. Apalagi, menurut cerita, bila pedanda yang bertugas sebagai pemanah itu kalah, ia akan mati dalam konfrontasi ini. Dalam kenyataannya, siang itu, yang terjadi bukanlah suatu duel yang dahsyat. Yang terasa adalah suasana lamban, yang serius, dan tanpa kejutan. Pendeta tua itu, Ida Pedanda Nabe Tulikup, dalam usianya yang 70-an tahun, bergerak pelan, khidmat, hati-hati. Wajahnya yang arif, dengan bulu mata yang meredupkan pandang, memang lebih perkasa: di kepalanya terpasang sebuah mahkota dengan beludru merah dan pucuk sebentuk gelas yang mirip bola lampu yang ditemukan Edison. Tapi ia tak bertindak sebagai jagoan, biarpun dengan busur di tangan. Ia tak bertindak sebagai algojo, bagi sang Naga. Anak panah itu tak terlepas. Yang terlontar: sepucuk kembang. Dan seakan-akan merasa gembira akan sukses pertarungan itu, gamelan pun kembali menggerimang, orang-orang bersorak dan bade diangkat. Artinya, telah tiba saatnya jenazah itu diboyong. Orang ramai pun menuju sebuah lapangan dekat kubur, satu kilometer jauhnya dari puri. Di situlah telah tersedia patung lembu yang bentuknya telah tersohor itu, tempat tubuh Anak Agung Niang Putu yang tua akan dibakar hingga jadi abu. Tiba-tiba saja, suasana tak lagi meriah. Tempo menjadi pelan. Sederet upacara panjang, yang terdiri dari bagian kecil-kecil, terinci monoton. Sebelum jenazah dibakar, keluarga dekat dan para pedanda naik ke tempat lembu ditegakkan, yakni sebuah pavilyun darurat bertiang empat yang dibangun di atas tujuh lapis tangga bata. Kain demi kain dilapiskan ke jenazah yang tersembunyi di perut lembu itu. Dua puluh lima kendil air suci dituangkan. Bungkusan demi bungkusan dibuka isinya ditata cermat. Seolah-olah ada seseorang yang disiapkan kopornya, sebelum berangkat ke negeri jauh. Di bawah, orang menunggu. Pengiring, pembantu, keluarga jauh, tamu. Dan turis. Pemandangan memang tidak sehari-hari. Di sekitar itu, di lapangan yang terbentang dekat makam di Setra Beng Gianyar itu, palebon ternyata tak hanya dilakukan oleh keluarga puri. Beberapa rombongan ngaben lain juga telah siap, bahkan di antaranya telah ada yang menyalakan api. Seakan-akan sebuah kampung baru telah muncul di areal itu, dengan gubuk-gubuk darurat, yang meriah dan berhimpit, dengan asap, bau jenazah terbakar, dan amisnya daging sesajian yang tertinggal. Artinya, sebuah penantian panjang telah dimulai. Jenazah Anak Agung Niang Putu, yang masih utuh dalam suntikan formalin, memakan waktu kira-kira empat jam sebelum jadi abu. Hari mulai senja. Para keluarga akan menginap di tempat itu, sementara tontonan wayang dipertunjukkan di malam hari. Petromaks-petromaks dinyalakan. Pada pukul empat dinihari nanti, orang-orang akan nuduk galih, mengumpulkan tulang-tulang yang telah dibakar - yang, menurut ajaran, berfungsi sama seperti pratiwi, bumi. Abu itu kemudian dibersih-kan dengan air, dibungkus dengan kain putih, dibentuk ibarat tubuh manusia. Esok malam, tiga bagian dari bentuk itu akan dilumatkan. Lalu, dengan ketekunan yang sabar, serbuk yang bercampur air itu dimasukkan dalam cupu-cupu kecil. Sisa-sisa Anak Agung Niang itu pada akhirnya akan tersimpan, di sebutir buah kelapa gading - wadah terbersih yang dipetik dari alam. Dan segalanya pun mulai ke antiklimaks. Senja jadi malam, malam jadi dinihari, dinihari jadi siang lagi. Lalu malam baru menyusul. Di bangunan bekas perabuan, yang bisa juga disebut balai pembasmian, nyala petromaks pun menampakkan orang-orang yang bersiap, di cahaya setengah gelap. Tak lama kemudian, setelah sederet upacara ditempuh, dan abu telah tersimpan di buah kelapa gading yang dibungkus kain putih, satu prosesi baru berangkat: prosesi perpisahan. Iring-iringan keluarga dan pengiring berputar beberapa kali mengitari balai pembasmian, seakan-akan mengucapkan selamat tinggal pada sebuah tempat tubuh akan kembali ke asal, sukma akan ke surga. Dan rombongan berangkat ke laut. Tujuh kilometer jauhnya dari sana, ada sebuah pantai. Malam makin gelap, tapi ada bulan yang cukup penuh. Truk dan mobil-mobil pun segera bertolak. Anak Agung Gde Oka, yang sebentar tadi ikut bersama anak istrinya di lapangan pembakaran, tak lagi tampak ikut: orang tua itu harus beristirahat di purinya. Tapi sejumlah tamu malah tak ingin pulang. Mereka ingin menyaksikan akhir dari acara panjang menuju surga itu, yang bagi setengah mereka merupakan peristiwa yang menakjubkan. Di pantai, apa yang bisa dikatakan menakjubkan mungkin tak ada - tapi agaknya suatu kombinasi alam dan manusia bisa juga memesonakan. Pantai itu landai. Pasirnya putih. Sederet jukung nelayan Bali bertengger di darat, mengaso tertib. Bulan seakanakan satu lontaran tingginya dari laut, tapi jauh di kaki langit. Gelap agak terlipur oleh sinarnya, juga oleh beberapa petromaks yang dipasang. Orang-orang duduk. Sejumlah anak-anak miskin mengais-ngais di pasir basah. Mereka mencoba menemukan kepeng, uang logam kuno yang terbuang dalam upacara rombongan-rombongan ngaben yang terdahulu. Dalam separuh gelap itu, mereka tak banyak berhasil. Kini mereka separuh menunggu, sampai rombongan baru itu rampung dari doa yang khidmat. Dan dalam bagian yang gelap, gamelan (yang beserta para penabuhnya dibawa dengan truk ke sana) berbunyi, seakan-akan dari tadi, seakan-akan dari dulu, dari jarak yang tak dikenal, bagian yang wajar dari pinggir laut yang sepi itu. Pasang mulai naik. Ombak mulai bersaing. Rombongan terus berdoa, khidmat. Di dekat sana, abu suci diletakkan dalam sebuah rumah-rumahan kertas. Warrla-warninya setengah mengkilap setengah muram oleh cahaya yang tak lengkap. Tombak-tombak kebesaran terpancang pada pasir. Di sampingnya, payung-payung. Orang seperti tak ada yang bicara. Sampai saatnya sebuah jukung siap, dan butir kelapa berbalut putih, yang berisi sisa tubuh Anak Agung Niang Putu itu, harus diberangkatkan. Orang masih seperti tak ada yang bicara, meskipun mereka sebenarnya bicara, atau berbisik. Yakni ketika cucu-cucu memberi penghormatan terakhir kepada sang nenek. Dipimpin oleh cucu kedua, Anak Agung Gde Agung Bharata, mereka satu demi satu menyunggi sebentar butir kelapa itu. Lalu segalanya bergerak, seperti dalam sebuah film berwarna yang bisu - kecuali bahwa gamelan masih berbunyi, motor di jukung tradisional itu telah dihidupkan, dan ombak makin besar. Akhirnya, jukung diluncurkan. Seorang cucu, dengan jas beskap putih dan destar yang telah dilepas, naik. Diiringi nelayan pengemudi perahu, dialah yang akan membawa butir kelapa gading itu ke tengah laut. Orang-orang melambai. Jukung menderu. Ombak menyibak. Bulan makin tinggi. Yang berangkat pun menembus gelap - dan Anak Agung Niang Putu, seorang wanita tua yang pernah ada di dunia, kembali bersatu dengan asal-usulnya. Tidak setiap tahun orang akan menyaksikan yang seperti itu lagi. * * * Memang, belakangan mulai berkurang upacara ngaben dengan kemeriahan seperti di Puri Gianyar itu. Bukan karena orang-orang di luar tembok puri tidak boleh menyamai kebesaran upacara itu, tetapi ada kesadaran untuk mulai menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi. Di Puri Gianyar itu sendiri, ngaben besar seperti yang terjadi di awal Agustus lalu sudah lama tak terjadi. Terakhir di tahun 1961, pembakaran jenazah raja Gianyar, Anak Agung Ngurah Agung - suami Anak Agung Niang Putu itu. Kemudian, dari 1961 sampai 1985 ada empat kali pembakaran mayat, tapi semuanya berlangsung secara sederhana. Padahal, jenazah yang dibakar termasuk istri-istri bekas raja. Sederhana atau mewah, ngaben adalah suatu keniscayaan bagi umat Hindu di Bali. Ritus ini adalah upacara penyempurnaan jasad, mengembalikan unsur-unsur yang membentuk tubuh manusia ke asalnya. Dalam ajaran Hindu Dharma (agama Hindu), tubuh manusia dibentuk oleh zat yang sama dengan yang menjadikan alam semesta. Karena itu, ada yang disebut bhuwana agung dan bhuwana alit. Unsur-unsur di dalam tubuh (bhuwana alit), seperti pula yang ada di alam jagat raya (bhuwana agung). Dalam ajaran Hindu, zat-zat itu disebut Panca Maha Bhuta, yakni pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Bahkan dikatakan, unsur dalam badan manusia bukan saja sama dengan yang di alam, tetapi tubuh manusia meminjam unsur-unsur dari alam. Pinjaman itulah yang harus dikembalikan, setelah roh pergi. Pengembalian "pinjaman" itu semakin cepat semakin baik, agar sang atma yang gentayangan lekas-lekas menemukan tempat istirahatnya - dengan hanya dikuburkan di dalam tanah, proses kehancuran mayat untuk menyatu dengan tanah, hal itu tentulah berlangsung berpuluh tahun. Sementara itu, sang atma tetap saja berutang, tetap gentayangan belum menemukan jalan ke terminalnya yang terakhir. Karena itulah ngaben diadakan. Tapi pembakaran jenazah bukan hanya demi sang roh. Ritus ini pun menjadi kewajiban ahli waris, kewajiban membayar utang. Agama Hindu mengajarkan, setiap orang berutang kepada orangtua yang melahirkannya. Yaitu berupa utang kama bang dan kama putih, yang menyebabkan terjadinya kelahiran. Dengan upacara ngaben, utang dua jenis kama itu dianggap lunas. Tentu, sebagaimana upacara keagamaan yang lain, ngaben tidaklah langsung pada maknanya. Ada suatu proses yang bisa sangat panjang dan mahal. Seorang tokoh sepuh agama Hindu, I Gusti Ketut Kaler, 65, mencoba memberikan keabsahan untuk upacara seperti itu. Katanya, "Dalam upacara ngaben, ada yang perlu mendapatkan kepuasan, yakni emosi, cita rasa, keharusan, keindahan, sopan santun, dan basa-basi," katanya. Memang, ujar pensiunan kepala Bimas Hindu dan Budha pada Kanwil Departemen Agama Bali ini, belakangan ada gejala baru melanda umat Hindu di Bali. Yakni apa yang disebut dalam bahasa daerah: lek kaciwa semu. Tapi ini cuma ekses samping, tak begitu menonjol. Ngaben tergolong kegiatan Pitra Yadnya, salah satu dari Panca Yadnya. Seperti halnya setiap yadnya, seseorang diwajibkan melaksanakan upacaranya, sebatas kemampuan. Seorang pengusaha hotel, atau pemilik toko kesenian yang punya penghasilan 50 dolar sehari - jenis orang kaya baru di jalur pariwisata Bali - tentu tidak akan memikul beban berat, misalkan ia harus ngaben dengan biaya Rp 500.000. Sebaliknya, masyarakat pedesaan yang hidupnya pas-pasan, yang belum menikmati gemerincing dolar yang dibawa orang asing, ngaben dengan biaya Rp 25 ribu bisa menjadi beban seumur hidup. Untunglah, tak ada agama yang sengaja menurunkan aturan yang membuat hidup jadi susah. Ada petunjuk ngaben secara hemat. Itu dimuat dalam lontar Yama Purwana Tatwa. Misalnya, dalam lontar itu dicontohkan sesajen yang tak makan ongkos besar. Dan, kalau saja orang yang mati itu pas harinya - artinya tidak pada hari upacara persembahyangan di pura (Dewa Yadnya), atau tidak pada bulan Purnama dan bulan Tilem - pada hari itu pula upacara pengabenan bisa diselesaikan, sehari tuntas. Tak usah menunggu. Secara garis besar, pelaksanaan ngaben sehari itu begini. Mayat dibungkus kain. Sesajen disiapkan, tirta (air suci) dimohonkan kepada yang berhak, misalnya pendeta. Kemudian jenazah diusung dari rumah ke kuburan. Di kuburan sudah disiapkan tungku pembakaran, cukup berdindingkan pohon pisang - agar tak mudah dimakan api - lengkap dengan kayu bakarnya. Sebelum mayat dibaringkan di tungku, upacara sederhana diadakan. Kain penutup jenazah dibuka. Tubuh lemas tak bernyawa itu diperciki toya panembak - ini air suci untuk menyatakan bahwa jasad itu sudah tak bernyawa lagi. Sesudah itu jenazah masih diperciki lagi dengan tirta pangentas, air suci bikinan pendeta. Maksudnya, agar roh yang dulu menghuni tubuh manusia mati itu menjauh dari badan kasarnya. Sisi si mati yang telentang itu dipenuhi sajen-sajen kecil. Sesajen berbagai bentuk itu agak rumit untuk dijelaskan. Namun, bagi ibu-ibu rumah tangga di Bali, sesajen seperti itu sudah di luar kepala. Lewat sesajen inilah dimohonkan bantuan Yang Mahakuasa agar jenazah cepat hangus, cepat kembali ke asalnya. Lalu, pembakaran pun dimulai. Setelah mayat jadi abu - beberapa daging yang sulit jadi abu langsung ditanam - pembakaran dihentikan. Sejumput abu diambil dari bekas kepala, tangan, punggung, dada, paha, dan kaki. Tentu, tidak persis abu kepala benar-benar. Sebab, selama api berkobar mayat itu diobrak-abrik, di balik-balik. Pada akhirnya mana kepala mana kaki sulit ditentukan. Lalu ditentukan saja, kalau waktu telentangnya tadi kepala berada di ujung sana, maka abu yang diambil dari ujung itu dianggap saja abu kepala, begitu juga dengan abu kaki dan tangan. Abu kakinya tentu di ujung yang satu lagi. Setelah dikumpulkan, abu-abu ini kemudian dimasukkan ke dalam kelapa gading yang masih muda. Dilengkapi sedikit sesajen lagi, abu ini pun dibawa ke laut, dihanyutkan. Kalau desa itu di pegunungan dan laut jauh, sedangkan keluarga yang punya hajat tak kuat mencarter mobil, abu cukup dihanyutkan di sungai terdekat. Orang Bali percaya, setiap air yang mengalir di sungai, bermuaranya ke laut jua. Ngaben sederhana itu memang terhitung jarang. Masyarakat Bali sudah terbiasa mengadakan uoacara yang meriah, warisan "kebudayaan" raja-raja sebelum kemerdekaan. Lontar Yama Purwana Tatwa seperti dilupakan. Baru pada 1962, petunjuk ngaben sederhana dihidupkan lagi, dikampanyekan oleh Pemerintah Daerah Bali bersama Dinas Agama Hindu dan Parisadha Hindu Dharma. Dan memang ada sebabnya. Waktu itu, 1962, sudah direncanakan persembahya-ngan besar seratus tahun sekali di Pura Besakih, di lereng Gunung Agung. Upacara Eka Dasa Rudra namanya, yang diniatkan diadakan sekitar April 1963. Syarat utama upacara luar biasa ini adalah Bali bersih dari jenazah umat Hindu. Semua jenazah harus sudah lebur kembali ke alam semesta, semua roh harus sudah berada di tempatnya masing-masing. Sementara itu, zaman itu adalah zaman orang antre beras dan minyak tanah. Jelasnya, masa ekonomi sulit. Tapi, harus bilang apa kalau saatnya telah datang upacara seratus tahun sekali di Pura Besakih, dan syaratnya harus seperti tadi itu? Orang pun lalu teringat pada lontar Yama Purwana Tatwa tadi. Dibantu panitia upacara Karya Agung di Besakih, kampanye ngaben hemat ini ternyata di desa-desa diterima dengan ikhlas. Ada yang mengikuti persis petunjuk dalam lontar. Ada yang mengambil jalan tengah. Yakni tetap membuat bade, tetapi biaya ditanggung secara kolektif. Itulah yang kemudian populer disebut Ngaben Kolektif. Bade-nya satu, sesajennya satu jenis, tetapi ada beberapa jenazah bahkan puluhan. Dengan demikian, pada puncak acaranya, ketika api berkobar, kelihatan pengabenan ini seperti ngaben besar. Sayang sekali, karya besar di Besakih itu batal. Tahun 1963 itu Gunung Agung meletus dengan hebat, dua bulan sebelum upacara direncanakan. Setelah amukan gunung itu mereda, para pemuka agama berkumpul untuk "membaca pertanda alam". Dan ditemukanlah sesuatu yang mencengangkan masyarakat Bali. Tahun 1963 bukan saatnya upacara seratus tahun di Besakih. Para pemuka agama telah salah hitung. Seratus tahun itu baru terjadi 1982. Eka Dasa Rudra abad ini memang dilangsungkan dengan mulus pada 1982 lalu. Tak ada gunung meletus, tak ada halangan apa pun. Bahkan, karena kehidupan sudah lebih baik, masyarakat sudah "lebih maju", pemerintah tak lagi mengkampanyekan ngaben hemat, waktu itu. Semuanya diserahkan kepada masyarakat sendiri. * * * Dulu, sebelum 1960, ada anggapan bahwa ngaben yang tidak memakai bade, tidak memakai lembu, tidak berhari-hari dengan hiburan setiap malam, bukan ngaben namanya. Padahal, kurang jelas sejarah ngaben harus dengan bade yang bertingkat-tingkat itu. Bade sulit dilacak karena miskinnya literatur soal ngaben yang bertulisan latin. Pun belum diketahui apakah sejarah itu terekam dalam daun-daun lontar dan di mana tersimpan. Baru I Gusti Ketut Kaler yang sejak 1982 mulai mencari bahan tentang ngaben, untuk ditulis, dibukukan. Dan naskah itu tetap tergeletak belum dikaji karena Ketut Kaler sakit di desanya, Blahkiuh, 17 km dari Denpasar. Menurut sang tokoh ini - ia mengutip dari berbagai lontar yang dikumpul-kannya - ngaben dengan segala kemeriahannya diatur semasa pemerintahan Dalem Sagening, maharaja Bali, yang berpusat di Gelgel, Klungkung. Ini pada abad ke-16. Yang pertama-tama diatur adalah tingkat bade. Untuk keluarga raja Gelgel - yang dianggap maharaja zaman itu - beserta keluarganya, bade ditetapkan bertingkat sebelas. Inilah hitungan tingkat tertinggi di Bali. Untuk raja lain di Bali (raja Tabanan, Badung, Gianyar, dan Karangasem) ditentukan bade bertingkat sembilan. Untuk pembesar kerajaan, pepatih, punggawa, dan sebagainya, dipergunakan yang bertingkat tujuh. Tingkat ini juga digunakan oleh seorang tokoh di masyarakat atas izin raja. Kemudian tingkat lima dan tiga dipergunakan oleh masyarakat biasa. Di masa pemerintahan Dalem Sagening inilah "kesenian" ngaben dikembang-kan. Bade, pengangkut jenazah ke kubur itu dibuat seperti meru di sebuah pura. Bedanya, meru dasarnya segi empat bujur sangkar dengan empat tiang, bade segi empat panjang dengan enam tiang. Rangkanya dibuat dari bambu. Tempat jenazah ada di tengah-tengah, dan di atas tempat jenazah itulah dipasang tumpang yang menunjukkan siapa yang meninggal dunia - berdasarkan banyaknya tumpang. Agar bau kemeriahan komplet, di zaman Raja Sagening itu dibuat pula kreasi baru. Yakni tungku pembakaran di pekuburan tidak sekadar tungku seperti membakar bata. Tungku pun dihias, dibuat dari papan yang diukir. Dan agar keindahan itu tak sia-sia, perlu pula dipamerkan dan diarak. Jadilah kemudian tungku itu berupa bentuk-bentuk binatang: lembu, singa, gajahmina (berbadan ikan berkepala gajah), beruang, dan binatang-binatang buas lainnya. Pemilihan bentuk-bentuk binatang itu pun tidak sembarangan, semuanya disesuaikan dengan asal usul keturunan dan "keyakinan". Agama Hindu di Bali masih menampakkan bekas-bekas sekte seperti agama Hindu di India. Bekas-bekas sekte inilah yang membedakan binatang-binatang itu. Mereka yang memilih binatang lembu adalah yang berasal dari sekte Ciwa. Yang memilih binatang air (gajahmina, nagakahang, dan sebagainya), bekas-bekas sekte Wesnawa. Sedangkan yang memilih binatang buas (macan, singa, beruang) adalah bekas-bekas keturunan sekte Brahma. Pilihan itu tak ada kaitannya dengan tinggi rendahnya kasta. Sarana pembakaran itu - di Bali disebut patulangan - ada pula yang bentuknya netral: kotak segi empat panjang biasa saja. Pilihan ini biasanya datang dari kelompok masyarakat yang tak percaya lagi bahwa sumber agama Hindu di Bali itu India, setidak-tidaknya mereka tak pernah menganggap sekte itu ada. Di Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Tengah sejak dulu jarang dijumpai patulangan berupa bentuk-bentuk binatang. Yang diarak ke pekuburan hanya bade dan tratag. Memang ada yang di luar aturan, yakni untuk pendeta. Pendeta dianggap orang yang sudah suci, yang segala nafsu duniawinya sudah hilang. Jenazahnya memang juga dibakar, tapi tanpa ritus yang meriah dengan bade berhiaskan kain dan bunga yang indah-indah. Suci semasih hidup, suci jualah dalam perjalanan ke tempat terakhir. Semakin tinggi ilmu pendeta itu, semakin mudah ahli warisnya menyelesaikan upacaranya. Contoh terakhir, ketika Pedanda Sidemen meninggal dunia beberapa bulan lalu, mayatnya cukup dibakar begitu saja. Bahkan pembakarannya itu sendiri tidak dilakukan di pekuburan, tetapi di tanah ladang biasa. Begitu tinggi ilmu tokoh undagi terkenal Bali ini sehingga Pedanda Sidemen menyiapkan sendiri air suci untuk tubuhnya, beberapa saat sebelum sang atma meninggalkan badan kasarnya. * * * Ada satu lagi sarana yang jarang ada. Nagabanda, berwujud sebuah patung naga yang besar dan panjang. Menurut asal muasalnya - seperti yang ditulis I Gusti Ketut Kaler dalam naskah yang belum terbit itu - panjang ekor nagabanda ini harus 1.600 depa. Jika ketentuan itu dipatuhi, betapa besar dan panjangnya naga mirip barongsay Cina ini. Dalam pelaksanaannya kemudian, selain ukuran depa yang dipakai adalah rentangan tangan anak kecil, bagian tubuh sang naga itu dibuat dengan tali biasa saja. Hanya formalitas, dan selanjutnya tali itu digulung. Yang boleh memakai nagabanda hanyalah raja, atau keluarga dan keturunan raja, dan itu pun atas anugerah raja. Ini adalah lambang bahwa yang dibakar seseorang yang pernah memerintah, yang punya ikatan erat dengan masyarakat yang dipimpinnya. Ia semasa hidupnya penuh dengan pergolakan untuk menyejahterakan masyarakat, menyelesaikan masalah duniawi. Jarang ada ngaben yang memakai nagabanda. Dan, konon, jarang pulalah ada pendeta yang berani memimpin upacara ngaben yang memakai nagabanda. Menurut cerita, ketika pendeta itu menembak dan membunuh nagabanda dengan panah bunga, di sana terjadilah "pertempuran". Jika pendeta kurang ilmu, kembang yang dipakai memanah itu tak layu, maka sang pendeta dikategori-kan kalah: ia bisa celaka. * * * Majemuknya masyarakat, perkembangan yang tak seragam, lingkungan yang berbeda, membuat ngaben tak selalu harus dengan api berkobar. Desa Pujungan, Kabupaten Tabanan, berada di lereng Gunung Batukaru. Gunung itulah yang sering disebut sebagai daerah Bali Tengah. Desa ini salah satu dari beberapa buah desa yang unik. Di sini tidak ada pembakaran mayat dalam arti yang sebenarnya, ketika upacara ngaben berlangsung. Masyarakat Pujungan justru menganggap pembakaran mayat bisa mengganggu kesucian Pura Luhur, yang terletak di puncak Gunung Batukaru. Yakni jika sampai terjadi abu jenazah terbang dibawa angin keatas gunung yang tingginya 2.276 meter itu. Lalu, apa yang mereka lakukan terhadap jenazah? Di pekuburan, jenazah dikeluarkan dari bade, kemudian pembakarannya dilakukan secara simbolis: dengan tiga batang dupa yang menyala. Lantas dikubur. Tak ada tungku pembakaran, atau patulangan yang berwujud binatang-binatang itu. Ngaben besar terakhir di Pujungan ini terjadi pada tahun 1962. Jenazah yang diupacarai, keluarga seorang pemuka agama, pemangku Pura Puseh. Jenazah itu sudah lama dikuburkan di sebuah tanah kebun kopi. Inilah yang di Bali disebut mekingsan, atau dititipkan. Tahap penitipan ini gunanya untuk memberi kesempatan kepada keluarga si mati mengumpulkan biaya. Titipan di dalam tanah (dikuburkan di luar pekuburan) tak boleh lebih dari dua tahun. Sebabnya, selama masih ada jenazah titipan, masyarakat tak boleh mengadakan persembahyangan di Pura Luhur, di puncak gunung itu. Sebulan sebelum puncak upacara ngaben, masyarakat sudah bergotong royong mempersiapkan upacara. Perempuan-perempuan membuat sesajen, laki-laki membuat bangunan-bangunan, balai-balai, panggung-panggung hiburan, dan membantu membuat bade. Dikatakan membantu karena arsitek bade itu sendiri orang upahan, biasanya dari Bali Selatan. Tujuh hari sebelum puncak acara, jenazah yang sudah dititipkan setahun lebih digali. Inilah mungkah, menggali kembali jenazah. Yang diambil hanya tulang-tulangnya karena memang jenazah biasanya tinggal kerangka. Dan sejak tulang-tulang itu dibawa pulang, setiap malam selalu ada keramaian: hiburan dan juga arena judi. Dua hari setelah mungkah, jenazah itu mestinya dibawa ke sebuah permandian setiap hari. Tentu saja tak mungkin tulang-tulang yang sudah terbungkus kain putih itu digotong tiap hari untuk disucikan. Maka, dibuatlah pengawak, biasanya dari kayu cendana dengan hiasan bermacam-macam. Sejenis wayang golek atau boneka ini sebagai ganti orang yang akan diupacarai. Pada setiap kali permandian, sanak keluarganya biasanya rebutan ingin menggendong boneka (pengawak) ini, sebagai wujud bakti kepada orangtuanya. Dua hari sebelum palebon dimulai dinamai hari nyuwung. Maksudnya, menyepi menjelang karya besar. Segala kerepotan yang berurusan dengan upacara dihentikan karena memang telah selesai. Sesajen sudah komplet, bade sudah jadi. Tak ada pekerjaan apa-apa lagi. Yang ada hiburan melulu, siang dan malam - meski tahap ini disebut menyepi. Misalnya, ada pementasan wayang. Ceritanya selalu berkisar pada pencarian tirta suci oleh keluarga Pandawa. Dan ketika tirta suci itu diperoleh dalam cerita wayang kulit itu, ki dalang juga membuat tirta suci untuk upacara pengabenan ini. Tirta ki dalang ini termasuk yang dipercikkan ke jenazah di pekuburan, esok harinya. Hiburan lain adalah gambuh yang mengambil cerita-cerita Panji. Pada puncak acara ngaben, pagi-pagi, bade sudah diletakkan di jalan, dekat dengan rumah yang punya hajat. Tentu saja, hal itu menjadi tontonan masyarakat. Sementara itu, undaginya membuat upacara pemelaspasan, meresmikan bade itu sebagai benda suci. Ini penting. Sebab, bukan mustahil bahan-bahan bade diperoleh dengan jalan tak suci, misalnya bambunya curian. Ketika jenazah dikeluarkan dari balai penyimpanan menuju bade, suasana begitu mengharukan. Puluhan meter kain putih dipegang berbaris oleh sanak keluarga jenazah. Kain itu rurub kajang namanya, ujungnya membalut jenazah. Dengan memegang kain itu, berarti orang ikut mengusung jenazah. Lalu jenazah siap dimasukkan ke dalam bade. Para pemikul, dengan kain putih yang melilit kepala masing-masing, tapi bukan destar, siap mengitari bade. Kaum wanita menjunjung air tirta suci dalam tempat-tempat tertentu. Orang hamil tak boleh ikut membawa tirta suci ini. Di atas senan bade, ada seperangkat gender wayang kulit, yang ditabuh mengalunkan suara memilukan, mengiringi perjalanan sang atma meninggalkan jasad kasar, konon. Sedangkan untuk mengiringi arak-arakan ke pekuburan itu, ada seperangkat gong baleganjur dengan suara ingar-bingar yang memekakkan. Selain untuk menambah semangat para pengusung bade, gong itu juga berfungsi membangunkan Panca Maha Bhuta yang akan menerima badan kasar yang meninggal itu. Masih ada satu simbol lagi yang penting. Pada bade, seorang lelaki berdiri, mengawal jenazah. Satu tangannya memegang erat tiang bade agar tidak jatuh, satu tangannya lagi membawa tongkat yang bermahkotakan seekor burung cenderawasih - yang diawetkan, tentu. Burung itu di Bali dijuluki Manuk Dewata, konon jenis burung yang bisa mondar-mandir di dua dunia: yang fana ini, dan dunia surga-neraka. Cenderawasih itulah yang akan menuntun sang atma pergi ke dunia lain itu, agar tidak kesasar. Ini legenda yang hidup di Bali, walaupun burung cenderawasih tak pernah hidup di Bali entah beratus tahun lalu. Di kuburan, sebelum jenazah diturunkan, seseorang melemparkan ayam yang tadinya ditaruh di sekitar jenazah. Ini juga perlambang bahwa roh siap pergi meninggalkan badan kasar. Ayam ini boleh jadi rebutan orang, tapi tidak boleh diambil oleh keluarga yang punya jenazah itu. Dan upacara ngaben pun mendekati akhir, jenazah diturunkan, pendeta memimpin upacara, jenazah dibakar secara simbolis, kemudian ditanam, dan selesai. * * * Ngaben di Desa Pujungan tahun 1962 itu menelan biaya seratus kuintal kopi - penduduk desa ini memang petani kopi, segala biaya dihitung dari berapa butir kopi yang dihabiskan. Itu masih ditambah seratus lima puluh ekor babi. Biaya-biaya ini selain untuk sesajen, honorarium arsitek bade, dan ongkos pendeta yang didatangkan dari Bali Selatan, juga untuk menjamu sekian manusia hampir selama sebulan - setidaknya dalam dua minggu menjelang ngaben, siang malam. Tak semua orang Pujungan taat pada aturan ini, memang. Selalu ada orang-orang yang menyebal - dan karena itu konon, dunia tetap berputar. Pada 1977, I Wayan Nesa Wisuandha menyelenggarakan upacara ngaben untuk kakeknya. Nesa masih keluarga dekat dari keluarga yang ngaben di tahun 1962. Bahkan ia yang menjadi ketua panitia waktu itu. Tetapi ketika ia mengadakan upacara untuk kakeknya sendiri, ia menempuh cara yang lain. Ia tidak memakai bade bertingkat tujuh. Ia tak memerlukan waktu sebulan atau seminggu, tapi hanya tiga hari. Dan yang sangat "berani", I Wayan Nesa tidak membutuhkan seorang pendeta yang berstatus peranda - dari kasta brahmana - sebagaimana lazimnya. Ia mengundang hanya seorang sri empu - ulama dari kalangan warga pasek - dan tugas ulama ini cuma mengawasi. Yang memimpin dan menyelesaikan upacara pengabenan itu tetap Wayan Nesa sendiri. Suatu kejutan buat masyarakat Pujungan. Upacara mungkah dilakukan dua hari menjelang palebon. Ini pun dengan simbolis karena jenazah yang diaben itu tidak dalam status mekingsan. Kubur tak dibongkar. Hanya sejumput tanah kuburan setelah roh dibangunkan untuk menempati tanah yang sekarang sudah dianggap badan kasar, yang diambil. Penggalian secara simbolis ini disebut ngulapin. Upacara pembersihan dilangsungkan sehari. Tak ada tontonan, tak ada wayang kulit. Masyarakat yang membantu upacara ini juga tidak banyak. Bade dibuat kecil saja, dan tidak bertingkat - inilah jempana. Tak perlu ada undagi, bahkan hiasan-hiasannya seadanya, berupa kain warna-warni yang digantung. Pada hari palebon, yang mengusung bade ini tak sampai sepuluh orang. Memang, ada seperangkat gong mengiringi usungan itu ke pekuburan, tetapi cukup dipukul sekitar delapan anak-anak kecil, dan asal bunyi saja. Tidak ada gender. Tidak ada burung cenderawasih yang diawetkan. Tidak ada tratag, dan tidak ada ayam yang dilemparkan. Tidak ada hiruk-pikuk. "Toh upacaranya selesai secara agamawi,"kata Wayan Nesa. "Kalau menunggu sampai terkumpul uang banyak, kapan ngaben? Dan dari mana mengumpulkan uang?" Untuk upacara ngaben berhemat ini, Wayan Nesa hanya harus mengeluarkan Rp 300.000 (tiga kuintal kopi). Itu sudah termasuk menjamu warga desa yang datang, dan juga beberapa undangan dari kota kecamatan dan kota kabupaten. Wayan Nesa, ketika itu kepala Desa Pujungan, sedang giat-giatnya memimpin desa untuk lomba (dan Desa Pujungan akhirnya memang juara pertama lomba desa se-Bali tahun 1980). Pujungan, desa yang tenteram itu, pada 1977 itu, tentu saja geger. Nesa, yang sebelumnya menjadi kepala desa dan sudah bertahun-tahun menjadi bendesa adat, dicemoohkan. Ia dinilai pelit, menjalankan upacara agama secara gampangan. Protes paling keras yang diterimanya, dan nyaris ia dilaporkan ke Dinas Agama Kabupaten Tabanan, karena ia berani memimpin upacara Pitra Yadnya. Wayan Nesa dianggap tak berhak memimpin upacara. Untung, protes itu tidak berlanjut - tak ada dasar hukumnya. Tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa setiap upacara - apa pun jenisnya - harus memakai pendeta dari kalangan Brahmana. Wayan Nesa tak diikuti orang-orang sedesanya, memang. Dua tahun setelah ia ngaben, di Pujungan dilangsungkan lagi pembakaran mayat. Kali itu 12 jenazah sekaligus diaben bersama, pengabenan kolektif namanya. Para ahli waris tak percaya ngaben gaya Nesa dibenarkan agama. Mereka percaya bahwa yang dilakukan para leluhur di zaman silam harus diikuti. Bila memang tak ada biaya, ngaben kolektif adalah pemecahannya. Maka, kembalilah hadir bade tingkat tujuh, hiruk-pikuk siang malam. Cuma, biaya ditanggung bersama, dan ngaben dilangsungkan di pekarangan ahli waris pembayar terbesar. * * * Tapi mengapa Wayan Nesa Wisuandha, 50, berani bertindak tidak populer? "Apa yang saya lakukan adalah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi," katanya. Dalam kamus orang ini, biaya ngaben yang begitu besar lebih baik digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak, atau untuk modal bekerja. Kelebihannya baru untuk ngaben yang besar. "Jangan sebaliknya, untuk biaya ngaben mencari utang, atau menjual kebun, sementara pendidikan anak-anak sama sekali tak mendapat perhatian." Ia setuju, dan malah mengatakan sudah seharusnya, bahwa biaya ngaben harus dirasakan sebagai beban. "Tetapi menjual tanah kebun yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan 'kan sudah kelewat beban?" katanya. Wayan berpendapat bahwa anggapan masyarakat ngaben harus mewah, mengikuti tradisi leluhur, karena faktor pendidikan masyarakat. Mereka tak mau lagi menggali ajaran-ajaran agama lewat berbagai sarana yang ada, katanya. Wayan Nesa, sejak lepas umur 30-an, tekun membaca kitab-kitab suci dan lontar-lontar yang dikumpulkan dari sana-sini. Bertahun-tahun drop out sekolah menengah afas di Yogyakarta, ia menjadi anggota DPR (GR) tingkat Kabupaten Tabanan. Pada saat ia telah merasa ilmu agamanya cukup, ia mediksa pada seorang pendeta. Karena itu, dia dianggap cukup mampu memimpin upacara yadnya, baik itu Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, maupun yadnya yang lain-lain. Nesa bukan satu-satunya. Sudah banyak orang seperti dia, bukan keturunan bangsawan yang mengambil peran sulinggih. Dalam kaca mata I Gusti Ketut Kaler - yang kebetulan keturunan bangsawan - ini suatu kemajuan. "Mengambil fungsi rohaniwan, bagi golongan masyarakat mana pun bisa, dan itu memang dibolehkan," katanya. Memang, kasta di Bali adalah kisah salah kaprah. "Apa yang disebut kasta seperti di India tidak ada diBali. Di Bali tidak ada kasta sudra seperti pengertian yang ada di India, yang dibatasi hak-haknya dalam menjalankan upacara keagamaan," kata Ketut Kaler. Dalam kuliah-kuliah di Institut Hindu Dharma Denpasar, Drs. Ida Bagus Putra juga secara berhati-hati menekankan bahwa masalah kasta di Bali sesungguhnya tidak ada. Yang ada, warna - fungsi sosial seseorang di dalam masyarakat. Penggolongan masyarakat di Bali karena fungsi sosialnya itu ditata di zaman Dalem Dimade, sekitar abad ke-16. Ada catur warna, atau empat fungsi. Yakni yang menjalankan dan memimpin upacara keagamaan yang memegang pemerintahan yang bergerak di bidang perekonomian: dan yang bekerja sebagai petani. Pembagian keempat warna inilah, beberapa puluh (atau ratus) tahun kemudian, agaknya, lalu disesuaikan namanya dengan kasta di India. Maka, jadilah urutan: brahmana, kesatria, wesya, dan sudra. Padahal, di zaman Dalem Dimade itu, penataan "kelas" di masyarakat berdasarkan fungsinya hanyalah dengan pemberian gelar di depan nama dan nama urut kelahirannya. Kaum pertama menyandang gelar Ida Bagus (lelaki) dan Ida Ayu (perempuan). Kaum kedua, katakanlah pegawai pemerintahan, bergelar Anak Agung, Tjokorde, Gusti Ngurah, Gusti, Dewa (untuk lelaki), dan Anak Agung Istri, Tjokorde Istri, Gusti Ayu, Desak (untuk perempuan). Kelas ketiga, yang bergerak di ekonomi bisnis, mendapat gelar Si di depan nama urut dan nama aslinya. Yang petani, cukup I (laki) dan Ni (perempuan). Kalau dikaitkan dengan kebangsawanan, hanya golongan petani yang tidak bangsawan, dan mereka disebut jaba. Warga pasek - seperti I Wayan Nesa Wisuandha itu - dulu, leluhurnya memilih profesi sebagai petani. Entah apa yang terjadi setelah Kerajaan Gelgel tidak lagi menjadi kemaharajaan di Bali. Yang pasti, gelar "jabatan fungsional" ini terus-menerus melekat ke anak turunannya, walaupun si keturunan itu beralih profesi. Dan raja-raja kecil di Bali - ada sembilan jumlahnya - tak berbuat apa-apa tentang gelar itu. Mereka tidak menyetop penyimpangannya, juga tidak membikin yang baru. Maka, sekarang, seorang Ida Bagus belum tentu tahu seluk-beluk upacara keagamaan. Bisa saja ia bekerja di bengkel mobil, atau jadi pedagang acung. Tetapi tetap Ida Bagus. Sementara itu, seorang I tanpa embel-embel, seorang jaba, bisa (dan boleh) menyelesaikan upacara keagamaan. Di Bali - terutama di pedesaan - masalah ini hanya bisa diomongkan dengan hati-hati. Apalagi di tahun 1970-an, warga pasek yang terpencar-pencar dan mempunyai riwayat tujuh leluhur, menghimpun diri dalam organisasi Warga Pasek Sanak Pitu. Organisasi ini aktif menggali "sejarah lama" dan giat dalam pelajaran keagamaan. Seorang sulinggih dari warga ini akhirnya diberi gelar sri empu, untuk membedakan dengan peranda - sulinggih dari kalangan brahmana. Sri bisa berarti orang suci, dan empu (lainnya arya, ki) adalah gelar-gelar sebelum zaman Dalem Dimade. Lihatlah tokoh masa itu: Empu Kuturan, Arya Belog, Ki Batan Jeruk, dan sebagainya. Sekarang ada gejala di antara para tokoh untuk menetralkan gelar itu, misalnya: gubernur Bali hampir selalu hanya menulis nama Mantra dalam surat-surat resmi. Juga Oka Mahendra, anggota DPR - orang bisa lupa kalau nama lengkapnya ada Anak Agung-nya. Dan Ida Ayu Agung ternyata Cheng Hian, istri Masagung yang sudah Islam. Kini, untuk menunjukkan kebaliannya, orang paling hanya memakai nama urut kelahiran: Wayan, Putu, Nengah, Made, Nyoman, Ketut. * * * Hal lain yang mempengaruhi besar kecilnya ngaben, selain tingkat ekonomi, adalah yang diaben jenazah langsung, atau simbolnya saja. Yang memakai jenazah langsung disebut nyawa wedana. Ini pun ada dua macam: jenazah disimpan di rumah, diawetkan dengan formalin seperti yang dilakukan untuk istri bekas raja Gianyar, yang dibakar pada 3 Agustus itu. Penyimpanan di rumah ini biasanya karena pihak keluarga masih menunggu waktu yang tepat untuk ngaben, terutama menunggu berkumpulnya seluruh keluarga. Dalam hal biaya, mereka yakin tidak ada hambatan. Cara lain, mekingsan. Ini pun ada dua macam. Mekingsan di api, mayat dibakar dengan upacara penguburan biasa dan abunya disimpan untuk nanti diupacarai ngaben. Dan, mekingsan dengan menanam mayat di luar kuburan, untuk nantinya mayat digali kembali. Cara ini ditempuh karena keluarga yang bersangkutan belum memastikan kapan upacara itu diselenggarakan, bisa setahun atau dua tahun. Ngaben yang tidak memakai jenazah langsung disebut nyewasta. Jenazah dikuburkan biasa di kuburan, yang nantinya diupacarai hanyalah segenggam tanah kuburan, sebagai wakil jenazah. Orang Bali tak pernah menggali jenazah dari kubur kecuali, belakangan ini untuk urusan kriminalitas. Cara nyewasta ini juga diberlakukan untuk mayat yang hilang dan tidak dikenal lagi (contohnya mati di peperangan, tenggelam di laut, atau sewaktu korban jatuhnya pesawat Pan Am di Bali, 1974). Roh untuk mayat jenis ini "dipanggil" dengan upacara di perempatan jalan di desa itu. Lewat empat penjuru angin, diyakini roh itu bisa diundang dan bersedia masuk dalam sebuah simbol badan kasar yang sudah disiapkan. Dengan demikian, setiap orang Bali (yang Hindu) harus diupacarai ngaben. Dan ada saja caranya, hingga ada bermacam-macam ngaben, agar upacara itu bisa dilangsungkan. Ada kekecualiannya, memang, yang bebas diaben. Misalnya, bayi yang meninggal dunia sebelum tali pusarnya putus. Dalam usia singkat seperti itu, si jabang bayi dianggap masih suci murni. Atmanya masih dianggap sejajar dengan para dewa, sedangkan badan kasarnya masih murni serupa air sehingga tak perlu dilebur lagi. Penguburan mayat ini pun mendapat perlakuan istimewa - tak memandang hari. Begitu meninggal, langsung bisa dikuburkan. Upacara dan sesajen juga tak di perlukan. Bayi yang berumur kurang dari asambutan, juga bebas ngaben. Bedanya dengan tadi, sebelum jenazah dikuburkan, ada upacara sedikit, yakni sesajen untuk mempersilakan Bhatara Kumara kembali ke kahyangan. Orang Bali percaya, bayi dalam usia seperti itu diasuh oleh Bhatara Kumara. Seorang anak yang meninggal sebelum gigi susunya tanggal juga mendapat keistimewaan sedikit. Anak seusia ini sudah dianggap punya "dosa", tapi belum sepenuhnya dosa itu adalah tanggung jawab si anak. Jelasnya, hanya badan luarnya yang berdosa, sedangkan pikirannya masih murni. Upacara ngaben dilakukan secara simbolis dan sangat sederhana, disebut nglungah. Asalnya dari kata klungah (kelapa muda). Disebut begitu karena rohnya cukup "dimasukkan" klungah, dan tak perlu memukur - upacara melepas sang atma ke tempat asalnya yang diadakan beberapa hari setelah ngaben. Di beberapa desa pegunungan, seperti Pujungan, anak yang gigi susunya belum tanggal ketika meninggal diperlakukan sama dengan bayi. Di Pujungan ada dua pekuburan yang jaraknya cukup jauh, untuk golongan dewasa (dihitung dari tanggalnya gigi susu) dan anak-anak. Mekingsan di api, belakangan semakin populer untuk umat Hindu di luar Bali yang tidak punya pekuburan khusus. Bila di permukiman transmigrasi sudah disediakan kuburan khusus untuk orang Bali (dibaca saja: untuk agama Hindu), itu berarti permukiman itu sudah lengkap sarananya sebagai desa adat. Yakni ada Tri Kahyangan. Tetapi bagaimana dengan di Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Medan? Di Jakarta misalnya, di setiap wilayah sudah terbentuk Banjar Bali. Kecuali di Jakarfa Pusat, yang tempat persembahyangannya masih bergabung dengan Jakarta Timur di Pura Rawamangun, semuanya punya tempat persembahyangan. Tetapi itu belum Tri Kahyangan, dan karena itu pula belum memenuhi syarat adanya desa adat yang bisa mengelola pekuburan. Lalu, bagaimana kalau orang Bali di Jakarta meninggal? Jenazah mau tak mau dikirimkan ke Bali, dikuburkan atau diupacarai ngaben di kampung kelahirannya. Jalan lain, dibawa ke krematorium yang ada di Cilincing, mayat dibakar. Inilah salah satu jenis mekingsan di api. Abunya tinggal dibawa ke desanya di Bali (bisa sebulan, dua bulan, atau berbilang tahun dengan naik kereta api atau bis), dan upacara ngaben bisa hanya simbolis. Sangat sederhana, hanya mengundang tetangga. Secara agama, tidak salah. Kecuali kalau keluarga "orang Bali Jakarta" itu seorang pengusaha besar, di kampungnya bakal muncul bisik-bisik: ndas keleng, demitne keliwat-liwat, tusing elas maang nasi krama banjar nang a tekor. (Artinya, lihat: Glossary Ngaben). * * * Tak selalu ngaben diadakan karena agama. Ngaben Rudolf Bonnet, misalnya, pelukis yang sampai akhir hidupnya tetap warga negara Belanda, yang diupacarai dengan cara mekingsan di api. Upacara ini lebih sebagai kecintaan Bonnet terhadap Bali dan kecintaan warga Desa Ubud terhadap bule yang bertahun-tahun bersamanya itu ketimbang persoalan agama. Kecintaan Bonnet terhadap Bali memang mendarah daging. Lahir di Amsterdam 1895 dan belajar seni lukis di Italia, Bonnet sejak 1928 menetap di Bali, mendirikan sanggar lukis di Campuan, sebelah barat Desa Ubud. Bersama Walter Spies, Tjokorde Gde Agung Sukawati, I Gusti Nyoman Lempad, mereka membentuk Pita Maha, organisasi seni lukis pertama di Bali pada tahun 1935. Perkumpulan inilah yang mengadakan pembaruan khas pada irama seni lukis Bali. Bonnet mencoba menerapkan realisme Barat pada dataran kelayakan seni lukis klasik Bali. Bonnet menyatu dengan orang Bali, ia senang dipanggil Made Bonnet, dan ia merasa sah jadi orang Bali, walaupun tetap Belanda. Di hadapan pelukis Ubud - temannya, muridnya - ia berikrar, ingin mati di Bali. Tahun 1937 Bonnet meninggalkan Bali. Tetapi setahun kemudian ia balik lagi. Ketika meletus Perang Dunia II, Bonnet ditawan di Makassar. Selesai ditawan. ia kembali ke Bali. Tahun 1958, ketika hubungan Indonesia-Belanda menggawat, Bonnet terpaksa pulang ke negerinya. Tetapi 1972, datang lagi ke Bali. Tahun 1978, ia pulang lagi menengok keluarganya. Kali ini ia tidak sempat kembali. Ia meninggal di Laren, 18 April 1978, meninggalkan surat wasiat: abunya harap dikirimkan ke dan diupacarai adat Bali. Walaupun Bonnet bukan pemeluk Hindu, kasus ini bukan persoalan pelik. Jasa Bonnet selama di Bali - mendirikan Pita Maha, mendirikan Yayasan Ratna Warta yang mengelola Museum Puri Lukisan Ubud (1956), hingga ia memperoleh piagam seni Dharma Kusuma dari Pemda Bali (1977) - cukup mengesahkan abu Bonnet untuk diupacarai diBali. Masalahnya kembali ke salah satu syarat ngaben itu: Bonnet harus dicarikan desa adat, di pekuburan mana jenazahnya (dalam hal ini abunya) diupacarai, dan sebagainya. Karena itu, abu Bonnet tak bisa diupacarai tersendiri. Jalan mengantarkan keinginan Bonnet terbuka ketika kawan seperjuangannya, Tjokorde Gde Agung Sukawati meninggal dunia, dan jenazahnya dibakar 31 Januari 1979. Abu Bonnet didomplengkan dalam upacara ngaben ini. Jika Tjokorde Sukawati memakai petulangan lembu, Bonnet memakai petulangan singa. Tidak jelas, apa pertimbangan masyarakat Ubud membuatkan singa itu. Kemungkinan, supaya lain dengan Tjokorde Sukawati. Juga, barangkali, Bonnet dianggap sejajar dengan pepatih kalau Tjokorde Sukawati dianggap simbol raja Ubud. Bonnet memang dicintai masyarakat Ubud. * * * Ngaben bisa jadi petunjuk apakah seseorang dicintai dan dihargai di masyarakat. Apakah orang itu, ketika masih hidup, rajin dalam segala kegiatan sosial di desanya. Terutama sekali, apakah orang itu, semasa hidup, suka melayat jika ada warga desa yang meninggal dunia. Kalau malas, maka warga akan menghukumnya. Hukuman itu dijatuhkan pada saat jenazah si orang malas itu diupacarai. Dengan demikian, yang paling merasakan hukuman itu adalah keluarganya. Seorang tokoh pendidikan yang cukup beken di kalangan pemerintahan, mengadakan upacara ngaben tahun lalu di Denpasar. Tokoh ini dikenal malas di desanya, dengan berbagai dalih, antara lain, sibuk, rumah dinasnya bukan di desanya lagi. Tetapi keluarganya yang lain, yang rumahnya masih di desa, juga malas. Ketika mereka mengadakan upacara ngaben, masyarakat memang datang bergotongroyong membantunya. Bagi orang Bali, gotongroyong yang berkaitan dengan kematian ini hampir-hampir suatu kewajiban. Hukuman dijatuhkan pada saat palebon, ketika lembu diarak ke pekuburan. Lembu itu diusung hilir-mudik, tidak mengikuti rute semestinya: dibawa ke depan gedung bioskop, ditaruh sebentar, dan pengusungnya berteriak: "Supaya bisa menonton film sebentar." Juga, dibawa ke alun-alun, dan sebagai alasannya disebut bahwa lembu perlu makan rumput. Lucu, tapi menyedihkan. Memang, hilirmudiknya lembu itu tidak sampai menodai upacara, dan menyalahi agama. Sebab, ketika dibawa ke pekuburan lembu itu belum berfungsi perutnya masih kosong. Jenazah masih berada di bade. Kasus yang menggemparkan, dan karena itu aparat pemerintah turun tangan, terjadi di Desa Mas, 1982. Warga desa adat itu pecah karena sesuatu hal. Sekelompok kepala keluarga dipecat dan dikeluarkan dari desa adat. Pada saat seorang dari kelompok ini mengadakan upacara ngaben, keributan terjadi. Yakni ketika iringan bade dan lembu dibawa ke pekuburan. Begitu sampai di pekuburan, sekelompok yang lain (yang setuju dengan pemecatan) mengusung lagi bade dan lembu itu ke luar dari kubur. Alasannya, jenazah tidak berhak memakai tanah kuburan adat karena sudah dipecat dari desa adat. Persoalan didamaikan berhari-hari, dan upacara jadi tertunda. * * * Apa yang akan terjadi dengan Pulau Bali di tahun 2000 nanti ? Apakah orang akan menempuh cara yang lebih praktis, cara yang melambangkan kemajuan zaman modern? Memasukkan jenazah ke krematorium yang beraliran listrik jutaan watt, kemudian baru abunya diupacarai dengan mengundang hanya tetangga dekat. Kini, bagaimanapun perubahan ngaben sudah tersirat. Misalnya, bila ada ngaben pegawai PLN kini sibuk: memutus kawat-kawat listrik di pinggir jalan tempat arak-arakan ngaben lewat. Tapi sadarkah orang-orang Bali tentang ini? Rupanya, tidak. Kecemasan kehilangan ngaben sulit ditemukan di wajah-wajah mereka yang berkeringat kepanasan kobaran api, 3 Agustus lalu itu. Tidak, kecemasan seperti itu tak ada. Setidaknya menurut "analisa" tokoh-tokoh keagamaan, misalnya I Gusti Ketut Kaler. Atau, yang disimpulkan oleh Ida Bagus Sudartha dari Gianyar (Bali Timur). Atau, tecermin dari ucapan I Wayan Nesa Wisuandha dari Pujungan (Bali Tengah/Utara). "Ngaben dengan segala kemeriahannya itu tak akan hilang selama orang Bali tidak menjadi miskin semua," kata Ketut Kaler. Ida Bagus Sudartha bahkan lebih optimistis lagi, melihat "perkembangan ngaben" masa datang. "Untuk apa bekerja keras, menumpuk kekayaan, kalau tidak untuk membahagiakan leluhur dan mendidik anak," katanya. I Wayan Nesa, yang membuat "revolusi ngaben" di Pujungan dengan hemat, bahkan sudah berkaul akan membuat upacara ngaben besar yang meriah kalau kebun cengkehnya sudah menghasil-kan. "Ngaben hemat yang dulu itu 'kan karena situasi ekonomi, bukan karena kemajuan zaman atau kemerosotan agama." kata Wayan Nesa, ulama yang disegani di desanya, yang punya kegemaran ngebrik. Tampaknya, selama "manusia Bali" masih percaya punya utang kepada leluhurnya, berupa kewajiban ngaben masih berkeyakinan bahwa upacara ngaben harus sampai menjadi "beban" memang akan masih ditemui upacara-upacara yang meriah itu nantinya. Lagi pula, biaya yang besar, seberapa besarkah sebenarnya? Menurut ukuran Jakarta - pada kelas-kelas tertentu - biaya ngaben tidak sebesar yang diduga. Bisa jadi sangat kecil dibandingkan upacara perkawinan yang diadakan para pengusaha atau pejabat tertentu. Meriah, memang. Karena upacara ngaben itu mampu menggerakkan lingkungan sekitarnya untuk bergotong-royong tanpa imbalan apa-apa, kecuali makan-minum. Bagi warga desa adat, hal itu sudah merupakan kewajiban. Maha Sabha Parisadha Hindu Dharma Pusat, bahkan, November 1964, menghimpun dan kemudian menetapkan menjadi salah satu keputusan, tentang keterikatan desa adat jika ada seseorang yang menyelenggarakan upacara ngaben. Warga desa adat patut menyumbangkan tenaga - mulai dari upacara memandikan jenazah, menyucikan jenazah, pembakaran jenazah, menghanyutkan abu jenazah, dan menerima tamu pada waktu serangkaian upacara itu. Bila rangkaian upacara itu berlangsung lebih dari tujuh hari, warga desa adat patut memberikan sumbangan yang terdiri dari - dan bisa dipilih beras, uang, bambu, kayu api, kain putih, kelapa. Kalau upacaranya bertingkat nista, "tuan rumah" boleh hanya memberikan rokok dan sirih untuk warga yang membantu ini. Kalau upacaranya madya, apalagi utama, "tuan rumah" wajib menghidangkan makanan untuk warga desa adat yang datang. Bahwa, ketentuan dan peraturan ini sampai tertulis, orang Bali mungkin banyak tak tahu. Tapi semangat bergotong-royong dan semangat "ikut memiliki upacara" sebenarnya sudah mendarah daging, dan belum luntur sampai hari ini. Kalau disebuah desa ada orang ngaben, yang disebut tamu adalah warga desa lain. Karena itu, kalau saja tingkat ngaben sudah di tetapkan, madya atau utama, apa pun yang terjadi, upacara pasti meriah. Bagaimana tidak meriah, seluruh desa menjadi "tuan rumah", mereka menyumbangkan apa saja yang perlu. Sekehe gong menyumbangkan bunyian gratis. Sekehe legong menarikan tarian tanpa dibayar. Kalau di desa itu ada seorang dalang, tanpa ada basa-basi, ki dalang sudah siap mendalang tanpa ada alasan macam-macam. Bagi yang tidak menaati "semangat gotongroyong" ini, risikonya adalah - tidak selalu begitu - seperti yang dialami tokoh pendidikan itu, ketika ia ngaben, dipermalukan. Jiwa dan semangat seperti inilah yang membuat upacara ngaben yang begitu meriah sesungguhnya tidak sampai menelan berpuluh-puluh juta. Semangat itu tetap kuat karena hampir semua orang Bali berpendapat: "Toh lain kali kita akan ngaben juga." "Kemegahan ngaben hanya pudar jika terjadi kemerosotan dalam kehidupan beragama," kata I Gusti Ketut Kaler dengan mata menerawang. Ya, kalau memang begitu bukan saja ngaben. Mungkin, kepudaran yang lebih luas lagi: kepudaran Bali itu sendiri. BOKS I GLOSARI NGABEN a sambutan = tiga bulan pawukon Bali atau 105 hari atma = roh bade = menara untuk mengusung jenazah ke kuburan bendesa adat = pimpinan desa adat bhuwana agung = alam semesta bhuwana alit = tubuh manusia bulan tilem = bulan mati depa = ukuran panjang rentangan tangan desa adat = sebuah desa yang punya Tri Kahyangan tersendiri, tidak harus sama dengan kelurahan tewasa = hari baik untuk upacara gong baleganjur = seperangkat gong yang ditabuh sambil berjalan. tidak memakai gender jaba = orang kebanyakan, bukan bangsawan kama bang = khromosom wanita kama putih = khromosom lelaki lek kaciwa semu = gengsi-gengsian lingga = ujung sebuah bade matya = tingkat menengah mahs saba = kongres mantra = puja-puja pendeta manuk dewata = burung kesayangan Tuhan ndas keleng, demitne . . . = busyet, pelitnya keterlaluan, tidak tega memberi warga banjar sebungkus nasi nista = paling rendah palebon = hari puncak upacara ngaben panca maha bhuta = lima unsur dalam alam raya, yang terdiri dari: pertiwi (tanah), apah (zat cair), teja (zat panas), bayu (udara), akasa (angkasa) panca yadnya = lima bentuk pengorbanan suci bagi umat Hindu, yang terdiri dari: Dewa Yadnya (persembahan kepada Tuhan), Pitra Yadnya (kepada leluhur), Manusa Yadnya (kepada manusia: misalnya potong gigi), Rsi Yadnya (kepada Resi yang menurunkan agama), Bhuta Yadnya (makhluk yang tidak kelihatan yang memelihara keseimbangan alam) rurub kajang = kain putih panjang yang menghubungkan jenazah di bade dengan keluarga jenazah di bawah sekehe = perkumpulan sulinggih = ulama Hindu tumpang = tingkat-tingkat dalam bade, diukur dari tempat jenazah tratag = tangga untuk menurunkan jenazah dan bade yang tinggi tri kahyangan = tiga pura yang harus dimiliki desa adat yakni Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem utama = tingkat tinggi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini