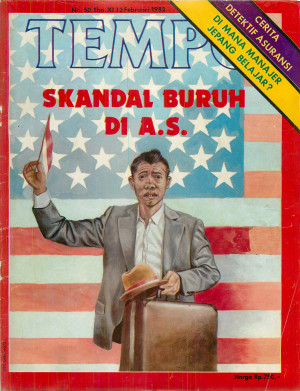ALI Bhutto, presiden Pakistan yang dihukum bunuh itu, pernah
melakukan tindakan yang sepintas lalu unik. Yakni meminta
kembali intan : Koh-i-Noor, yang kini jadi per mata utama
mahkota Ratu Inggris. Tapi itu hanya satu contoh tuntutan serupa
dari banyak negeri berkembang, yang makin gencar menuntut
warisan budaya mereka kepada negeri-negeri bekas penjajah.
Majalah South edisi Januari kemarin memuat berbagai kasus dan
perbincangan hukum mengenai masalah ini.
Asantahene dari Ghana misalnya. Ia juga menggugat Inggris--untuk
benda-benda kebesaran Asante yang telah diboyongnya dahulu.
Benda-benda itu menurut keyakinan rakyat Ghana sungguh keramat,
mengandung "jiwa bangsa". Terhadap permintaan itu, seorang
anggota Majelis Tinggi Inggris bertanya: "Tidakkah mungkin
Tuan-tuan membiarkan barang-barang itu tapi mengembalikan 'jiwa
penghuninya'?" Pertanyaan yang khas. Dr. de Silva, direktur
museum-museum Sri Langka, dalam pada itu menunjukkan daftar
benda milik negerinya yang kini menghuni banyak museum luar
negeri. Sebagian, yakni semua yang ada di Inggris, sudah
dimintanya kembali. Namu permintaan itu hampir pasti akan
ditolak hingga de Silva memusatkan usahanya hanya pada satu
benda yang punya nilai khusus bagi Sri Lanka. Yakni sebuah
Patung perunggu. Tara, patungabad X yang unik itu, kini ada di
British Museum, London. Motif permintaan ketiga negeri itu
mungkin berbeda. Namun ketiganya mewakili suara tunggal Dunia
Ketiga yang makin lama makin menyadari kehilangan mereka dan
majalah itu kini tercantum dalam agenda Unesco, terkoordinasi
di bawah sebuah komite khusus. Komite yang bernama panjang ini,
The Intergovernmental Committee for Promoting the Return of
Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution
in Case of Illicit A ppropriation (Panitia Antar-negara untuk
Menggalakkan Pengembalian Milik Budaya ke Negara Asal, dan
seterusnya), membuktikan kesepakatan antara para anggotanya di
satu pihak dan hasrat Unesco di pihak lain untuk meredakan
suasana. Paling tidak untuk menyalurkan tuduhan dan lengkingan
ke dalam bahasa diplomasi yang "lebih bersahabat."
Hasil panitia pada tahun pertama tercapai di bidang propaganda
umum. Masyarakat Barat kini, untuk pertama kalinya, jadi sadar
akan kerugian budaya besar-besaran yang diderita negeri bekas
jaiahan mereka. Pengertian mereka akan pantasnya tuntutan itu
jadi semakin baik.
Semula tanggapan atas permintaan Dunia Ketiga memang tidak
menggembirakan. Karena takut milik mereka akan ludas-tandas,
para penjaga barang berharga di Eropa dan Amerika itu bersikap
menantang. Ibarat raksasa penjaga bulu domba emas, mereka malah
melingkarkan ekor melindungi harta karun yang tersimpan dalam
museum-museum mereka.
Karenanya, dengan tujuan meredakan kecemasan tersebut, Direktur
Jenderal Unesco, Amadou M'Bow, menghimbau agar museum dan
lembaga sejenis di Barat "berbaik hati membagi benda simpanannya
dengan negara-negara yang menciptakannya, yang terkadang tak
lagi memiliki satu contoh sekalipun . . . Paling sedikit
memberikan sebuah benda dan mengembalikannya ke negara aslinya."
Bahkan pada sebuah simposium tentang 'Warisan yang Hilang' di
London, permulaan tahun ini, M. Salah Stetie, ketua panitia
antar-pemerintah itu, dengan lebih terperinci merumuskan jenis
benda yang menjadi pokok asuhan panitianya. "Tentu saja kami
tidak mengatakan semua benda budaya harus dikembalikan. Itu
tidak realistis. Kami hanya bicara soal benda-benda yang punya
arti asasi bagi tradisi suatu negara Hanya beberapa antara
beribu-ribu benda di museum Dunia Barat."
Sebagai contoh, disebutnya tiga kitab Quran tertua yang kini
semuanya berada di negara bukan-Islam. Juga karya unggul seni
Benin, yang tak sebuah pun tinggal di Benin sendiri. Para
penuntut, ketua itu menandaskan, sebenarnya bukan bermaksud
mempersulit negara yang kini menyimpannya. Pun bukan semata
tercekam kedongkolan masa lampau. Katanya, bagai berkhutbah,
"Negara-negara ini mencoba memastikan suatu identitas politik
dan bangsa setelah bertahun-tahun menjadi jajahan. Bendaseni dan
artifak adalah bukti nyata dari identitas budaya mereka itu,
kesaksian bagi masa lampau dan jaminan untuk masa depan. Demi
membangun dunia yang lebih adil, kita harus mencoba meluruskan
ketidakseimbangan ini."
Dalam praktek, tuntutan pengembalian seluruh harta budaya memang
lalu bergeser menjadi permintaan akan beberapa benda khusus
saja. Dan ini memudahkan kerjasama. Hanya saja, keruwetan yang
timbul ternyata bukan hanya antara negeri pemilik asli dengan si
bekas penjajah. Melainkan juga bisa antar-negeri Dunia ketiga
sendiri.
Ambil contoh intan Koh-i-Noor, yang tersohor di antara semua
harta budaya. Benda itu bukan saja diperebutkan India dan
Pakistan. Tapi juga Iran dan Afghanistan. Malah ratna itu konon
bukan dirampas, melainkan "dihadiahkan" kepada Ratu Victoria,
kemudian menjadi dasar tradisi negara terakhir tempat ia
bermukim. Statusnya dianggap berbeda dengan tandakebesaran adat
Asanle, yang benar-benar harta rampasan ekspedisi militer
Inggris ke Kumasi 1874.
Kontroversi seperti itu lantas dijadikan bahan oleh negara
pemilik terakhir untuk, betapapun, mengaburkan masalah. Mereka
misalnya bilang asal benda kurang jelas. Atau cara memperolehnya
sah. Andai sebagiannya benar, toh mereka masih berkeberatan
melepaskan yang lain.
Keberatan Dunia Barat yang lebih nyata adalah kurangnya
peralatan museum yang sesuai, dan staf terdidik, di banyak
negara Dunia Ketiga dan ini harus diakui."Kami ini sudah bisa
dipercaya. Kami mengenal benda-benda ini, dan punya ahli-ahli,"
demikian Wilson dari British Museum.
Namun Dunia Ketiga bisa saja menuding: kekurangan itu justru
akibat infrastruktur miskin selama penjajahan. Pengumpulan dan
perawatan benda-benda budaya di negeri asalnya menjadi tidak
mungkin, dan inilah sebagian dari keseluruhan utang pihak
penjajah.
Tentu saja Dunia Barat agak berbeda menafsirkan utang itu.
Menurut mereka, negara-negara penuntutlah yang berutang pada
negara-negara Barat yang selama itu berjasa sebagai "wali
pelindung" harta tak ternilai itu. Kalau tidak, pastilah
benda-benda itu sudah lenyap karena tidak terpelihara, akibat
pergolakan dan revolusi--dan kebodohan. Namun, seramah-ramah
wali, bukankah tugasnya akan berakhir bila orang yang
ditanggungnya meningkat dewasa, dan menuntut warisan mereka
sendiri?
Lagi pula soal "perwal ian " ini bisa memperoleh wajah yang
berbeda. "Kalau British Museum hendak dirusakkan dengan
mengambil benda-benda di dalamnya, itu sama buruknya dengan
meledakkan Parthenon," ucap direktur museum itu. Padahal, lebih
banyak benda pualam Elgin yang tersohor itu hancur berantakan
ketika mereka angkut dari Parthenon --atau hilang di dasar laut
dalam perjalanan ke Inggris-- daripada yangakhirnya sampai ke
British Museum.
Museum Dunia Barat tampaknya menemukan perlindungan teraman di
belakang undang-undang negeri masing-masing. Undang-undang
nasional di banyak negara memang secara tegas melarang
pemindahan barang apa pun yang tcrsimpan dalam museum. Tapi, di
segi lain, berbagai konvensi dan perseujuan internasional yang
dirumuskan di Eropa abad ini tegas-tegas menuntut pengembalian
benda budaya yang terampas di masa perang. Termasuk benda-benda
tambahan yang diperoleh dengan "cara yang tampak sah" atau
"disahkan." Dalam kategori terakhir ilu malah bisa masuk pcrmata
Koh-i-Noor.
Di sinilah justru Dunia Barat terjerat dalam suatu dilema yang
menyiksa hati. Andai pihaknya menyetujui prinsip pengembalian
itu sesuai dengan kode moral dan etiknya sendiri, yang mula-mula
mereka pakai di antara sesama bangsa Eropa, mereka juga harus
mengakui bahwa pada dasarnya benda-benda itu diperoleh dengan
cara gelap. Dan ini betapapun menuniukkan segi hitam dari "tugas
membudayakan bangsa-bangsa" yang diemban Eropa.
HARI-HARI kolonialisme barulah satu generasi di belakang kita.
Belum lama. Toh, sementara dari kita sendiri banyak sekali orang
yang sudah "lupa", bagi Eropa rupanya diperlukan waktu lebih
lama lagi untuk menulis kembali sejarah penjajahan--dari sudut
yang lain dari yang selama ini mereka ambil dan cekokkan ke
bekas negeri-negeri jajahan sendiri.
Sementara itu memang diperlukan banyak persiapan, sebelum benda
budaya memulai perjalanan pulang. Bantuan teknik untuk
menciptakan infrastruktur museum, serta latihan para pegawainya,
sudah dimulai oleh Unesco. Sudah dirintis pula peminjaman jangka
panjang benda-benda dan koleksi-koleksi khusus, yang bisa
diperpanjang lagi tanpa batas waktu dan tanpa kemungkinan
diminta kembali. Namun ini sempat mencetuskan kemarahan, Karena
langgap memahayakan prinsip restitusi. Di samping itu di Dunia
Barat sendiri undang-undang sedang disesuaikan, supaya bisa
memungkinkan pertukaran benda budaya secara bilateral. Jadi
orang boleh bersabar.
Tapi agar panitia Salah Stetie bisa berhasil, sebagi landasan,
para anggota dianjurkan menandatangani dan memperkuat
persetujuan 1970--yang melarang ekspor gelap benda antik dari
negara peserta konvensi. Sebab, sebagai alasan tidak mau
mengembalikan artifak, negara Barat memang sering mengemukakan
bahwa sejumlah besar benda budaya masih senantiasa
mengalir--secara gelap--dari Dunia Ketiga sendiri. Diperkirakan
dari India saja, misalnya, keluar sekitar 50.000 benda dalam
hanya satu dasawarsa lampau. Dan negara-negara Baratlah yang
menyediakan pasaran untuk benda-benda selundupan itu. Dan mereka
pula yang masih perlu membubuhkan tanda tangan pada persetujuan
tersebut.
Adakah pengembalian harta budaya merupakan suatu senjata
politik? Tidak, sebenarnya. Atau belum. Tapi Irak pernah
mencobanya. Ketika seorang utusan Prancis datang menanyakan
minyak, ia dibalas dengan tuntutan agar Codex Hammurabi
dikembalikan!
Bayangkan, alangkah seru jika Nigeria membatalkan impor buku
dari Inggris karena negeri itu tidak mengembalikan benda-benda
perunggu asal Benin. Atau seandainya Arab Saudi dengan sopan
minta salah satu saja dari tiga kitab Qur'an di "rantau" itu,
sebagai ganti minyaknya.
Keyakinan bahwa ada kewajiban mengembalikan milik budaya yang
diambil atau dirampas sewaktu perang, sebenarnya bukan hal baru.
Bukan pula ciptaan Dunia Ketiga.
Konsep itu, seperti sudah disebut, berasal dari peradaban Eropa
sendiri -- dari Yunani kuno--yang mencuat kembali 2000 tahun
kemudian. Kini etik tersebut tertera dalam hukum internasional,
kendati anehnya sering bertentangan dengan undang-undang negara
masing-masing.
Lembaga seperti British Museum, misalnya berlindung di bawah
undang-undang British Museum 1963. Museum Louvre di Prancis pun
dipelindungi secara itu. Padahal konsep restitusi, yang
jelas-jelas diletakkan dalam hukum kasus di Inggris, justru
lebih-tua dan lebih luas jangkauannya daripada undang-undang
British Museum misalnya.
Bukti pertama tentang pengembalian benda budaya dalam sejarah,
diberitakan oleh sejarawan Yunani kuno Polybius. Kasus yang
dikisahkannya bahkan menarik karena berkaitan dengan
kolonialisme--sehingga langsung dapat dibandingkan dengan
keadaan sekarang.
Terjadi di zaman Kerajaan Romawi, sekitar 2000 tahun lalu. Dalam
kasus paling tersohor itu, In Verrem Cicero, ahli pidato dan
ahli hukum, Romawi menggugat gubernur Sisilia yang waktu itu
jajahan Romawi. Ia menuduh gubernur itu merampasi berbagai
gedung umum dan kuil di Sisilia untuk koleksi pribadi. Di situ
Cicero membandingkan keserakahan pejabat tersebut dengan
kebijaksanaan jenderal Romawi, Scipio, yang pernah menaklukkan
Kerajaan Karthago di Afrika Utara. Karthago sendiri sebelumnya
pernah menjajah Sisilia.
Kata Cicero: "Karena tahu bahwa Sisilia sering dan
berlarut-larut menanggung perampasan bangsa Karthago, maka
Scipio mengumpulkan semua penduduk Sisilia. Ia memerintahkan
mereka meneliti apa saja yang dirampas dari harta mereka (oleh
Karthago), dan ia berjanji akan mengembalikan pada setiap kota,
milik yang ditemukannya." Sehadi hasil usaha Cicero melawan
Gubernur Verres tadi lengkap dengan perbandingannya dengan
tindakan Scipio terhadap Karthago--maka Senat Romawi akhirnya
memutuskan denda 45 juta sesterce yang harus dibayar sang
gubernur, khususnya sebagai ganti rugi perampasan itu.
Itulah hikmah kebijaksanaan kuno. Tetapi baru pada abad XIX
secara resmi dibuat suatu persetujuan internasional tentang
pengembalian harta budaya. Hanya saja, mungkin karena dirumuskan
di masa puncak ekspansi imperialisme, persetujuan itu hanya
berlaku untuk daerah perang Eropa. Bukan dalam hubungan dengan
negeri jajahan di Timur. Sialan, memang.
Contohnya: ketika Napoleon ambruk, negara-negara pemenang lantas
memaksa pemerintah Prancis mengembalikan banyak rampasan benda
seni--meskipun diperoleh sebagai "hasil persetujuan" dengan
Napoleon Sebab, dengarlah ucapan Lord Castlereagh selama
perundingan perdamaian di Kongres Wina 1815. Wakil Inggris itu
merumuskan: "Rupanya tidak bisa ditempuh jalan tengah tanpa
membedakan berbagai jenis perampasan yang diselubungi
perjanjian, yang mungkin lebih menyolok sifatnya dari tindakan
perampasan tanpa malu. Prinsip milik yang dikendalikan oleh
tuntutan daerah tempat milik itu dirampas, adalah satu-satunya
petunjuk keadilan yang paling tepat."
Dengan itu harta Eropa dikembalikan ke pemiliknya. Tapi
benda-benda Mesir yang disita dari Prancis oleh Inggris, tahun
1801, masih menghiasi British Museum sampai kini.
Di samping itu, pada paruh kedua abad lalu, ide menghargai benda
budaya pihak laan sebenarnya sudah cukup berakar dalam
pemikiran hukum. Maka jadilah ia bagian tak terpisahkan dari
Deklarasi Brussel 1874 tentang 'Kebiasaan dalam Perang'.
Deklarasi ini ditandatangani 15 wakil negara Eropa, termasuk
Jerman, Belgia, Spanyol, Prancis, Inggris dan Turki. Dalam
naskah itu "penghimpunan barang rampasan" dilarang secara resmi.
Juga dianggap perlu diselamatkan, sejauh mungkin, gedung-gedung
bersifat agama, seni, ilmu atau sosial. Dinyatakan pula, "Semua
pendudukan atau penghancuran, maupun pengrusakan secara sengaja
atas gedung bersejarah, karya seni dan ilmu, harus dituntut di
muka pengadilan berwenang."
Deklarasi Brussel itu menggambarkan kesepakatan ahli hukum
internasional - bahwa semua fasilitas budaya, ilmu serta karya
seni harus dihormati dalam suatu sengketa militer. Memang masih
dibedakan antara i'milik masyarakat yang berhak disita oleh
pihak pemenang " dan "milik pribadi yang bebas" dari hak
penyitaan itu. Tapi deklarasi tersebut menyatakan bahwa hak
penyitaan tidak berlaku untuk benda seni, ilmu, pengetahuan
alam, perpustakaan atau arsip negara. Semua itu harus
diperlakukan sebagai milik pribadi. Tak boleh diboyong.
Dan prinsip-prinsip itulah yang dituangkan dalam 'Konvensi
tentang Hukum dan Kebiasaan dalam Perang di Daratan', tahun 1899
dan 1907 di Den Haag. Diputuskan: harta milik lembaga, agama,
sosial dan pendidikan, serta benda seni dan ilmu, "harus
diperlakukan sebagai milik pribadi." Dan perlindungan milik
budaya di waktu perang itu juga menjadi pokok pembicaraan pada
konvensi khusus di Den Haag, 1954, dengan kesimpulan yang sama.
Tapi di tahun 1874 itu sendiri, Inggris menyerang Kumasi. Dan
1897 menyerang Benin. Keduanya berupa "ekspedisi
penghukuman"--termasuk perampasan dan perampokan besar-besaran.
Dua peristiwa itu menjadi bukti tercela tentang penerapan
standar arad ke-19 perihal kelakuan dalam perang.
Dan bila ditanya tentang soal Asante, para pejabat Inggris tetap
bersedia bertengkar. Kata mereka, regalia emas yang diambil dari
koleksi negara di Kumasi itu diperoleh secara sah sebagai ganti
rugi. Padahal, meski sementara bangsa Asante memang membayar
ganti rugi kepada orang Inggris, berupa perhiasan emas dan
serbuk emas, tidak lah masuk akal bahwa mereka akan mau
mengorbankan benda-benda adat seperti pedang upacara, harta
kerajaan dan topeng emas untuk itu.
Bahkan penyelidikan kemudian tentdng ekspedisi itu menunjukkan,
perampasan koleksi Asante dijalankan sebagai bagian kampanye
militer sebelum ganti rugi untuk berdamai diumumkan. Perampasan
inilah juga contoh menyolok dari perampokan "dengan tedeng
perjanjian", seperti pernah dikecam Castlereagh setengah abad
sebelumnya. Harta pusaka Kotd Benin, termasuk topeng-topeng
gading, piagam perunggu, patung-patung dan lain-lain, semua
diangkut dalam ekspedisi militer tersebut.
Kini, apa yang dihadapi Komite Inesco sebenarnya berasal dari
suatu seri resolusi yang dicetuskan dalam forum internasional -
dan mulai di PBB tahun 1973. Dalam pidatonya di PBB tahun itu,
Presiden Mobutu Sese Seko menghimbau Sidang Umum, untuk
menyokong resolusi yang minta agar negara kaya yang mempunyai
barang seni negara miskin mau mengembalikan sebagiannya--"supaya
kami bisa mengajar sejarah negeri kami pada anak-anak kami."
"Benda-benda itu," katanya, "bukanlah bagian dari bahan mentah
kami. Melainkan hasil ciptaan nenek moyang kami." Ia menyesalkan
pemindahan-besar-besaran benda seni itu, "hampir tanpa
bayaran", sering sebagai hasil pendudukan kolonial atau bangsa
asing. Resolusi itu menyerukan pengembalian "tanpa
biaya"--sebagai cara mempererat kerja sama internasional.
Termasuk ke dalamnya "reparasi untuk kerusakan yang terjadi".
Beberapa resolusi serupa juga diajukan oleh Konferensi Umum
Unesco, Dewan Internasional Museum (Icom) dan Konerensi
Bangsa-bangsa Non-Blok.
Seyogyanya Presiden Mobutu bisa mengutip suatu kejadian
sebelumnya di PBB, untuk menunjang seruannya. Pasal ini bisa
dipakai untuk bidang tak tertentu--berupa benda apa saja yang
dipindahkan di masa pendudukan kolonial, di luar rumusan tentang
rampasan perang. Tanggal 5 Januari 1943, pada puncak Perang
Dunia II, sebuah deklarasi diumumkan bersamaan di London, Moskow
dan Washington oleh negara-negara Sekutu.
Isinya: anjuran kepada PBB untuk "meniadakan hak melakukan
pemindahan atau pengangkutan barang-barang apa pun yang berada
atau pernahberada di daerah pendudukan atau daerah yang secara
langsung maupun tak langsung berada di bawah pengawasan
pemerintah pihak lawan. Ataupun barang yang menjadi milik
pribadi di daerah tersebut . . . Juga bila pemindahan itu bukan
berupa perampasan nyata melainkan transaksi yang kelihatan sah
dan seakan tanpa paksaan."
Perkara pemilikan konon merupakan sembilan persepuluh dari
seluruh isi hukum. Toh perimbangan kekuasaan masih memenangkan
Dunia Barat. Hanya sedikit kisah kerja sama yang berhasil dalam
pemulangan artifak budaya. Sebuah, sebagai contoh, adalah saling
bantu antara Belgia dan Zaire.
Negeri terakhir itu dahulu bernama Kongo Belgia. Belgia sama
sekali bukan negara penjajah besar: satu-satunya jajahan ya
Kongo itulah. Pun dalam kenyataan, Belgia lebih akrab dan
bersahabat dalam seni dan sejarah, dibanding kebanyakan negara
penjajah.
Museum-museum Zaire sendiri menderita kerusakan cukup hebat
dalam masa pergolakan setelah kemerdekaan. Ini berarti
pertengkaran antara bangsa sendiri. Karena itu dibutuhkan suatu
pembenahan budaya. Namun baru setelah sepuluh tahun rembukan
gigih persetujuan Zaire-Belgia bisa ditelurkan 1970.
Tujuan utama: menyediakan ahliahli ilmu dan teknik Belgia untuk
membantu menyusun suatu jaringan museum, dan menata perpindahan
koleksi etnografi dan seni. Sebab, harusdiingat, pemeliharaan
sebuah museum di samping memerlukan tenaga-tenaga. Ahli juga
bukan main mahal--kalau memang mau serius. Dan itulah memang
segi positif penyimpanan barang-barang purba tersebut di negeri
Barat.
PARA kurator Belgia kemudian dipekerjakan di Institut Musees
Nationaux du Zaire (IMNZ). Program membangun koleksi itu
memadukan restorasi benda dari Brussel dengan pengumpulan dan
pendaftaran benda yang masih banyak bertebaran di Zaire sendiri.
Juga sejauh mungkin menghapuskan ekspor gelap artifak budaya.
Rencana ini sangat berhasil. Kini, koleksi di IMNZ jauh
melampaui koleksi museum Belgia sendiri--baik dalam ruang
lingkup maupun kualitas barangnya.
Ada kalanya pihak Belgia memang berkeras: "kualitas dan hasil
pilihan" koleksi mereka tidak boleh terjamah. Toh dikembalikan
juga akhirnya dua ratus benda dari periode dan cabang seni.
IMNZ sendiri lebih dari sekedar pameran barang seni. Tujuannya
memberi gambaran selengkapnya tentang perkembangan sejarah dan
masyarakat Zaire. Sampai kini,1000 contoh alat, senjata dan
benda rumah tangga telah dikembalikan. Sedang biaya pengangkutan
ditanggung pihak Belgia.
Pengalaman Belgia-Zaire ini, meski bukan tanpa
hambatan--terutama keengganan semula dari Belgia--merupakan
contoh menggembirakan. Keikhlasan pada akhirnya memang
diperlukan. Termasuk keikhlasan untuk mengmenghapus kenangan
buruk
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini