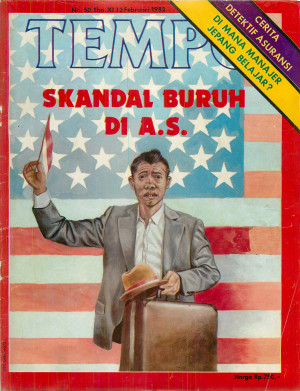KETIKA orang Jepang pertama kali membuat alat pemotret, mereka
lebih dulu membongkar sebuah kamera Amerika. Semua bagian
ditiru, sampai onderdil yang paling halus dan musykil. Kemudian
'penemuan' itu dikembangkan -- hingga akhirnya kamera Amerika
sendiri tersudut di pasaran. Demikian kata dongeng.
Mungkin cerita tersebutdikarang sekedar menggampangkan
penggambaran "semangat berguru" Jepang yang menggebu, terutama
sekali di lapangan perdagangan. Bertahun-tahun Jepang
mengirimkan ribuan pemudanya keberbagai sekolah dagang di
Amerika Serikat. Mereka terus terang mengaku belajar banyakdari
pengalamandan teknik manajemen sana.
Sekarang pun, berbagai perusahaan Jepang masih mengirimkan para
eksekutif yuniornya ke Amerika, terutama untuk program MBA
(Master of Business Administration). Tak ada angka yang pasti
mengenai jumlah siswa itu setiap tahun. Namun "berdasarkan
percakapan dengan sejumlah pejabat sekolah dagang AS,
pendaftaran dan penerimaan siswa Jepang di sekolah-sekolah
tersebut terus meningkat," tulis majalah Business Week.
Tapi alas yang mendorong para eksekutif muda itu meninggalkan
kampung halamannya sudah mengalami perubahan--beberapa tahun
ini. Mereka, sebenarnya, tidak lagi tertarik mempelajari
"teknik baru" untuk dipraktekkan di negeri sendiri. Mereka lebih
banyak didorong oleh kepentingan lain: berkenalan--melalui
sekolah dagang tadi--dengan para calon eksekutif dunia usaha AS,
yang akan memainkan peranan penting di masa depan.
"Mereka juga ingin mengetahui bagaimana para manajer Amerika
mengambil keputusan," kata Business Week menambahkan. "Tujuan
akhir mereka ialah menjadi saingan yang lebih kuat--baik untuk
perusdhaan AS maupun perusahaan internasional umumnya. "
KESIMPULAN itu tak dibantah Noritake Kobayar shi, direktur
sekolah dagang Universitas Keio. "Banyak perusahaan Jepang
sekarang ini mengarahkan pandangan pada operasi internasional,"
katanya. "Mereka ingin para manajernya menjalin 'budaya bisnis'
yang layak dengan para saingan di Barat."
Pembicaraan dengan sejumlah eksekutif Jepang lulusan Amerika
justru memperkuat bukti. "Saya banyak memetik pelajaran dari
Wharton," ujar Yotaro Kobayashi, sekarang Direktur Fuji Xerox
Co. "Terutama bukan dari kurikulumnya--melainkan dari kontak
perorangan." Seorang MBA lulusan Universitas Colomb ia, yang
kini bekerja d i sebuah bank Tokio, menambahkan: " Kami belajar
menjadi lebih agresif."
Edward T. Lewis, pembantu dekan Graduate School of Business,
Universitas Cornell, pernah mengajukan pertanyaan kepada
sembilan orang siswa Jepang yang sedang menempuh program MBA di
situ. Apa sebetulnya alasan mereka belajar ke Amerika?
Jawabannya berkisar di sekitar "menambah teori penunjang,
mempelajari manajemen berpikir dan bertindak cara Amerika, dan
memperlancar bahasa Inggris." Tampaknya, "mempelajari
ketrampilan manajemen AS" sudah bukan tujuan pokok.
Ini tak berarti perusahaan Jepang sama sekali tak menarik
manfaat dari teknik manajemen yang mereka pelik di berbagai
sekolah dagang AS. Tapi untuk waktu yang lama mereka tampaknya
lebih banyak ditempa praktek dagang sehari-hari.
Beberapa tahun lalu, banyak perusahaan Jepang mengirimkan tim
belajar untuk mcnekuni ketrampilan tertentu. Pulang ke kampung
halaman mereka menerangkan kepada perusahaan masing-masing
metode menerapkan ketrampilan tersebut.
Karena para eksekutif Jepang umunya menduduki masa jabatan yang
panjang, ketrampilan tadi bertahan dan tak segera hilang.
"Sepuluh tahun lalu saya mempunyai banyak siswa Jepang untuk
jurusan manajemen operasi," tutur Martin K. Starr, profesor ilmu
manajemen pada Universitas Columbia. "Mereka mempelajari analisa
kelayakan, kemudian memperkenalkar, teknik itu kepada
perusahaannya masingmasing." Kini, dari 17 siswa Jepang calon
MBA di Columbia, tak seorangpun mcngambil jurusan itu lagi.
Sebetulnya para siswa Jepang itu sendiri tak begitu suka akan
pelbagai ilmu yang harus mereka pelajari di AS. Apalagi setelah
mereka melihat praktek manajemen yang diterapkan di perusahaan
Amerika. Mereka terutama bingung melihat ketergantungan para
manajer Amerika pada permainan angka.
Seorang MBA lulusan Universitas New York, kini bekerja pada
sebuah perusahaan jasa di Tokyo, mengatakan: "Rakyat Amerika
bisa dibuat gemetar dengan sebuah kalkulasi finansial." Padahal
di Jepang, hal itu merupakan "barang biasa."
Nada yang sama diucapkan oleh Noboru Terashima, lulusan
Universitas New York yang kini bekerja pada Okasan Securities
Co. " Keputusan manajemen Amerika didasarkan pada studi
statistikal dari pelbagai kuisioner dan data," katanya Sementara
di Jepang, "keputusan diambil berdasarkan hubungan pribadi dan
perhitungan kemanusiaan." Ia kemudian seperti ngecap: "Gaya
Jepang lebih realistis."
Menurut sementara eksekutif muda Jepang ini, program MBA di
Ameriha tak begitu tahan uji. Mereka menyinggung siklus
pelajaran yang tak berubah, sementara dunia dilanda pelbagai
kejutan--misalnya krisis minyak. Temperamen dan tingkah laku
para saingan asing juga tidak bisa ditebak dan diramalkan oleh
pengetahuan yang bergayut pada perhitungan kalkulator.
Di lapangan organisasi, sebagian mereka menilai pelajaran yang
diberikan sekolah dagang Amerika "kurang manusiawi." Di sana
organisasi dibangun berdasar fungsi jabatan yang abstrak. Sedang
di Jepang, "kami membangun organisasi berdasar ketrampilan
karyawan yang sudah jelas."
Pelajaran "mengarahkan karyawan tingkat rendah" juga tidak
menarik hati para MBA Jepang. Mereka berada di tengah
lingkungan, tempat karyawan semua tingkat memandang hari depan
mereka sejalan dengan hari depan perusahaan. "Kami tak
memerlukan rayuan psikologis," ujar Yoshikazu Nakashima, MBA
lulusan Universitas Columbia yang kini bekerja pada Toyota.
Dari segi lain, ijazah MBA Amerika ternyata tak otomatis
menjanjikan kursi yang empuk. Mungkin berbeda dengan keadaan
yang dialami teman-teman Amerika mereka. Bagian personalia
perusahaan Jepang misalnya tak memberi keistimewaan apa pun
untuk para MBA itu, baik dalam hal gaji maupun tanggung jawab.
"Setelah saya pulang (dari Amerika)," tutur Noboru Terashima,
"gaji saya lebih rendah dari rekan-rekan seusia." Soalnya selama
dua tahun menuntut ilmu dia dihitung tidak bekerja. Nasib lebih
buruk menimpa seorang bankir lulusan Universitas New York.
"Menurut pikiran manajemen Jepang," katanya mengeluh, "sekolah
dagang Amerika Itu abstrak dan mubazir."
Mungkin karena itu, bebcl-apa lulusan Amerika memilih pindah
kerja saja ke perusahaan asing. Seperti yang dilakukan Kensuke
Shizunaga, MBA lulusan Universitas Columbia. Setahun setelah
pulang kampung, ia hengkang dari Trio Kenwood Corp. "Perusahaan
itu tak mempunyai strategi mendayagunakan pendidikan bisnis
saya," katanya. "Mereka mempekeriakan saya seperti kerani, tanpa
tambahan pendapatan apa pun." Ia diterima di Smith Barney,
Harris Upham & Co, Tokyo, dengan gaji dua kali lipat. "Pekerjaan
baru ini lebih menantang. Dan gelar MBA saya meniadi lebih
berharga."
Meski demikian, untuk sebagian besar orang Jepang meninggalkan
perusahaan yang telah menyeponsori program MBA mereka merupakan
tindakan ingkar yang sulit sekali bisa dipuji. Mereka
berpendapat, "memanj.lkan MBA lulusan Amerika merupakan ekses
yang sama pandirnya dengan keengganan perusahaan Jepang
memanfaatkan tenaga para MBA itu."
Karena itu mereka menyarankan semacam jalan tengah: memakai
tenaga-tenaga terpelajar itu seraya tetap mempertahankan
karyawan lama. Mereka yakin, Jepang bisa menyerap banyak dari
ketrampilan marketing Amerika. Nakdshima, dari perusahaan
Toyota, memuji kemampuan Amerika "menidentifikasikan pasar
yang potensial demi menjajaki kebutuhan yangpotensial." Mereka
juga terkesan pada "kebebasan Amerika" yang memperkenankan suatu
perusahaan menyerang saingannya secara langsung melalui iklan.
Di Jepang, perbuatan ini masih merupakan pamali.
Kenyataan ini diakui seorang manajer penjualan sebuah bank
penting di Tokyo, dengan gelar MBA untuk marketing. "Teknik
marketing Amerika lebih sistematis," katanya."Banyak salesman
Jepang cenderung mendalangi hanya langganan yang mereka sukai
Dan mereka enggan menganalisa keputusannya secara obyektif."
Manfaat "ilmu Amerika" itu juga bisa dilihat Nitake Kobayashi
dari Universitas Kcio. Ia melihat, akhir-akhir ini perusahaan
Jepang lebih terbuka menghadapi beberapa keuntungan yang bisa
dipetik dari sekolah-sekolah dagang Amerika.
Di tengah pendapat dan kesimpulan yang masih simpang-siur itu,
semangat belajar ke AS tetap tinggi di kalangan calon eksekutif
Jepang. Musim gugur tahun lalu misalnya, Bank Dai-Ichi Kangyo
menerima permohonan dari 700 karyawan untuk ksempatan belajar
di universitas mancanegara. Hanya 10 yang akhirnya terpilih.
Pilihan tidak didasarkan pada perhitungan ekonomis, melainkan
kepentingan profesi dan pengalaman calon bersangkutan. "Secara
ekonomis," kata Edward T. Lewis dari Universitas Cornell, "siswa
Jepang itu merupakan elite tersediri." Berbeda dengan
rekan-rekannya dari Amerika, "mereka menerima gaji penuh
selama menuntut ilmu."
TAPI ada pula efek sampingan dari 'kemakmuran' ini. Karena
mereka umumnya lebih mampu, dan kurang fasih berbicara Inggris,
mereka cenderung membentuk "klik" di sekitar kampus. Padahal
kecenderungan ini agak bertentangan dengan niat perusahaan
mengirim mereka.
Hanya saja orang Amerika yang sudah-kenal lama tabiat pengusaha
Jepang tak gampang terpengaruh. Menurut mereka, "tampang
canggung" para siswa Jepang itu hanyalah tindakan
pura-pura--justru dalam usaha mengumpulkan lebih banyak
informasi berharga.
"Pada dasarnya orang Jepang adalah bangsa yang sangat agresif,"
kata David Nadler, guru besar pembantu pada Universitas
Columbia, yang pernah bermukim agak lama di negeri itu. "Mereka
mempraktekkan tradisi Samurai di lapangan bisnis."
Tujuan mereka ke Amerika, sebetulnya, adalah untuk "mengenal
saingan lebih baik." Dalam bahasa Samurai, menurut David Nadler,
tujuan itu berarti "mengenal musuh lebih dekat."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini