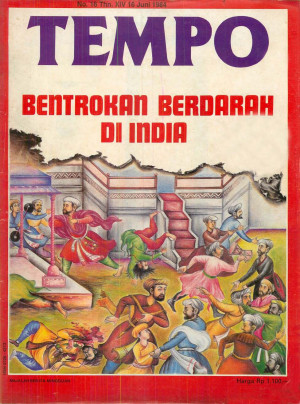DARI pesawat kecil di atas, tampak rumah-rumah beratap seng mengkilat di hantam matahari. Rumah-rumah di bawah itu berjajar dikiri-kanan lapangan terbang rumput sepanjang 800 meter. Selebihnya, yang tampak cuma kehijauan tumbuhan di lembah sempit itu. "Itulah Kecamatan Waris," kata Hanny, pilot AMA, sambil memutar turun pesawat Cessna (tepat di atas garis perbatasan RI-Papua Nugini!) menuju landasan. Waris berpenduduk 655 orang dari tiga desa di wilayah itu: Pund, Yuwainda, dan Banda. Desa yang disebut terakhir itu yang paling dekat dengan garis batas menjadi ibu kota kecamatan. Penduduk Banda 220 jiwa - dan tinggal hanya 1,8 km dari perbatasan kedua negara. "Waris memang merupakan kecamatan paling depan," kata Barnabas (Bas) Youwe, bupati Jayapura. Di Banda terdapat puskesmas (tanpa dokter), koramil dan markas sekaligus asrama untuk tim Nanggala dari Kopassandha dan dari Yon 726 Hasanuddin. Ada tiga bangunan di kompleks kosek (polsek) yang tanpa penghuni lagi. Kini dirubung ilalang setinggi pagar dan atap. Di depan bekas kosek, menyeberang air strip, berdiri kantor kecamatan dengan tiang bendera di depannya. "Bendera ini tak pernah diturunkan siang-malam," ujar T.H. Sitinjak, camat Waris, sambil menunjuk. Itulah Bendera Merah Putih satu-satunya yang ada dan berkibar di bibir wilayah RI itu. Di sudut lain, menempel di punggung bukit, ada pos imigrasi yang baru setengah tahun dibuka. "Penduduk yang mau ke seberang harus melapor ke sini. Mereka diberi pas lintas batas (border pass) tutur P. Katok Doan, kepala pos imigrasi itu. Menurut perhitungan pihak pos, setiap bulan rata-rata 40 orang dari kecamatan itu melintasi perbatasan masuk wilayah PNG. "Itu baru yang tercatat dan mendapat border pass. Puluhan orang menyeberang setiap bulannya tanpa melapor," ujar Katok Doan. Mereka, yang melapor atau yang tidak. tergolong "penyeberang tradisional", yang menuru hasil perundingan panitia penghubung (liaison officer) Jayapura-Vanimo tak perlu memakai paspor ataupun visa. Sepanjang 720 km garis batas dari utara ke selatan terdapat enam pos imigrasi khusus untuk para penyeberang jenis itu. Yakni, kecuali di Waris, di Sota, Mindiptana, Waropo, Kiwirok, dan Skouw. Dua pos lagi, untuk di Senggen dan Ubrub, sedang dipersiapkan. Pembangunan pos-pos baru ini dianggap penting, kata Bas Youwe. Soalnya, "tak mungkin orang yang mau menyeberang di Ubrub atau Senggen harus jalan berhari-hari dulu untuk mengambil pas lintas batas di Skouw, misalnya." Juga tingginya angka penyeberang gelap, yang menimbulkan soal jika mereka ditangkap polisi PNG, mengharuskan imigrasi membuka lebih banyak pos di desa-desa sepanjang garis batas. Hanya itulah alternatif - sebab untuk melarang mereka menyeberang tentu saja tak mungkin. "Penyeberang tradisional punya ikatan darah dan historis dengan suku-suku yang mendiami tanah yang sekarang masuk wilayah PNG," ujar bupati Jayapura itu. Begitu juga penduduk PNG yang melintasi perbatasan, berkunjung kepada keluarga di wilayah Irian Jaya. Yang ke Waris saja, yakni yang datang terus melapor di pos imigrasi, sebulannya 20 sampai 25 orang. "Arus pelintas batas ini akan membanjir jika ada pesta adat atau upacara kematian," kata Katok Doan, kepala pos itu. Saling kunjung penduduk Ir-Ja dan PNG itu, khusus bagi yang berdiam di desa-desa perbatasan, tak dianggap perjalanan antarnegara. Bagi rakyat di situ pengertian masuk wilayah negara lain memang kabur. "Pokoknya, jika ke keluarga di seberang harus minta izin," kata Daniel Meho, penduduk Waris yang dua kali sebulan pergi ke PNG. "Anak-anak saya semuanya di sana. Yah, tinggal di sana atau tinggal di sini sarna saja," kata Wim Mae, kepala adat di Desa Banda. Kakek delapan cucu yang semuanya warga negara PNG itu tiga kali sebulan pergi ke Pendesi, desa PNG di Provinsi Sepik Barat. Untuk sampai ke sana, Wim, 54 tahun, berjalan sembilan jam. "Pendesi tak jauh dari tugu batas. Hari ini berangkat besok bisa pulang," tutur Wim, yang lahir di Pendesi. Hampir seluruh penduduk Waris, menurut Camat, punya hubungan dengan penduduk desa-desa PNG: Pendesi, Mink, atau Imonda. "Ada yang lahir di sana, ada yang punya anak tinggal di sana, atau saudaranya di sana. Ada yang lahir di sini lantas tinggal di sana, atau kawin dengan orang sana, kemudian boyong ke sini," kata Sintinjak, camat Batak yang sudah lima tahun bertugas di Waris. Tak jarang pula pemuda Waris pacaran dengan gadis "sana" itu. Atau sebaliknya. Misalnya Moses Tawa, 25 tahun, lahir di Mink. Kemudian menjadi warga negara RI dan tinggal di Waris. Pacaran di Mink, lantas kawin dengan pacarnya di sana. Kini mereka tinggal dan berkebun di Waris. "Tinggal di sini atau di sana sama saja. Tapi di sini saya dapat rumah dari Pemerintah," kata Moses. Di Waris memang rumah-rumah penduduk dibangun dengan bantuan presiden sejak empat tahun lalu, yang sampai kini terhitung sudah 120 rumah. Kontak antarpenduduk kedua negara ini bagaimanapun membawa dampak budaya. "Orang-orang seberang bisa berbahasa Indonesia. Bahkan di antara mereka sendiri kadang digunakan bahasa kita," tutur Hendrikus Mai, bekas penduduk Pendesi yang sudah empat tahun jadi pegawai penerbangan sipil - penjaga air strip Waris, dengan golongan I C. "Punya kita yang dipakai di sana," kata D.Y. Mai, kepala desa Banda yang kelahiran Pendesi, "bukan cuma bahasa. Mereka juga kadang membawa beras, gula, kain batik, atau sarung dan garam dari sini." Menurut Pak lurah ini, di antara rakyatnya yang rutin pergi ke desa-desa seberang itu tak jarang yang berdagang. Dari sini membawa gula, garam, sarung, atau batik - yang dibeli di Jayapura - dan kembali dari sana membawa uang kina (mata uang PNG) plus sabit atau parang. Uang itu kemudian ditukar dengan rupiah pada Pater atau pilot AMA yang sekali sebulan terbang ke Waris. Kecuali tempat menukar uang, Pater dan pilot AMA biasa mereka titipi membeli barang-barang yang laku di Pendesi, di Jayapura. Kalau tidak titip, mereka harus berjalan kaki ke Jayapura dalam seminggu, melewati hutan perawan dan rawa. "Mencari untung sedikit sambil lihat televisi di Jayapura," kata Wim Mai polos. Yang dikatakan untung itu ternyata cuma Rp 100 atau Rp 200. "Tapi itu besar, buat kitorang di sini," ujar Dusylina Mai, 26 tahun, ibu dua anak, yang suka membawa gula ke Pendesi dan Mink. Dua kali sebulan melintas batas, "Sekali pergi saya bawa 10 kilo gula dan beberapa bata garam," katanya. Lahir di Mink, Lina mengaku bisa dapat untung beberapa ratus perak untuk sekilo gula yang di jualnya dengan 1 atau 1 1/2 kina (1 kina nilainya sekitar Rp 1.200, tapi dinilai Rp 900 bila ditukar di pilot atau Pater). Gula dibeli Lina di Jayapura dengan harga Rp 800. Di Waris tak ada pasar. Bahkan kios tak ada. Ternyata, bukan cuma barang-barang itu yang ditunggu-tunggu orang Pendesi. "Batu baterei, kalau kita jual, bisa laku cepat," ujar Hendrikus Mai, yang mengenakan jam tangan Citizen. Pegawai penerbangan sipil ini paling senang membawa baterei ke desa-desa di PNG, yang di samping cepat laku jika dijual "juga paling disenangi keluarga kalau dikasih sebagai hadiah." Katanya, baterei barguna untuk dibawa berburu. Penduduk Pendesi, Mink, dan Imonda, menurut Hendrikus, sulit mencari barang-barang itu. "Disana tak ada kios atau toko. Ada satu kios di Imonda, api harga barangnya mahal," tuturnya. Orang sana, kalau mau belanja yang murah, harus pergi ke Vanimo - jalan kaki. Ada pesawat kecil yang sekali sebulan mendarat di Imonda, tapi ongkosnya tak terjangkau kantung penduduk. Lapangan terbang itu - macam yang ada di Waris - lapangan rumput. Beberapa penduduk yang ditanya tentang kehidupan di Pendesi dan Mink rata-rata menilai hidup di Waris lebih baik. Ukuran mereka, ternyata, rumah. "Rumah di sana jelek. Masih atap alang-alang. Disini 'kan rumah begitu sudah tak ada. Semuanya sudah atap seng," kata Wim Mai sembari menggaruk kulitnya yang belang-belang hitam. Hanya, yang paling merepotkan penduduk Waris adalah tak tersedianya lapangan kerja. "Kami menganggur saja kalau sudah selesai di kebun," kata Andreas Tawa, pemilik tanah yang ia tanami rambutan yang belum berbuah. Selain tanaman keras, di kebun juga mereka tanam ketela dan ubi jalar untuk makan sehari-hari, di samping sagu. Banyak buah-buahan lain, seperti jeruk dan. mangga, tapi, "Buahnya membusuk saja. Siapa saja bisa mengambil. Orang sini sudah bosan: mau dijual ke mana? Di sini tak ada pasar. Paling-paling ditawarkan ke rumah atau asrama tentara. Lumayan kalau dibayar dengan rokok beberapa batang," kata.Andreas. Camat Sitinjak pernah mencoba mencari jalan agar buah-buahan hasil tanaman penduduk, yang ia anjurkan dulu, bisa dijual. "Pasar mendadak dibuka di depan rumah saya. Tapi minggu kedua pasar jadi' sepi. Habis, siapa pula yang mau beli? Semua penduduk menjual, tidak ada yang membeli. Mau saya borong untuk didrop ke Jayapura, ongkos pesawatnya lebih mahal ketimbang untungnya," tutur Camat Sitinjak. Di halaman rumah-rumah penduduk bisa ditemui buah jeruk jatuh berserakan di bawah pohon, membusuk. Sia-sia. Di pohonnya sendiri menggantung buah-buah jeruk. Ada yang sampai pecah, dengan isinya yang merah merangsang, terutama bagi orang yang kebetulan lagi puasa. Mubazir. "Mencarikan mereka pekerjaan untuk menambah penghasilan amat susah. Maka, amat gembira mereka jika ada proyek padat karya. "Mereka bisa dapat makan gratis dan rokok." Tapi, sialnya, proyek macam itu tak setiap tahun ada. Untuk tetap menyibukkan mereka, Camat membelikan dua gergaji mesin. "Di sini banyak kayu. Kalau roboh dan busuk, 'kan sia-sia. Mendingan kita pakai membangun rumah penduduk mereka bisa dilatih mendirikan rumah." Kendati proyek padat karya tak setiap tahun, kalau kebetulan turun banyak juga penduduk seberang yang ikut bekerja. "Mereka itu cepat tahu kalau ada padat karya di sini. Mungkin saudara-saudaranya di sini memberi kabar," kata camat berusia 38 tahun dan asal Balige itu. "Jika ketahuan bahwa mereka orang seberang, biasanya kami suruh pergi. Daripada bikin soal." Arus pendatang dari sana bukan saja terdiri dari mereka yang mencari kesempatan ikut menimbrung padat karya, tapi juga yang datang berobat. "Tidak banyak. Paling satu-dua orang sebulan," kata Herman Amo, mantri di Puskesmas Waris. Menurut penuturan beberapa penduduk, di Pendesi dan Mink memang tak ada balai pengobatan. Kalau orang dari dua desa itu sakit, harus ditandu dulu di Imonda, desa pusat kecamatan sana. Menurut mereka, daripada dibawa ke Imonda, lebih dekat dibawa ke Waris. Penduduk seberang, yang ke Waris, biasanya membawa oleh-oleh parang, sabit panjang - mirip pedang - dan baju-baju kaus T'shirt. Sebaliknya, di Waris banyak betul laki-laki yang memakai kaus berlogo PNC dengan gambar belahan timur Pulau Irian. "Ini oleh-oleh anak saya dari Imonda," kata Meno Namalo, pegawai kantor kecamatan yang hari itu masuk kantor dengan kaus tadi. * * * Kecamatan yang dingin itu berada 1.800 meter di atas muka laut. Dikurung jajaran Bukit Kandep di timur sampai selatan dan Bukit Monka di utara, Waris adalah sebuah lembah sempit. Kalau diukur dari bukit-bukit di utara dan selatan, lahan yang kini disebut Waris itu lebarnya cuma 1,1 km - memanjang di dua sisi air strip. Tapi tanah sempit itu tak disangka telah menumpahkan darah ratusan orang warga suku-suku yang berperang memperebutkannya. Yang menguasai dan memiliki kawasan ini dahulu adalah suku Tabu. Anggota generasi terakhir suku Tabu, yang berkuasa di sana, adalah kakek Martin Tabu, gembong Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kini di Jakarta itu. Ketika ondoafi (kepala suku) dijabat oleh kakek Martin Tabu, Waris diserang suku-suku Walsa dan Mai. Kalah perang, suku Tabu mundur ke arah Senggen dekat Yuruf. Kemudian berkuasalah, atas milik suku Tabu, dua suku penyerang: Walsa dan Mai. Mereka itu tadinya berada di sebelah timur garis batas, di wilayah PNG. "Itulah sebabnya banyak orang sini punya hubungan keluarga dengan orang Pendesi atau Mink," kata Wim Mai, sang kepala adat. Bagi dua suku yang kini hidup di Waris, tak ada kawasan hutan di situ yang asing. Rimba sekitar Waris sampai garis batas, dan sejak garis batas ke timur, di wilayah PNG hingga ke sekitar Pendesi, adalah kawasan sah mereka menurut adat - buat berburu babi, kadang menjangan, dan sagu. Dengan celana pendek dan kaus usang yang sobek di lengannya, Wim berpetuah bahwa pembagian tanah perburuan itu harus dihormati. Juga sekali-kali tak dibolehkan berburu di luar tanah yang sudah ditetapkan bersama suku lainnya. "Kita di sini tak boleh berburu di tanah hak Suku Tabu di selatan. Itulah perjanjian setelah perang dulu," kata Wim serius. Tapi bagaimana dengan garis batas antarnegara? Wim bingung juga menjawab. Lantas berkata, "Itu 'kan batas negara. Kitorang tidak pakai batas itu." Menurut Wim, kalau untuk kepentingan berburu masuk ke wilayah seberang, biasanya penduduk tak pakai melapor ke pos Imigrasi. "Kitorang'kan tidak menginap. Habis berburu, malam itu juga pulang," kata kepala suku yang pernah ikut menjadi anggota Badan Musyawarah Pepera tempo hari. Ia bercerita banyak tentang Jakarta, Semarang, dan Surabaya yang ia kunjungi bersama ratusan kepala suku lainnya. Ia juga pernah menjabat sebagai kepala desa Banda sejak selesai Pepera sampai 1979. "Sekarang saya sudah tua. Biarlah yang muda-muda yang memegang jabatan. Toh mereka anak-anak saya juga," katanya - maksudnya, bukan dari suku lain. Ia belakangan selalu mengeluh sulit mendapat rokok. "Dulu Pater suka kasih saya rokok. Sekarang sudah jarang. Pater jarang datang ke sini. Saya bisa dapat rokok kalau ada tamu kemari, seperti anak ini," ujarnya sembari menunjuk saya. Rokok dan bir memang menjadi kegemaran laki-laki Irian. Masih berakarnya kekuasaan kepala suku dengan sendirinya membuat aparat di kecamatan itu susah mengatur warganya. "Apalagi kalau sudah menyangkut masalah tanah," kata Camat Sitinjak. Untuk membebaskan tanah buat membangun sekolah saja luar biasa sulitnya. "Akan banyak yang ribut bisa terjadi permusuhan." Pernah, misalnya, timbul suasana panas yang hampir saja menyebabkan perkelahian massal antara suku Walsa dan suku Mai - gara-gara Camat meminta tanah untuk membangun SD Inpres. "Dua suku itu masing-masing mengakui bahwa merekalah yang punya itu tanah. 'Kan saya jadi bingung: kepada siapa saya harus membayarkan ganti rugi tanahnya," menurut Camat. Karena tak ada yang mau mengalah, juga tak ada yang bisa menunjukkan bukti bahwa tanah itu miliknya, diputuskan saja untuk tidak membayar - tapi tanah tetap dipakai membangun SD. "Ini jalan terbaik. Mau bagaimana lagi ?" Yang diganti rugi hanya pohon-pohonan di tanah itu dibayarkan kepada siapa yang menanamnya. Cara semacam itu kini banyak dipakai di Irian Jaya untuk pembebasan tanah ulayat yang memang sulit dan selalu menimbulkan sengketa. Contoh perselisihan yang berlarut-larut adalah tanah adat yang dipakai membangun jalan Jayapura-Sentani. Suku-suku sepanjang jalur itu sampai sekarang masih menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Yang membangun jalan itu dulu Belanda. * * * Waris bisa dicapai dengan heli atau pesawat kecil jenis Cessna - setengah jam penerbangan arah tenggara Sentani. Di samping, tentunya, jalan kaki merambah hutan dan rawa, seminggu sampai ke Jayapura. Tapi beberapa bulan lagi jalan trans-lrian, yang kini dikerjakan, akan sampai ke Waris. Persoalan kini: jalan itu tak boleh terlalu dekat dengan garis batas. Setelah Hmbul protes PNG tempo hari, yang mengira pembangunan itu masuk ke wilayahnya, ada goodwill di pihak RI untuk membelokkan arah jalan yang terlalu dekat perbatasan. Masalahnya kemudian, pusat pemerintahan Waris di Desa Banda itu, seperti sudah disebut, jaraknya cuma 1,8 km dari garis batas. Jadi, jalan yang tadinya direncanakan membelah tepat di tengah desa terpaksa dibelokkan ke pinggir barat desa - di radius 5 km dari perbatasan. "Maunya 10 km, tapi kita pikir terlalu besar dan luas sekali wilayah kita yang bebas," kata Bupati Bas Youwe. JALAN trans-lrian, khusus sektor utara yang dibangun mulai Jayapura (Abepura), kini sudah mencapai 80 km. Rentangan itu melewati Arso terus ke Waris, dan baru sampai di tengah-tengah antara kedua "kota". Berikutnya, nanti jalan akan terus menyusur ke selatan menuju Senggen, Ubrub, Vyuruf, dan bertemu dengan jalan trans-lrian yang dibangun dari sektor selatan mulai dari Merauke. Jalan yang dibangun dari Merauke itu kini sudah 190 km sampai ke Mindiptana. Panjang keseluruhan jalan ini kelak akan mencapai 1.500 km, termasuk yang membentang sampai Wamena dan Nabire. Jalan yang sudah jadi masih berupa tanah, belum aspal. Tapi cukup lebar dan rata untuk ngebut gaya Irian. Di situ sudah ada angkutan pedesaan, Toyota Kijang. Kecamatan Waris dulunya berpusat di Kenandega - sampai 1977. Kenandega ditinggalkan karena banyak penduduk hilang, lari ke hutan. Kenandega kosong pusat pemerintahan pun dipindahkan ke Banda. Dulu kawasan kecamatan ini suka diganggu gerombolan Martin Tabu, dan itulah sebabnya banyak penduduk menyelamatkan diri ke hutan selain memang ada juga yang ikut bergabung dengan gerombolan. Bahkan camat Waris waktu itu, sebelum Sitinjak, pernah ditawan Martin Tabu beberapa bulan. Kawasan kecamatan ini memang wilayah rawan. Pernah seluruh penduduk satu desa di Kenandega hilang semua - lalu kembali lagi, dan tinggal di Banda, menghindar dari gerombolan. Soal lari ini bukan hanya cerita lama. Di awal tahun 1982 penduduk Waris berjumlah 448 orang - 85 keluarga. Ketika 28 Juni sampai awal Juli 1982 dihitung ulang, ketahuan jumlah mereka hanya 245 orang alias 47 keluarga. Dan kini sudah membengkak lagi, menjadi 655. orang. * * * Di samping malaria, musuh utama tentara kita di perbatasan adalah kebosanan, tentu saja. "Nggak tahan, Mas," kata Sersan Dua Solihuddin, anggota Kopassandha asli Kediri. Dia baru dua bulan di Waris, "Rasanya sudah setahun." Kebosanan timbul, katanya, karena kita tak punya musuh yang harus diganyang. "Kami disuruh menunggu begini gampang membuat rindu kampung dan anak istri. Tapi ini 'kan tugas negara". Ketika saya pulang ke Jayapura semua anggota Kopassandha menitipkan surat untuk keluarga mereka, yang harus saya poskan di Jayapura. Mereka sudah siap dengan. prangko, rupanya. Hidup dan bergaul dengan penduduk, anggota Kopassandha rata-rata mengaku akrab dengan mereka. "Kami sering dibawai buah-buahan. Yah, itulah yang menghibur kami," tutur Sariman. Bagi tentara yang Islam, repotnya kalau sudah hari Jumat. "Di sini 'kan tak ada masjid. Selama di sini kami tak pernah jumatan," cerita Sersan Dua Daud, 23 tahun, asal Madiun. Jumatan diganti saja dengan salat lohor biasa. Bagi yang kebetulan Katolik, tak ada soal. Tiap Minggu di gereja kayu yang dibangun misi Katolik sejak 1950-an - dan kini sudah compang-camping - ada misa. Cuma satu kali misa, dan tentara bergabung di sana bersama penduduk yang semuanya Katolik. Misa dipimpin oleh guru Injil. Hanya sekali dalam tiga bulan, untuk satu kali misa Minggu, Pater datang dari Jayapura - diterbangkan dengan Cessna AMA. Di Waris, Pater punya rumah, semacam vila, di puncak bukit. Dari ketinggian itu Pater bisa leluasa memandang seluruh Waris - yang memang tak seberapa besar itu. Di samping vila Pater tadi ada ruang SSB, juga milik misi. SSB inilah yang berguna untuk berhubungan dengan Jayapura atau untuk keperluan menuntun pesawat yang hendak mendarat di Waris. Oh, ya. Kantor kecamatan juga punya satu SSB - yang kerap ngadat. Milik misi Katolik lainnya masih ada. Yaitu SD Yl'K, yang dibuka se jak 1959. SD ini j dengan gedung papan berlantai tanah, punya murid tak banyak. Satu kelas paling pol dihuni enam anak yang belajar. Bahkan ada kelas yang punya hanya dua orang murid. Belajar dengan baju tak seragam - apalagi bersepatu - sandal saja pun tidak - toh mereka bisa menikmati buku-buku bacaan (juga matematika, misalnya) yang baru, sama dengan murid-murid sekolah lainnya di kota. Di sana juga secara rutin diajarkan menyanyi Indonesia Raya dan Dari Barat sampai ke Timur. Dua lagu itulah yang paling dihafal anak-anak situ. Mereka baru saja menyelesaikan dari Barat sampai ke Timur, lalu Martinus meminta mereka menyanyikan Indonesia Raya. Murid kelas III yang jumlahnya enam orang itu pun serentak berdiri. Ada yang terlihat sobek bajunya. "Pelajaran kesadaran berbangsa memang diutamakan. Bisa disisipkan di tengah cerita tentang perjuangan atau pelajaran PMP," kata Stanis Psebo, guru di situ. Bila istirahat, anak-anak itu enak saja bemain petak umpet atau bola kasti di lapangan depan sekolah yang becek disiram hujan semalaman. Masuk kembali ke kelas dengan lumpur yang menempel di badan. Di rumah-rumah penduduk di Waris tak ada jamban atau kamar mandi. Mencuci diri, cuci pakaian, dan berak biasa dilakukan di kali berair jernih yang mengalir di selatan permukiman di pinggir bukit. Kali ini mengalir dari kawasan PNG. "Kami di sini hidup dari air asal negeri seberang," kata Camat Sitinjak. Di Waris memang ada beberapa pompa umum yang dibangun bersamaan dengan pembangunan rumah banpres. Tapi pompa-pompa itu hampir tak berguna. "Lebih senang mandi di sungai. Tidak lelah main pompa," kata Daniel Meho. Tampaknya, yang menonjol di sini kesadaran berpakaian. Menurut Wim Mai, sang kepala suku yang sudah disebut, dulu orang Waris memakai walo - koteka model setempat. Berbeda dari koteka yang dipakai di Jayawijaya dan Nabire, walo lebih besar dan panjang. Kenapa harus panjang? "Mungkin punya orang sini lebih besar daripada punya orang Wamena," jawab Wim tertawa-tawa. Sedangkan para cewek menutup aurat mereka dengan daun saga - di Wamena menggunakan daun alang-alang. Jauh sebelum Operasi Koteka dicanangkan, "Kitorang di sini sudah semua pakai baju," ujar Wim. Adalah Thibelt, kalau tak salah diingat Wim, yang pertama-tama membawa pakaian ke Waris - "dan menyuruh kitorang di sini membuang walo untuk diganti dengan baju yang dia kasih." Thibelt itu, menurut Wim, warga negara Belanda yang menyebarkan agama Katolik di Waris. Dia pertama kali datang dan membawa pakaian untuk orang situ pada tahun 40-an. "Rumah Thibelt di atas sana," sambil menunjuk hutan di pinggang gunung yang nyaris tertutup kabut. Gunung itu kini termasuk wilayah PNG - beberapa menit saja jalan kaki dari tugu perbatasan. "Waktu dia pertama kali datang dan mau bangun rumah di sana, kitorang bawa penduduk untuk memikul barang-barangnya." Thibelt datang bersama tiga Belanda lain. Kini rumahnya sudah tak ada bekasnya, dimakan hutan. Yang perlu dicatat, di samping kesadaran berpakaian, adalah kesadaran mengikuti upacara bendera pada tanggal 17 setiap bulan. "Kami anggap seperti kewajiban pergi ke gereja," kata Blasius Maunda, 35 tahun. Upacara ini bisa ditambah lagi dengan kedatangan hari besar - Hari Pendidikan, misalnya. "Untuk upacara kitoran selalu sedia baju yang bagus." Menurut Camat, meski tak diwajibkan memakai pakaian bagus (boleh dengan celana pendek sekalipun). "Penduduk tampaknya menganggap istimewa hari upacara. Mereka bertingkah gembira seperti di hari Natal." Sayangnya, rumah penduduk tak ada yang punya bendera, hingga pada Hari Kemerdekaan penduduk tak memasang bendera. "Kami sudah minta pada Pak Bupati untuk membagi bendera kepada penduduk, satu-satu. Tapi sampai sekarang rupanya belum bisa itu bendera ke sini," kata D.Y. Mai, kepala desa Banda. Wakil gubernur Irian Jaya, Sugijono, mengakui pembagian bendera belum dilaksanakan. Tapi sebenarnya "penduduk bisa saja membeli sendiri kalau mereka mau. Mereka punya uang kadang-kadang habis untuk minuman keras," ujar Sugijono. Bukan cuma bendera agaknya yang diperlukan penduduk. Juga gambar wakil presiden yang baru. Di semua rumah terpampang foto Presiden Soeharto dalam ukuran kuarto, gambar resmi. Tapi gambar Wapres Umar belum ada - bahkan di kantor kecamatan. Di sebelah gambar Pak Harto kini masih terpasang dengan gagahnya foto Adam Malik dalam ukuran yang sama. Yang hebat di rumah Wim Mai. Di sana gambar Pak Harto dan Pak Adam berjejer dengan gambar Paus Yohannes. Lalu di bawah ketiganya ada selebaran stensilan yang sudah kuning dengan bercak-bercak cokelat. Selebaran itu berkop: Badan Perencana Kemerdekaan Papua Barat. Yang menandatanganinya adalah Pendeta Hazer Demotokai. Isi selebaran itu: seruan Pak Ketua kepada gerombolan untuk kembali ke desa, jangan terus-terusan mengacau di hutan. Sebab, begini bunyi selebaran tadi, "Apa yang diperjuangkan dan diimpikan sebagai Kemerdekaan Papua Barat kini sudah bukan merupakan impian orang waras lagi. Impian itu hanya berguna 20 tahun yang lalu. Sekarang Republik Indonesia sedang membangun untuk kita juga. Maka saya serukan untuk turun dari gunung. Dan bekerja kembali seperti sediakala." Pendeta itu kabarnya sudah meninggal - anak asli Genyem, dekat Sentani. "Dia anak Keerom asli,"kata Wim. Dulu sekolah di Malang. Stensilan itu, yang juga tanpa tanggal, juga banyak dijumpai di rumah-rumah penduduk lain. Penduduk, yang ditanya, tak ada yang tahu atau merasa pernah mendengar baik nama Umar Wirahadikusumah maupun Sri Sultan. Bahkan Wim sendiri - padahal dia mengaku pernah masuk Keraton Yogyakarta waktu selesai Pepera dulu. "Kalau Bung Karno kitorang tahu. Kitorang banyak dengar ceritanya," katanya. Kantor desa yang berada di ketinggian itu dilengkapi banyak meja dan kursi. Masih baru. Debu tebal menempel di permukaan kursi, tanda tak pernah diduduki. Pada jam kerja itu saya harus menunggu dulu Kepala Desa yang dipanggil untuk membuka kantornya. Juga ada sebuah mesin ketik. Nasibnya sama, berdebu. Menurut D.Y. Mai, 44 tahun, kantor itu baru saja dibangun penduduk. Belum setahun. "Mau dibuka terus-terusan, orang yang mengurus surat tak ada yang ke kantor. Mereka lebih enak ke rumah. Di rumah bisa minum kopi dan dapat rokok," katanya . Menurut Mai, semua penduduk sudah punya KTP. Dan untuk mengurus KTP itu cukup lama. "Bikin pasfoto mesti jalan kaki dulu ke jayapura," kata Moses Tawa. Tak heran, saya pun, yang kelihatan menenteng tustel, diminta penduduk memotret. "Untuk KTP kelak, Bapak," kata mereka. Ketika diberitahu bahwa fotonya harus dicetak di Surabaya, mereka kecewa. "Ke jayapura itu jauh, Bapak," kata salah seorang sembari menyodorkan buah jeruk sebagai imbalan foto yang dipesannya. Membandingkan Indonesia dengan Belanda, dalam hal perlakuan terhadap penduduk, beberapa orang tua yang ditanya - termasuk Wim - mengaku tak ada bedanya. "Sama saja. Pemerintah mana saja baik-baik. Kitorang tinggal ikut omong pemerintah saja," kata Dominikus Ibe, 59 tahun. Hanya, pemerintah sekarang, "Mau bikin rumah buat rakyat.Dulu kitorang bikin rumah sendiri." Rata-rata penduduk tak merasa mereka orang Indonesia - meski setiap tanggal 17 berupa cara bendera. "Kitorang orang asli sini. Di sini ada orang Walsa dan ada orang Mai," ujar Dominikus lagi. "Sekarang pemerintah Indonesia yang atur, kitorang ikut. " Anehnya, mereka juga tak mengerti sebutan "orang Irian". Tahunya cuma Walsa dan Mai tadi. angan pula ditanya apa arti Melanesia. Bahkan Wim yang kepala suku itu tak tahu. Kalau Pendesi, Mink, atau Imonda mereka kenal. PNG? Mereka terbengong-bengong mendengarkannya. Ketika saya bilang, PNG itu "orang yang berkuasa di Vanimo, di ibu kota Provinsi Sepik Barat," Wim men jawab, "Kitorangdi sini belum ada yang pernah ke Vanimo." Susah. Sama seperti yang dikatakan Willem Maloali, wakil ketua DPRD Irian ava. Orang Irian laya, katanya, "Tak tahu dirinya orang Indonesia. Irian aya sendiri istilah untuk pembagian wilayah. Melanesia istilah antropologi. Orang sini merasa orang sukunya - di situ ia lahir, besar. hidup, terikat lahir batin, dan mati." Menurut Maloali, yang perlu dicarikan jalannya sekarang memang bagaimana menggalang perasaan orang suku-suku itu agar merasa sebagai orang Indonesia. Caranya? "Saya sendiri belum tahu," jawab pendeta asal Sentani itu. Karena tebalnya kesukuan itu. Maloali menganggap "orang Irian aya ini ibarat pasir. Dari jauh tampak menggumpal, padat dalam satu kumpulan, ada kohesi yang mengikat. Tapi begitu kita ambil pasir itu, segera ketahuan bahwa yang tadinya gumpalan itu cuma_serpih-serpih kecil." Mereka terpecah-pecah dalam ribuan -ribuan! - suku-suku besar dan kecil. * * * Orang Waris tak suka pacul. Ratusan pacul yang diberikan lewat banpres bernasib sia-sia: ditaruh begitu saja di dapur, "Atau sengaja tak mereka ambil dari kantor camat," kata Mai, si kepala desa. Pemerintah memang sudah pernah membagikan pacul untuk kepentingan berkebun penduduk. Orang Waris lebih memerlukan parang dan tembilang - untuk menebang pohon dan membersihkan hutan guna membuka lahan baru. "Di sini masih ada yang suka bertani berpindah-pindah," kata Sitinjak. Setelah menebang pohon-pohonan, membakarnya, mereka menanamkan jagung, atau ubi, atau singkong, ke dalam lubang yang dibuat satu-satu dengan tembilang. Pantaslah kalau pacul tak berguna. Kalau merasa tanah sudah tak subur, mereka pindah lokasi. Babat lagi, bakar lagi, tanam lagi, pindah lagi. Buat apa pacul? Tak ada soal dengan sagu, karena dusun - begitu orang Irian menyebut ladang sagu mereka - tak bakal habis. Toh sering juga terjadi keributan antar keluarga gara-gara sagu. Di samping mengunjungi dusun masing-masing setiap hari untuk makan, penduduk Waris yang sudah punya rumah lantai papan setengah meter di atas tanah, model rumah seng banpres - menanami halamannya dengan sayuran, bawang, sawo, singkong, pohon nangka, dan lain-lain. Di utara air strip ada dua jalan yang sejajar dengan jalan pesawat itu. Di tepi jalan yang rumputnya dipangkas rapi itu membentang lurus pagar tanaman hidup yang juga rapi. Begitu pula di selatan air strip di sini cuma ada satu jalan. Kalau rumah-rumah di utara sudah pada jadi, di selatan sedang sibuk dikerjakan - satu per satu. Dengan tangan tukang dari antara penduduk sendiri, dan dengan bantuan tetangga, rumah-rumah itu dibangun berdasarkan gambar konstruksi kayu dari PU. Agak aneh rasanya melihat orang pedalaman Irian mengukur panjang kayu sembari membolak-balik gambar yang dibeli Pak Camat di Jayapura itu. "Pakai gambar lebih bagus. Rumah tidak miring kiri atau kanan," kata Petrus Meho. Ia sedang membangun rumahnya tepat di belakang kantor camat. Yang juga aneh adalah mendengar lagu rock Barat berteriak dari sebuah tape recorder milik tetangga Petrus. Tape recorder, jam tangan, minyak wangi murahan - yang dipakai kalau ke gereja dan mengikuti upacara bendera - dan celana Levi's ternyata bukan tak ada di sini. Yang amat jarang dijumpai mungkin hanya sandal dan sepatu. Tapi buat apa sandal atau sepatu, untuk kaki-kaki yang setiap saat naik turun hutan? Juga bukan hal aneh bila anak-anak dimandikan ibu mereka dengan sabun Lux di kali. Mereka membeli barang macam itu di Jayapura. Titip pada tetangga. Yang tak ada di sini: teve. Kalau radio, banyak. Siaran RRI Jayapura ditangkap bersih di Waris.juga Radio Australia. Acara yang terhitung digemari rakyat di sini adalah siaran dari sebuah pemancar milik Katolik yang diudarakan dari Filipina dengan acara agama, dalam bahasa Indonesia. Anehnya, acara ini, menurut radio itu, dipaketkan dari Batu, Malang. Toh orang-orang masih suka merubung pesawat yang mendarat. Entah sudah berapa ribu kali mereka merubung pesawat. Kalau dua kali pesawat mendarat dalam sehari, dua kali pula mereka berlari-lari ke lapangan terbang. Orang yang baru mendarat selalu diikuti dari belakang sampai ke rumah Camat tempat para pendatang menginap. Yang berbuat begitu bukan cuma anak-anak. Tapi juga Wim, si kepala suku. * * * Berangkat pagi-pagi, pukul 7.00, ketika udara benderang cerah tetapi dingin (agak siang sedikit Waris sudah berkabut, dan biasanya hujan), kami setengah jam berjalan kaki menyusuri kali yang berhulu di PNG itu. Sebelum sampai di kali, perjalanan melewati jalan setapak yang licin dan sempit hanya beberapa menit. Di kiri kanan jalan setapak membentang jurang yang tak terlalu dalam. Jalan tikus ini bersih, pertanda kerap dilalui. Sampai di sungai kemudian menyusur, menyeberang beberapa kali ke utara, lantas menyeberang lagi ke selatan, menyeberang kembali ke utara - "untuk menyiasati mencari jalan yang aman," kata Letnan Aris. Tak sampai setengah jam, tepatnya 28 menit, sudah terlihat di seberang kali, di pucuk tebing terjal, sebuah tugu. Nah. Untuk sampai ke sana kita harus menyeberang lagi ke selatan. Lalu, dengan seutas tambang yang dikaitkan ke pohon di atas tebing, naiklah pasukan para mencapai tugu. Ada pula yang memaksa naik tanpa tali, langsung melewati tebing licin. Sampai juga. Dengan parang dan sabit panjang, rumput yang hampir sama tingginya dengan tugu itu dibabat habis oleh Wim yang hari itu memakai baju dril warna khaki dengan bintang Pepera di dada. "Kalau kita tidak ke sini, rumput ini tidak ada yang potong, hee," katanya terengah-engah. Dikungkungi pohon-pohon besar, di rimba yang boleh dibilang hutan primer itu, di kesenyapan alam, tugu beton setinggi tiga meter ini bagai makhluk aneh. Tidak berlumut, tapi sudah kehilangan warna campuran semennya, tonggak yang dipancangkan 23 Agustus 1966 itu bertuliskan ini: Aust Survey Team. Itu dipahat pada sisi yang menghadap ke timur. Sedangkan pada sisi berbentuk kerucut bagian bawah besar, bagian atas mengecil - yang menghadap ke barat, dipahat tulisan: Team Survey Indonesia. "Inilah patok perbatasan kita," ujar Sitinjak. Menurut Sitinjak, setiap orang baru yang datang ke Waris pasti ingin melihat tugu itu. "Dijadikan tempat pesiar," katanya. "Entah berapa jarak antara tugu ini dan tugu lain. Semuanya berjajar dari utara sana ke selatan sana, sepanjang garis batas," kata Camat . Menurut bupati ayapura, yang juga menjadi ketua Liaison ayapura-Vanimo, di sepanjang perbatasan ada 14 tugu. Yang membangunnya dulu Indonesia : bersama dengan Australia, yang pada -l966 masih memerintah di Papua. "Akan ditambah dengan 17 tugu tahun ini. Tim gabungan dari Bakosurtanal dengan pihak PNG sedang bekerja sekarang ini," kata Bupati Bas Youwe di kantornya di ayapura. Idealnya, menurut Bas, harus ada satu patok untuk satu kilometer. Minimal harus dibangun 720 tugu, jadinya. "Biar gampang ketahuan mana wilayah kita, mana wilayah orang," katanya. Pernahkah terpikirkan membuat tembok? "Ah tidak. Cukup tugu yang banyak, dengan beberapa koridor untuk pelintas batas tradisional dan pos imigrasi macam di Waris itu," kata Bupati.Ia menginginkan seperti yang di Kalimantan - di perbatasan kita dengan Malaysia. Yang boleh melintas di koridor memang cuma pejalan tradisional. Di seluruh Kabupaten layapura terhitung sekitar 6.000 penduduk yang tergolong penyeberang tradisional. Belum termasuk penduduk desa-desa yang masuk wilayah kabupaten-kabupaten Jayawiiaya dan Merauke. Dari tugu di tebing tadi, 200 meter ke arah timur kembali menyusur kali, setelah turun dari tebing ada lagi sebuah tugu. Yang ini dibuat mirip plang papan nama kantor. Punya PNG. "Di tempat ini dulu ada plang bertuliskan bahasa Belanda dan Inggris. Sampai tahun 1959 masih berdiri di sini." Karena papan itu sudah berganti tuan, tak ada lagi orang Belanda, kini tinggal yang berbahasa Inggris - yang sudah diubah - dengan terjemahan Indonesia yang kaku . Tinggi keseluruhan pancang yang menghadap utara (sungai) dan membelakangi hutan itu sekitar 2,5 meter. Tiangnya dicat putih. Inilah tulisan yang tertera di situ: Notice. Territory of Papua and New Guinea. Your are now in the Territory of Papua and New Guinea - D.O. Hav, Administrator. Di bawahnya, dipisahkan oleh garis panjang setengah lebar plang, terjemahan berbunyi: "Pemberitahuan. Daerah Papua dan New Guinea. Kamu sekarang ini dalam tanah Papua dan New Guinea - D.O. Hay, Pengurus Pengatur." Tulisan itu masih cukup mencolok untuk sekadar dapat dibaca dari arah sungai. Ditulis dengan cat merah pada warna dasar putih pucat. "Ini sudah wilayah mereka. jangan bikin soal berjalan-jalan kearah sana. Ingat, kita tak tergolong penyeberang tradisional vang sedikit bebas masuk ke sana," terdengar seorang anggota Kopassandha mengingatkan. Siapa yang mau ke sana? Berbeda dengan tugu 200 meter arah barat, yang dibangun Australia dan Indonesia tadi, papan ini bersih di sekitarnya. Rumput dan ilalang ditebas pendek, hingga hampir rata dengan tanah basah di situ dalam radius lima meter. "Ini baru dorang potong. Paling lama kemarin," Wim nyeletuk, sembari tetap duduk di tanah meneliti bekas tebasan. Wim baru bangkit begitu anggota Kopassandha berteriak menemukan sebatang pelepah daun lontar yang dipotong dan dilipat membentuk sebuah segitiga, semacam isvarat yang biasa ditemukan di hutan-hutan Irian, tepat di belakang plang. Wim, yang menelitinya, bilang, "Oh, ini cuma tanda bahwa pinang itu jangan diganggu," sembari menunjuk pohon pinang di dekat situ. Simpul segitiga itu bagian ujungnya yang runcing memang menunjuk ke arah pinang. Simpul-simpul begini amat dihormati penduduk Irian. Rumput yang baru dipotong menandakan baru ada patroli PNG yang sampai ke situ. "Patroli mereka bukan tentara. Mereka pakai polisi yang bawa pentungan," tutur Wim. Penduduk lainnya yang ditanya juga menjelaskan, mereka sering menemui polisi bawa pentungan hitam di tengah perjalanan ke Pendesi, Mink, atau desa lainnya di seberang. "Paling-paling dorang cuma periksa kitorang punya pas. " Ada juga tentara berpakaian lengkap dengan senjata panjang, meski tak pernah ditemukan sampai nyenong ke hutan sekitar perbatasan. "Biasanya, tentara sana datang pakai heli ke Pendesi. Nginap dua malam terus pergi lagi pakai heli," cerita Moses Tawa. Juga ke Mink begitu. "Tentara mereka sedikit saja," kata Wim. Patroli gabungan TNI dan tentara PNG belum pernah ada dan memang belum pernah diwujudkan. "Padahal, pernah juga disinggung, kadang-kadang, dalam perundingan perbatasan," kata Bas Youwe. "Mungkin belum saatnya." Di sebelah timur plang PNG tadi ada bekas jalan yang tak ditumbuhi rumput. "Itulah jalan ke Pendesi!" ujar Wim menuding. Rupanya, itulah jalan yang sering dilalui penduduk, juga yang dilalui lima anak Waris yang bersekolah di Pendesi. Setiap minggu pulang ke Waris pada hari lumat, lalu kembali ke Pendesi hari Ahad, lima murid itu belajar di community school satu-satunya di Pendesi. "Biar pintar bahasa Inggris," kata salah seorang ayah mereka. "Rata-rata- mereka memang pintar bahasa Inggris," Camat membenarkan. Tapi tahun ajaran mendatang ini Camat akan mengusahakan agar mereka mau pindah saja ke SD di Waris. Lho? Camat khawatir nantinya mereka repot dalam soal kewarganegaraan, katanva. Tapi Moses Tawa adalah satu contoh. Bersekolah di Mink, lahir di sana, lalu pindah ke Waris dan lulus SD. Balik lagi ke Mink, tak betah di sana, kembali ke Waris dan kawin. Seperti dikatakan Camat sendiri: "Ia tak punya surat. Saya juga tak tahu surat apa yang diperlukan untuk kewarganegaraan di sini. Dia ada di sini, yah, saya anggap saja dia warga negara RI. Saya kasih dia KTP segala. Pokoknya dia ada di sini."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini