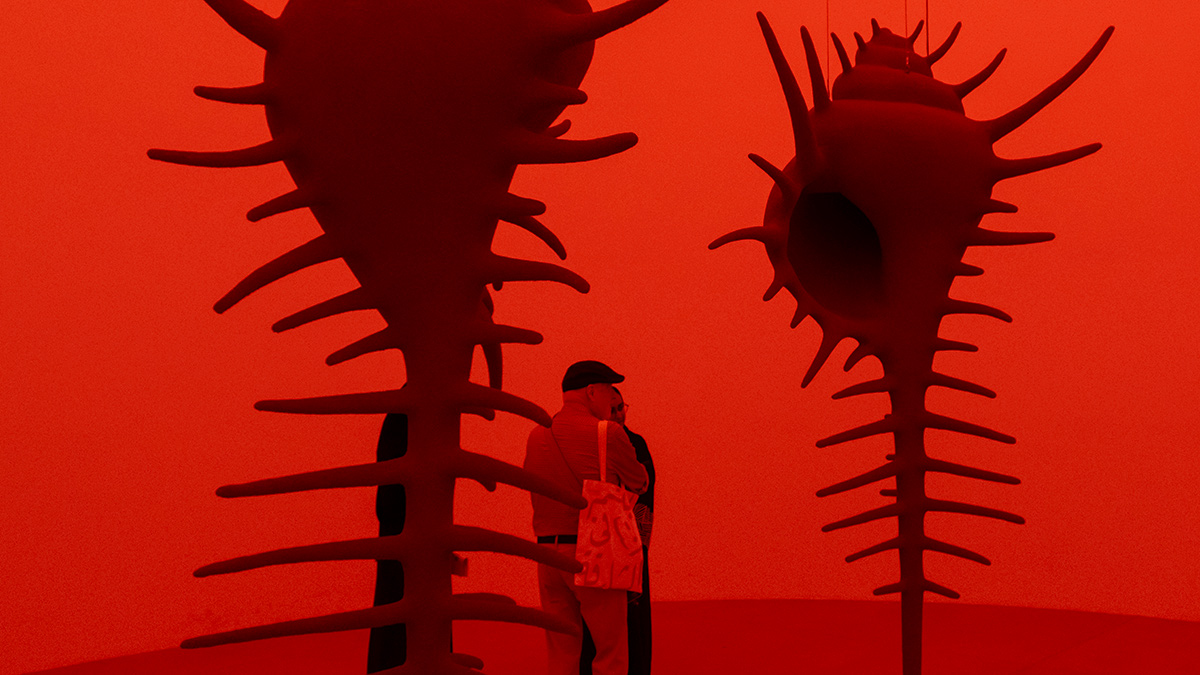Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Moewardi diculik oleh empat pemuda yang diduga merupakan anggota Front Demokrasi Rakyat yang berteriak seolah-olah ada seseorang yang terluka parah di halaman rumah sakit.
Sehari sebelumnya, ia sudah diberi peringatan agar tidak berpraktik dulu dan dijaga oleh pengawal pribadi, tapi ia mengabaikannya.
Kedekatan politiknya dengan Tan Malaka hingga membentuk Gerakan Revolusi Rakyat dianggap ancaman oleh Front Demokrasi Rakyat yang belakangan menjadi Partai Komunis Indonesia.
TAK seperti biasa, Moewardi berpamitan dua kali setelah menyantap sarapan kepada istrinya, Soesilowati. Hari itu 13 September 1948. Pada pukul 09.00 dia pamit karena andong milik Perguruan Tinggi Klaten, tempat ia mengajar, sudah menunggu untuk mengantarnya ke tempatnya berpraktik, Rumah Sakit Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Dokter 41 tahun itu mengecup kening istrinya, lalu dua anak mereka yang masih berumur dua dan satu tahun.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo