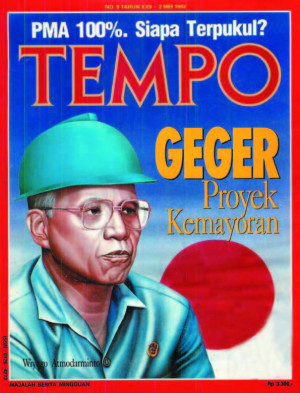National Gobel mungkin bisa menjadi model usaha patungan yang sejak awal menggelinding dengan lancar. Walaupun demikian, setelah 22 tahun berpatungan, perusahaan tuan rumah PT Gobel & Cawang Concern belum juga menguasai saham mayoritas. Saham terbesar masih berada di tangan sang partner Jepang, yaitu Matsushita Electric. Ketika ditanyakan soal itu, Jamien H. Tahir seakan merasa terusik. "Apa ada untungnya kita paksakan pemodal asing jadi minoritas," kata Wakil Presiden Direktur PT National Gobel itu. Soalnya, Matsushita sudah memilih Indonesia sebagai salah satu wilayah relokasi bagi industrinya. Kini, setelah ada PP 17/1992 yang mengizinkan investasi asing 100 %, dapat saja Matsushita yang mempunyai 48 pabrik di 37 negara, beroperasi tanpa partner lokal di Indonesia. Dengan demikian, posisi partner Jepang itu lebih kuat, sementara pihak Indonesia belum tentu bisa menghasilkan produk yang bisa menyaingi produk Matsushita. Jangan lupa, Matsushita sudah menggeluti industri elektronika sejak tahun 1918. Singkatnya, dari sisi teknologi maupun hukum, Indonesia berada dalam posisi yang tidak begitu mujur. Tak heran bila Jamien tidak melihat urgensinya memperjuangkan saham mayoritas. Lagi pula risiko cukup besar. Terlebih, selama ini tak ada hambatan serius yang merintangi kerja sama Gobel & Cawang Concern dengan Matsushita. Pokoknya mulus. Perkara 60 % saham di tangan Matsushita dan hanya 40% saham di genggaman Gobel & Cawang, kan tidak buruk? "Itu kan merupakan itikad baik untuk berjoint venture," kata Jamien. Tak heran bila gagasan ambil-alih saham asing belum sekalipun terlontar dalam rapat pemegang saham National Gobel. Sesuai dengan kontrak yang ditandatangani almarhum H.M. Gobel tahun 1970, kerja sama Gobel & Cawang dengan Matsushita akan berakhir tahun 2000. "Diteruskan atau tidak bergantung pada kedua belah pihak. Kalau masing-masing menganggap ada timbal baliknya, ya diteruskan," ujar Jamien. Agaknya, kerja sama ini akan berlanjut. Paling tidak, belum ada petunjuk bahwa kongsi itu akan retak. Matsushita yang semula menyetor modal US$ 15 juta, kini menambah penyertaan modal sampai US$ 50 juta. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa komposisi kepemimpinan dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan komposisi modal. Jadi, dari lima direksi, ada tiga orang Jepang dan dua orang Indonesia. Sedang untuk kontrol kualitas, pada tiga belas divisi produksi National Gobel terdapat seorang penasihat Jepang. Akan halnya transfer teknologi, Matsushita ternyata membuka pintu untuk itu. "Banyak sekali lokalisasi komponen, desain pabrik, maupun beberapa desain produk. Saya kira penyerapan teknologi di National Gobel cukup baik," kata Jamien. Freeport Indonesia Company Awal April lalu, Aburizal Bakrie resmi menjadi anggota dewan komisaris Freeport Indonesia Company (FIC). "Itu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menghendaki lebih banyak orang Indonesia dalam FIC," kata Direktur Utama FIS, Hoediatmo Hoed, dalam rapat umum pemegang saham FIC yang mengangkat orang nomor satu Grup Bakrie itu ke jajaran komisaris FIC. Pengangkatan itu merupakan tindak lanjut dari pembelian 10 % saham FIC oleh Grup Bakrie di bursa saham New York. Nilainya mencapai US$ 213 juta. Masuknya Bakrie ke FIC menunjukkan dua hal. Pertama, perusahaan tembaga ini memerlukan dana murah. Kedua, kecenderungan Bakrie untuk mengusai sedikit saham di sebuah perusahaan berskala besar, ketimbang menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan kecil. Dari pihak FIC sendiri, niatnya untuk melepas saham ke investor lokal, -- di luar pemilikan saham pemerintah Republik Indonesia yang 10 % -- akhirnya terlaksana. Saat ini asset FI diperkirakan US$ 1,3 milyar dengan omzet sebesar US$ 500 juta pada 1991. Sejak berdiri tahun 1967, perusahaan modal asing pertama di zaman Orde Baru ini secara bertahap melaksanakan Indonesianisasi. Hanya tujuh tahun setelah beroperasi di Indonesia, jabatan Direktur Utama sudah diserahkan pada orang Indonesia asli: Ali Budiardjo. "Yang paling mengesankan di Freeport adalah proses Indonesianisasi," kata Ali ketika ia menyerahkan jabatan Direktur Utama pada Usman Pamuntjak tahun 1985 lalu. Kini, di tangan Hoediatmo Hoed, Freeport mendapat izin untuk memperpanjang kontraknya sampai tahun 2021. Ini berarti perpanjangan delapan belas tahun dari kontrak pertama (tahun 1967) yang akan berakhir tahun 2003. Di samping itu, dari 100.000 ha, areal penambangannya diperluas hingga 2,6 juta ha. Tapi dengan perpanjangan kontrak itu, Freeport tak lagi mendapat keringanan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Bumi dan Bangunan seperti selama ini. Kini, FIC diharapkan mampu menyetor dana yang lebih besar pada pemerintah. Pada tahun 1990 misalnya, FIC menyetor US$ 51,8 juta yang meliputi PPh sebesar US$ 41,6 juta dan royalti pada pemerintah sebesar US$ 10,2 juta. FIC juga siap mengembangkan kapasitas produksi dari 20.000 ton menjadi 40.000 ton dengan anggaran US$ 511 juta. FIC juga tak lupa membangun kawasan di sekitarnya. Setelah membangun kota Tembagapura, kini FIC menyiapkan dana sebesar US$ 500 juta untuk mengembangkan prasarana di kota Timika, 50 mil dari lokasi penambangan. Asahimas Flat Glass PT Asahimas Flat Glass adalah industri kaca pertama di Indonesia yang berdiri April 1973. Dengan modal awal Rp 5 milyar, Asahimas merupakan usaha patungan Rodamas dengan partner Asahi Glass (Jepang) yang menguasai saham sebesar 49 %. Ketika meresmikan pabrik Asahimas di kawasan Ancol, Menteri Perindustrian M. Yusuf mengharapkan, usaha patungan itu mampu memenuhi kebutuhan kaca dalam negeri sekaligus menembus pasar ekspor. Ternyata, misi itu berhasil ditunaikan oleh Asahimas. Tahun 1989 misalnya, produksi Asahimas mencapai 6,4 juta peti kaca datar dan sebanyak 3,8 juta peti ditujukan untuk pasar domestik. Namun, tahun 1991 kebutuhan kaca domestik meningkat sampai lima juta peti sehingga volume ekspor semakin kecil. Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan itu, sejak Oktober 1990 Asahimas membangun pabrik unit dua dengan kapasitas tambahan 500 ton per hari. Pabrik yang diharapkan selesai tahun 1992 ini akan melipatgandakan kapasitas Asahimas jadi 1000 ton per hari. Jenis kaca yang dihasilkan mulai dari ketebalan 2 mm sampai 19 mm dengan desain dan teknologi yang masih diimpor dari Jepang. Dari seluruh produksi kaca Asahimas, sekitar 65 % di antaranya masih dipergunakan untuk kebutuhan kaca bangunan. Sedang untuk kebutuhan industri mobil, Asahimas mendirikan industri khusus, PT Asahimas Jaya Safety Glass. Yang disebut terakhir ini diarahkan memenuhi kebutuhan industri perakitan mobil di Indonesia, yang produksinya 270.000 unit pada 1991. Di samping itu, Asahimas sedang bernegosiasi dengan PT Purnomo Sejati Industrial, sebuah industri kaca di Surabaya. Diharapkan industri kaca patungan itu akan menambah kapasitas produksi kaca Indonesia sampai 500 ton per hari. Majalah Glass International terbitan Inggris, yang menyebut Asahimas sebagai pionir industri kaca di negeri ini, memperkirakan pada tahun 1995 Indonesia akan jadi eksportir gelas terbesar di Asia Pasifik. Cold Rolling Mill Indonesia (CRMI) Ibarat orang melepas bara, baik investor asing maupun pihak swasta nasional berlomba melepas saham mereka dari PT Cold Rolling Mill Indonesia (CRMI). Karena itu pula dalam tujuh tahun saja, CRMI langsung berubah status dari PMA ke PMDN. Dan sejak Oktober 1991, CRMI, yang merupakan pabrik baja canai dingin ini, resmi menjadi BUMN di lingkungan Krakatau Steel. Ada apa? Sejak beroperasi pada tahun 1984, CRMI terus merugi. Pernah dalam satu tahun, pabrik ini tekor sampai 825 juta dolar. Utangnya pun terus membengkak. Gambaran suram ini menggoyahkan komitmen pemilik PT Kaolin Indah Utama (Liem Sioe Liong dan Ciputra) pada CRMI. Kaolin menguasai 40% saham CRMI, sementara Sestiacier S.A. dari Belgia menguasai 20%. Sejak tahun 1990, tahap demi tahap ketiga swasta itu mencoba melepas saham mereka. Pada akhir 1990, saham swasta asing dan nasional tinggal 15%. Puncaknya adalah Oktober 1991. Semua saham mereka di CRMI, tandas tak bersisa. Caranya? Tak pernah jelas benar. Yang pasti, untuk menebus saham-saham tersebut, Krakatau Steel telah menyuntikkan modal tambahan sebesar 290 juta dolar plus mencari pinjaman baru sebanyak 560 juta dolar. Hasilnya, "Utangutang masa lalu telah kami lunasi," kata Tungky Ariwibowo, Menteri Muda Perindustrian yang juga menjabat Dirut di sana. Belum lagi misteri alih saham swasta itu terungkap, Tungky mengumumkan bahwa CRMI berhasil melunasi semua utangnya akhir tahun lalu. Tak lupa dipaparkannya bahwa pada semester I 1991, CRMI berhasil meraih laba Rp 19 milyar. Kabarnya, CRMI baru dapat memetik untung setelah memproduksi sebanyak 680 ribu ton -- 80% dari kapasitas terpasang, 850 ribu ton setahun. Target itu baru pada tahun 1990 bisa dicapai. Ada memang faktor yang memungkinkan CRMI bergerak lebih efisien. Dengan menjadi anak Krakatau dan tanpa ikut modal swasta, produk CRMI terbebas dari pajak penjualan dan PPN. Tapi dua keringanan itu nilainya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, terlalu kecil untuk membuat si canai dingin melaba dengan cepat. Lantas kenapa? Tungky pekan lalu, hanya berkomentar, "Masalah CRMI sudah beres. Pokoknya semakin majulah." PT Inalum Jika Anda ingin mengetahui model kerja sama dengan swasta asing (Jepang) yang retak, Asahanlah proyeknya. Tepatnya, industri aluminium PT Inalum yang berlokasi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Di perusahaan ini, tiga tahun lalu, pernah terjadi perselisihan seru dan alot antara pihak Indonesia dan Nippon Asahan Alumunium. Kalau Menko Ekuin Radius Prawiro tak segera turun sebagai penengah, silang pendapat itu diperkirakan bisa merembet ke tingkat pemerintahan (Indonesia vs Jepang). Silang selisih ini memang sempat mengundang campur tangan para pejabat Jepang. Mereka sampai berulangulang mengingatkan agar pihak Otorita Asahan mengalah. Dan ini bukan peringatan sembarangan. Soalnya, pihak Jepang mulai mengaitkan perselisihan itu dengan besarnya pinjaman yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Untunglah "perang" ini tak berkepanjangan. Setelah Radius menengahi, soal pembagian hasil produksi (yang menjadi sebab munculnya perselisihan tersebut) bisa dimusyawarahkan. Artinya, pihak Jepang menyetujui penambahan alumunium bagian Indonesia sesuai dengan besarnya saham yang dikuasai, yakni 41% dari total produksi yang 190 ribu ton per tahun. Sisanya yang 59% merupakan bagian lima perusahaan Jepang (Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Showa Denko, dan Nihon Keikinzoku) yang menjadi pemegang saham asing dan tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium. Tapi bukan hanya itu yang akhirnya disetujui kedua belah pihak. Dalam perjanjian berikutnya, awal 1989, Indonesia memperoleh kebebasan untuk mengekspor aluminium yang menjadi bagiannya. Padahal Indonesia sebelumnya hanya diperkenankan menggunakan jatahnya untuk keperluan dalam negeri. Dan kalaupun hendak mengekspor, diharuskan melalui Nippon Aluminium Asahan. Kini suasana di pabrik yang menelan investasi 2 milyar dolar itu sudah lama adem. Tapi dari sana bisa diperoleh pelajaran yang sangat berharga, terutama tentang betapa pentingnya sebuah perjanjian kerja sama yang rinci dan ketat. Liston P. Siregar dan Budi Kusumah
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini