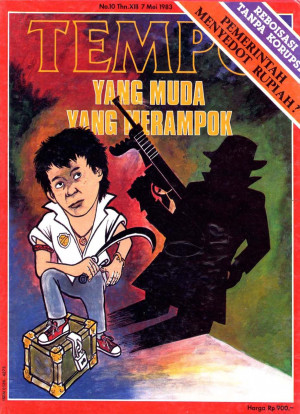THAILAND adalah negeri dengan peninggalan kebudayaan yang kaya.
Di sana terdapat kuil-kuil kuno berusia ratusan tahun. Kehidupan
rakyat yang penuh warna-warni -- mulai dari orang-orang Islam di
selatan sampai suku Meo di utara.
Tapi semua itu tak banyak menarik hati turis pria. Sebagian
besar mereka datang ke Thailand adalah untuk menikmati
keramahtamahan industri hiburan yang didukung oleh gadis-gadis
bar, penari go-go, dan sejumlah panti pijat. Pusat segala
industri jasa itu adalah Bangkok -- nama yang sudah kesohor ke
mana-mana.
Tahun 1980, Dinas Pariwisata Thailand mencatat hampir 2 juta
pelancong datang ke negeri itu. Selama tinggal di sana mereka
menghabiskan US$ 870 juta.
Kini pariwisata merupakan salah satu sumber pemasukan valuta
asing terbesar bagi Thailand. Ia bahkan memukul industri gula --
yang sebelumnya nomor dua setelah beras.
Melambungnya industri hiburan di Thailand ada kaitannya dengan
kehadiran tentara Amerika dan sekutunya dalam Perang Vietnam
lalu. Seperti biasanya personil militer, yang jauh dari sanak
keluarga, selalu haus hiburan.
Semula diduga, setelah perang selesai, industri hiburan di
Thailand akan mati. Ternyata tidak. Ia bahkan bangkit, kali ini,
dengan tumbuhnya pariwisata.
Tahun-tahun terakhir ini "pariwisata seks" merupakan bisnis
besar di Thailand. Menurut sebuah laporan PBB, pengikut
pariwisata jenis ini pria, baik perorangan maupun kelompok. Ada
kalanya paket ini diberikan kepada sejumlah karyawan -- semacam
bonus perusahaan.
Peserta "pariwisata seks" bisa memilih wanita pasangannya
sebelum berangkat -- melalui album, tentu saja. Tetapi bisa juga
menentukan putusan segera setelah menginjakkan kaki di Thailand.
Tak ada soal. Di mana-mana, di negeri ini, "dara-dara nan
eksotis" mengimbau dari segala penjuru.
Sekali-sekali harga diri bangsa ada juga diperhitungkan. Pada
awal 1980, misalnya, Dinas Pariwisata Muangthai mengimbau
biro-biro perjalanan untuk sedikit menahan diri. Mereka
dianjurkan untuk menitikberatkan promosinya pada kuil-kuil yang
bersejarah atau keindahan alam. Tetapi seruan itu tidak
mendatangkan perubahan berarti.
Lebih 500 ribu wanita muda ambil bagian dalam "industri" yang
asyik ini. Mereka beroleh pendapatan antara 1.000 (sekitar Rp
25.000) sampai 15.000 sebulan. Menurut Dr. Pasuk Phongpaichit,
seorang ahli ekonomi yang mengamati gejala "industri hiburan",
perubahan drastis dalam bisnis ini berakibat besar kepada
keseimbangan tenaga kerja dan pendapatan.
Namun demikian, turisme tidak bisa dijadikan satu-satunya
kambing hitam dalam berkembangnya pasar pelacuran Muangthai. Ia,
konon, ditunjang dan ditenggang pula oleh faktor sosiokultural,
bahkan sistem ideologi dan politik. Bagaimana ceritanya?
Menurut sebuah undang-undang tahun 1960, pelacuran digolongkan
barang haram di Thailand. Setiap orang yang kedapatan terlibat
dalam urusan ini, termasuk memiliki fasilitasnya, diancam
hukuman kurungan 3 sampai 12 bulan, atau denda 1.000 sampai
2.000. Namun sudah menjadi rahasia umum, hiburan jenis ini bisa
dibeli melalui 120 panti pijat (hanya satu di antaranya pijat
tradisional Thai), 119 tempat cukur, 97 klub malam, 248 kedai
kopi, dan 394 tempat disko itu baru di Bangkok saja.
Tempat hiburan itu terdaftar secara sah sebagai bar atau rumah
makan. Masyarakat juga mafhum semua tempat itu mendapat
perlindungan polisi setempat. Karena itu, jangan heran, jarang
sekali polisi nongol ke sana. Kalau pun sampai terjadi, biasanya
soal "uang keamanan" ekstra.
Perkembangan industri seks di Thailand harus dilihat dari segi
ekonomi, sosial, dan sejarah. Seperti dalam banyak kebudayaan
dengan sejarah aristokrasi, wanita biasanya ditempatkan sebagai
status simbol ketimbang tenaga produksi. Sementara itu, wanita
dari kalangan lebih rendah sering kali menjadi korban
pelampiasan nafsu belaka.
Pola ini kemudian bertahan bahkan berkesinambungan -- setelah
aristokrasi kehilangan kekuatan politiknya dan digantikan oleh
kaum birokrat dan pemimpin militer. Tradisi poligami dan
perseliran lalu tampak sebagai "adab" yang jamak.
Lewat studi mendalam di dunia panti pijat Bangkok, Dr. Pasuk
menemukan, ledakan urban Thailand memperlihatkan dua
perkembangan penting di lapangan seks. Pertama, berkembangnya
pelacuran. Dan kedua, diakuinya semacam "hak" kaum berkuasa dan
kaya untuk memelihara lebih dari seorang istri.
Pendek kata keadaan sekarang ini banyak berbeda dengan kebiasaan
di masa lampau. Mempunyai beberapa istri atau "simpanan" sudah
dipandang biasa. Sebaliknya, kalangan miskin beroleh semacam
kebanggaan bila sesekali mampu "berbelanja" ke rumah bordil.
Bentuk lain dari eksploitasi seks, menurut Pasuk, adalah kontes
kecantikan. Kesempatan seperti itu biasanya digunakan para tokoh
politik yang berkuasa untuk berburu istri muda. Seringkali
kontes dimenangkan gadis-gadis dari kawasan utara Muangthai --
yang memang kesohor sebagai gudang wanita rupawan. Maka, jangan
heran, 75% pelacur Thai datang dari kawasan ini, plus sedikit
dari daerah timur laut.
Di samping itu harus pula diperhitungkan peranan wanita Thai
secara tradisional -- terutama di masyarakat terpencil. Sudah
turun-temurun wanita Thai memegang peranan sosial dalam
mengemban tanggung jawab ekonomi. Antara lain, mengatur belanja
rumah tangga.
Wanita Thai juga mengambil tempat penting dalam perimbangan
tenaga kerja. Menurut survei tenaga kerja 1978, jumlah wanita
Thai yang bekerja mencapai 70% jumlah kaum pria. Atau sekitar
2f3 jumlah wanita dewasa.
"Faktor ekonomilah terutama yang membuat kaum wanita memilih
pekerjaan pelacur," tulis Yuli Ismartono, pembantu TEMPO di
Bangkok. Kawasan utara dan timur laut Thailand, gudang wanita
cantik itu, juga terkenal sebagai daerah miskin.
Sebuah studi Bank Dunia mengungkapkan, pendapatan per kapita
penduduk kawasan ini adalah 188 -- terendah di seluruh Thailand.
Di Bangkok, angka pendapatan per kapita itu tercatat 605.
Sedangkan angka rata-rata adalah 1.324.
Karena itu tidak mengherankan bila wanita muda dari daerah
tergerak pindah ke kota beramai-ramai. Didorong oleh tradisi
membantu keluarga mereka datang ke Bangkok dengan niat mencari
kekayaan. Dan jalan yang paling gampang adalah mengambil bagian
dalam pasar seks -- yang juga sudah mendapat pengakuan
tradisional. Dalam kata-kata Dr. Pasuk, "industri pelayanan seks
di Bangkok dengan demikian bertahan kukuh . . . dan tampil
sebagai bagian logis sosio-ekonomis Muangthai masa kini."
Di Desa Dok Kam, sekitar 500 km di utara Bangkok, orangtua Noi
baru saja membuat sumur untuk menjamin persediaan air minum
mereka. Tiga tahun lalu, keluarga petani miskin dengan tujuh
anak ini tidak mempunyai sumber air minum. Kediaman mereka pun
tidak lebih dari teratak beratap ilalang.
Keluarga ini sangat berterima kasih kepada Noi yang bekerja di
Bangkok. Setiap bulan ia mengirim uang ke kampung. Kini keluarga
itu menempati rumah, meskipun sederhana, terbuat dari kayu.
Dalam pikiran keluarga ini, tentulah Noi menjadi tukang jahit
yang sukses, dan memiliki kedai sendiri di Bangkok sebagaimana
cita-cita putrinya dulu.
Tetapi Noi bukan seorang penjahit. Para penjahit sudah beruntung
bila berhasil mengumpulkan sekitar 12.000 sebulan -- jumlah yang
paspasan untuk hidup di Bangkok. Noi mampu mengirim duit ke
kampung karena bekerja di sebuah panti pijat. Dan lebih dari
itu, ia memberikan pelayanan seks kepada langganan yang
membutuhkan.
Di tempat ini ia bisa mencapai penghasilan lima kali dari yang
diperoleh seorang penjahit. Setiap malam, bahkan kadang siang
hari, Noi duduk dan menunggu bersama 300 wanita muda lainnya.
Mereka dipajang di sebuah show room yang luas dengan kaca satu
arah. Dari balik kaca itulah para peminat menaksir dan memilih
pasangannya.
Pilihan dijatuhkan menurut nomor yang disematkan di baju
masing-masing wanita itu. Setelah membayar tarif yang
ditentukan, para wanita ini bisa dibawa untuk minum-minum atau
bercengkerama di kedai kopi. "Tetapi biasanya mereka langsung
menuju kamar di lantai atas," tulis Yuli Ismartono dalam
laporannya.
Jika nasib lagi baik, wanita seperti Noi bisa mengumpulkan
sekitar 10.000, plus kemungkinan mendapat bonus. Jumlah ini
sekitar 25 kali pendapatan rata-rata golongan menengah di
lapangan pekerjaan lain.
Statistik yang tepat agak sulit diperoleh. Tetapi menurut
perkiraan, sekitar 500 ribu wanita terlibat dalam bisnis ini.
Atau 10% dari jumlah wanita dalam kelompok usia 14-24 tahun.
Ketika Dr. Thepanom dari Universitas Mahidol melakukan studi
tentang kesehatan para pelacur di Bangkok, 1964, polisi
memberikan angka 400 ribu.
Beberapa gadis seperti Noi sebetulnya datang ke Bangkok dengan
itikad baik. Mereka mengharapkan bisa memperoleh pekerjaan yang
patut. Misalnya, menjadi salesgirl, waitress, penjahit pokoknya
pekerjaan yang tidak memerlukan terlalu banyak keterampilan.
Beberapa bahkan memilih untuk menjadi pembantu rumah tangga.
Tetapi, tidak lama kemudian, mereka segera tergoda oleh rezeki
lebih besar yang ditawarkan berbagai bar dan panti pijat. Banyak
pula gadis yang langsung dari desa terjun ke panti pijat.
Biasanya mereka dihubungkan oleh teman atau bahkan sanak famili.
Mereka, tentu saja, dijanjikan kehidupan mewah dan gaji yang
menarik. Dengan demikian, bahkan para orangtua gadis-gadis itu
mendorong anaknya untuk berangkat.
Begitu berada di Bangkok, dan mendapatkan dirinya sebagai
pelacur, para wanita itu pada mulanya mengalami kekecewaan.
Tetapi pilihan lain hampir tidak ada. Meski tidak menyenangi
pekerjaan itu, sebagian besar mereka segera memahami keadaan.
"Saya membenci pekerjaan ini," kata Noi, "tetapi saya
berkewajiban membantu keluarga. Sedang saya tak punya kebiasaan
lain."
Noi tidak menilai pekerjaan ini aib -- kendati sadar banyak
orang memandang rendah para wanita seperti dia. Baginya, bisnis
seks sama sahnya dengan bisnis lain.
Noi, 23 tahun, yang sudah tujuh tahun melacur, tetap melihat
pekerjaan ini sebagai profesi sementara. Membanting tulang
sekarang, sambil menabung untuk persiapan "pensiun"
sewaktu-waktu. "Saya ingin membuka bisnis menjahit pakaian suatu
ketika," katanya.
Namun tidak semua wanita muda itu seberuntung Noi: bisa
merencanakan saat "pensiun", dan bekerja di tempat yang relatif
aman dan menyenangkan. Seperti bisnis lain, rumah-rumah hiburan
ini juga terbagi dalam beberapa kelas.
Memang banyak panti pijat mewah dan gemerlapan yang bisa
dibandingkan dengan hotel-hotel kelas satu. Tetapi, tidak kurang
pula tempat serupa yang meladeni hajat buruh kasar, sopir, dan
golongan berpenghasilan rendah lainnya. Tempat-tempat seperti
ini biasanya gelap, kotor, dengan perlengkapan yang sangat
sederhana. Seorang gadis yang memulai "karir"nya di tempat
begini sulit diharapkan bisa meningkat.
Dalam kasus Noi, keputusan menjadi pelacur itu boleh dikatakan
sukarela, meski pada mulanya ingin pekerjaan lain yang "sah".
Tetapi bagi gadis lain, dan mungkin bagi sebagian besar mereka,
profesi itu datang sebagai suatu paksaan. Misalnya, setelah
menerima atau meminjam uang dari seorang agen atau perantara.
Contoh yang khas bisa diambil dari kasus Lek. Dua tahun lalu,
orangtua Lek meminjam uang 2.000 dari seorang rekan. Sebagai
imbalannya, Lek, 20 tahun, harus bekerja di kantor rekan tadi di
Bangkok. Rekan ini ternyata "perantara" dan yang disebut
"kantor"nya itu tidak lebih dari sebuah panti pijat kelas
murahan. Dalam keadaan seperti itu Lek tidak bisa mendapatkan
uang untuk dirinya sendiri.
Ketika utang hampir lunas Lek bersiap-siap pulang ke kampung.
Tetapi mendadak ayahnya datang dan membuat pinjaman baru. Dengan
sendirinya "masa bakti" Lek di panti pijat itu diperpanjang dua
tahun lagi. Harapan untuk keluar bertambah kecil.
Sekali terjun ke dalam bisnis ini harapan keluar tipis sekali.
Semuanya tergantung belas kasihan para majikan. Tidak ada jam
kerja yang pasti. Jaminan kesehatan sangat rendah. Bahkan tidak
jarang para wanita itu menerima siksaan badan. Perlindungan
hukum pun hampir-hampir tidak bisa mereka harapkan.
Kendati sebagian besar wanita itu ingin memilih pekerjaan lain,
beberapa di antaranya toh menerima nasib dengan tawakal. Mereka
menyimpan uangnya berdikit-dikit dan mengharapkan suatu ketika
"kembali ke masyarakat. Mereka selalu berangan-angan tentang
munculnya seorang "juru selamat", seorang pengusaha kaya atau
seorang asing, yang mengangkat mereka dari lembah durjana itu ke
dunia yang sama sekali berbeda.
Akibat bisnis ini pun mudah sekali dibayangkan. Dalam penelitian
Dr. Thepanom terhadap seribu pelacur, 41% menderita penyakit
kelamin. Dan dalam penelitian yang dilakukan klinik pemerintah
pada 1979, dari 700.000 penderita penyakit kelamin, 100.000
adalah para wanita yang memberikan "pelayanan khusus". Di
samping itu, 71% penderita lelaki mengaku mendapat penyakit itu
dari berhubungan dengan pelacur.
Pengguguran kandungan merupakan sisi lain industri hiburan.
Karena aborsi dilarang oleh hukum Thailand, pekerjaan itu
dilakukan di lorong-lorong belakang, dengan segala risikonya.
Ada juga penggunaan obat bius, termasuk heroin, oleh sebagian
wanita itu. Dalam penelitian Dr. Thepanom, 25% di antara wanita
ini menggunakan amphetamine, seconal, dan heroin. Beberapa di
antara mereka mengaku menjadi langganan minuman keras.
Sikap masyarakat terhadap "industri" yang sedang berkembang ini
sulit ditentukan. Kadang-kadang sikap mereka keras. Misalnya,
ketika dua kapal perang Amerika berlabuh di dekat Pattaya dan
melepas ratusan pelautnya ke daerah hiburan sekitar sana,
sekelompok rakyat turun ke jalan memprotes. Tetapi sikap itu
tidak bisa dijadikan standar.
Kalangan atas melihat persoalan ini sebagai gejala lapisan bawah
yang berpendapatan rendah -- kendati para langganan bisa saja
datang dari kelompok elite. Sedangkan di daerah udik, tempat
asal para pelacur, masyarakat biasanya lebih toleran. Rakyat di
sana hanya mencemooh wanita yang pulang kampung tanpa membawa
kekayaan bagi sanak familinya. Mereka tidak peduli apakah
kekayaan itu datang dari hasil menjual badan.
Jika pun ada suara keras menentang pelacuran ia lebih bersifat
menggugat sifat eksploitasi dan paksaan dalam profesi ini. Juga
semacam tuntutan agar para pelacur mendapat perlidungan yang
lebih jelas. "Kita harus realistis," kata bekas ketua Asosiasi
Pengacara Hukum Wanita Khunying Khanita Wichiencharoen. Khunying
adalah gelar yang diberikan raja untuk para bangsawan dan wanita
yang diakui berprestasi.
"Sepanjang komoditi ini masih dibutuhkan, dan selama keadaan
ekonomi belum memberi alternatif lain, kita tidak bisa
mengharapkan pelacuran dibasmi," kata Khunying Khanita. "Jadi,
lebih baik kita berusaha agar para wanita ini mendapat hak-hak
mereka, dan menerima perlakuan serta upah yang lebih layak
seperti dalam bisnis lainnya."
Khunying Khanita dan sejumlah simpatisannya percaya bisnis akan
lebih mudah diatur bila pemerintah mendaftar semua pelacur.
Dengan demikian standar juga bisa ditetapkan dan para wanita
mendapatkan perlindungan. Tetapi tidak semua orang sependapat
dengan gagasan ini.
Dua tahun lalu, sebuah rancangan untuk mengesahkan pelacuran
ditolak mentah-mentah oleh parlemen Thailand. Sejak itu masalah
ini tidak pernah dibicarakan lagi.
Kalangan yang menentang pengesahan pelacuran juga tidak
kekurangan alasan. Karena para gadis itu terjun ke dalam profesi
ini lantaran tekanan ekonomi, "mengesahkan pelacuran sama
artinya dengan mengakui kegagalan pemerintah memberikan
alternatif pekerjaan yang lebih berharga," kata mereka.
"Pemerintah akan tampak seperti calo," ujar seorang sosiolog
yang mati-matian menentang segala bentuk pengesahan pelacuran.
Padahal, sementara itu, setiap orang maklum akan industri seks
Thailand yang terus meningkat -- dan menunjang perekonomian
negeri itu. Lalu, bagaimana jalan keluarnya?
Untuk Thailand, jalan keluar dari masalah ini mungkin berbeda
sekali dengan pemecahan yang ditempuh negeri Asia lain. Sebuah
laporan PBB mengungkapkan program rehabilitasi dan moralisasi
dalam masalah industri hiburan ini memperlihatkan hasil yang tak
memadai.
Yang dibutuhkan, agaknya, ialah sebuah jalan keluar yang
realistis, berpandangan jauh, dan dalam jangka panjang. Yang
mempertimbangkan faktor sosiokultural, politik, dan ekonomi.
Yang . . . pendeknya, terpadu.
Tetapi yang paling penting, menurut laporan itu, adalah
identifikasi yang lebih akurat tentang apa yang biasanya
dinamakan "problem kelompok". Ada kecenderungan tradisional pada
masyarakat untuk memandang para pelacur sebagai kelompok yang
memerlukan rehabilitasi. Padahal, dalam kenyataannya, "problem
kelompok" ini menyangkut banyak hal.
Ia bersangkut paut dengan masalah pria dewasa yang merasa berhak
mendapat pelayanan seksual asal mampu membayar. Ia juga
menyangkut para agen, perantara, dan calo yang menarik
keuntungan dari perdagangan seks ini. Dan ia juga menyangkut
peranan para orangtua yang menjual anak-anak mereka dalam bisnis
ini. Pokoknya menghapuskan bisnis maksiat ini, rumit deh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini