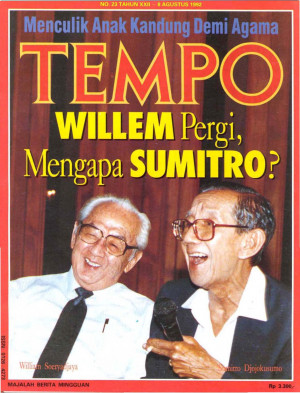"HARADA menghendaki diriku penuh untuk dirinya sendiri. Bagi tamu-tamu perkebunan itu tidak dirasakan kehadiran diriku. Kalau kebetulan sedang ada tamu di perkebunan itu, aku dilarang untuk menampakkan diriku. Tamu cukup dilayani oleh wanita-wanita yang lain," -- (Kadarwati, Wanita dengan Lima Nama, novel karya Pandir Kelana, halamana 41). TAK semua wanita yang jatuh di kaki tentara Jepang lalu dijebloskan ke bordil dan menjadi jugun ianfu atau wanita penghibur yang ikut tentara. Ada saja perwira atau pimpinan Jepang yang lain yang lalu melindungi wanita itu untuk dirinya sendiri. Dan mereka bukan cuma Harada, tokoh fiktif dalam novel Kadarwati yang dikutip dalam awal tulisan ini, yang menjadikan Kadarwati semacam wanita simpanannya. Mereka, orang Jepang yang dulu terlibat Perang Asia Timur Raya dan pernah bertugas di wilayah Indonesia, sebagai tentara atau bukan, memang belum ada yang menceritakan pengalaman mereka menyimpan wanita Indonesia. Tapi beberapa wanita Indonesia yang pernah terpaksa mengalami dipiara Jepang mengungkapkan pengalaman mereka pada wartawan TEMPO. Salah satu wanita itu kini tinggal di Solo. Ia tak mau disebutkan namanya, karena malu kalau sampai diketahui tetangganya. Ketika tentara Dai-Nippon menduduki Jawa pada tahun 1942, ia baru 16 tahun, tinggal di Solo bersama ayah dan lima saudara kandungnya. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil. Ayahnya menjadi serdadu Belanda, dan sering dikirim ke luar Solo. Suatu hari datang orang mengabarkan bahwa bapaknya terbunuh oleh Jepang dalam sebuah pertempuran. Maka, ia dan saudara-saudaranya, sejak Jepang datang itu, harus mencari makan sendiri. Suatu hari ia diajak oleh seorang temannya melamar pekerjaan di sebuah restoran Jepang di Cepu, Jawa Tengah. Diterima. Selain memasak, ia juga melayani pembeli yang kebanyakan orang Jepang. Di sinilah ia bertemu dengan Yata Masami, serdadu Nippon yang masih muda, kira-kira 25 tahun. "Tubuhnya kencang dan gagah. Ketika pertama kali melihat saya, ia tampak terpesona," ceritanya. Ia sendiri waktu itu, menurut perasaannya, tergolong cantik dan seksi. Dada dan pantatnya berisi. Lehernya jenjang. Sosoknya termasuk tinggi semampai bila dibandingkan dengan kebanyakan perempuan Solo waktu itu. Kulitnya kuning langsat. Singkat kata, Masami lalu sering berkunjung ke restorannya dan memberikan tip padanya. "Jadi saya pun melayaninya dengan manis," tuturnya. Suatu petang Masami bertindak lebih jauh. Ia menariknya ke kamar mandi restoran. "Seluruh tubuhku dirara-raba. Saya gemetaran. Saya meronta. Akhirnya saya bisa melepaskan diri," ceritanya. "Malamnya, saya tak bisa tidur. " Lain hari Misima datang lagi dengan sejumlah kawannya. Kali ini khusus untuk mabuk-mabukan. "Dengan bahasa Indonesia yang grothal-grathul, saat itu ia memuji kecantikan saya dan mengaku menyukai saya," kata wanita yang kini 66 tahun itu. Hari itu tak terjadi apa-apa kecuali seperti yang biasa dilakukan oleh serdadu Jepang terhadap pelayan restoran: mencolek-colek seenaknya. Suatu malam, Masami datang lagi. Sendirian saja. Ia kali ini minta ditemani. Kali ini Masami memberi tip agak banyak. Lalu, usai makan, tentara itu mengajaknya ke kamar kecil yang terletak di bagian belakang restoran itu. Ia tak tahu mengapa ia menurut. Ketika itulah ia tak kuasa menolak paksaan si serdadu itu. Dan kemudian hubungan itu sering berlangsung. "Kadang saya diajak jalan-jalan, pergi ke suatu rumah berdua saja," tuturnya. Yang pasti, mereka lalu hidup bagaikan suami-istri. "Dia butuh hiburan. Saya menghiburnya. Dia suka, saya suka. Maka, hiburan kami jadi menyenangkan." Apalagi, katanya, Masami berjanji membawanya ke Jepang, sehabis perang. akhirnya ia hamil. Masami senang. Suatu hari mereka harus berpisah. Masami ditugaskan ke medan perang. Ketika itu kandungannya berusia lima bulan. Ia pun pulang ke Solo untuk melahirkan di rumah salah seorang saudaranya. Tiba saatnya, anak itu lahir dan diberinya nama Masako, nama yang diminta Masami sebelum pergi. Namun, sejak itu Masami tak muncul-muncul. Ia terpaksa bekerja lagi sebagai pelayan di restoran Jepang yang lain. Tapi kini ia tak akan membiarkan bila ada Jepang lain yang berani menariknya ke kamar kecil. "Saya bukan pelacur. Cuma Masami yang pernah berhubungan dengan saya. Kami saling mencintai," katanya. Dan memang tidak ada tentara Nippon lain yang mencoba mengganggunya. Mereka, katanya, menghormati Masami. Ia mengaku setia menunggu Masami. Kepada tiap tentara Jepang yang datang ke rumah makannya, ia selalu menanyakan kabar Masami. Sialnya, tak ada yang tahu. Sampai akhirnya Jepang kalah, Republik Indonesia diproklamasikan, Masami tak pernah muncul lagi. Maka, ia pun memutuskan kawin lagi dengan orang Sunda dan dikaruniai anak pula. Kini ia tinggal bersama salah seorang anak dari suami Sundanya. Suaminya itu sudah meninggal beberapa tahun lalu. Adapun Masako tinggal tak jauh dari tempatnya kini tinggal, juga sudah berkeluarga. Sampai sekarang ia mengaku masih ingin mengetahui nasib Masami, hidup atau mati. Ia tak menuntut santunan atau ganti rugi dari pemerintah Jepang. "Tapi, kalau diberi, ya, saya tak menolak," katanya. Yang ia minta dari pemerintah Jepang saat ini adalah kabar suaminya. "Kalau ia sudah mati, di mana kuburnya. Kalau masih hidup, bagaimana caranya saya dan Masako, anaknya, bisa bertemu dengannya." Itu harapannya. KISAH PENJUAL JAMU GENDONGAN Dari Barongan, Kudus, Jawa Tengah, seorang penjual jamu gendongan bernama Djamirah, 62 tahun, menuturkan riwayatnya. Tatkala Jepang datang, ia baru 12 tahun. Biarpun masih kencur, tubuhnya subur. Ditambah sedikit pupur, kecantikannya membikin Jepang tergiur. Di kampungnya, katanya, waktu itu ia memang kembang desa. Djamirah tak tahu mengapa ia lalu termasuk yang dipilih oleh pamong desa setempat untuk dipekerjakan di pabrik goni di Desa Jatikulon, masih kawasan Kudus. Ia pun heran mengapa yang dipilih kebanyakan perempuan. Ia hanya mendengar-dengar bahwa semua itu adalah permintaan Jepang yang belum lama mendarat di Jawa. Begitu masuk, Djamirah yang masih 12 tahun ini langsung diangkat menjadi hanco -- mandor. Ia pun heran mengapa ia yang dipilih, padahal banyak wanita yang lebih tua ketimbang dia. Eh, baru beberapa hari menjadi mandor, ia pun dipindahkan ke rumah Siontani, wakil kepala pabrik. Katanya, ia diberi tugas mengawasi penjahit-penjahit yang bekerja di rumah itu. Ternyata ia memang disuruh mengawasi penjahit di rumah itu, yang jumlahnya cuma tiga orang. Tapi memang ada tugas lain yang tak dikatakan kepadanya. Yakni melayani Siontani di tempat tidur. "Karena takut, saya terpaksa meladeninya," tutur Djamirah. Mulai saat itu, ia menjadi gundik wakil kepala pabrik goni. Beberapa lama kemudian ia tahu, beberapa orang Jepang yang menjadi pimpinan pabrik juga mengambil gundik dari pabrik. Dipilih menjadi gundik Jepang ternyata membawa berkah bagi orang tua dan delapan saudaranya. Selain memberi gaji sekitar Rp 200 per bulan, acap kali Siontani memberinya tambahan uang. Kadang Rp 100, kadang kurang dari itu. Di samping itu, Siontani masih suka menghadiahinya kain bahan pakaian. Itulah mengapa saudara-saudara Djamirah bisa memakai pakaian dari kain, sedangkan kebanyakan orang Jawa waktu itu memakai pakaian dari goni atau lembaran karet. Tiga tahun berlalu, dan Jepang pun kalah perang. Seperti kisah hubungan Jepang dan gundiknya yang lain, Djamirah juga terpaksa berpisah dengan Siontani yang pulang ke Jepang. "Suami"-nya itu tak meninggalkan apa-apa selain sebuah mesin jahit Singer dan uang Rp 20. Sepeninggal Jepang, Djamirah kawin secara sah dengan anak seorang ulama. Tujuh bulan kemudian -- cuma tujuh bulan setelah kawin -- ia melahirkan anak perempuan. Djamirah tak bersedia menceritakan siapa sesungguhnya bapak si jabang bayi. Suaminya meninggal tak lama kemudian. Djamirah terpaksa mengongkosi hidupnya dengan bekerja di pabrik tenun di Kudus Kulon. Tahun 1960-an, ia pindah ke pabrik tekstil, lalu berwiraswasta. Sebelum menjadi bakul jamu seperti sekarang, ia pernah menjadi pedagang kain. Kini ia punya sepuluh cucu. DUA LAI DARI TORAJA Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada masa Perang Asia Timur Raya adalah salah satu lumbung perbekalan tentara Jepang. Di Rantepao, masih kawasan Kabupaten Toraja, Jepang membuka pertambangan dan mendirikan pabrik karung bernama Chuwonoschaten Kayogi. Pekerjanya diambil dari penduduk setempat. Jumlah tentara Jepang yang ditempatkan di Toraja, menurut W.L. Tambing, bekas anggota DPR Pusat, tak seberapa, hanya sekitar 1.000 personel. Mereka tak garang, tak menyusahkan penduduk. Setahu Tambing, tak ada wanita Toraja yang dijadikan jugun ianfu. "Yang ada adalah wanita-wanita yang dikawini serdadu Jepang," kata Tambing. Salah seorang di antara wanita itu adalah Lai Rapung, penduduk Desa Barana, desa tetangga Rantepao. Pertengahan tahun 1944, ketika tentara Jepang merambah kampungnya, Lai Rapung masih berusia 18 tahun. Rupanya, gadis ini menarik perhatian Takeda San -- begitu Lai menyebut nama seorang serdadu Jepang. Serdadu itu memaksanya kawin. "Kalau saya tak mau, kepala saya dan kepala ayah akan dipenggal," kenang Rapung. Mereka pun kawin secara resmi. Semula Rapung merasa terpaksa lantaran takut, tapi hari-hari berikutnya ia justru merasa terlindungi dalam dekapan Takeda. Pada zaman pancaroba itu, hidupnya terjamin. "Saya tidak pernah kekurangan sandang pangan. Ia baik sekali," katanya. Sayang, Takeda hanya sebentar memeluknya. Selagi Rapung mengandung tiga bulan, Jepang bertekuk lutut pada Sekutu. Mereka harus kembali ke negerinya. Takeda sempat meninggalkan alamat dan memberi Rapung sejumlah uang, pakaian, dan makanan yang bisa dinikmati selama satu tahun. "Dia berpesan agar menyuratinya bila anak kami lahir. Saya juga disuruh menyusul ke Jepang. Tapi ibu saya selalu menghalangi," cerita Rapung yang kini berusia sekitar 66 tahun. Tampak matanya berkaca-kaca. Enam tahun kemudian ia menikah lagi dengan laki-laki pribumi, dan mereka dikaruniai dua anak. Kata Rapung, anak hasil hubungannya dengan Takeda sekarang tinggal di Jakarta. Ia sudah kawin dan sudah punya anak pula. Anak itu sempat sempat pergi ke Jepang menemui ayahnya. Bahkan kemudian Takeda selalu mengirimi uang kepada anak itu, sampai bekas serdadu Jepang itu meninggal pada tahun 1982. Lai Rapung sendiri tak pernah kebagian satu yen pun. Masih dari Tana Toraja. Seorang nenek bernama Lai Saba, kini 67 tahun, punya nasib serupa dengan Lai Rapung. Ia tinggal di Desa Madandan. Jepang datang, ia bekerja di pabrik karung goni. Karena punya pendidikan cukup tinggi -- lulusan sekolah kepandaian putri setingkat SMP -- ia di angkat menjadi hanco atau mandor di pabrik tersebut. Gajinya 10 sen per bulan, tergolong besar menurut ukuran waktu itu. Lalu cerita zaman itu pun berulang. Yokoyama, bosnya, perlu teman tidur. "Dia memaksa saya agar mau dikawininya. Saya tak berani menolak," tutur Saba. Singkat kata, akhir tahun 1944 itu, ia menjadi istri Yokoyama, di samping tetap menjalankan tugas sebagai mandor. Dari perasaan terpaksa, Lai Saba pun akhirnya bersyukur. Yokoyama orang baik. Kebutuhan Saba terpenuhi semua. Pada 10 Agustus 1945 lahirlah Pang Ronde. Yokoyama hanya sempat menggendong bayinya beberapa saat, karena harus pulang. Jepang menyerah karena dibom atom oleh Amerika beberapa hari kemudian. "Sebelum kami berpisah, dia berjanji akan kembali dan berpesan agar saya tidak kawin lagi," tuturnya. Namun, seperti nasib Rapung, Saba yang menunggu akhirnya yakin bahwa Jepangnya tak bakal menjenguknya. Enam tahun kemudian ia kawin lagi dengan pemuda sekampungnya di Desa Madandan. Mereka memperoleh delapan anak. Ia tak pernah mendengar kabar tentang Yokoyama sekalimat pun. "Mungkin ia sudah meninggal," kata Saba. IA DIBELIKAN KUDA Seorang wanita yang kini berusia 67 tahun, tinggal di Kotamobagu, ibu kota Kecamatan Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara, juga menyimpan kenangan. Sebut saja nama samarannya Dince Pangalia. Sewaktu Jepang memasuki Minahasa, ia berumur 20 tahun. Kizuke Saito, yang diberi tugas menjadi kepala polisi di situ, rupanya jatuh hati padanya, lalu melamarnya. Tentu, tak ada kata menampik bila seorang serdadu atau polisi Jepang melamar wanita di kawasan yang didudukinya. Singkat kata, Dince merasa beruntung. Sebab, kemudian ia tahu sekitar 200 wanita Minahasa juga dibawa Jepang, tapi dimasukkan ke bordil. Sewaktu Kizuke pindah tugas ke Tondano, masih di daerah Minahasa, ia dibawa. "Kizuke baik sekali. Ia tampan. Saya tak pernah disiksa. Sering saya diberi hadiah. Pernah saya dibelikan seekor kuda," tuturnya. Ia hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Reiko. Kemudian Sekutu menguasai Minahasa. Kizuke harus pergi. Dince mengantarnya ke Manado dengan mengendarai kereta kuda. Sebelum mereka berpisah, Kizuke berpesan agar Dince merawat Reiko dengan baik. "Ia tampak begitu sedih. Saya menangis. Tak tahan rasanya menghadapi perpisahan itu." Selain Dince, menurut Victor Simbar, pribumi yang pernah menjadi anggota Ka in Josejo -- salah satu pasukan angkatan laut Jepang -- banyak gadis cantik setempat yang dipelihara tentara Jepang, baik secara paksa maupun baik-baik. Beberapa di antaranya masih hidup, termasuk Dince tadi. Priyono B. Sumbogo (Jakarta), Kastoyo Ramelan (Semarang), Andi Reza Rohadian, Waspada Santing, dan Mochtar Touwe (Ujungpandang)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini