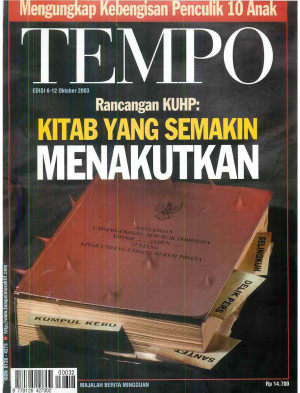Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ni Luh Erniati, 32 tahun
Putu Agus Iriawan, seorang bocah berumur tujuh tahun, kerap melontarkan pertanyaan ini kepada Ni Luh Erniati: ”Bu, kira-kira Bapak lahir kembali di mana, ya?” Mendengar pertanyaan anak sulungnya, ibu dua anak itu, yang tiba-tiba menjanda dalam usia 31 tahun, hanya mengusap matanya. Suaminya, Gde Badrawan, tewas saat bom meluluhlantakkan Sari Club—sebuah tempat hiburan di Kuta, Bali—pada 12 Oktober 2002. Malam itu, Badrawan tengah bertugas di restoran tersebut. Nyawanya langsung lepas bersama puluhan pengunjung Sari Club sesaat setelah ledakan mengguntur.
Gde Badrawan mewariskan dua anak kepada Erni, yakni Agus dan adiknya, Made Bagus Ariadana, yang berumur dua setengah tahun, serta tabungan sebesar Rp 20 juta yang kini sudah ludes untuk biaya pemakaman Badrawan. Erni sendiri masih sulit melepaskan diri dari seluruh kenangan dengan suaminya. Dia dan Badrawan tadinya rekan kerja di Sari Club. ”Karena sering ngobrol di saat bekerja, kami lantas pacaran,” kenang Erni. Dia syok bahwa di Sari Club pula—tempat mereka pertama kali bertemu—Badrawan meninggalkan dia dan dua anak mereka untuk selama-lamanya.
Kedua anak itulah yang membuat Erni terus bertahan. Guna mengasapi dapur, dia belajar menjahit dan membuat tas-tas kecil, selendang, serta suvenir dari kain. Di sela-sela kerja, ibu muda ini mengamati betapa anak sulungnya amat tertekan karena kehilangan ayahnya. Putu Agus suka melamun dan jarang bermain bersama temannya. Bila disapa, dia tiba-tiba menangis dan menanyakan perihal reinkarnasi ayahnya.
Adik Agus, Made Bagus, justru memberikan reaksi yang amat berbeda. Saban kali ada lelaki dewasa datang, Bagus serta-merta mendekati orang itu. ”Mungkin si kecil mengira orang itu bapaknya,” kata Erni. Badrawan memang punya kebiasaan mengajak Bagus bermain setiap kali berada di rumah.
Walau masih muda, Erni tak berniat menikah lagi. Dia khawatir, bila dia menikah, secara adat anak-anaknya menjadi hak keluarga besar suaminya.
Alhasil, kini yang ditekadkan Erni adalah mengumpulkan uang seberapa dapat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu, dia memerlukan biaya besar untuk upacara ngaben suaminya. Untunglah, di tengah kesusahan ditinggal suami, kenalannya asal Australia, pasangan David dan Moira, mengulurkan bantuan. Mereka menyumbangkan biaya hidup Rp 600 ribu per bulan di samping modal usaha serta peralatan jahit.
Bersama lima orang janda korban bom Bali, Erni mendirikan Adopta Co Op, sebuah usaha garmen kecil-kecilan. ”David juga mengundang ahli untuk melatih kami menjahit aneka barang,” tuturnya kepada TEMPO. Erni mengakui, proses bekerja ini tidak mudah karena sebelumnya mereka hanyalah ibu rumah tangga biasa.
David juga mengontrakkan rumah serta bengkel kerja untuk mereka. ”Saya tak tahu sampai kapan mereka membantu. Kami berharap segera mandiri,” katanya. Erni mengaku agak lega bernapas karena biaya sekolah kedua anaknya mendapat sokongan dari Yayasan Bali Kids. Apa pendapatnya tentang hasil sidang para pelaku bom Bali? ”Apa pun vonisnya, hal itu tak akan mengembalikan suami saya,” ujarnya.
Ngesti Puji Rahayu, 41 tahun
Hingga sekarang, Yayuk—panggilan Ngesti Puji Rahayu—masih tak berani melewati jalanan di depan Legian, Kuta. Lebih-lebih di kawasan Sari Club dan Paddy’s Café. Bom Bali masih membekaskan trauma yang mendalam pada diri wanita ini. Suatu ketika, pada awal tahun 2003, Yayuk mengunjungi adiknya di Lawang, Jawa Timur. Ketika mobil yang dia tumpangi melintasi Banyuwangi, Yayuk melihat api membara dari te-ngah ladang. Kontan saja dia menjerit-jerit tanpa terkendali. Padahal jarak api dan mobil itu sekitar 10 meter. ”Saya hampir pingsan karena takut,” katanya.
Beruntung, sopir segera tanggap. Ia menghentikan mobil dan menenangkan Yayuk. Setelah itu, barulah mobil dipacu menuju Lawang, di luar Kota Malang. Yayuk tak tahu kapan ia bisa bebas dari trauma itu. Toh, ia bertekad untuk ikut serta dalam peringatan setahun tragedi bom Bali pada Minggu, 12 Oktober. Katanya, ”Kalau bersama korban bom lainnya, mungkin saya berani.”
Apa yang dialami Yayuk hingga traumanya masih sedalam itu? Pada malam itu, dia nongkrong di Paddy’s Café bersama Desi, teman sekaligus bosnya. Dari tempat kerjanya di Warung Road Kill, di Seminyak, Yayuk dan Desi meluncur ke Paddy’s. Mereka tiba di sana sekitar pukul 21.30 WIT. Baru saja 30 menit mereka bersantai, suara ledakan dahsyat berdentum di kuping Yayuk. Dia masih sempat melihat kilatan cahaya putih sebelum merasa terlempar dalam kegelapan. ”Saya masih melihat bunga api yang memercik dan membakar tangan kiri saya.”
Dari temannya, Yayuk kemudian tahu bahwa dia sempat mengalami koma tiga hari. Saat siuman, dia menemukan wajah, leher, dada, punggung, dan tangannya sudah melepuh terbakar. Kini wajahnya berangsur pulih setelah menjalani operasi plastik di Perth, Australia. Meski begitu, bekas luka bakar di wajahnya tak dapat disembunyikan. Di atas bibirnya terdapat keloid sebesar kacang. Yang lain menempel di dagu kirinya. Rasa nyeri dan gatal masih dia rasakan. ”Hihhh…, rasanya sakit, seperti dicubit,” beberapa kali dia mengeluh selama bersama TEMPO. Ledakan bom itu juga membuat telinga kanannya rusak. Kemampuan mendengar Yayuk kini cuma 75 persen.
Yayasan Bali Hati turun tangan untuk membiayai pengobatan Yayuk. Kini dia sudah bisa bekerja kembali. Enggan kembali ke bidang hiburan malam, Yayuk membantu kegiatan Pendeta Wayan Dwija dan Gayle di Bali. Di samping memperoleh ketenangan, dia mendapat kompensasi uang saku Rp 400 ribu.
Brian Deegan, 47 tahun
Liburan itu telah lama diimpikan ayah dan anak ini: Brian Deegan dan Joshua Deegan. Keduanya datang ke Pulau Dewata pada Oktober tahun silam. Deegan senior sudah menginjak tanah Bali pada 1970-an. Dan dia langsung jatuh cinta pada pulau itu: keindahan alam serta keramahan penduduknya. Tak mengherankan jika Joshua meniru jejak ayahnya dan memilih Bali untuk tempat berlibur. Siapa kira pulau ini kemudian menjadi tempat perpisahan terakhir bagi ayah-anak tersebut.
Saat bom meledak di Paddy’s Café, Joshua Deegan tengah melantai. Anak muda itu tewas, sedangkan ayahnya selamat. Brian sendiri cukup berjiwa besar menerima kematian anaknya. Lima pekan setelah peristiwa itu, Brian, yang sehari-hari bekerja sebagai hakim, menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Australia John Howard di koran The Australian. Dalam surat itu, Brian Deegan menggugat Howard yang mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak. Dia percaya bahwa Australia menjadi sasaran teroris karena apa yang dia nilai sebagai ”aksi ikut-ikutan” Australia.
Tragedi bom Bali, menurut Brian Deegan, membuatnya lebih peka terhadap persoalan kemanusiaan. Ayah empat anak ini bercerita kepada TEMPO begini. Suatu hari, setelah menonton televisi, anak perempuannya yang bernama Eloise bertanya, ”Ayah, mana yang disebut dunia Barat?” Brian menjelaskan, Australia adalah bagian dari dunia Barat. Wajah gadis kecil itu muram seketika. ”Eloise baru 14 tahun. Dia biasanya tak tertarik pada politik. Tapi sekarang dia dibayangi rasa waswas,” tutur Brian prihatin. Sejak saat itu, Eloise segan tidur sendirian.
Awal tahun ini, Brian menyempatkan diri berlibur ke Bali. Di sana, dia menapak tilas ke tempat-tempat yang punya ikatan emosional dengannya, misalnya Jalan Legian—lokasi meninggalnya Joshua. Brian juga mengunjungi Rumah Sakit Sanglah, tempat ia menemukan jenazah Joshua. Sebelum kembali ke Australia, Brian kebetulan mendengar nasib sepasang anak (Sara dan Sabdar) yang ditinggal ibunya di Bali untuk menemui ayah mereka yang dipenjarakan di Australia.
Brian berupaya menemui Sara dan Sabdar. Dia bertekad membawa keduanya ke Australia untuk menemui ayah mereka, Ibrahim Samaki—yang tengah dipenjarakan di Australia. ”Sebagai ayah, saya bisa membayangkan perasaan Ibrahim saat anak-anak itu berpisah dengan ibu mereka, yang menyusulnya ke Australia,” Brian memberikan alasan.
Malang, permohonan visa bagi Sara dan Sabdar ditolak pihak imigrasi Australia. Alasannya, pertemuan Ibrahim dan anaknya yang cuma satu-dua minggu itu tak ada artinya. Phillip Ruddock, Menteri Imigrasi Australia, malah berpendapat, jika Ibrahim ingin bertemu dengan anaknya, dia harus dideportasi dulu ke Indonesia atau Iran.
Brian kecewa dengan sikap pemerintahnya. ”Tak ada manfaatnya? Jika saya diberi lima menit saja untuk bertemu dengan Joshua, saya akan amat bahagia,” kata Brian sambil menggelengkan kepala. Maksud Brian membawa kedua anak itu menemui Ibrahim adalah sebagai ”hadiah” dari Joshua. ”Hubungan ayah dengan anak adalah sesuatu yang istimewa,” katanya
Untuk mengusir kesedihan karena kehilangan Joshua, Brian rajin menulis apa yang dia rasakan setelah kematian putranya. Yang menarik, Brian justru menentang hukuman mati atas para pelaku pengeboman dalam tragedi Bali. Katanya, ”Sebagai hakim, saya terbiasa melihat masalah dari kedua sisi. Saya marah kepada pembunuh anak saya. Tapi sikap pemerintah AS dan Australia juga sama dengan (orang-orang) yang mereka tuduh teroris.”
Lynley Huguenin, 23 tahun
Jauh sebelum bom Bali meledak, Lynley Huguenin sudah kerap melancong ke pulau tersebut. Wanita muda yang berdiam di Boronia, kawasan suburb di Melbourne, itu punya perusahaan impor kerajinan Bali. Pada 12 Oktober tahun silam, Lynley tengah berada di Bali. Hari itu, dia menemui Kim, temannya dari Melbourne, yang datang ke Bali bersama orang tuanya. Setelah makan malam, mereka ramai-ramai ke Paddy’s Café untuk bersantai.
Saat itulah sebuah ledakan dahsyat menggelegar. Lynley dan Kim terlontar ke lantai dekat sebuah meja yang terguling. Lynley berusaha bangkit. Bukan main kagetnya sewaktu dia melihat kilatan api di punggungnya. Tapi dia tidak panik. Cepat saja dia mengguling-gulingkan diri hingga apinya padam. Saat itulah dia melihat Kim terbaring tak berdaya. Bagai disuntik kekuatan ekstra, Lynley berdiri dan memapah Kim keluar dari pintu belakang Paddy’s.
Seorang ibu yang tinggal di dekat Paddy’s kemudian menolong mereka. Dalam keadaan luka parah, Kim dan Lynley dibawa dengan sepeda motor oleh anak lelaki si ibu menuju Rumah Sakit Sanglah. Apa yang dialami Lynley di sana tak kalah mengerikan. Untuk mengobati lukanya, para dokter membersihkan luka bakarnya dari pecahan kaca dan bom tanpa memakai obat bius.
Sekembali ke Australia, Lynley segera dibawa ke Rumah Sakit Alfred, Melbourne, untuk dioperasi. Dokter mencangkok kulit dari bagian tubuhnya yang masih utuh untuk menutup luka di punggung yang terbakar. Lynley menderita luka bakar sebanyak 30 persen dari tubuhnya. Gadis cantik itu sempat merasakan jadi ”mumi” selama dua minggu lebih karena seluruh tubuhnya dibalut. Sembilan bulan sesudah operasi, Lynley harus memakai kaus ketat di seluruh tubuh agar bentuknya kembali normal.
Yang mengharukan dari pribadi wanita muda yang bekerja sebagai ahli kecantikan ini adalah ketegarannya. Dia berkata, ”Saya tak menyalahkan orang Indonesia. Toh, ada juga yang jadi korban.” Lynley mengaku ingin ke Bali untuk ikut memperingati setahun bom Bali. ”Saya cinta Bali. Saya akan ke sana Oktober ini.”
Nagiyah Aprilia, 29 tahun
Nagiyah mengaku tak punya firasat buruk apa pun ketika suaminya, Harna, berangkat kerja pada Selasa, 5 Agustus lalu. Padahal Harna sempat ragu karena tengah membuat mobil-mobilan dari tripleks buat Fachri, anak bungsunya. Saat itu Kamal, ayah Nagiyah, sempat menahan menantunya agar tak bekerja dan menyelesaikan saja dulu mainan Fachri. Tapi garis hidupnya berbicara lain. Sopir taksi Silver Bird itu tetap saja bekerja. Dari pangkalan Silver Bird di Mampang, Harna mengarahkan taksinya ke Hotel JW Marriott di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Baru 15 menit mobilnya nongkrong di lobi hotel mewah tersebut, sebuah mobil Kijang yang berjarak sekitar 30 meter dari tempat Harna parkir meledak. Pria itu tewas bersama tiga rekannya sesama sopir Silver Bird.
Dua bulan telah berlalu sejak kejadian nahas tersebut. Kini giliran Nagiyah yang memeras tenaga dan otak untuk menghidupi ketiga anaknya. Untungnya, ibu muda ini mendapat simpati dari beberapa pihak. Umpamanya, saat acara tabur bunga memperingati bom Marriott pada Agustus lalu, Yayasan Putri Indonesia memberikan beasiswa bagi Gina, yang berusia enam tahun, Dini, empat setengah tahun, dan Fachrial, satu setengah tahun, ketiga anak Nagiyah-Harna. Yayasan ini berjanji menyokong biaya ketiga ayak yatim itu hingga lulus SMU.
Bantuan lain datang dari instruktur senam Berty Tilarso. Berty mengirimkan beras 10 kilogram dan duit Rp 500 ribu setiap bulan bagi Nagiyah. Sedangkan untuk tempat tinggal, dia cukup menumpang di rumah ayahnya di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Nagiyah sendiri tak cuma berpangku tangan. Dia berjualan pakaian anak-anak. Di ruang tamu kediamannya, seluas lima meter persegi, dia menggantung belasan baju anak di sebuah tiang. ”Lumayan, Mas, daripada tidak sama sekali,” ujarnya kepada TEMPO.
Nagiyah mengaku ikhlas melepas kepergian suaminya yang mendadak itu. Ketiga anaknya juga mulai pulih. Mereka selalu minta diajak saban kali ibunya berziarah ke makam Harna di Kemang, Jakarta Selatan. Tapi hati Nagiyah masih saja pedih bila Fachri, anak bungsunya, berlari ke luar rumah setiap kali mendengar sepeda motor melintas di gang depan. ”Itu bukan Bapak. Dia sudah ada di atas,” Nagiyah berusaha menjelaskan kepada Fachri.
Perempuan berdarah Betawi itu mengaku, sebulan pertama sepeninggal suaminya adalah masa yang amat berat. ”Setelah diberi tahu Paman bahwa suami saya kena ledakan bom, badan saya lemas,” tuturnya. Diantar pamannya, dia menjenguk jenazah suaminya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tapi, baru saja turun dari bajaj, Nagiyah jatuh pingsan. Akhirnya dia sama sekali tak menengok jenazah Harna hingga saat suaminya dimakamkan.
Nagiyah bertekad untuk segera keluar dari balutan kesedihan. Dia ingin berusaha sendiri. Katanya, ”Awal tahun depan, saya ingin kursus catering. Saya yakin bisa buka usaha kecil-kecilan.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo