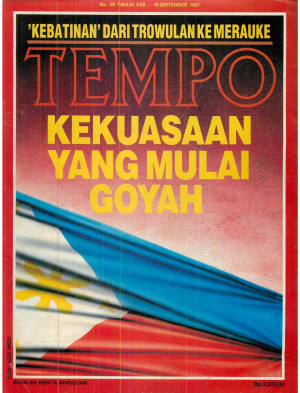AKU tak pernah memikirkan kemungkinan datangnya bahaya yang mengancam Anwar di hari yang dia banggakan. Yakni 6 Oktober, ketika rakyat Mesir, dan juga suamiku, merayakannya dengan penuh kemenangan. Tanggal yang diperingati setiap tahun sejak 1973. Di hari itu kami mengenang kembali kepatriotan tentara Mesir menyeberangi terusan Suez, merebut kembali tanah-tanah kami yang direbut Israel. Kami melupakan semua pertentangan: perbedaan ideologi, agama, politik, sosial, dan perbedaan lainnya. Suamiku, Anwar Sadat, telah membuka gerbang keadilan dan membangkitkan rasa harga diri negeri dan rakyat Mesir dari perasaan terhina -- karena kerapnya kami kalah melawan Israel. Setiap 6 Oktober Anwar selalu menghadiri parade militer di Kota Nashar. Aku sendiri hampir tak pernah menyertainya. Juga pada 6 Oktober 1981, sebenarnya aku tak ingin hadir. Aku minta izin tetap di rumah, bekerja menyelesaikan disertasi Ph.D.-ku di Universitas Kairo. Dan kini aku tak tahu apakah aku harus berterima kasih kepada pengawalku, yang karena omelannya (kok aku tak mendampingi Anwar) membuatku akhirnya pergi juga. Karena dialah seumur hidupku aku tak bakal melupakan suara berondongan senapan yang merenggut hidup suamiku dan sembilan orang lainnya. Di mataku selalu terbayang percikan darah Anwar yang membasahi lantai kayu mimbar. Aku selalu teringat jerit dan tangis ketakutan cucu perempuanku di tengah desingan peluru yang menghantam tembok penghalang di sampingku. Peristiwa itu membuat cucuku, waktu itu 5 tahun usianya, tak bisa tidur nyenyak dan tenang selama beberapa waktu. Ia selalu mendapat mimpi menakutkan. Untuk memperlihatkan diri sebagai orang penting, sebagai seorang perwira tinggi dalam kesatuan tentara Mesir, Anwar tak pernah lupa memasang tanda pangkat jenderal, tanda-tanda jasa, dan lencana jabatan pada baju seragamnya. Itulah yang kurang kusukai, dan aku biasanya protes. "Orang akan menduga, kau ingin memperlihatkan kekuasaanmu," kataku selalu. Tapi ia tak pernah peduli. "Beginilah gaya hidup seorang tentara," jawabnya, sambil menyelipkan tongkat komando. Ia tak pernah melupakan tongkat itu bila mengenakan seragam militer. Tapi hari itu, 6 Oktober 1981, tongkat itu tak dibawanya. Apakah ia lupa? Atau memang disengaja? Sampai kini ihwal tongkat tetap misterius. Memang, hari itu terasa segalanya di luar biasanya. Tahun-tahun sebelumnya, biasanya aku sudah selesai berdandan, dan kemudian membantu suamiku mengenakan seragamnya. Hari itu -- karena keputusanku untuk menyertainya ke tempat upacara baru kuambil pada menit-menit terakhir -- meski aku sudah buru-buru, Anwar pergi lebih dulu ke tempat upacara. Aku tak sempat mengucapkan selamat jalan, tak sempat menciumnya, bahkan tak melihatnya ketika ia pergi. Aku hanya mendengar deru mobilnya ketika meninggalkan halaman rumah. Pagi harinya, ketika Anwar masih berbaring, aku masih sempat menaruh cucuku, anak Yasmin, di sebelahnya. Bocah yang baru berusia dua tahun itu menarik-narik kumisnya, dan ketika mau dicium, ia melengos. Anwar tertawa. Lalu ia mengingatkanku agar tak lupa membawa serta Syarif, cucuku yang satunya lagi. Ia juga mengingatkan agar anak itu memakai baju seragam tentara. Persis ketika aku dan Syarif akan pergi ke tempat upacara, ketiga cucu perempuanku merengek ingin ikut. "Kenapa tidak?" pikirku. Hari ini adalah hari besar dan istimewa bagi kakek mereka dan negeri kami. Aku takkan pernah melupakan senyumnya ketika ia menaiki mimbar kehormatan diiringi tepuk tangan hadirin. Sesaat dia melirik ke belakang. Kulihat mukanya agak sedikit merah terkena panasnya matahari. "Ah, senyumnya itu," bisik kawanku, Dr. Zeinab El-Sobky, anggota parlemen. Ia benar. Senyumnya itu penuh arti. Senyum dari seorang yang sangat mencintai negerinya. Senyum seorang lelaki yang lebih mencintai keluarganya daripada dirinya sendiri. Dan itulah senyum terakhirnya. Barisan sepeda motor melewati mimbar kehormatan, mengawali acara parade. Barisan lain di belakangnya belum muncul juga. "Kenapa mereka terlambat?" tanyaku kepada Suzanne Mubarak, istri Wakil Presiden Hosni Mubarak, yang duduk di sampingku. "Kita saksikan sekarang kebanggaan kita, kesatuan gerilya," terdengar penjelasan lewat pengeras suara. Tapi mana? Beberapa menit telah lewat, pasukan itu belum muncul juga. Parade ini tampaknya tak serapi tahun-tahun sebelumnya. Banyak waktu terbuang. Dan kemudian, di atas kepala kami beberapa pesawat jet Phantom dari angkatan udara Mesir menderu, terbang dalam satu formasi. Mereka melakukan aerobatik, seraya mengeluarkan asap warna-warni. Pita merah, biru, dan hijau -- warna bendera kami -- terjulur dari pesawat itu. "Inilah atraksi terbaik," kata Nyonya Mubarak sambil tertawa. Aku pun ikut tertawa, di tengah kebisingan suara jet dan tepuk penonton. Sesaat aku khawatir akan keselamatan para pilot pesawat itu. Pasti Anwar senang melihat atraksi ini, pikirku. Aku memandangnya sesaat. Seperti yang lainnya, ia menengadah, mengikuti gerak laju Phantom-Phantom itu. Tiba-tiba, truk militer itu keluar dari barisan. Apa yang terjadi? Tiga tentara lari mendekati mimbar kehormatan dengan senjata otomatis di tangan. Ketika itulah aku mendengar ledakan. Asap menyebar, mengaburkan pandangan. Cepat aku menengok ke arah Anwar. Ia berdiri sambil menunjuk pengawalnya. Saya mendengar ia berteriak, "Hentikan semua itu!" Itulah terakhir kali aku melihat suamiku hidup. Suara tangisan, jerit ketakutan, kepanikan, desing peluru, kaca pecah. Aku mencoba mendekati suamiku, tapi pengawalku menghalangi. "Saya mohon Ibu jangan meninggalkan tempat ini," pintanya. "Jangan halangi aku," kataku, mencoba mendesak turun ke mimbar. Pengawal itu mendorong sehingga aku jatuh ke lantai. Huru-hara meledak. Semua cucuku menjerit dan menangis. "Tenang, tenanglah," bujukku, mencoba meredakan ketakutan mereka. Aku sendiri memang tidak terlalu panik, juga tidak merasa takut. Bahkan aku tak begitu mengkhawatirkan keadaan dan keselamatan suamiku aku yakin, tentara takkan menyakiti dan melukainya. Dia, suamiku, selalu memanggil dan menganggap para prajurit itu sebagai anak-anaknya. Dan "anak-anak" itu tampaknya sangat mencintai komandan tertinggi mereka. Kursi-kursi berantakan. Tak jauh dariku, aku melihat orang bergeletakan. Petugas PPPK sibuk mengangkut sebagian dari mere. ke mobil ambulans. Mereka yang tidak mengalami cedera berdiri bengong. Saya mencari Anwar. Aku melangkah ke bawah, mendekati panggung kehormatan dengan sangat hati-hati. Aku mencoba tak menjadi panik, untuk enunjukkan kepada suamiku dan negara bahwa aku tabah. "Di mana Presiden Sadat?" tanyaku kepada seorang pengawal Presiden yang seragam putihnya berlumur darah. "Saya baru saja mengantar beliau ke helikopter yang membawanya ke rumah sakit Al Maadi. Saya yakin Presiden baik-baik saja. Kelihatannya dia hanya terluka tangannya," jawab pengawal itu panjang. "Antarkan saya ke rumah sakit," kataku mencoba bersikap setenang mungkin. Tapi sesungguhnya aku cemas, banyak hal yang helum aku ketahui dan mengerti. Apakah ini awal satu kudeta? Apakah anak-ankku di rumah selamat? Dan bagaimana keadaan suamiku sebenarnya? Aku melihat Fawzi Abdul Hafiz, Sekretaris Pribadi Presiden, digotong dalam keadaan luka parah. Aku ingat, ia duduk persis di belakang suamiku. Tapi aku tetap yakin suamiku tak apa-apa, pasti ia selamat. Aku segera membawa cucu-cucuku masuk mobil untuk menuju ke helikopter yang telah disediakan. Dengan heli itulah kami ke rumah sakit. Anak-anak ini mengalami guncangan. Terpikir untuk lebih dulu mengantar mereka ke rumah. Kepada pilot aku minta agar kami diturunkan di rumah saja. Untuk ke rumah sakit aku dapat menggunakan mobil. Ketika memasuki rumah sakit, tak seorang pun menegurku. Dokter dan perawat yang menyambut hanya berdiri memandang. Padahal, hampir semua dokter dan perawat di rumah sakit ini sudah lama kukenal. Aku bergegas menuju ruang tunggu, tempat semua anggota keluargaku dan para pejabat pemerintah berada. Rasanya, lorong yang kulalui begitu panjang dan tak berujung. Alhamdulillah anak-anakku selamat dan mereka semua sudah lebih dulu tiba. Pasti mereka melihat peristiwa yang menimpa ayah mereka lewat TV yang menyiarkan seluruh acara perayaan itu. Wakil Presiden Mubarak dan para pejabat yang selamat sudah pula datang. Tangan Mubarak yang tersrempet peluru telah dibalut. Tak seorang pun yang membuka percakapan ketika aku menggabungkan diri dengan mereka. Aku pun tak mencoba bertanya. Hassan Mara'i, menantuku, mendekat. Ia mengatakan baru saja menerima telepon dari Gamal, anak lelakiku yang berada di California. Ia akan segera datang. Sudah setengah jam aku berada di ruang tunggu. Aku pikir aku harus berbuat sesuatu untuk mengakhiri kebisuan ini. Dengan perasaan tak menentu, aku berdiri dan menghampiri Mubarak. "Saya kira Presiden Sadat telah berpulang," kataku dengan tenang. "Tugas Andalah sekarang memimpin negeri dan rakyat Mesir." Mubarak menatapku dengan tegang. "Jangan berkata begitu, Nyonya. Jangan berkata begitu." (Lihat Selanjutnya: Selamat Tinggal Anwar, dan Pilihan Jehan)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini